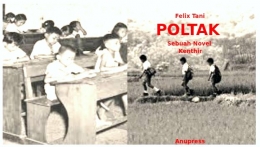"Biarkan saja, Poltak!" Teguran kakeknya menghentikan upaya Poltak menggebah induk ayam betina piaraan mereka.
"Kasihan anak-anaknya, Ompung! Dipatuki terus!"
"Biarkan saja. Induknya sedang menyapih anaknya. Begitu cara ayam memandirikan anak-anaknya. Agar tak tergantung pada induknya terus." Kakek Poltak menjelaskan. "Kau juga, begitu Poltak. Suatu saat nanti, Ompung akan mematukmu."
"Ompung mematuk aku? Ompungku, kan bukan seekor ayam." Poltak membatin. Diamatinya wajah kakeknya. Siapa tahu ada tanda-tanda akan tumbuh paruh besar di sana.
"Poltak! Jangan melamun terus kau. Sudah sore. Sana, jemput kerbau kita!" Teriakan neneknya menyentak Poltak dari lamunannya. Tak sadar dia, neneknya sudah berdiri di hadapannya, di teras rumah.
"Olo, Ompung!" Poltak spontan bangkit dari duduknya. Lalu beranjak pergi menuju Holbung, tempat kerbau-kerbaunya ditambatkan untuk merumput.
Nenek Poltak mengikuti Poltak dengan tatapan mata sedih. "Poltak, cucuku, kau masih terlalu kecil untuk mengambil-alih tugas kakekmu," gumamnya, pelan, kepada diri sendiri.
Bermula dari hari Sabtu, minggu lalu, seusai makan siang dengan lauk ikan mujair arsik. Di teras rumah, saat menikmati sebatang rokok lintingan sendiri, mendadak kakek Poltak batuk-batuk.
"Ompungni Poltak, aku kenapa ini. Batukku berdarah."
Kakek Poltak menunjukkan bercak darah di telapak tangan kanannya. Nenek Poltak, yang memburu datang ke teras, terkesiap. Roman mukanya mendadak berubah, menunjukkan rasa khawatir mendalam.
"Sudah kubilang, kurangi merokok. Tapi kau tak mau dengar kata-kataku." Nenek Poltak menyesali suaminya. Marah, sedih, cemas, bercampur.