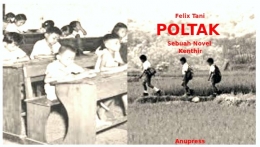Ada kalanya hujan mendadak turun di tengah terik matahari. Kejadian tak disangka. Mestinya menimbulkan syak-wasangka.
"Poltak! " Suara panggilan itu akrab di telinga Poltak. Itu suara bapaknya. "Sini sebentar!" Bapaknya melambaikan tangan dari halaman depan kedai Ama Rosmeri.
Poltak berada di halaman depan gereja. Sambil menunggu giliran masuk kelas, dia sedang martumbang, main tembak karet gelang dengan Alogo, Nalom, dan Gomgom. Karet gelang taruhan dikalungkan pada cagak kecil yang menancap di tanah. Lalu ditembak dengan karet gacok dari jarak tiga meter. Kalau kena dan lepas dari cagak, maka karet itu menjadi hak penembak.
"Among, mau kemana?" tanya Poltak setelah berada tepat di depan bapaknya. Heran, dia sangat heran. Selama ini, bapaknya tak pernah tahu urusan sekolahnya. Kenapa sekarang tiba-tiba ada di sini?
"Ke rumah buyutmu. Ada keperluan. Kita minum teh manis dulu," jawab bapaknya sambil melangkah ke dalam kedai. Poltak mengekor di belakangnya.
Poltak tidak bertanya lagi. Dia menepis syak-wasangka dari pikirannya. Lagi pula, segelas teh manis dan dua buah lampet sudah terhidang di atas meja. Itu sudah culkup untuk menghapus pikiran yang bukan-bukan.
Tapi Poltak lupa. Dalam masyarakat Batak, selalu ada hata ni sipanganon, maksud dari pemberian makanan. Sebab makanan juga bermakna simbolik. Orang Batak bilang, "Katakanlah dengan makanan."
Seusai minum teh manis dengan bapaknya, Poltak kembali martumbang melawan Alogo, Nalom, dan Gomgom. Jonder juga ikut bergabung.
Tiba-tiba Bistok datang membawa kabar, "Poltak! Tadi kulihat bapakmu dan nenekmu naik sepeda ke arah Portibi." Kampung Portibi ada di sebelah barat sekolah.
"Hah?" Poltak kaget tak terkira. Rupanya, itulah pesan dari segelas teh manis dan dua buah lampet. Nenek dan bapaknya diam-diam mau pergi ke suatu tempat.
Tanpa pikir panjang, Poltak memungut buku-bukunya dari tangga gereja, lalu berlari seperti anak kerbau mengejar nenek dan bapaknya. Setelah berlari kurang lebih setengah kilometer, barulah dia bisa melihat nenek dan bapaknya bersepeda di kejauhan.
"Ompung! Ompung! Ompung!" Poltak berteriak sekuat tenaga memanggil neneknya. Larinya semakin cepat. Tak percuma tadi minum segelas teh manis dan makan dua buah lampet panas.
Teriakan Poltak terdengar oleh nenek dan bapaknya. Mereka berhenti menunggu. Poltak menambah kecepatan larinya.
"Aku ikut, ompung," pinta Poltak setelah berhasil menyusul.
"Jauh. Ke rumah ompungmu di Silosung. Bermalam di sana." Bapaknya memberitahu Poltak tempat tujuan bepergian. Kampung Silosung terletak di pantai-luar timur Danau Toba. Berada di gigir sebuah teluk kecil.
"Ah. Sudah kubilang tadi, tak usahlah mengajak dia minum di kedai." Nenek Poltak menyesali dan menyalahkan bapak Poltak. Lalu agak menyalahkan Poltak, "Jadi alpalah kau sekolah besok."
"Tak apalah. Ayo, Poltak, naik." Bapak Poltak memberi persetujuan.
Dengan sigap, Poltak naik dan duduk serong di pipa-atas tulangan sepeda, antara sadel dan setang. Bukan posisi duduk yang nyaman. Tapi Poltak tak hirau. Sebab hatinya nyaman, tak akan kehilangan neneknya, walau hanya semalam.
Jarak Hutabolon ke Silosung kurang lebih delapan kilometer. Setelah melewati hutan pinus, Poltak bersama nenek dan bapaknya tiba di Desa Sibisa. Dari situ perjalanan bersepeda dilanjutkan ke arah selatan, ke Hutaginjang, kampung terakhir di gigir tebing pantai Danau Toba. Di kampung itu, sepeda dititipkan di rumah satu keluarga yang masih terbilang kerabat.
Perjalanan dilanjutkan berjalan kaki. Berjalan kurang-lebih tigaratus meter ke arah selatan, Poltak bersama nenek dan bapaknya tiba tepat di bibir tebing.
Poltak terpana takjub. Untuk pertama kali sepanjang hidupnya dia menyaksikan Danau Toba dari ketinggian. Jarak dari bibir tebing ke bawah, ke bibir pantai, kurang lebih seratus meter. Kemiringan tebing itu sekitar tujuh puluh derajat.
Dari bibir tebing, Poltak melihat permukaaan Danau Toba tampak sebagai cermin berkilauan. Beberapa perahu partoba, nelayan Danau Toba, tampak bergerak pelan di sekitar pantai. Dari atas, perahu-perahu itu tampak kecil. Seperti serpihan-serpihan kayu mengapung di air.
"Itu Silosung. Kita ke situ." Bapak Poltak menunjuk sebuah kampung di dasar tebing, berada pada dataran sempit yang agak menjorok ke danau, semacam semenanjung kecil dalam teluk. Dari atas tebing, barisan rumah-rumah beratap seng berkarat tampak kecil.
"Bagaimana cara kita ke sana, Among?" tanya Poltak sedikit bingung.
"Merayap. Turun tebing," jawab bapaknya. "Kau bisa, kan?" Poltak mengangguk.
"Harus hati-hati. Jalan curam sekali. Bahaya. Jangan sampai terpeleset." Nenek Poltak mengingatkan. Serius, sangat serius.
"Ayo, kita turun." Bapak Poltak mulai melangkah menuruni tebing lewat jalan setapak. Poltak mengikut di belakangnya. Paling belakang, neneknya.
Baru sekitar lima meter menuruni tebing, batu sebesar kepalan yang diinjak Poltak tercungkil dari tanah. Poltak hilang keseimbangan. Lalu terpeleset menggelosor.
"Poltak!" Neneknya berteriak histeris. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H