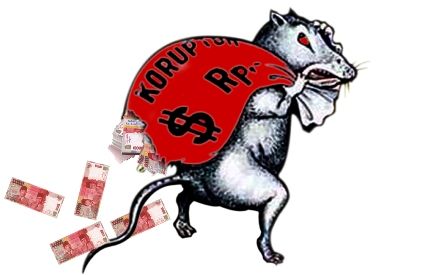Tadi pagi rekan S. Aji menaja artikel "Menteri Korupsi Zaman Pandemi, Bagaimana Nasib Jelata?" di K ini. Itu sebuah amarah yang liris terhadap minus-empati dua koruptor kaliber menteri terhadap derita jelata yang cuma dihargai suaranya saat Pilkada. (Syukurlah artikel itu sudah naik ke AU).
Karena saya tahu Aji selalu menulis dengan hati beralas pikir, maka wajib hukumnya bagi saya membaca dan mengomentarinya. Komentar saya begini. Suatu ketika nanti dalam KBBI akan ada lema seperti ini: negara /ne.ga.ra/, kb. perusahaan nenek loe. Saya separuh yakin rekan Daeng Khrisna Pabichara akan mendukung temuan baru arti kata itu. Kecuali dia mendukung korupsi dan koruptor.
Bicara koruptor orang mengambil tikus sebagai simbolnya. Tentu dengan dasar asumsi tikus itu pencuri makanan manusia. Bukan dengan dasar asumsi tikus itu pelaku inses bajingan serupa babi dan betinanya bisa melahirkan ribuan ekor anak. Sungguhpun mungkin ada koruptor seperti itu, tapi bukan tabiat itu yang dirujuk. Tapi tabiat nyolongnya.
Sebenarnya perujukan itu tak terlalu pas karena dua alasan. Pertama, tikus tak bisa bercocok tanam atau bikin pabrik kue, sehingga dia terpaksa mencuri padi petani atau kue di warung. Kedua, tikus hanya mengambil sejumlah volume perutnya Tidak pernah mencuri makanan berlebihan sampai harus menyimpan di bank pangan, koper, atau ember.
Tapi sudahlah, jika ngotot pakai tikus sebagai simbol koruptor, ya, semongko. Walau saya agak keberatan sebab lebih tepat koruptor dijadikan simbol tikus. Tapi, jika dibuat begitu, mungkin tikusnya akan unjukrasa atas pasal penistaan nama baik. Hadeuh, lieur, euy.
Koruptor dan tikus silahkan saja berdebat tentang siapa yang pantas menjadi simbol siapa. Tapi kedua pihak harus sadar ada satu kesamaan hakiki di antara mereka yaitu sama-sama dungu.
Lha, kok bisa dama dungu. Kan volume otaknya beda. Benar, tapi ini soal volume otak terpakai. Kalau volume otak yang dipakai koruptor untuk korupsi sama besar dengan volume otak tikus, ya, bisa saja sama dungu.
Poltak sudah membuat pembuktian sederhana. Di pekarangan rumahnya di Gang Sapi Jakarta, dia berseteru dengan para tikus celurut. Tikus-tikus itu rajin menggerogoti tanamannya, semisal singkong sayur, sereh, kunyit, jahe, dan laos. Poltak memutuskan menjebak para celurut itu dengan perangkap tikus berumpan kepala ikan goreng.
Hasilnya sungguh menakjubkan. Dalam tiga bulan terakhir, sudah enam ekor celurut tertangkap tangan. Poltak lalu menjemur tikus-tikus celurut itu di bawah pancaran sinar matahari. Tujuan utamanya untuk memberi pelajaran, seperti dulu gurunya di SD menjemurnya di bawah matahari kalau nakal. Bahwa kemudian tikus celurut itu mati kepanasan, itu efek sampinglah.
Satu hal yang bikin Poltak takjub, ternyata para celurut itu tak pernah belajar bahwa perangkap bisa menjebak mereka. Poltak berteori bahwa tikus itu telah berpikir bahwa manfaat umpan kepala ikan lebih besar ketimbang risiko terjebak perangkap. Bahwa faktanya kemudian para celurut itu masuk perangkap, itu membuktikan otak mereka sepenuhnya dungu. Tapi mereka pikir otak mereka pintar.
Kesimpulan hipotetis tentang kedunguan celurut itu kemudian dikenakan Poltak pada koruptor. Hasilnya mengejutkan. Para koruptor ternyata tak pernah belajar bahwa KPK bisa menangkap mereka. Mereka pikir manfaat uang hasil kerupsi jauh lebih besar ketimbang risiko tertangkap tangan oleh KPK. Bahwa faktanya kemudian mereka tertangkap oleh KPK, tak lain artinya sama seperti celurut, otak koruptor itu dungu juga. Tapi mereka selalu berpikir dirinya pintar.
Saya tahu bahwa kesimpulan tikus dan koruptor sama dungunya akan mengundang perdebatan. Tapi pikirkanlah konsekuensi logis ini: menolak kesimpulan itu berarti bersimpati pada koruptor, menerimanya berarti menghina kemanusiaan.(*)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI