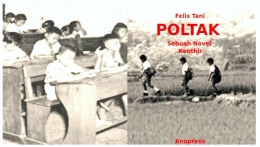Hari pertama sekolah. Pagi-pagi benar, Poltak sudah menambatkan kerbaunya ke lembah Holbung. Pulang dari Holbung, dia membenamkan tubuhnya di saluran irigasi. Mandi pagi. Giginya digosok menggunakan daun oma-oma, sejenis rumput rawa berdaun jarum. Tanpa pasta.
Tubuh segar bersih, gigi putih bersinar. Setidaknya begitulah perasaan Poltak. Dia siap menjalani hari pertama sekolah.
Beginilah stelan Poltak siap sekolah. Rambut dioles minyak kelapa, disisir ke belakang mirip gaya sisiran bos mafia. Kemeja baru, motif daun maple di atas warna dasar putih. Celana pendek, baru, bahan keper warna coklat.
Tapi yang paling spektakuler adalah sepatunya. Khusus untuk hari pertama sekolah, oleh neneknya, Poltak dibelikan sepasang sepatu model spartakus. Nama spartakus itu pemberian pedagangnya di Tigaraja. Modelnya menyerupai brongsong anjing, dikenakan menutup lidah kaki sampai bawah betis.
"Oi, bagus kali sepatumu, Poltak. Sepatu spartakus!" Binsar berteriak takjub melihat Poltak mengenakan sepatu spartakus.
"Haa! Spartakus pergi sekolah!" Bistok berteriak menimpali.
"Poltak Spartakus!" anak-anak lain ikut bersorak.
Poltak bunggah. Amangudanya, Parandum, pernah bercerita, Spartakus itu adalah pemberontak perkasa yang berperang melawan tentara Romawi. Dia suka Spartakus.
Sekarang dia jadi Spartakus. Dari delapan orang anak Panatapan yang berangkat sekolah pagi itu, hanya dia yang mengenakan sepatu. Itu sepatu spartakus. Tujuh anak lainnya, termasuk Binsar dan Bistok, kaki ayam alias nyeker.
"Besok kau pasti tak mau lagi pakai sepatu." Binsar meramal. Poltak diam saja. "Ah, dasar iri saja kau, Binsar," bathinnya.
Sepatu spartakus Poltak terbikin dari bahan plastik keras. Jarak dari Panatapan ke Hutabolon, tempat Sekolah Dasar berada, sekitar tiga kilometer.
Kebunggahan Poltak sewaktu di Panatapan mulai berubah menjadi kesakitan saat tiba di Hutabolon. Sepanjang perjalanan sepatu berbahan plastik itu telah menggigiti kaki Poltak tepat pada tendonnya hingga terluka. Luka itu menyebabkan Poltak harus berjalan dengan gaya langkah kuda.
Lonceng tanda masuk sekolah berdentang. Semua murid, dari kelas satu sampai enam, disuruh berbaris di halaman gedung sekolah. Guru-guru berdiri di depan mereka.
Itulah barisan anak-anak seribu warna-warni bunga di taman. Baju bebas, warna-warni. Sebab sekolah Dasar Hutabolon belum mengenal seragam sekolah. Juga tidak mengenal sepatu atau sandal. Pada hari pertama sekolah di tahun 1967 itu, hanya seorang morid baru yang mengenakan sepatu: Poltak.
Guru Henok, Kepala Sekolah, menyampaikan sambutan selamat datang kepada murid baru dan, kepada semua anak, nasihat untuk lebih giat belajar.
"Anak-anakku, kelas satu, setelah setahun, kalian semua akan pintar membaca, menulis, dan berhitung. Kalian akan diajar seorang guru yang hebat. Guru Barita!"
Guru Henok memberi wejangan khusus untuk anak-anak kelas satu. Guru Barita, tinggi besar, kulit putih bersih lagi tampan, melambaikan tangan sambil tersenyum menunjukkan dirinya.
"Hati-hati kau, Poltak. Kepalan tangan Guru Barita itu berbisa. Kalau kau dodong, lalu kepalamu digetoknya, bisa benjol sebesar jengkol." Binsar, dari barisan di samping kiri, membisikkan berita teror ke telinga Poltak. Tak urung, Poltak jadi kembut dibuatnya.
Setelah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, dilanjutkan lagu rohani gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan ditutup dengan doa yang dipimpin Guru Gayus, guru agama, murid-murid bubar dan berlari masuk ke kelas masing-masing.
Murid kelas empat, lima, dan enam menempati tiga ruang kelas di gedung sekolah yang dibangun pemerintah. Hanya tiga ruang kelas. Tanpa ruang guru. Itu sebabnya kedai kopi Ama Rosmeri, di sebelah depan sekolah, berfungsi sebagai ruang guru bagi guru-guru Sekolah Dasar Hutabolon.
Murid-murid kelas satu menempati ruang gereja HKBP Hutabolon. Gereja ini, sejak masih berupa bangunan sederhana di penghujung 1910-an, sudah difungsikan sebagai ruang kelas pendidikan informal. Itu bagian dari sumbangan gereja terhadap pendidikan umatnya.
Pada tahun 1967, gereja itu sudah berupa gedung permanen, kokoh dan berwibawa. Untuk kepentingan sekolah, ruang gereja yang jembar itu dibagi dua. Bagian depan untuk kelas satu dan dua, bagian belakang untuk kelas tiga.
Untuk kelas satu dan dua cukup satu ruangan. Karena kelas satu belajar hanya dua setengah jam di pagi hari, lalu dilanjut dengan kelas dua. Gurunya sama, Guru Barita.
Tidak ada sekat pembatas, antara ruang kelas, kecuali papan tulis kelas tiga yang berfungsi sebagai tanda batas ruang. Inilah ruang kelas tanpa rahasia. Murid kelas tiga bisa tahu siapa saja murid kelas atau atau dua yang kepalanya benjol sampai menangis digetok guru. Sebaliknya juga begitu.
"Ayo, baris dulu di depan sini." Guru Barita mengatur murid-murid kelas satu. Semua murid berbaris, tepatnya menumpuk, di depan kelas. Jumlahnya duapuluh anak murid.
Guru Barita mengabsen murid. Setiap kali nama dipanggil, setiap kali pula ditunjukkan pula bangku tempat duduknya. Bistok dan Binsar sudah mendapat tempat duduk. Berdampingan, karena kebetulan nama mereka dimulai dengan suku kata yang berdekatan, "bis" dan bin".
"Polmer! Nah, kau duduk di bangku sana!" Guru Barita menunjuk ke satu titik bangku di baris belakang.
"Poltak! Kau duduk di samping Si Polmer. Sana!"
Poltak segera berlari kecil gaya kuda menuju tempat duduk yang ditetapkan untuknya. Sebab tendonnya terasa sakit, terluka oleh sepatu spartakusnya.
Poltak mengamati Polmer, tetangga sebangkunya, di sebelah kanannya. Perawakannya melampaui ukuran rata-rata anak kelas satu. Lebih tinggi dari Binsar dan lebih gempal dari Bistok. Wajahnya sangat Batak.
"Anak-anak, perhatikan Pak Guru. Kita belajar lipat tangan." Guru Barita memberi perintah dari depan kelas.
"Satu, dua tangan lurus ke depan. Dua, letakkan tangan kiri di atas siku tangan kanan. Tiga ..."
"Srot ..." Tiba-tiba bunyi "srot" dahsyat mengema dari lubang hidung Polmer. Spontan Poltak menoleh ke kanan. Polmer sedang melap ingusnya dengan lengan kanannya, sehingga posisi lipat tangannya buyar.
"Polmer! Telapak tangan kiri di atas siku tangan kanan!" Guru Barita beteriak.
"Olo, Gurunami," Ya, Guru kami.
"Tiga, lipat tangan kanan di atas tangan kiri!"
"Srot ..." Lagi bunyi "srot" yang lebih dahsyat mengema dari lubang hidung Polmer. Kali ini dia tidak berani lagi melap ingusnya dengan tangan.
Akibatnya fatal. Dua garis hijau kental mengalir dari lubang hidung sampai bibir atas Polmer. Perlahan tapi pasti, aliran kental bernama ingus itu mulai merembes ke dalam mulutnya.
"Gurunami!" Poltak mengacungkan telunjuk. Cemas dan dan sedikit jijik melihat kondisi Polmer, tetangga bangkunya.
"Diam kau, Poltak! Pak Guru belum selesai bicara!"
"Gurunami!" Poltak berkeras kepala. Dia tidak takut. Karena dia adalah Spartakus.
"Bah! Tak bisa diperintah pakai mulut kau rupanya!" Guru Barita gusar. Diambilnya sebatang lidi dari atas meja dan segera bergegas mendekati bangku Poltak. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H