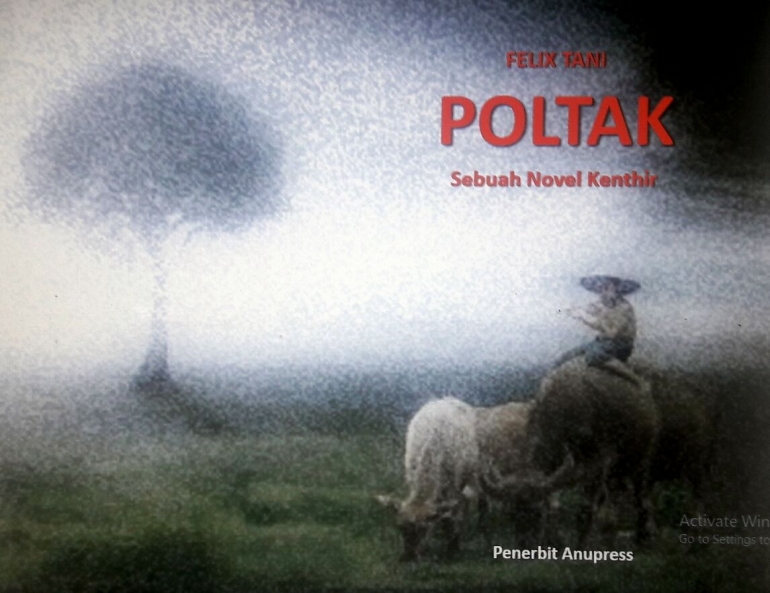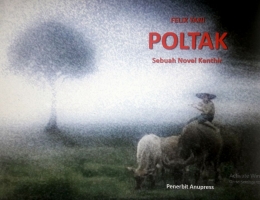Kedatangan bapaknya, Amani Poltak, siang itu ke rumah kakeknya, oleh Poltak dianggap biasa saja. Bukan sekali dua kali bapaknya, juga ibunya, mampir di situ. Apalagi, rumah kakek Poltak berada di antara Robean, tempat tinggal bapaknya dan areal sawah miliknya di sebelah selatan dan timur Panatapan.
"Sedang melukis apa kau, Nak." Bapaknya sempat menyapa Poltak di halaman, sebelum masuk ke dalam rumah. Poltak diam saja. Tersenyum. Meneruskan lukisannya di tanah. Dia pikir, bapaknya bisa melihat sendiri lukisannya.
Bapaknya berbincang dengan kakek dan neneknya di dalam rumah. Tak begitu jelas terdengar di telinga Poltak. Tapi dia juga tidak ingin tahu. Itu urusan orangtua.
"Saya mau bawa Poltak pulang ke Robean. Anak sulung harus tinggal bersama orangtuanya," Amani Poltak menegaskan keinginannya. Dia tidak mampu lagi membendung tuntutan ibu Poltak. "Masa anak buhabaju, panggoaran kita tidak tinggal bersama kita. Macam kita tak mampu membesarkannya. Malulah sama orang sekampung." Ibu Poltak protes keras. Ini perkara harga diri orangtua.
Dalam masyarakat Batak anak buhabaju, sulung, pembuka pertama baju ibunya untuk menyusui, sekaligus panggoaran, penamaan orangtua, semisal Amani Poltak dan Nai Poltak, lazimnya harus tinggal bersama orangtua. Sebab anak sulung adalah identitas sosial orangtua Batak.
"Biarkan dia di sini saja. Tinggal bersama kami. Supaya kami tidak kesepian. Biarlah kami yang membesarkannya," pinta nenek Poltak dengan sangat. Baginya, cucu pertamanya itu sudah serasa anak bungsu. Begitu juga bagi kakek Poltak.
"Tidak, Inong, Among. Poltak tanggungjawab kami, bapak dan ibunya." Amani Poltak berkeras. Tak ingin lagi dia mendengar protes Nai Poltak, jika gagal membawa pulang Poltak ke Robean. Bujukan menambah anak lagi sudah tak mempan. "Saya mau anak pertama, bukan kelima atau keenam," begitu tangkisan Nai Poltak.
"Ayo, Nak. Kita pulang ke Robean. Rumah kita di sana." Amani Poltak langsung mencengkeram tangan Poltak dan menariknya untuk ikut ke Robean.
Poltak bagai disambar petir. Tapi juga bingung tak mengerti. Mengapa harus ikut bapaknya ke Robean.
"Tidak mau! Rumahku di sini! Aku anak ompung!" Poltak meronta hebat. Tangisnya meledak, mengemparkan seisi Panatapan. Warga datang merubung. Ingin tahu apa yang terjadi.
Di dalam kerumunan, terselip jugalah Ama Ringkot. Dia tampak puas menyaksikan nasib Poltak. Gara-gara kepahlawanan Poltak, dia gagal mencuri tanggalan, daging leher kerbau sewaktu upacara adat sarimatua Ompu Maruhal. Dendamnya serasa terbalaskan kini. Begitulah, pencuri malah dendam, bukannya malu.
Binsar dan Bistok tak ketinggalan. Mereka hanya diam berdiri. Prihatin menyaksikan Poltak, kawan karib mereka, diseret-seret bapaknya sendiri. Mahakuasa seorang bapak Batak.
"Bah! Nak, kau dilahirkan ibumu, bukan nenekmu!" Amani Poltak membentak anaknya yang dianggap kurang ajar itu. Amani Poltak menyeret pergi anaknya, Poltak.
"Ompung! Tolong, Ompung!" Poltak meraung minta tolong. Dia tak mau dipisahkan dari kakek-neneknya.
Tapi kakek-neneknya diam saja. Mereka tidak kuasa berbuat apa pun. Hanya bisa berdiri muram di teras rumah, pasrah menyaksikan cucu kesayangan mereka dibawa pulang bapaknya.
Tenaga Poltak bukan tandingan untuk bapaknya. Terpontal-pontal dia setengah berlari diseret oleh bapaknya. Jerit tangisnya tiada mereda sepanjang jalan, sekitar satu kilometer jauhnya. Itu jarak Panatapan ke Robean.
Begitu masuk rumah di Robean, pintu- pintu langsung dikunci. Agar Poltak takbisa kabur, kembali ke rumah kakek-neneknya di Panatapan.
Poltak duduk teronggok layaknya tahi kerbau di lantai papan di ruang tengah rumah. Pikirannya buntu, sebuntu-buntunya. Perasaannya bantat, sebantat-bantatnya.
Ketiga adiknya, Benget, Tiurma, dan Sahat berdiri mematung di pintu tengah. Diam mengamati Poltak, dengan sorot mata penuh tanya. Juga tatapan prihatin.
"Ini, minum limun, Nak," ibu Poltak menawarkan segelas limun. Mata Poltak memaku segelas limun itu. Gelembung-gelembung karbon dioksida berkejaran naik ke permukaan cairan merah manis segar itu.
Poltak merasa asing di rumah Robean. Asing kepada bapaknya, ibunya dan tiga orang adiknya. Dia sadar itu bapaknya, ibunya, dan adik-adiknya. Tapi hatinya tidak ditaruh pada mereka. Melainkan pada kakek-neneknya di Panatapan.
Tapi Poltak tak merasa asing dengan segelas limun merah yang begitu menggoda. Dia tergila-gila pada sensasi cubitan-cubitan karbon dioksida limun pada lidahnya. Bagi Poltak, juga anak-anak Panatapan lainnya, limun adalah minuman surgawi.
Glek, glek, glek. Serasa di bawah sadar, Poltak tanpa kendali telah menyambar dan menenggak habis segelas limun itu. Ajaib. Pikirannya mendadak terbuka. Perasaannya mendadak sarang. Akal sehatnya langsung bekerja. Kelak ibunya akan menyesal karena telah memberi segelas limun untuknya.
Poltak mendadak berpikir lebih cerdas dibanding bapaknya. Bagi bapaknya pintu adalah satu-satunya jalan keluar-masuk rumah. Bagi Poltak, semua lubang di dinding adalah pintu keluar-masuk rumah. Termasuk jendela ruang tengah yang terbuka lebar di hadapannya.
"Ini kesempatanku," Poltak membathin, hatinya bersorak. Bukan Poltak namanya kalau menyia-nyiakan kesempatan baik. Bukan Poltak juga kalau tidak berhitung dalam tindakan. Setiap kesempatan harus diambil dengan risiko gagal terkecil.
Selang beberapa waktu, ketika tiada sebelah mata pun yang melihatnya, Poltak pelan-pelan menjinjit tanpa derit menuju jendela yang terbuka itu. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H