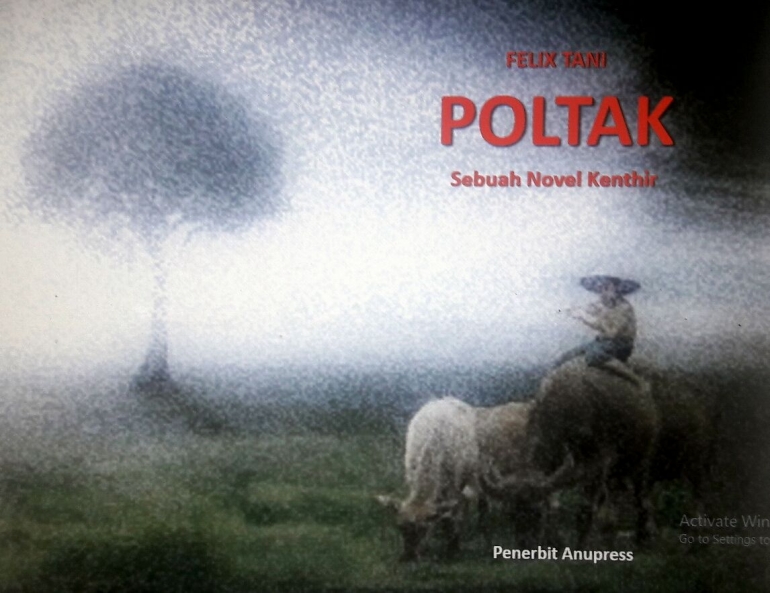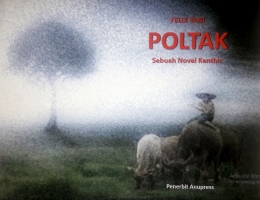Kali kedua kokok ayam jantan berkumandang di Panatapan. Bersahut-sahutan dari satu ke lain kolong rumah. Itu penanda waktu. Pukul tiga dini hari sudah tiba.
Hujan lebat yang mengguyur Panatapan, dan kampung sekitar, sejak tengah malam, sudah reda. Meninggalkan dingin.
"Poltak! Bangun! Siap-siap ke Losung" Nenek Poltak menggoyang-goyang tubuh Poltak yang terbalut hangat di bawah siluban, tikar selimut.
Dini hari mereka harus berangkat ke Losung Aek, lesung yang digerakkan dengan kincir air, di kampung Toruan. Di sana, mereka akan menumbuk gabah menjadi beras. Persediaan beras di dapur sudah menipis.
Sebenarnya ada empat cara warga Panatapan untuk mendapatkan beras. Jika persediaan masih memadai, mereka bisa menunggu hari Sabtu, hari pasaran, untuk menggiling gabah di mesin penggilingan di Tigaraja, Parapat.
Jika persediaan sudah menipis, maka pilihannya pergi menumbuk gabah ke Losung Aek di kampung Toruan.
Bila persediaan beras habis, darurat, ada dua pilihan. Menumbuk sendiri menggunakan lumpang dan alu. Atau marsali boras, pinjam beras, dari tetangga sebelah. Nanti dikembalikan jika beras sudah ada lagi.
"Ayo! Adikmu sudah bangun." Benget, adik Poltak, kemarin merengek minta ikut ke Losung Aek. Katanya, dia belum pernah ke sana. Karena itu, kemarin sore dia datang dan menginap di rumah nenek Poltak, neneknya juga.
Poltak dan adik-adiknya tinggal pisah rumah. Poltak tinggal bersama kakek-neneknya. Sedangkan Benget dan dua orang adiknya yang lain tinggal bersama bapak-ibunya di kampung Robean, di lereng perbukitan sekitar satu kilometer di arah barat laut Panatapan.
Menurut tuturan, dulu, sewaktu bapak-ibunya merintis kampung baru di Robean, Poltak dititipkan pada kakek-neneknya. Kadung teramat sayang kepada cucu pertamanya itu, kakek-nenek Poltak kemudian hari menolak untuk menyerahkannya kepada bapak-ibunya.
"Ya, sudahlah, Inang ni ucok. Biarlah Si Poltak tinggal bersama kakek dan neneknya. Kita bikin anak baru saja." Ama ni Poltak, bapak Si Poltak, memberi pengertian kepada isterinya, Nai Poltak yang protes keras.
Maka jadilah seperti itu. Setahun kemudian lahirlah Benget. Karena dirasa kurang ramai, ditambahlah dua orang anak lagi: Tiurma, anak perempuan dan Sahat, anak laki-laki. Semudah itulah hidup.
Poltak masih meringkuk di ranjang. Rasa malas menjalari seluruh otot dan sendinya. Tambahan, sakit giginya kambuh pula.
"Ayo, Poltak! Ayam saja sudah bangun!" Kakek Poltak berteriak dari dapur.
"Iya, ompung," Poltak melompat dari ranjang. Terkantuk-kantuk, sambil memegangi pipi kirinya yang terasa bengkak karena sakit gigi, dia melangkah ke dapur.
Di depan perapian, kakek, nenek dan Benget sedang berdiang. Berada pada ketinggian 1,200 meter di atas permukaan laut, suhu udara Panatapan sangat dingin. Berdiang adalah solusinya.
"Kumat lagi sakit gigimu, ya," tanya neneknya. Poltak mengangguk, dengan mimik kesakitan.
"Sudahlah. Jangan jadi alasan. Kau berjalan pakai kaki, bukan gigi," tukas kakeknya. Poltak mati kutu.
"Ayo, berangkat. Keburu pagi." Nenek Poltak mengajak Poltak dan Benget pergi. Kakek Poltak tinggal di rumah.
Udara di luar rumah lebih dingin lagi, tinggalan hujan tadi malam. Gigi Poltak gemerutuk, menambah rasa sakit, walau tak dipakai untuk jalan.
"Enak benar menjadi kakek," sungut Poltak dalam hati. "Tak perlu ikut menyunggi gabah ke Losung Aek."
Jarak Panatapan ke Losung Aek sekitar dua kilometer. Menyunggi sekarung kecil gabah, sekitar 25 kilogram di atas kepala, jarak itu adalah derita panjang untuk Poltak.
Dia terseok di belakang neneknya yang menyunggi sekarung besar gabah dan adiknya yang melenggang tanpa beban.
Tekanan seperempat kuintal gabah di kepalanya membuat leher Poltak terasa sakit. Dia harus menahannya. Sambil berpikir, "Inilah sebabnya mengapa saya tidak tumbuh tinggi seperti Binsar."
Poltak heran bagaimana bisa neneknya jalan melenggang seolah setengah kuintal gabah di kepalanya itu tak lebih dari segumpal sanggul.
Ah, Poltak, dasar anak kecil. Dia tidak tahu, di bawah panji patriarki, perempuan Batak telah dilatih untuk menanggung segala beban. Khususnya suami, yang terberat dari segalanya.
Setelah sekitar empat puluh menit perjalanan, lewat jalan raya Trans-Sumatera ke selatan, membelah kampung Toruan, lalu menuruni jurang, akhirnya tiba juga rombongan kecil itu di Losung Aek.
Losung Aek itu sarana komunal. Semua warga Panatapan dan Toruan, serta Sosorlatong di selatannya, berhak menggunakannya. Untuk keperluan pemeliharaan, pengguna akan menyisihkan beras sebagai imbal jasa. Jumlahnya antara setengah sampai satu liter.
Rumah lesung itu, terbuat dari kayu dengan atap seng, dibangun di tengah persawahan. Sebagian debit air irigasi yang bersumber dari hutan Gunung Simarnaung dialihkan untuk memutar kincirnya.
Teknologinya sederhana. Sumbu kincir itu adalah ujung as balok bulat besar yang dipasangi enam pasak selang-seling. Saat kincir berputar, enam pasak as itu secara bergantian akan mengangkat dan menjatuhkan enam alu kayu besar berpasak. Dengan cara itu, alu akan menumbuk gabah pada ceruk lumpang semen di bawahnya.
"Kalau mau tidur lagi, sana, naik ke para-para." Nenek Poltak menyarankan kedua cucunya untuk tidur lagi. Dia mulai sibuk menumbuk gabah.
Itu saran yang sia-sia. Suasana Losung Aek yang agak mistis membuat Poltak dan Benget tak berani memicingkan mata barang sekejap pun. Gerak nyala sejumlah obor penerang di dinding bangunan lesung menghasilkan tarian bayang-bayang hitam yang kadang bentuknya menyeramkan.
Sudah menjadi rahasia umum, Losung Aek itu dianggap angker. Setiap tahun ada saja yang celaka di situ. Entah itu jari atau telapak tangan pengguna yang remuk ditimpa alu. Atau tangan patah dihajar tuas alu.
"Roh penjaga lesung minta tumbal." Demikian tersiar kepada khalayak, termasuk anak-anak, sebagai penjelasan untuk kejadian-kejadian nahas itu.
"Poltak! Jaga adikmu itu!" Nenek Poltak berteriak mengingatkan, di tengah dentum alu bertalu-talu menghajar ceruk lumpang.
Nenek Poltak harus bekerja dengan presisi tinggi. Menyiduk gabah lepas kulit dari ceruk lumpang perlu ketepatan waktu. Kalau tidak, jari atau telapak tangan bisa ikut lepas kulitnya.
"Bang Poltak, lihat sini! Bagus kali ini!" Benget memanggil Poltak ke beton dudukan as lesung. Poltak mendekat.
"Ini bagus. Berkilau!" kata Benget, sambil jari-jarinya meraba sumbu besi di ujung as lesung yang berputar pada dudukannya. Sumbu besi itu berkilauan diterpa cahaya obor.
Sensasi geli pada ujung jari yang ditimbulkan putaran sumbu besi itu rupanya membuat Benget kecanduan menyentuhnya.
"Jangan, Benget. Bahaya itu!" Poltak berteriak mengingatkan.
Ada rasa cemas di hati Poltak. Sepengetahuannya, tahun ini Losung Aek belum makan tumbal. Harus hati-hati. Jangan sampai jadi korban.
"Bang! Bang Poltak! Tolong! Tolong!" Tiba-tiba Benget menjerit keras, minta tolong.
Poltak tersentak kaget. Spontan merapat, melihat apa yang menimpa adiknya.
Celaka. Benget dalam bahaya besar. Dia menjerit ketakutan. Mukanya pias. (Bersambung)