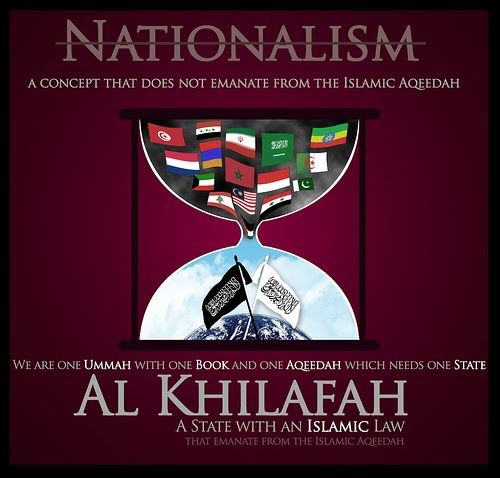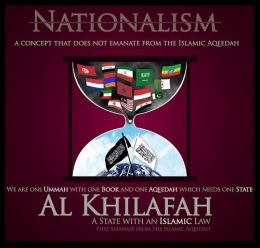Tulisan pendek ini dimaksudkan untuk memberi komentar (counter argument) atas sebuah artikel yang berjudul "BUNGKAM PARA PENGHINA ISLAM DENGAN KHILAFAH !" yang dipublish di kolom website Nusantara News pada hari minggu (15/11/20) lalu. Di dalam artikel tersebut tertuang seruan agitatif untuk bersama-sama memboikot produk Prancis sebagai reaksi umat Islam atas ucapan Presiden Macron yang secara terang mendukung karikatur Nabi Muhammad sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
Berkembangnya deretan kasus penghinaan terhadap Islam, menurut artikel tersebut, adalah disebabkan oleh ideologi dan tata nilai barat (demokrasi-kapitalisme dan sekluar-liberalisme) yang menjangkiti negara-negara Islam juga umat muslim sendiri. Ideologi-ideologi itu dianggap sebagai faktor persoalan utama yang selalu berujung pada penghinaan dan pelecehan terhadap Islam atau simbol-simbol Islam selama ini. Sehingga, khilafah-Islamiyah menjadi satu-satunya sistem yang sesungguhnya sangat dibutuhkan umat Islam bahkan oleh dunia.
Memahami Persoalan
Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat dimuliakan umat Islam. Beliau adalah prototype paling sempurna bagi terminologi yang absolut tentang agama Islam, umat muslim dan al-Qur'an. Sehingga, menjadi wajar jika penghinaan terhadap Nabi menimbulkan reaksi keras dari seluruh umat Islam di dunia.
Tetapi, apapun bentuknya, penghinaan terhadap Nabi sejatinya adalah perbuatan yang tidak berdasar. Karena tidak ada suatu kehinaan apapun pada diri Nabi.
Kontroversi karikatur yang diterbitkan majalah satir Charlie Hebdo beberapa pekan lalu, harus dipahami sebagai 'gambaran mereka terhadap Nabi', bukan 'gambaran Nabi'.
Mereka mengilustrasikan Nabi sebagaimana informasi yang ada di kepala mereka. Di mana hal itu sangat terkait dengan fakta sosiologis bahwa penduduk Prancis adalah mayoritas non-muslim, sehingga sangat mungkin mendapat suguhan artikulasi tentang Islam yang salah. Kedua, keniscayaan oknum atau kelompok yang seringkali tampil serba mengerikan dengan atas nama Islam, tak dapat dipungkiri juga turut menjadi dasar mereka dalam memberi stigma buruk terhadap Islam dan Nabi Muhammad secara general.
Fenomena Prancis dan Macron tersebut, jika kita amati, barangkali terjadi di antara dua faktor: mereka yang minim integritas dan toleransi, atau krisis pengetahuan dan informasi.
Islam menuntut umatnya untuk bersikap bijak dalam menghadapi segala persoalan. Bagiamana sebuah masalah harus diolah dan dipertimbangan secara mendalam meliputi aspek sebab dan akibatnya yang akan ditimbulkan. Mengapa hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana dampaknya.
Ajakan boikot misalnya, yang dimaknai sebagai bagian dari "hukuman", harus dipertimbangkan sematang mungkin. Memboikot artinya menghentikan transaksi dan membatalkan interaksi. Keadaan itu hanya mungkin dilakukan jika "subjek hukum" berada dalam satu suara secara kolektif-kolegial. Bagaimana mungkin? Sementara banyak saudara muslim kita berpenduduk di sana, juga bekerja di perusahanaan-perusahaan mereka.
Jadi itu solusi atau tragedi?
Menggeneralisasi keadaan adalah ciri pikiran yang hampa konsep. Dan berpikir tanpa konsep adalah ciri intelektual yang kacau.
Memancing di Air Keruh
Di dalam teori psikososial, tema-tema tentang ketidakadilan, kesengsaraan dan ketertindasan yang terjadi di dalam sistem sosial selalu menjadi stimulus yang efektif untuk menumbuhkan obsesi perubahan (wave of revolution), mendemonstrasi (demonstrating), dan memobilisasi masa (mobilizing the community).
Keadaan semacam itu, menurut Hamdi Muluk, menjadi ladang subur bagi tumbuh-kembangnya gerakan populisme, baik yang berbasis agama maupun nasionalisme. Fakta degradasi itu selanjutnya akan mendorong psikologis sosial untuk cenderung mencari pegangan pada ideologi yang menawarkan jawaban absolutis: hitam-putih, benar-salah. Sehingga, menjadi masuk akal jika ormas seperti FPI dan HTI, yang berhaluan semacam itu, mendapat atensi besar dari masyarakat karena bias posisi mereka terhadap narasi populisme yang sublim.
Di Indonesia, melalui pembacaan sejarah tentang politik Islam pada era reformasi, Azyumardi Azra mengatakan, meskipun di era Habibi terlihat bagaimana "euforia politik" melahirkan lebih dari empat puluh partai Islam, namun eksistensinya tidak pernah populer di Indonesia. Hal ini, menurut Azra, disebabkan setidaknya oleh dua hal: pertama, karena "Ideologi Islam" dinilai seringkali mengubah perebutan kekuasaan menjadi lebih elemental (pragmatisme politik adalah atribut terpenting dari kebanyakan perilaku pemimpin politik muslim pada umumnya). Kedua, fakta masyarakat muslim Indonesia sesungguhnya lebih menyukai Islam substantif daripada Islam formal, yaitu Islam yang berbasis pada ritual.
Oleh karena itu, ambisi untuk mendirikan khilafah di tengah bangsa majemuk adalah bentuk arogansi sosial yang saat ini justru menjadi distopia masyarakat yang harus disadari bersama.
Segala persoalan dan dinamika kebangsaan sesungguhnya tidak bergantung pada sistem dan bentuk negara yang digunakan; apakah monarki, teokrasi, demokrasi, aristokrasi dan sebagainya.
Tetapi, problem itu sepenuhnya bergantung dan berpusat pada dua hal: antara yang mengatur (government) dan yang diatur (socity governed). Jika keduanya baik, sistem apapun yang digunakan akan tetap menghasilkan kebaikan dan keadilan, sekalipun dengan sistem yang saat ini dianggap sebagai yang paling buruk: totaliter misalnya.
Apakah mereka tidak membaca sejarah secara jujur?
Bahwa seluruh ide tentang bentuk pemerintahan telah selesai diucapkan oleh sejarah. Pro-kontra khilafah akan terus terjadi sebagaimana perpecahan juga terjadi. Negara ini dihuni oleh mayoritas umat muslim. Sementara mereka juga sadar akan banyaknya masyarakat muslim kita yang menentangnya. Bila arogansi merubah negara itu dipertahankan, artinya, mereka menginginkan pertengkaran dengan saudaranya sendiri. Jadi, demi apa sebenarnya agenda khilafah itu?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H