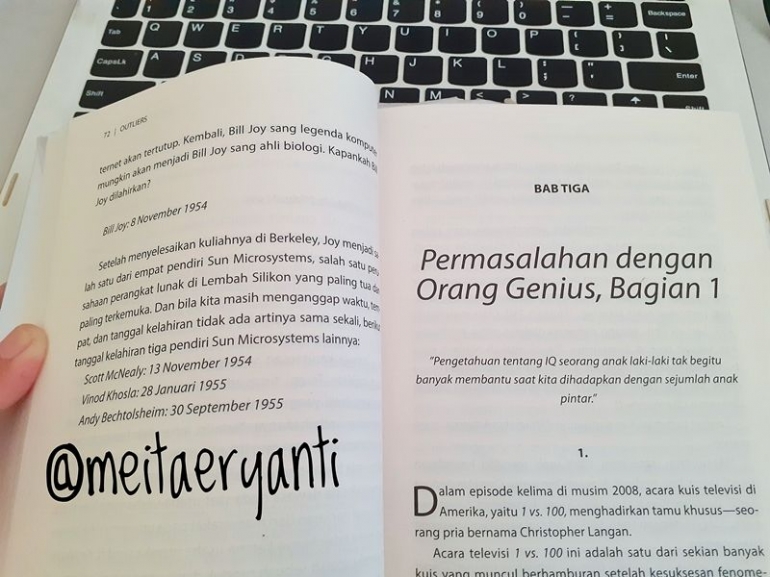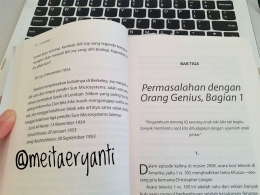Salinan transkip pidato Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja dilantik, di hari guru tanggal 25 November 2019 kemarin mengundang banyak tanggapan dari orang-orang. Terutama menyangkut kemerdekaan belajar dan mengajar. Ada yang mengapresiasi. Ada juga yang mencibir, "memangnya kerepotan birokrasi yang dialami oleh guru-guru itu siapa yang membuat?"
Bukan Pak Nadiem, sih. Namun, kini beliau adalah pimpinan tertinggi dari lembaga yang mengatur segala urusan tentang pendidikan. Sebagai orang yg menghabiskan 12 tahun waktuku untuk bersekolah, aku juga ingin berpendapat. Aku akan memulainya dengan sebuah cerita.
Ini adalah cerita tentang seorang anak genius yang menjalani hidup biasa-biasa saja. Ceritanya bisa dibaca di buku Outliers bab 3 dan 4 yang berjudul "Permasalahan dengan Orang Genius".
Ada seorang jenius bernama Cristopher Langan. IQnya 155. Dengan IQ setinggi itu, seharusnya dia menjadi seorang peraih nobel atau semacamnya. FYI, Einstein memiliki IQ 150. Dia bukanlah sosok yg istimewa. Dia menjalani hidup dengan biasa saja di sebuah peternakan kuda di daerah pinggiran Missouri.
Di sela-sela waktunya, dia membaca buku-buku bagus (saat diwawancara, beliau baru selesai membaca karya ahli bahasa Noam Chomsky) dan menuliskan apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak pernah mempublikasikan sebuah karya, berbicara di sebuah konferensi, atau memimpin sebuah seminar. Semacam ironi yah?
Sejak kecil dia sebenarnya cukup menonjol. Dia sudah mulai berbicara saat usia 6 bulan. Saat usia 3 tahun, dia mengajari dirinya sendiri membaca dengan mendengarkan radio tentang pembacaan komik. Di sekolah, dia bisa membaca buku cetak selama 3 menit dan lulus tes dengan sempurna. Pada usia 16 tahun, dia sudah memahami Principia Mathematica.
Sayangnya, dia menghabiskan masa kecil di tempat yang tidak mendukung bakatnya, termasuk sekolah tempatnya belajar dan gurunya. Dia dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Ibunya bukan orang yang mengerti tentang pendidikan anak dan sibuk untuk mencari uang. Ayahnya sering mabuk dan menghilang. Saking miskinnya dia berkata, "aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang semiskin aku dulu."
Saat kuliah, sebenarnya bisa saja Crist Langan mendapat beasiswa. Sayangnya, ibunya kebingungan dengan persyaratan beasiswa yang diberikan oleh universitas. Karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan, beasiswa untuk Langan diberikan ke orang lain. Crist menyayangkan ketidak pedulian universitas tempatnya berkuliah karena tidak ada konseling atau bimbingan untuknya dan orangtuanya.
Karena masih ingin berkuliah, dia bekerja di perusahaan konstruksi dan tim pemadam kebakaran api kehutanan selama 1 setengah tahun untuk membayar kuliahnya. Sayangnya, ketika Crist mengalami satu masalah dan dia meminta jadwal kuliah paginya dipindah ke sore, dosennya tidak mau memenuhi permintaannya. Akhirnya, dia merasa sakit hati dan berhenti berkuliah. Dia merasa sudah melakukan segalanya untuk bisa berkuliah tapi dia tidak mendapat bantuan apapun dari tempat kuliahnya. Bahkan, seorang dosen kalkulus merasa enggan untuk berdiskusi dengannya.
Crist Langan kemudian menjadi seorang tukang pukul di sebuah bar di Long Island sambil terus belajar filsafat, matematika, dan fisika. Dia mengerjakan sebuah risalah yang disebutnya sebagai Cognitive Theoretic Model of the Universe. Sayangnya, tanpa gelar akademik, risalah yang dibuatnya serasa omong kosong. Dia tidak akan bisa menerbitkannya di jurnal sains.
Aku sakit hati lho mendengar ceritanya. Jika saja sekolahnya mau memberi informasi tentang beasiswa dengan lebih rinci dan mengatakan dengan jelas pada ibu Langan apa yg harus dilakukan supaya Langan tetap bisa mendapat beasiswa, mungkin cerita hidup Langan akan berbeda.