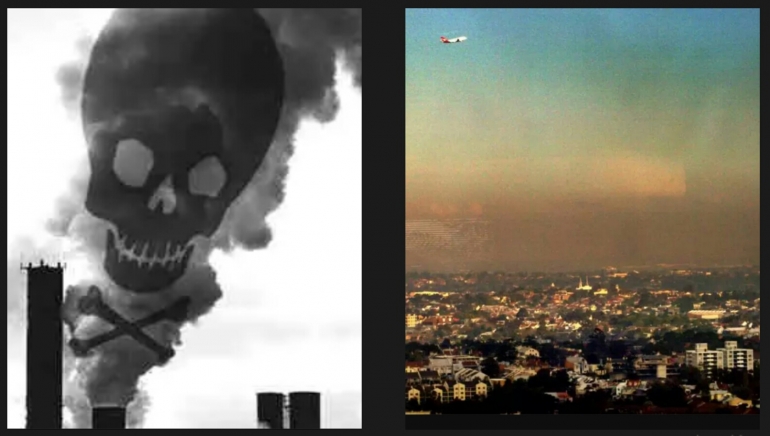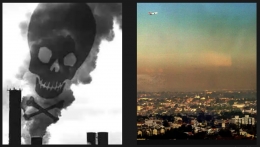Entah kemana hilangnya kebiasaan berembug dan sikap hati-hati yang dulu dimiliki Presiden Jokowi. Beberapa proyek yang telah dimulai sebelum era kepemimpinannya dipercepat dengan kesan tergesa-gesa. Brexit contohnya, setelah mendapat kecaman keras barulah diakui ada beberapa titik lemah yang seharusnya bisa diantisipasi hingga tak muncul korban.
Terkait PLTSa atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Bapak Jokowi menginstruksikan percepatan pembangunannya dengan menerbitkan Perpres Nomor 18 Tahun 2016. Ada 7 daerah yang diharuskan membangun PLTSa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Makasar, Kota Semarang, Kota Surabaya serta Kota Tangerang. Disebutkan dalam Perpres, kepala daerah akan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau menunjuk badan usaha swasta yang mendapat kemudahan untuk memulai konstruksi bersamaan secara paralel dengan pengurusan izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan.
Sungguh mengherankan, bagaimana izin lingkungan begitu disepelekan mengingat PLTSa, khususnya yang berbasis incinerator merupakan teknologi pengolahan sampah yang rentan kebocoran serta menghasilkan abu golongan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sesuai penjelasan Yuyun Ismawati, Senior Advisor Bali Fokus. Tim amdal ITB juga mengemukakan bahwa pembangunan PLTSa akan menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan seperti turunnya kualitas air dan terjadi amblasan tanah (klik di sini).
Sudah sejak awal dicetuskan, sekitar tahun 2009, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak PLTSa. Walhi merupakan organisasi lingkungan hidup independen, non profit terbesar di Indonesia, yang dikunjungi secara khusus oleh Bapak Jokowi pra pilpres. Tak heran, bersama organisasi sipil lainnya yaitu YPBB, ICEL, Bali Fokus, Ecological Observation, Greenpeace Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, dan Gita Pertiwi, Walhi membentuk koalisi untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.
Tentu ada alasan kuat mengapa teknologi pengolahan sampah yang nampak keren, ditolak oleh koalisi pejuang lingkungan. Apa saja?
Bukan teknologi ramah lingkungan
Walau menghasilkan energi terbarukan, PLTSa yang berbasis insinerator bukanlah teknologi ramah lingkungan. PLTSa membutuhkan bahan bakar minyak (energi fosil) dan air bersih untuk operasionalnya. Seperti diketahui cadangan energi fosil kita semakin menipis dan tragedi stress air berada di depan mata.
Energi fosil juga dibutuhkan untuk mengangkut sampah sebagai bahan bakar dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke PLTSa. Sehingga bisa dibayangkan betapa borosnya penggunaan bahan bakar minyak bumi demi operasional PLTSa, sungguh kontradiktif dengan tekad Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang telah dimulai sejak tahun 2004. Dalam konferensi perubahan iklim 2015 di Paris , Indonesia kembali mengemukakan inisiatifnya untuk menurunkan emisi GRK hingga 26 % atas usaha sendiri, dan mencapai 41 % dengan bantuan internasional pada tahun 2020 kelak.
Bukankah amanah yang diemban pak Jokowi tidak hanya sekedar meneruskan proyek yang mangkrak tapi juga komitmen pemerintah Indonesia di skala internasional?
Sampah akan tetap berceceran
Keberadaan PLTSa tidak menjamin sampah tidak berceceran di lokasi penumpukan sampah formal dan non formal, sewaktu sampah diangkat dan ketika warga mengumpulkan sampah di situ. Belum lagi sampah yang dibuang sembarangan di ruang-ruang publik.
Penekanan ini perlu karena tanggung jawab moril warga yang teramat rendah terhadap sampah yang dihasilkannya. Usai sholat Idul Fitri 1437 H yang baru lalu, linimasa dipenuhi netizen yang gusar melihat banyak warga yang meninggalkan sampah kertas alas sholat yang dengan enteng berkata: “Ah, nanti ada pemulung”. Bisa dibayangkan jika kelak PLTSa jadi dibangun, maka mereka akan bilang: “Kan bisa untuk listrik”. Cara ngeles yang teramat khas.
Teknologi mahal yang tidak sebanding
Tanpa tipping fee rupanya badan usaha pengelola PLTSa akan kesulitan. Hasil penjualan listrik tidak sebanding. Contoh paling mutakhir adalah kasus Bantar Gebang. Untuk menjamin kelancaran proses pengolahan sampah DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya tetap membutuhkan tipping fee, hasil penjualan listrik ternyata tidak mencukupi. Tipping fee merupakan biaya pengelolaan sampah yang dibebankan kepada pemerintah daerah sebagai penerima jasa.
Tapi yang paling lucu adalah kasus PLTSa Kota Surakarta yang akan dibangun di TPA Putri Cempo. Karena hanya memproduksi sampah sejumlah 260 ton sementara kapasitas PLTSa yang akan dibangun adalah 1.000 ton maka dirancang 6 kabupaten tetangga untuk mengirim sampahnya ke kota Solo. Sayangnya tetap kurang. Diprediksi sampah terkumpul sebagai bahan baku hanya sekitar 750 ton. Kurang 250 ton.
Membayangkan Kota Solo mendapat kiriman sampah dari daerah lain sudah menyedihkan apalagi menghitung biaya angkut yang dibutuhkan. Ya boros anggaran, ya meningkatkan emisi karbon. Hadeuhhhh …… ^-^
Rawan disabotase
Jakarta pernah mengalami darurat sampah. Bandung juga pernah. Sering malah. Bagaimana rasanya? Asyik kan? Di mana-mana tercium aroma busuk sampah. Tumpukan sampah menjijikkan nampak teronggok di seantero kota. Mulai berlendir , mengeluarkan lindi dan muncul belatung-belatung yang sedang asyik memakan sampah oganik.
Jika PLTSa mulai beroperasi dan ada teroris yang cerdik ingin mengacau keamanan wilayah, dia akan merusak sistem transportasi atau jalannya PLTSa maka niscaya kegaduhanpun akan terjadi. Seisi kota akan panik. Para petinggi negara, anggota DPR dan anggota kabinet akan saling menyalahkan. Terlebih dunia maya, akan terjadi huru hara di lini masa yang lebih riuh dibanding kebakaran hutan.
Mungkin ini pikiran ngaco bin ngawur, tapi percayalah apapun bisa terjadi jika proses pengelolaan sampah dilakukan secara sentral.
Solusinya?
Desentralisasi tentu saja. Tidak hanya ramah lingkungan, murah tapi juga mendewasakan. Semakin sering dan semakin banyak pemerintah mengambil alih tugas warganya, maka rakyat akan semakin manja, mirip anak yang buang sampahpun tak bisa. Contohnya ya seperti kasus pengguna alas sholat di atas. Atau pembuang sampah di jalan umum. Mungkin dia pikir jalan = tempat sampah, atau berpikirpun dia enggan?
Inisiatif pengolahan sampah telah banyak dilakukan warga. Mereka membentuk komunitas-komunitas pengolahan sampah seperti bank sampah, penggunaan biodigester pengolah sampah dapur menjadi gas metan di kompor dan masih banyak lagi. Tidak dapat ditulis secara spesifik di sini karena setiap wilayah mempunyai ciri khasnya masing-masing sehingga mereka bisa memilih cara yang paling tepat dan paling sreg dilakukan.
Seorang kawan yang kebetulan menghuni perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) berkisah bahwa di wilayah ini sudah diberlakukan retribusi sampah secara progresif. Sampah yang diambil petugas harus dalam keadaan terpilah dan jika ada penghuni yang enggan membayar retribusi sampah maka rumahnya akan ditempeli stiker bertuliskan: “Rumah ini tidak berlangganan pengelolaan sampah”. Malu kan?
Bank sampah mungkin sulit dilakukan di BSD, toh sampah anorganik telah diambil petugas yang berasal dari perusahaan swasta yang ditunjuk. Tetapi warga bisa menggunakan biodigester pengolah sampah organik atau memperoleh kompos yang berasal dari hasil penebangan pohon peneduh seperti di kota Nagold, Jerman berikut.

Sumber :
Kompas cetak 15 juli 2016
Sumber foto:
www.unwelcomeguests.net ; stmarysstar.com.au (asap; kota)
Maria N. Petronella (Nagold, jerman)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H