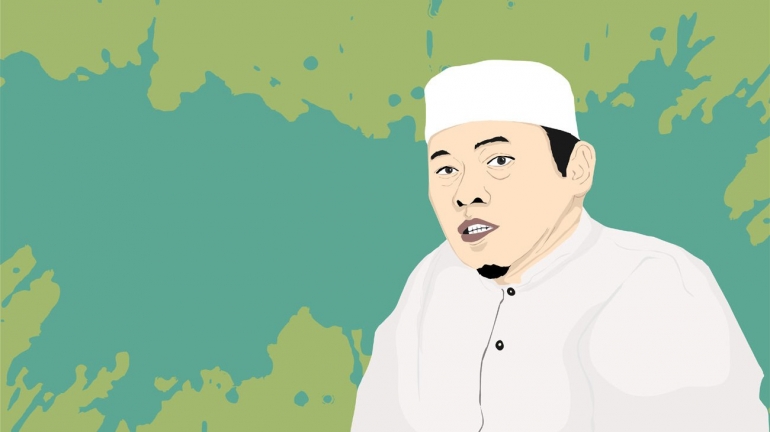Beberapa jam sebelum dilaksanakan aksi unjuk rasa 313 pada tanggal 31 Maret 2017, publik dikejutkan kembali dengan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap lima orang yang diduga akan melakukan makar. Kelima orang itu yakni Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansrah, Veddrik Nugraha alias Dikho, dan Marad Fachri Said alias Andre.
Tiga tersangka, yakni Al Khaththath, Zainudin Arsyad, dan Irwansyah dijerat dengan pelanggaran Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Sedangkan dua tersangka lain, yaitu Veddrik dan Marad dijerat pelanggaran Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Keduanya diduga melakukan penghinaan pada etnis tertentu.
Mereka ditangkap dini hari pada Jumat, 31 Maret 2017 di tempat-tempat yang berbeda. Al-Khaththath dijemput saat sedang menginap di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat sebelum memimpin aksi 313.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, alasan pengangkapan tersebut dikarenakan adanya pertemuan-pertemuan, dalam suatu ruangan tertentu, lebih dari satu orang, kemudian rencana untuk menggulingkan/melengserkan pemerintah yang sah.
Polisi mencurigai adanya rencana menggulingkan pemerintahan dari pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh sebelum aksi 313 berlangsung. Namun, Polisi tidak menjelaskan secara rinci di mana lokasi pertemuan yang dilakukan para tokoh tersebut.
Sehari sebelum melakukan aksi 313, memang sempat dilakukan konferensi pers di Masjid Baiturrahman, Tebet, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers itu, para tokoh menjelaskan mengenai tuntutan dari aksi 313.
Massa 313 menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya karena tengah tersandung kasus dugaan penodaan agama.
Meski menciduk para tokoh tersebut sebelum aksi 313 berlangsung, Polisi membantah bahwa penangkapan itu dimaksudkan untuk menggembosi aksi 313. Penyidik kepolisian telah memiliki alat bukti permulaan terkait dugaan pemufakatan makar sebelum menangkap kelima orang tersebut.
Diduga para tokoh itu akan menggerakkan massa untuk menduduki Gedung DPR/MPR RI. Polisi telah menyita beberapa dokumen terkait dugaan pemufakatan makar dari penangkapan kelima tokoh tersebut. Namun, Polisi enggan menjelaskan secara rinci apa saja dokumen yang dimaksud.
Meski para tokoh penggagas diciduk Polisi sebelum memimpin aksi, massa 313 tetap melaksanakan unjuk rasa di siang harinya. Mereka melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Para perwakilan pengunjuk rasa itu gagal bertemu dengan Jokowi di Istana. Mereka hanya dipertemukan oleh perwakilan pemerintah yaitu Menkopolhukam Wiranto.
Perwakilan massa aksi 313 yang bertemu Wiranto adalah Amien Rais, Usamah Hisyam, Ustadz Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Ustaz Edi, Ustaz Zakir Husain, Abbe Muhambar, dan TB M. Shiddiq. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa menuntut sejumlah hal kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta kriminalisasi terhadap ulama-ulama di Indonesia dihentikan. Mereka menilai, kriminalisasi ulama masih sering terjadi.
Kedua, mereka meminta Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dicopot dari jabatannya karena berstatus sebagai terdakwa dugaan kasus penodaan agama. Massa juga meminta agar Ahok segera ditahan.
Ketiga, mereka mengusulkan agar peraturan daerah bernuansa syariah di semua wilayah Indonesia tidak dibatalkan. Bahkan, massa meminta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dibebaskan.
Menjawab tuntutan dari massa yang meminta Al-Khaththath dibebaskan, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, "Ditahan atau dilepaskannya Sekjen FUI itu bergantung dari hasil pemeriksaan penyidik selama 1x24 jam."
Penangkapan tokoh atau aktivis bukan sekali ini saja dilakukan pada saat Pemerintahan Jokowi.
Sebelum ayam berkokok pada hari Jumat, 2 Desember 2016, 11 orang juga ditangkap pihak kepolisian. Para aktivis itu adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati, Sri Bintang Pamungkas yang diduga terlibat percobaan makar. Jamran dan Rizal dijerat tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), serta Ahmad Dhani dituduh menghina penguasa.
Penyidik kepolisian menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamal, dan Rizal. Sedangkan delapan tersangka lainnya tidak ditahan.
Tudingan ini mengingatkan pada cara rezim Orde Baru dalam membungkam kritik, bahkan sampai menculik para aktivis pro demokrasi 1997-1998 yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.
Desmond Junaidi Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR, pada saat itu mengatakan, “Kalau tuduhan akhirnya tidak terbukti, berarti pemerintahan sekarang ini pemerintahan yang lemah. Pemerintah yang takut dan nakut-nakuti.”
Pada kenyataannya, karena minimnya bukti, tokoh-tokoh yang ditangkap sebelum aksi 212 itu telah dilepaskan.
Apa sih kata makar itu? Mari kita lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam pasal 87 KUHP dinyatakan, "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53."
Jika merujuk pada pasal 87, terlihat bahwa pasal tersebut sebenarnya tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan makar. Pasal 87 hanya mengatur bahwa jika niat telah ada dan telah ada permulaan pelaksanaan, maka telah sempurnalah makar untuk melakukan suatu perbuatan. Namun pertanyaan apa itu makar, tidak terjawab dari pasal 87 ini.
Pasal makar yang menjerat mereka, sejatinya telah melewati berbagai periode zaman yang panjang. Istilah makar berasal dari bahasa Belanda yaitu “aanslag”. Dalam bahasa Belanda, aanslag diartikan sebagai serangan yang bersifat berat (violent attack/fierce attack/onslought).
Istilah makar dapat dipahami sebagai persekongkolan dengan maksud hendak melakukan perbuatan penyerangan terhadap pemerintahan. Sedangkan maksud dari menggulingkan pemerintahan ialah menghancurkan bentuk pemerintahan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan.
Pasal makar sendiri terdapat dalam Buku III Bab I, terkait Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ada beragam rentetannya, mulai dari Pasal 104 KUHP tentang makar terhadap keselamatan presiden dan wakilnya, Pasal 106 KUHP tentang makar kepada wilayah negara, dan Pasal 107 KUHP tentang makar kepada pemerintahan. Sisanya, tiga pasal lain terkait makar yang berhubungan dengan negara sahabat.
AB Loebis dalam bukunya berjudul Apa Itu Kejahatan-Kejahatan Politik menegaskan bahwa tuduhan makar (conspiracy) adalah sulit untuk dibuktikan. Sebab hal tersebut lumrah ditafsirkan oleh masyarakat atau orang awam sebagai alasan yang dicari-cari. Dia juga menganggap bahwa pasal makar sering digunakan penguasa untuk menghukum lawan politiknya. Dengan tegas dia menyatakan, tuduhan makar adalah tuduhan yang samar-samar.
Hal serupa dikatakan oleh Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa. Dia menilai, pasal makar merupakan ketentuan dengan kriteria yang tidak terukur dan multitafsir. Sifat subyektifnya untuk menafsirkan secara karet, berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah. Maka secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Sebab pasal karet tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Kebanyakan pasal ini digunakan untuk memberangus aksi-aksi damai yang tak disukai pemerintah. Misalnya pejuang Filep Karma yang ditahan hanya karena aksi damai meminta Papua Merdeka.
“Itu pasal karet karena selalu mudah diterjemahkan oleh penguasa ataupun aparat terhadap aksi-aksi demokratik ataupun aksi menyampaikan pendapat yang sebetulnya dilindungi undang-undang. Pasal ini bermasalah dan selalu digunakan sebagai alat untuk menghambat kemerdekaan berekspresi ataupun menyampaikan pendapat,” bebernya.
Jika meninjau frasa “dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan” dalam Pasal 107 KUHP, memiliki rumusan atau kriteria yang tidak jelas, tidak terukur dan multitafsir. Ketidakjelasan ini berpotensi digunakan oleh pemerintahan yang berkuasa untuk menekan dan memberangus lawan-lawan politik dan para aktivis pro demokrasi, setidak-tidaknya digunakan untuk menakut-nakuti mereka.
Memang tuduhan makar seringkali menjadi alat untuk melawan orang atau kelompok tertentu yang oleh pemerintah dianggap sebagai ancaman atau musuh. Pasal tersebut pernah digunakan sesuai fungsinya di ranah politik untuk menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang kerusuhan Tragedi 21 Mei 1998. Partai Rakyat Demokratik dituduh memunculkan kegaduhan dan makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Maka dari itu, Budiman Sudjatmiko, yang kala itu menjadi Ketua Umum PRD, ditahan bersama rekan-rekan seperjuangannya.
Pasal makar ini mengebiri hak atas kebebasan untuk menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Melalui aparatur penegak hukum, pemerintah bisa dengan mudah meredamnya. Jika diteruskan, penerapan pasal ini tentu akan mengurangi keterlibatan warga untuk turut serta mengkritisi dan mengontrol agar tercipta pemerintahan yang bersih KKN.
“Makar seharusnya diartikan, sebuah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan. Ketakutan kita, ini justru akan membuat orang-orang takut untuk membicarakan ketidakpuasannya pada pemerintah,” ujarnya.
Materi muatan Pasal 107 KUHP juga tergolong represif. Hal itu lantaran mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang. Di sisi lain, menimbulkan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah yang berkuasa.
Meredam Lawan Politik
Jokowi tadinya banyak didukung oleh aktivis pro-demokrasi karena dianggap tidak akan "main tangkap" para pengkritik. Namun kenyataannya, para pengkritik ditangkapi dengan dugaan makar. Pasal makar pada masa kepemimpinan Jokowi, dijadikan sebagai salah suatu keistimewaan guna memberikan perlindungan yang sangat berlebihan terhadap kepentingan kekuasaan.
Padahal di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, banyak pihak yang menginginkan dia dijatuhkan. Namun, karena hal tersebut hanya sebatas penyampaian ekspresi tanpa unsur penyerangan dan kekerasan, maka SBY tak menghantamnya dengan pasal makar.
“Tidak ada yang dijerat pasal makar aktivis-aktivis yang teriak turunkan SBY, gulingkan SBY. Yang ada hanya klarifikasi atau manuver politik tertentu SBY untuk meredam. Tapi tidak menggunakan institusi kekuasaan atau institusi penegak hukum untuk meredakan itu semua,” tuturnya.
Maka dari itu, Alghiffari mengusulkan agar pasal makar dalam KUHP dihapuskan. Sebab pasal tersebut telah ketinggalan zaman (kuno). Negara demokrasi haruslah menghormati prinsip-prinsip supremasi hukum dan HAM. Kalaupun tidak ingin dihapuskan, DPR harus berhati-hati dalam merevisi KUHP, khususnya terkait pasal makar.
“Seharusnya DPR merumuskan pembeda dengan betul-betul, mana yang merupakan makar dengan kekerasan, mana yang hanya sekedar menyampaikan ekspresi, misalnya mengibarkan bendera ataupun berujar hal-hal yang menunjukkan ketidakpuasan pada pemerintah. Itu harus dihapus dari KUHP ketentuan pidana seperti itu. Tapi DPR harus mempertegas bahwa tindakan makar adalah tindakan dengan kekerasan melakukan penyerangan untuk menggulingkan pemerintah,” jelasnya.
Delik makar dalam KUHP memang mengandung unsur dari Undang-Undang subversif. Maka dari itu, jalur lain untuk mengubahnya ialah melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini yang mendorong Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) pada tanggal 16 Desember 2016, setelah aksi penangkapan aktivis dalam demo 212, kemudian melayangkan uji materi pasal makar ke Mahkamah Konstitusi (MK). ICJR meminta tafsir definisi “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
ICJR beralasan, ada perbedaan definisi makar dalam KUHP terjemahan bahasa Indonesia dan KUHP (asli) versi Belanda yang mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan pasal-pasal tindak pidana makar dalam praktik peradilan pidana. Sebab, merujuk Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), istilah makar disebut aanslag yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “serangan”.
Menurut Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus A. T. Napitupulu, kata aanslag yang diterjemahkan sebagai makar tidaklah tepat. Makna keduanya dalam konteks bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Kata aanslag jika diterjemahkan lebih tepat diartikan sebagai “serangan”. Hal ini berakibat ketujuh pasal tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan dan tujuan (asas legalitas) yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap delik makar.
Erasmus mengatakan, “Ketika aanslag diterjemahkan menjadi makar terjadi pergeseran makna. Ini dikarenakan karena istilah makar dalam KUHP adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti "penghianatan". Akhirnya pasal makar dalam KUHP juga dimaknai secara sederhana berupa penghianatan."
Bagi ICJR, pengertian makar sendiri diartikan sebagai sifat dari suatu perbuatan. Seperti, makar menggulingkan pemerintahan yang sah, makar untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia, makar membunuh Presiden dan Wakil Presiden. Dengan begitu, apabila makar diartikan sebagai serangan mesti memenuhi unsur adanya serangan dalam konteks tindakan kekerasan.
Atas dasar itu, ICJR meminta agar kata “makar” dalam Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama seperti aanslag atau serangan. Ini penting supaya aparat penegak hukum memiliki indikator yang jelas untuk membedakan mana yang benar-benar makar dan mana yang bukan.
Erasmus menambahkan bahwa selama ini, beberapa kasus delik makar memiliki karakteristik yang sama. Baik jaksa maupun hakim tidak menjelaskan unsur makar sebagai serangan. Seperti, kasus Sehu Blesman dalam putusan MA No. 574 K/Pid/2012, dan kasus Semuel Waileruny dalam putusan MA No. 1827 K/Pid/2007. Keduanya divonis 5 tahun dan 3 tahun penjara karena terbukti makar, memiliki niat memisahkan diri dari Indonesia hanya karena merayakan kemerdekaan Papua Barat dan hendak mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS).
Akan sangat berbahaya jika masyarakat atau mahasiswa demo yang meneriakkan orasi, "Turunkan presiden!" bisa disebut makar. Kualitas penyampaian harapan, permintaan dan tuntutan para demonstran tidak boleh sekadar dilihat dari ungkapan kata-kata. Tetapi juga apakah demonstrasi akan dilakukan secara terpimpin, terkontrol, tertib, aman, dan damai.
Demontrasi merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam menyampaikan ekspresi hak kodrati manusia baik pikiran dan perkataan. Demonstrasi juga merupakan salah satu sarana memperjuangkan keadilan di tengah rendahnya kejujuran atau fair trial dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Tatanan demokrasi akan rusak jika pikiran kritis pada pemerintah dimaknai sebagai upaya makar.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI