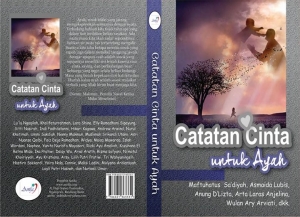Ting…Ting…Ting…
Pooor…Campoooor…Campoooooor…!
***
Suara itu mengingatkanku pada seseorang.
Dentingan suara oleh pukulan sendok pada dinding mangkuk. Disusul suara seseorang dengan sedikit berteriak. Otot-otot lehernya pun terlihat saat dia semakin menaikkan suara. Memanggil orang-orang agar menghampiri. Tak jerah, peluhpun menemani setiap ayunan langkahnya. Kendati mendorong gerobak kayu berisikan lontong, perkedel singkong, tahu goreng, selada, tauge, mie kuning, semangkuk petis, sambal, satu panci kuah, dan irisan daging sapi.
Suara itu semakin dekat.
Seperti eufoni yang senantiasa menemani lelaki paruh baya itu tatkala senja mulai menyentuh kanvas langit. Sedang langkah kecil menjadi pensil yang melukis (kembali) garis takdirnya. Melangkah dan melangkah. Hingga waktu menutup pintu yang malam. Barulah dia mengizinkan tubuhnya untuk merebah.
Aku ingat saat itu.
Saat pertama kali kaki menginjak di pelataran tanah yang begitu lembab. Beratapkan genting usang tersusun renggang hingga air hujan pun kerap kali menyusup ke dalamnya. Dinding anyaman bambu yang tak lagi tegak menjadi pembatas antara kontrakan dan sang pemilik kontrakan. Sebuah sumur dengan kedalaman 4 meter disertaikolam mandi yang kecil lagi berlumut, menjadi tempat antrean sepuluh penghuni rumah itu.
Tatapanku nanar ketika melihatnya kali pertama. Sepuluh orang menyewa kontrakan dalam satu rumah yang sama. Tidak ada tempat tidur, lemari, meja, kursi, bahkan bantal sekalipun. Hanya tampak seperti ruang dapur yang serbaguna. Dapur yang untuk memasak, tidur, sholat, tempat berkumpul, bahkan gerobak pun masuk di dalamnya.
Hanya ada tikar plastik sebagai alas tidur mereka, termasuk lelaki separuh baya itu. Tidur berbantal dingklek (kursi kecil yang terbuat dari kayu). Tidur di samping gerobak dan kompor masing-masing. Bohlam remang-remang. Tikus setiap waktu berkeliaran di sekitar. Baju-baju berseliweran di tali rafia yang dikaitkan antara satu tiang dengan tiang lainnya. Membawa ponselpun harus sembunyi-sembunyi. Men-charger-nya saat kulakan di pasar. Karena pemilik kontrakan tidak mengizinkan.
Aku menahan embun di pelupuk mata.
Kubandingkan saat aku dan lelaki separuh baya itu masih sama-sama berada di satu kota. Aku yang saat itu kuliah dan tinggal di asrama dengan berbagai fasilitas lengkap. Tempat tidur empuk, lemari mulus, meja-kursi bagus, kamar mandi bersih, berdinding tembok kokoh, beralas keramik mengkilat, beratap plafon putih, dan masih banyak lagi. Sedangkan dia? Fasilitas yang amat dan sangat terbatas. Tidur tak bisa nyenyak. Penghasilan pun tidak seberapa. Namun, dia tak pernah mengeluh ataupun putus asa dalam menjalani skenario takdir. Justru dia mengajarkan kami agar selalu bersyukur.
“Sekecil apapun pemberian Allah, kita harus mensyukurinya, Nduk. Terlebih karunia sehat. Karena dengan sehat, kita dapat belajar, bekerja, dan beribadah.” Ujarnya suatu ketika.
Tiga puluh tahun telah terhitung jejak-jejak perjuangannya di bumi rantau. Demi tanggung jawabnya terhadap istri serta anak-anaknya. Tak peduli panas ataupun hujan. Dia tetap berjalan dan menerobosnya seraya mendorong gerobak di sepanjang jalan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Atas jerih payah serta kucuran peluhnya, kini kami (anak-anaknya) bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
Dan, suara itu kini terhenti oleh panggilanku.
“Beli berapa, Mbak?”
“Dua mangkuk.”
Kutahu, eufoni itupun menemani awal senjamu kini. Semoga dengan aku membeli Tahu Campur di sini, akan ada puluhan orang yang membeli Tahu Campurmu di sana. Bapak, maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu. Izinkan aku mencintaimu karena Allah.
Lamongan, 09 Agustus 2014
(Based On True Story)
*Tulisan ini dibukukan dalam antologi “Catatan Cinta Untuk Ayah” oleh Penerbit Asrifa
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H