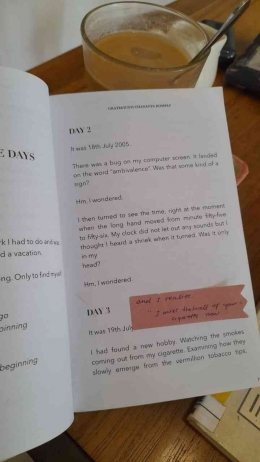Dari patjar merah pula saya berhasil mengajak seorang teman yang dulu hanya menggeluti dunia desain dan ilustrasi, menjadi gemar pula membaca buku, meski prosesnya mungkin tidak sebentar. Saya merasa telah berhasil menularkan apa yang selama ini hanya menjadi dunia saya, pada orang yang benar-benar baru menapakkan kaki pada buku. Bahwa kita tak akan pernah bisa lepas dari teks, itulah yang ingin saya tularkan, karena apapun produk karyanya, pasti berangkat dari teks. Lukisan hebat harus mampu menceritakan apa yang ada di pikiran pelukis, dan meski tidak semua pelukis akan menerjemahkan maksudnya, setidaknya dalam pameran-pameran penjelasan tersebut akan dituliskan lewat teks.
Tulisan ini benar-benar murni saya tulis dengan sukarela, tanpa bermaksud mempromosikan patjar merah kepada siapa pun teman-teman yang membaca. Namun, saya sangat ingin berterima kasih pada sosok Windy Ariestanty, yang menginisiasi festival literasi kecil ini, dan sampai sekarang konsisten berkeliling untuk menghadirkan buku pada teman-teman yang cinta literasi.
Kerennya, patjar merah pun hadir tidak terbatas pada buku. Ia terus berupaya untuk relevan dengan menghadirkan pula musisi, penulis-penulis kekinian, pegiat media sosial, influencer, pembuat karya audio visual, dan masih banyak lagi. Jadi meskipun tema utamanya adalah buku, tetapi buku tidak hadir secara eksklusif. Buku ditemani dengan medium-medium lain yang menguatkannya untuk jadi tetap relevan, menepis segala data dan penghakiman dari dunia yang terlanjur menasbihkan Indonesia sebagai negara yang tidak literat, negara yang tidak mencintai buku.
Buku-buku yang hidup dalam Perpustakaan Independen
Tak hanya patjar merah, ruang-ruang komunal yang merawat kecintaan pada buku terus hidup dalam perpustakaan independen, yang menyediakan buku-buku klasik, atau zine, dan konsisten mengadakan kumpul-kumpul buku yang mengajak buku agar tidak menjadi kaku. Buku seperti dihadirkan di meja makan sebagai menu utama yang lezat, setelah sebelumnya dihidangkan makanan pembuka, juga penutup yang menjadikannya semakin lengkap.
Saya akan menyebut dua ruang baca yang pernah saya datangi, dan memberikan memori cukup membekas tentang buku. Pertama, Kineruku di Bandung, dan C20 di Surabaya.
Saya akan menceritakan tentang Kineruku terlebih dahulu. Sebuah ruang baca yang sejuk dan terpencil di Hergamanah, yang selalu menguarkan rasa rindu saya akan Bandung, saksi hidup dunia perkuliahan yang akhirnya menyeret saya lebih dalam lagi pada buku, puisi, musik, film, dan hal-hal menyenangkan yang timbul dan memberi kekuatan pada saya untuk tetap konsisten bekerja di bidang-bidang ini.
Sejauh yang saya tahu, di tahun 2009 band Efek Rumah Kaca pernah tampil nge-gig di Kineruku membawakan lagu Balerina. Cek saja di Youtube, masih ada. Kineruku memang meminjamkan dan menjual buku, tapi tidak berhenti di situ saja. Ia juga menjual kaset piringan hitam, punya ruang sendiri dimana kita bisa melihat-lihat souvenir antik, dan oh, betapa kopinya juga enak.
Maka saya tidak setuju jika toko buku harus berdiri secara eksklusif untuk menjual buku, karena memang mungkin inilah cara mereka untuk tetap bertahan.
Di Kineruku, saya membaca trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dengan tenang, perlahan, dan selesai. Sampai saat ini, tokoh Srintil dan Rasus selalu saya nobatkan sebagai dua tokoh favorit saya dari penulis Ahmad Tohari. Betapa dia bisa menulis dengan begitu runut, berdasarkan pengalaman sejarah tetapi juga penuh dengan nasihat-nasihat khas masyarakat desa yang bijaksana.