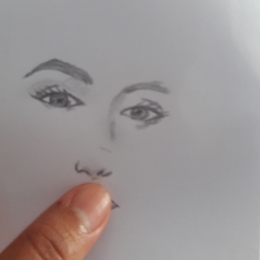"Siapa ayahnya?"
Entah sudah berapa kali kata itu muncul di kepala. Cuma dua kata, tapi rasanya seperti hantu atau mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ingin sekali lepas dari bayang-bayang itu, tapi itu tidak mungkin. Nasi sudah menjadi bubur.
Tiap hari Marni sibuk membolak-balik lembar kalender di meja kamarnya, seperti saat ini. Matanya tidak mau beralih dari tanda silang merah, yang penuh di tiga lembar lalu. Rasa di hatinya bergemuruh. Keringat dingin tiba-tiba penuh di wajah dan tangannya. "Bagaimana kalau dia tahu? Dia pasti akan marah besar," gumamnya. Batinnya diamuk gelisah.
Dia lempar kalender itu, jauh mengenai koper hitam besar di pojok kamar. Dadanya sesak, air mata jatuh dari ujung kelompak matanya. Tiba-tiba pintu kamar di gedor kuat. Seorang wanita berteriak memanggil namanya di luar sana.
"Kenapa sih, teriak-teriak, Mbak?" seru wanita hitam manis itu setelah membuka pintu. Suaranya masih terisak. Sisa air mata masih membekas di pipi.
"Tuh, taksinya udah datang. Lagian ngapain sih, nangis terus. Percuma tahu enggak." Mira membuang muka, meninggalkan kamar Marni.
Sebenarnya mereka saudara sekaligus sahabat, tapi itu dulu. Sebelum Marni memutuskan untuk kabur dari rumah majikannya. Miralah yang mencarikan tempat kos, bahkan kerjaan baru untuk dia. Namun, kebaikan tak selamanya berbuah manis. Marni mencoreng kepercayaan sahabatnya. Dia hamil dan tidak tahu di mana lelaki bejat itu berada sekarang. Menyembunyikannya sebagai TKI kaburan sudah penuh resiko. Dia tambah lagi dosa yang menyakiti hati adik Mira, suami Marni.
Selang beberapa menit, Marni keluar dengan koper dan tas digendongannya. Wajahnya terus menunduk. Percecokan semalam sudah cukup membuatnya malu dan bersalah. "Mbak maafin saya, saya pamit," ujar Marni mengulurkan tangan kanannya.
Namun, di luar dugaan, Mira justru menepis tangan Marni, "Enggak usah sok baik. Kamu mending mikirin, gimana supaya adik saya mau berbaik hati sama kamu. Tapi saya enggak yakin dia akan maafin kamu." Nada benci sangat terasa di suara Mira.
Sementara mulut Marni terkunci. Tak ada kata yang cocok untuk membela diri. Kata-kata Mira adalah tamparan keras yang buat dia sadar, dirinya tidak pantas untuk dihargai. Akhirnya dia berlalu menghampiri taksi yang sudah menunggu lama dan mereka pun melesat menuju bandara.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih empat jam dari Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan, Marni tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, kemudian transit ke Bandara Raden Intan selama setengah jam.
Pandangan Marni menyapu tiap sudut ruang tunggu penjemputan. Dia amati satu per satu wajah orang-orang di sana. Namun, kenyataan lagi-lagi menorehkan luka. Tak ada seorang pun dari keluarganya datang. Dia kembali tertunduk lesu. Mengusap perut yang telah ditempati buah hasil perbuatannya.
Dua hari lalu, seharian menanti dering ponsel yang tak kunjung berbunyi. Berulang kali dia membuka pesan yang telah terkirim lima jam lalu. Ruang chat itu masih sama. Kosong. Hanya sederet pesan darinya tanpa satu balasan pun.
"Maafkan aku, Mas," suaranya lirih. Sejurus kemudian dia melangkah ke parkiran dengan sisa kekuatan yang dia punya.
Tidak lama, sebuah taksi menghampiri. Marni pun naik. Sesak di dada tak lagi dapat tertahan. Bulir-bulir bening jatuh dari sudut matanya. Mengiringi waktu menuju lelaki yang telah sah menikahinya.
***
"Jadi begitu ceritanya, Ndok," ujar Laila. Bola matanya berkaca-kaca.
"Jadi Marni itu .... Terus, akhirnya gimana, Bu. Suami Ibu Marni apa mau menerima dia lagi?"
Laila menghela napas berat. Dia menerawang jauh ke masa beberapa tahun lalu. "Sudahlah, Ndok. Yang penting kamu sudah tidak penasaran siapa kamu. Jangan dengarkan orang-orang di luar sana. Ambil hikmah dari ini semua."
Seketika Rahma jatuh ke pelukan Laila. Pipinya bahas. Dadanya sesak. Langit cerah tak mampu menutupi mendung di hatinya. Kenyataan telah menjadi pukulan besar. Gadis hitam manis itu memberi kecupan di pipi kanan Laila, beralih ke pipi kiri, kening, kemudian dia rangkulkan kedua tangannya ke pundak Laila. Dia berbisik, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah ikhlas merawat Rahma seperti anak sendiri."
Disaksikan sepiring pisang goreng yang sudah dingin, Rahma mengucap janji. Tak akan ada dengki untuk orangtuanya. Seburuk apapun ibu, tetaplah harus dihormati, sejahat apapun ayah, dialah sebab dia hadir di dunia. Takdir telah mengantarnya ke keluarga Laila. Rumah penuh cinta dan kasih sayang.
"Besok kita ziarah ke makam ibu kamu, ya, Ndok?" ujar Laila mengusap pundak anaknya.
Langit bermega menghentikan dua obrolan hati. Semeribit angin mengguncang batang-batang bambu, membawa dingin sampai ke kulit. Mereka pun beranjak dari kursi bambu di bawah pohon rambutan. Meninggalkan tiap luka di sana. Kini, puing-puing masa lalu orangtua, dia lipat dan album kenangan yang indah. Beribu lantunan syukur melangit dari bibir ranum Rahma.
Hong Kong, 18 November 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H