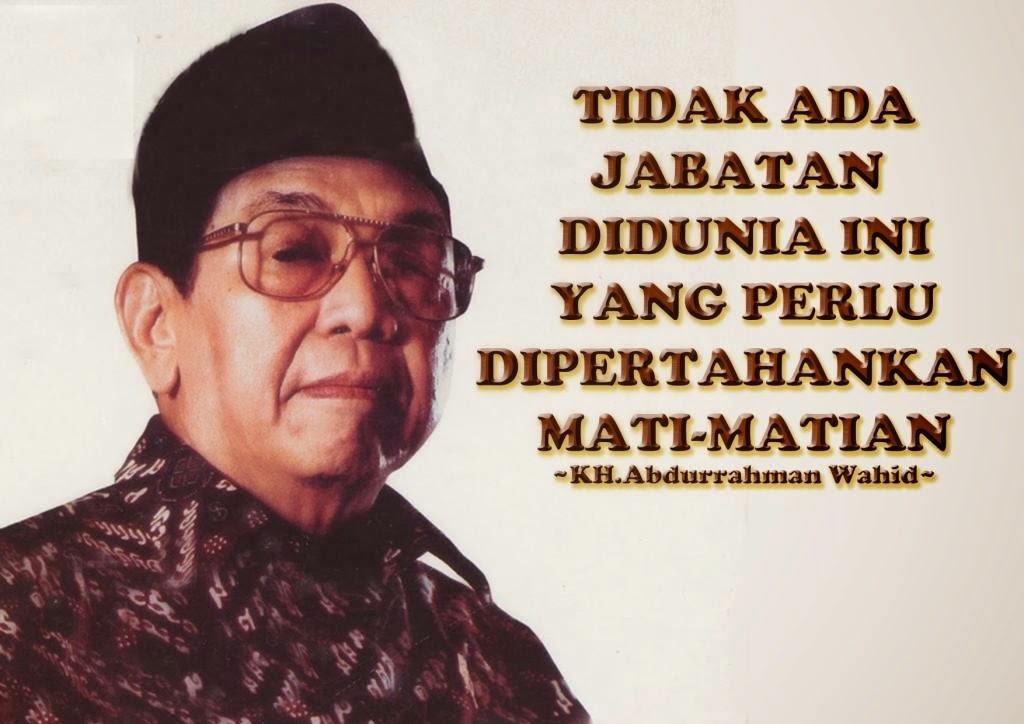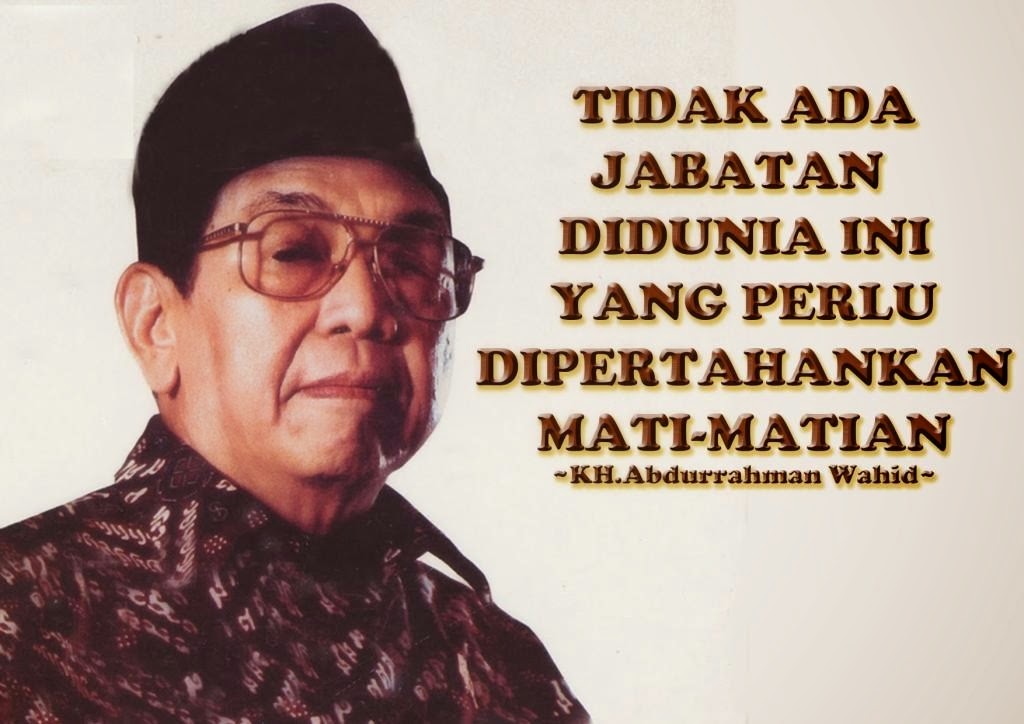[caption caption="ilustrasi: biografiku.com"][/caption]Berawal ketika Soeharto menjalankan rezim, poros kekuasaan Soekarno dihancurleburkan. Gerakan yang berbau sosialis dibubarkan agar tidak berkembang. Dan, propaganda anti terhadap komunisme dan marxisme terus-menerus digelorakan di tengah-tengah masyarakat. Semua itu demi satu masa yang disebut orde baru, orde kapitalisme.
Peristiwa pembumihangusan PKI yang menelan banyak korban orang Jawa dan Tionghoa hanyalah sepenggal kisah pengantar dari perubahan politik secara massif. Fasisme rezim Soeharto menggantikan paradigma sosial demokratis ala Soekarno. Kekuatan militer dipakai untuk meruntuhkan pilar-pilar NASAKOM.
Padahal, gagasan NASAKOM Soekarno merupakan strategi untuk membendung efek Perang Dingin dimana ada perebutan kepentingan internasional antara negara-negara komunis dan kapitalis sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Selain itu, Soekarno ingin menjaga stabilitas politik nasional dari kelompok-kelompok nasionalis, komunis, dan Islam. Sistem demokrasi parlementer waktu itu dinilai gagal dan tidak sesuai dengan keadaan alami Indonesia yang memiliki ketiga unsur kelompok tersebut.
Setelah Soeharto berkuasa, kepentingan nasional Indonesia bergeser ke negara-negara kapitalis. Ia tidak melanjutkan konflik “Ganyang Malaysia” yang terjadi pada masa Soekarno. Malaysia adalah negara persemakmuran Inggris dan dianggap antek neo-kolonialis atau imperialis di Asia Tenggara. Akibatnya, tragedi Mangkok Merah di Kalimantan Barat dan pemberantasan Paraku-PGRS tahun 1967.
Kemudian, asing mulai masuk dan menancapkan cakar kapitalismenya di nusantara. Meskipun kaum Tionghoa menjadi korban peralihan rezim Soeharto, mereka mendapat tempat istimewa di serambi perekonomian nasional. Tetapi, kaum Tionghoa dijauhkan dari dapur politik kekuasaan.
Gaya pemerintahan orde baru tak ubahnya pada masa penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda membagi masyarakat kedalam golongan eropa, timur asing, dan golongan Indonesia (bumiputera). Para bumiputera atau pribumi tidak memperoleh hak dan kemudahan dalam kegiatan perekonomian.
Tatanan sosial yang penuh ketimpangan itu menyimpan kecemburuan dari lapisan masyarakat pribumi yang merasa jauh dari kesejahteraan. Roda pembangunan nasional yang diprakarsai oleh Soeharto menciptakan kesenjangan lebar antara si kaya dan miskin. Mereka, asing dan aseng adalah penikmat terbesar kue pembangunan.
Ketimpangan sosial ibarat bom waktu yang suatu saat akan meledak. Karena itu, kecemburuan yang terpendam membuncah seketika dalam tragedi 1998. Pengusaha Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Pembakaran dan penjarahan berlangsung di berbagai kota, seperti Solo dan Jakarta. Soeharto akhirnya lengser. Siapapun dalang di balik tragedi kemanusiaan itu tidak menutup persoalan nyata tentang ketidakadilan yang dialami masyarakat.
Apabila masing-masing mengakui dirinya sebagai bagian dari nusantara, sebagai rakyat Indonesia, istilah pribumi dan non-pribumi tidak perlu diwacanakan. Namun, masih ada kelompok kepentingan yang menunggangi kekuasaan dengan rasisme. Kelompok itu tidak muncul terang-terangan di hadapan publik. Mereka belajar bahwa sentimen mayoritas tidak laku jual. Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014 mengirimkan pesan supaya mereka mencari strategi lain, yakni isu pro-minoritas.
Mereka diam-diam merencanakan infiltrasi sejak Pilkada DKI 2012. Ini akibat pragmatisme Prabowo yang membawa kucing kampung ke Jakarta. Prabowo tak mengira si kucing berubah jadi macan kota. Ia lupa bahwa orang yang dibawanya itu bukan Soe Hok Gie. Alhasil, si kucing menarik simpati kawanannya untuk berjibaku dalam kancah politik. Sebab, mereka hanya mampu mengais kekayaan di zaman Soeharto.
Dengan perkembangan pola pemikiran masyarakat awam dan terpelajar, isu minoritas menuai perhatian yang besar. Mereka akan mengecam model propaganda SARA yang ditujukan untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Layaknya sinetron, lakon yang teraniaya mengambil hati pemirsa. Propaganda itu melukai kebhinnekaan, sehingga simpati mereka membuahkan dukungan kepada pihak yang terdiskriminasi.
Ternyata, model penarikan simpati kepada kelompok minoritas juga terjadi menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Propaganda pro-minoritas dikerahkan dengan beragam cara walaupun baru sebatas di lingkup media sosial. Opini publik coba dialihkan pada pertentangan SARA, lepas dari argumentasi logis yang mensyaratkan penalaran kritis. Inilah yang saya sebut sentimen melawan akal sehat.
Uniknya, isu pro-minoritas tidak dihembuskan oleh partai politik. Seandainya parpol ingin memainkan isu SARA, isu mayoritas yang akan dihembuskan kepada kader-kadernya. Toh, belum ada partai dakwah yang resmi mengusung calonnya. Jika parpol golongan nasionalis melakukannya, tidak perlu sembunyi-sembunyi karena memang banyak kelompok minoritas yang bernaung didalamnya. Lalu, siapa?
Untuk itu, saya mengamati isu minoritas yang akhir-akhir ini mengemuka dan mendapati isu semakin santer setelah Ahok menyatakan diri untuk menempuh jalur independen. Tak dipungkiri, pendukung Ahok sedang berkejaran dengan waktu. Mereka apes harus mengulang perolehan fotokopi KTP dari warga Jakarta akibat kesalahan surat formulir dukungan sebelumnya.
Tampak begitu ngototnya Teman Ahok berniat mengusung Ahok. Di situs mereka TemanAhok.com, digambarkan sepak terjang mereka menyerupai semangat para pemuda dalam peristiwa Rengasdengklok. Fakta Sejarah digunakan sebagai kamuflase gerakan lewat jalur independen yang esensinya sekedar mempertahankan Ahok menjabat gubernur. Ada apa sesungguhnya di belakang mereka, konglomerasi kapitalis?.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI