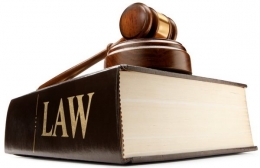Seorang pemikir Prancis, Jacques Derrida menulis bukunya berjudul Force of Law: The Mystical Foundation of Authority. Buku ini pada dasarnya berbicara mengenai tiga hal, yakni keadilan, hukum, dan kekerasan. Tiga hal ini dikelola dan dianalisis secara kritis menggunakan istilah penting Derrida, yakni dekonstruksi.
Dekonstruksi Derrida bergerak untuk memecahkan paradoks mengenai hukum. Ketika membaca teks Derrida mengenai Force of Law, pertanyaan yang muncul adalah "Bagaimana kita dapat membedakan antara penegakan hukum yang adil maupun yang tidak adil? Bagaimana kita melihat otoritas kekuasaan yang menopang berdirinya hukum, dengan kekerasan dan karakter memaksa yang menyertainya?"
Kata to enforce the law dalam bahasa Prancis -- appliquer la loi -- dapat berarti penetapan, penegakan, penerapan atau kekerasan yang diotorisasi (law is authorized force). Dalam upaya mencapai sebuah keadilan, hukum harus ditegakkan. Keadilan hukum didukung oleh kekuatan-kekuatan lain yang mendasari lahirnya hukum itu sendiri. Di balik momen berdirinya hukum, ada begitu banyak ketimpangan yang terjadi.
Dengan kata lain, pengaruh kepentingan dan berbagai orientasi personal atau kelompok ikut diselipkan ke dalam pembentukan hukum. Misalkan di Indonesia, DPR pernah berusaha mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arah dan tujuan revisi UU KPK belum jelas. Revisi UU KPK diusulkan masuk prolegnas 2015.
Isi revisi UU KPK ini, antara lain memperlihatkan bahwa KPK hanya eksis dalam jangka waktu 12 tahun dari dikeluarkannya draf UU tersebut. Usulan pembatasan usia KPK tertuang dalam pasal 5 Rancangan UU Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat pleno badan legislasi, Selasa (6/10/2015), di Jakarta.
Dalam draf revisi UU ini juga disebutkan bahwa KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua Pengadilan Negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar dan tak boleh melakukan penuntutan. Usulan ini menjadi prioritas prolegnas 2016 yang ditetapkan DPR.
Usulan ini datang dari enam fraksi, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP dan PKB. Pengajar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mencurigai upaya revisi UU KPK dengan membatasi usianya merupakan bagian dari pelemahan secara langsung terhadap upaya pemberantasan korupsi. Janji presiden untuk memperkuat KPK, dalam hal ini, dipertanyakan. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji, mengatakan bahwa KPK sudah bagus, dan yang boleh direvisi adalah terkait pengawas di luar struktur internal KPK.
Revisi UU ini juga merupakan bentuk kesalahpahaman atas arti kata ad hoc lembaga KPK. Pemahaman ad hoc tidak dapat didasari atas waktu berlakunya, melainkan kondisi yang menentukan hal tersebut (Kompas, 7/10/2015).
Kata to enforce the law, sejatinya memuat dua elemen yang membuat hukum dipertanyakan, yakni kata force (daya, kekuatan, paksaan) dan implikasi yang tidak kelihatan dari bentuk pemaksaan yang dipayungi hukum itu sendiri, yaitu violence (kekerasan). Dua implikasi kata to enforce the law membuat makna keadilan dikarantina. Ketika hukum menerapkan prinsip memaksa, kekerasan justru hadir membayangi dengan karakter ketaatan.
To enforce sebagai bentuk Pemaksaan
To enforce dapat diartikan sebagai penegakan hukum. Kata "penegakan hukum" adalah suatu keharusan dalam ilmu hukum. Alih-alih untuk mencapai keadilan, hukum harus ditegakkan. Pada momen "penegakan hukum", ada suatu tindakan penetapan yang menguatkan pernyataan ini, yakni legitimasi (pengesahan).
Hukum mulai diberlakukan setelah dipromulgasikan atau disahkan. Lalu, pertanyaannya adalah "Siapa yang berhak menetapkan hukum?" Di Indonesia, mereka yang menetapkan hukum adalah parlemen. Parlemen diberi kepercayaan untuk menetapkan hukum (fungsi legislasi).
Akan tetapi, proses penetapan hukum selalu bersentuhan dengan politik. Parlemen sebagai industri hukum, tidak lagi berdiri sendiri, namun cenderung "bermain mata" dengan politik. Perselingkuhan antara politik dan hukum, kadang-kadang melahirkan produk hukum yang intensional. Sebagai contoh di Indonesia, DPR pernah mengesahkan UU Pornografi, Pasal Kretek, UU Kebudayaan, UU KPK, yang sarat kepentingan dan selalu bertentangan dengan kepentingan publik.
Hukum pada dasarnya adalah produk dari kekuasaan. Di berbagai negara -- terutama negara demokrasi -- dibuat pembagian kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif (Presiden), legislatif (DPR) dan yudikatif (pengadilan). Ketiga lembaga ini beroperasi melalui kekuasaan. Parlemen sebagai kekuasaan yang membentuk hukum, seringkali menelurkan produk hukum yang bermasalah.
Hukum sebagai produk kekuasaan bukan tanpa kepentingan, karena klausal hukum normatif justru ditunggangi oleh kepentingan dan asumsi-asumsi politik. Agar produk hukum yang ditunggangi kepentingan bisa dipromulgasikan, maka hukum perlu ditegakkan (law must be enforced). Setiap warga negara akhirnya "dipaksa" untuk menaati hukum yang notabene syarat kepentingan.
Pemaksaan pengaplikasian pasal-pasal atau undang-undang bertujuan agar hukum dapat ditegakkan. Dalam hal ini, aspek legislasi (pengesahan atau dukungan dari publik) tidak lagi diperhatikan. Ketika hukum mendapat pengakuan oleh karena paksaan (have to, must, ought to), maka segala sesuatu dimungkinkan. Menurut Immanuel Kant, tidak ada hukum tanpa paksaan (no law without force).
Penerapan atau penegakan hukum bukanlah suatu kemungkinan kedua yang ditambahkan sebagai suplemen. Dalam bukunya Force of Law, Derrida menulis demikian: "Applicability, "enforceability," is not an exterior or secondary possibility that may or may not be added as a supplement to law. It is the force essentially implied in the very concept of justice as law, of justice as it becomes law of the law as law" [Prancis: de la loi en tant que droit].
Artinya, hukum membawa serta unsur penegakan atau karakter memaksa dalam penerapannya. Di balik karakter memaksa -- harus ditaati semua warga hukum -- hukum tidak lagi berdiri sebagai pelayan keadilan. Unsur pemaksaan dari hukum, lahir bersamaan ketika hukum dipromulgasikan. Karakter memaksa dari upaya penegakan hukum justru cenderung melahirkan kekerasan performatif -- orang tunduk pada hukum, karena hukum memaksa. Kekerasan performatif biasanya beroperasi melalui bahasa, baik berupa perintah maupun larangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H