[caption id="attachment_367420" align="aligncenter" width="400" caption="Satu dari sekian banyak olah kutipan yang pernah saya buat"][/caption]
Hanya dalam hitungan jam ke depan, “ayah” saya akan dilantik menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia. Loh, kok "ayah"? Bagaimana ceritanya? Mungkin itu pertanyaan Anda. Oleh karenanya, izinkan saya berkisah...
* * *
Nama saya Khun. Saya lahir di sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah bernama Donggala. Nama ini tidaklah populer, namun saya cukup berbangga karena tercantum di permainan Monopoli. Saya adalah generasi kedua dari pasangan “manusia perahu” yang berlayar dari daratan Tiongkok untuk mencari tanah tempat pengharapan bisa disemai.
Bersama nama tengah, saya bisa dipanggil Tek Khun. Kakek-nenek saya tiba di tanah yang asing bagi mereka dalam kondisi memprihatinkan. Impitan hidup kian melekat saat mereka harus memikul beban membesarkan delapan anak. "Banyak anak banyak rezeki" ternyata tak terbukti bertuah di sini. Berpindah dari desa ke kota kecil bernama Donggala, membuat situasi agak melegakan. Kakek saya memulai usaha sebagai pedagang kaki lima (PKL). Sebagai anak sulung, ayah saya turut menjadi tulang punggung keluarga, meninggalkan bangku sekolah di kelas tiga Sekolah Rakjat (SR).
Menyandang marga, nama lengkap saya Ang Tek Khun. Di mata orangtua, saya adalah anak yang tak berguna, setidaknya selama hidup bersama mereka kala SD hingga SMP. Jika ayah saya telah memanggul beban mencari nafkah sejak usia dini di SR, saya lebih suka membaca komik. Semasa kecil ayah saya rajin memulung kaleng bekas lalu diolahnya jadi corong minyak tanah untuk dijual. Sementara saya? Lebih sering mengeluh panjang pendek saat diminta menjaga toko sepulang sekolah.
“Prihatin” adalah tema utama kehidupan keluarga besar ayah saya. Peristiwa kebakaran yang meludeskan toko sekaligus rumah tinggal, membuat jam “banting tulang” kian panjang. Itu sebabnya hubungan saya dan ayah saya tak pernah dekat, tak bisa hangat, sering kali berbantahan. Pilihan saya akan masa depan, kian memperuncing konflik kami. Saya tak pernah tertarik untuk mendampingi, apalagi meneruskan usaha kelontongan yang dirintis ayah saya. Kepergian saya ke Surabaya untuk menempuh pendidikan lanjutan, lalu merantau dan menetap di kota Yogyakarta hanyalah peredam pendek. Sampai saat kami bertengkar hebat, dan hubungan mendingin, lalu terpisahkan oleh maut.
* * *
Politik? Asing! Politik praktis? Tabu! Partai politik? No!
Hidup ini sudah terlalu repot untuk menginvestasikan waktu dalam urusan di area "gelap" seperti itu. Maka, kehidupan nyata dan politik bagai dua dunia terpisah bagi kami. Seolah dua sisi rel yang bisa menempuh ratusan kilometer tanpa pernah bersatu—bahkan mungkin tak pernah bertegur sapa.
Indonesia? Soeharto! Saya tumbuh dan besar dengan nama itu. Ketika angin perubahan bertiup, alarm jam seolah membangunkan banyak orang dari tidur lelap, termasuk saya. Namun, harapan agar kondisi lebih baik, bagai berayun dari satu dahan ke dahan lain. Itu sebabnya ketika tiba saatnya Gubernur DKI Jakarta harus berganti, rasanya tak ada yang istimewa. Ngapain diurusin?
Perlahan namun pasti, kehadiran sosok Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mulai menarik perhatian saya. Ekspos media yang gencar, menyodok pasangan ini ke depan mata saya. Dengan kerap mendengar dan membaca perihal keduanya, tiba-tiba muncul intuisi berbeda dari dalam diri saya terhadap mereka. Disusul keyakinan bahwa mereka memang “berbeda”. Alhasil, warga Ibukota pun menaruh amanah di pundak mereka.
Hiruk-pikuk Pilgub DKI telah usai saat saya mengenali gerakan media sosial bernama Jokowi Ahok Social Media Volunteer (JASMEV). Sangat terlambat, membuahkan perasaan gelo yang sangat dalam di hati karena tidak terlibat di dalamnya. Untuk menghibur diri, saya mem-follow beberapa akun twitter terkait JASMEV dan membaca jejak kicau mereka. Itu sudah cukup menghibur. Bahkan kagum pada pilihan keberpihakan mereka.
* * *
Mengapa sosok Jokowi kemudian menawan hati saya? Benar ia bertindak berbeda dengan pejabat pada umumnya, benar ia mengesankan sebagai sosok yang bersih dan berintegritas. Benar pula dari aspek wajah, tampang beliau itu ndeso. Namun, ada satu alasan yang menggetarkan hati. Postur dirinya mirip ayah saya! Dalam usia yang sepantaran, ayah saya kala itu, hanya dua hal yang berbeda secara mencolok. Pertama, Jokowi tidak merokok, sebaliknya ayah saya perokok berat yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Kedua, Jokowi tampak betah bercelana panjang, sementara ayah saya lebih mirip Bob Sadino yang dalam keseharian menyukai celana pendek.
Diam-diam, saya berubah jadi “fans” beliau. Aksi-aksi beliau dan Ahok adalah menu bacaan dan tonton saya sehari-hari selama lebih dari setahun. Menonton Youtube atau liputan TV atau sajian media daring, menjadi kegemaran baru saya. Melalui itu semua, seolah ayah saya kembali hadir dalam bentuknya yang lain.
Dengan kesukaan yang membuncah itu, saya menggagas buku tentang beliau yang kemudian diwujudkan seorang rekan dan terbit dengan judul The Jokowi Secrets. Lalu, atas inisiatif pribadi, saya membuat jaringan sosial media (multi-platform) kecil-kecilan untuk menyuarakan dukungan agar beliau terus berbuat yang terbaik bagi warga DKI serta menampilkan standar baru kinerja pejabat sebaligus etalase bagi warga di 33 propinsi lainnya.
* * *
Saya bergegas kembali ke kantor dan membuka TV. Benar kabar yang sedang diperbincangkan di media sosial, Jokowi nyapres! Dengan napas masih berkejaran, bersama rekan kantor lainnya, kami menonton dengan berisik. Antusias. Hingga tayangan itu berganti dan rekan-rekan saya kembali ke meja kerjanya masing-masing. Saya mematikan TV, menarik napas panjang. Lega. Saat beringsut kembali ke ruang kerja, mata saya agak basah. Dada saya dipenuhi rasa syukur. Saya pun teringat pada almarhum ayah saya.
Saya hampir saja kehilangan pengharapan beliau akan nyapres. Sepengetahuan saya, tidak banyak kelompok massa yang terang-terangan mendorong hal ini. Tak sebanding dengan “serangan” yang menentang. Saya agak paham dua hal ini: Jokowi tidak akan pindah partai demi ambisi politik dan beliau adalah orang Jawa. Beliau tidak akan pernah bersedia nyalon bila tidak diizinkan partai secara formal. Never. Gaya berpolitik seperti ini, menurut pendapat saya pribadi, tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang yang tak mengerti budaya Jawa yang otentik. Di mata mereka, seorang petarung bisa dianggap sebagai “boneka”. Oleh karena itu, bersama seorang kawan kami jadi “relawan amatiran” yang merancang endorser tertentu yang tak bisa diungkap di sini agar Jokowi dicapreskan.
Ketika tersiar berita JASMEV bangkit (lagi), saya bagai kejatuhan duren. Telusur sana dan sini, hingga saya mendapatkan alamat kontak untuk mendaftar sebagai relawan. Semangat saya menggunung, mengingat perasaan "gelo" saat tak ikutan di pilgub DKI. Namun saya harus menelan kekecewaan karena surat elektronik saya tak direspons—hingga suatu hari direspons dengan formulir pendaftaran. Namun, saya kembali kecewa karena balasan surel saya kembali tak mendapatkan respons. Tak habis akal, saya lalu mendaftar (lagi) melalui website, namun hasilnya setali tiga uang.
Hari-hari berlalu, saya perlu memupuk tekad agar tak padam. Tak habis akal, melalui Twitter saya nekat me-mention langsung dirijen JASMEV. Dan, ajaib! Tweet saya direspons. “Lamaran” saya diterima. Beberapa data saya kirimkan melalui DM, lalu petunjuk teknis pun saya terima. Sejak hari itu, saya jadi bagian dari keluarga besar JASMEV!
Di JASMEV, saya bergabung dengan kawan-kawan yang baru saya kenal. Dengan mengikuti beberapa kali pelatihan yang diselenggarakan JASMEV, saya kian tahu sebagian di antara mereka adalah relawan yang sudah aktif sejak pilgub DKI Jakarta. Bergabung bersama sekian banyak orang yang tersebar di seantero nusantara, membuat saya merasa tidak sendirian dan terus termotivasi. Menjadi satu dari antara sekian Koordinator Wilayah (Korwil) JASMEV, membuat saya merasa terhormat.
* * *
Menjadi relawan JASMEV tidaklah mudah. Pesan untuk berperilaku baik karena "relawan adalah etalase kandidat", sungguh menyiksa. Di tengah kepungan kampanye hitam, ingin rasanya menyerang balik. Namun kampanye positif sebagai filosofi dasar dan utama JASMEV, serta pesan untuk "eling" serta tips "wudhu" terlebih dahulu sebelum merespons “penyerang”, meloloskan diri saya dari predikat "hatter". Bahkan sebaliknya, sempat menuai pujian dari tokoh yang saya kagumi, Wimar Witoelar, melalui tweet beliau. Begitu juga kesempatan dilatih oleh tokoh pujaan saya, Prof. Rhenald Kasali, sungguh menguatkan saat beliau meminta kami mengeksplorasi hal-hal positif—bukan kampanye hitam.
[caption id="attachment_367420" align="aligncenter" width="400" caption="Satu dari sekian banyak olah kutipan yang pernah saya buat"]
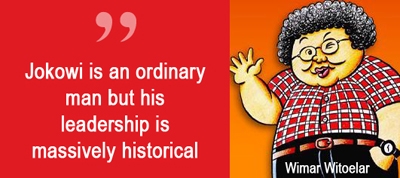
[caption id="attachment_367421" align="aligncenter" width="400" caption="Pelatihan JASMEV dengan narasumber Prof Rhenald Kasali dan diliput oleh stasiun TV Jerman"]

Keterlibatan emosi yang kian dalam, selaras dengan debar jantung yang kian kencang. Pada hari-hari menjelang 9 Juli, gejolak di dada bagai roller coaster yang melaju dahsyat. Kadang di atas, dipenuhi sukacita kala jadi bagian dari relawan yang berhasil mengukir Trending Topic Dunia di Twitter (terutama pada masa debat capres/cawapres). Kadang terpuruk hingga stres, terutama saat hasil survei menunjukkan elektabilitas kandidat nomor Dua terus melandai. Hati galau, membuat hari terasa hampa dan menatap linimasa dengan mata nanar.
[caption id="attachment_367422" align="aligncenter" width="400" caption="Kreativitas tak mengenal batas, ide datang begitu saja, dan saya membuat TTS ini"]

Namun, menggunakan bekal ilmu psikologi dan diskusi dengan seorang kawan membuat saya bisa melihat secara helicopter view dan kian meyakini bahwa ada “jalan tersembunyi” yang sedang terjadi. Dan, benar saja. Hari-hari rebound kemudian terjadi. Ketegaran seorang Jokowi, kematangan seorang Jusuf Kalla, serta interaksi dan saling berbagi dengan sesama relawan yang bangkit luar biasa, membuat hati terhibur dan keteguhan dapat dihimpun kembali. Hingga tiba pada hari ketika saya mencelupkan dua jari ke botol tinta.
[caption id="attachment_367423" align="aligncenter" width="400" caption="Ini Opor Rakyat, berkala iseng tapi serius, yang sempat terbit sekian edisi"]

* * *
"Ayah, saya memang anak yang berguna di masa pengharapan kauletakkan di pundak. Saya tidak juga menempuh jalan kesukaanmu. Kepergianmu yang begitu cepat tak memberi ruang bagi saya untuk membuatmu tersenyum, bahkan merasa bangga. Namun, dalam beberapa kali mata basah saat menatap wajah Jokowi, saya sedang menatap engkau.
"Ayah, melalui kesempatan sebagai relawan amatiran ini, saya diberi peluang untuk berdebar bagimu, terguncang untukmu, dan tersenyum untukmu. Inilah cara yang saya tahu dan bisa saya lakukan dalam upaya membalas budi.”
Apakah hal terindah dalam hidup ini selain memiliki kesempatan untuk mengantarkan seorang "ayah" ke tempat ia akan mengabdi kepada warganya, kepada bangsanya? Dan, apa pun yang terbaik bagi bangsa, itulah yang terbaik untuk diperjuangkan. Tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa embel-embel.
Selamat menunaikan tugas yang kami embankan, “ayah”. Kami percaya pundakmu yang tampak ringkih itu akan kekar untuk memikulnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H









