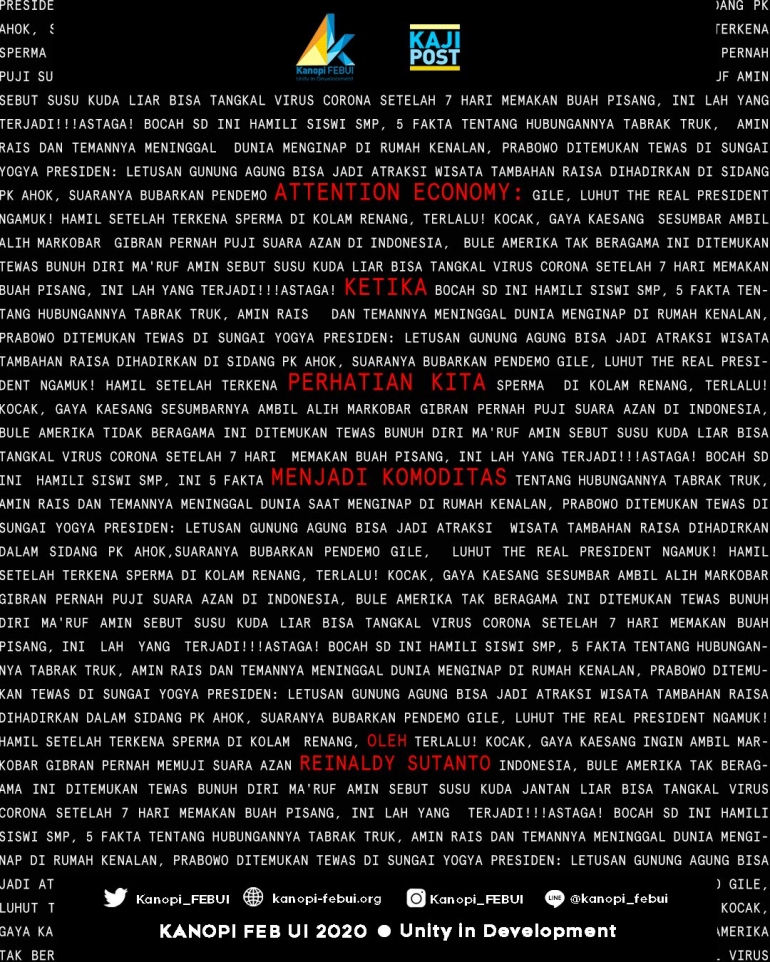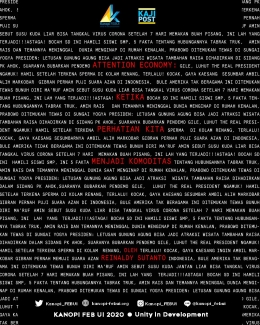Di tengah dunia jurnalistik yang makin kompetitif, clickbait hadir sebagai salah satu pilihan menarik. Tidak sedikit dari perusahaan media kemudian menciptakan clickbait hanya demi popularitas. Kecaman dan hujatan tentunya terus berdatangan, mengingat kelakuan mereka yang sulit diterima akal sehat.
Akan tetapi, apa yang diharapkan justru terjadi sebaliknya. Mereka yang kini populer hanya perlu bersantai sembari menunggu antrean iklan dari AdSense yang kian menumpuk. Tak ayal, keadaan tersebut juga terjadi oleh karena andil kita semua. Apakah itu?
Jawabannya adalah perhatian. Ya, perhatian yang kita dedikasikan kepada clickbait yang sengaja diciptakan. Perhatian itu pula diperebutkan oleh banyak perusahaan yang ingin menaruh iklannya di halaman pembuat clickbait. Lantas setelah melihat sekilas singgungannya dengan aktivitas ekonomi, adakah cara ilmu ekonomi untuk memaknai 'perhatian' yang kita miliki?
Guna menjawab pertanyaan di atas, kita dapat memulainya dari definisi ilmu ekonomi sendiri. Menurut Mankiw (2018), ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengelola sumber daya yang terbatas. Kelangkaan selanjutnya menjadi fenomena utama yang dikaji oleh para ekonom di seluruh dunia. Dalam konteks tulisan ini, 'perhatian' merupakan sumber daya yang terbatas itu.
Topik yang lebih dikenal sebagai attention economy rupanya telah lama menjadi perbincangan. Peraih nobel ekonomi Herbert Simon (1971) menyatakan bahwa kehadiran informasi telah mengonsumsi perhatian kita, dan semakin berlimpahnya informasi menyebabkan perhatian kian terbatas pula.
Apa yang disampaikan olehnya tentu sangat relevan dengan situasi saat ini. Sebagai gambarannya, 350 juta foto di Facebook dan 500 juta kicauan di Twitter diunggah setiap harinya pada tahun 2019. Sementara itu, kita tetap hanya memiliki waktu 24 jam dalam sehari.
Kompetisi untuk Atensi
Berdasarkan sejarah, kompetisi untuk merebut perhatian sebenarnya bukanlah hal baru. Kita bahkan bisa menelusurinya hingga dua ratus tahun yang lalu ketika harga koran-koran di New York masih sekitar enam sen.
Pada waktu itu, Benjamin Day datang bersama terobosan koran The Sun yang hanya berharga satu sen dan seketika kemudian populer. Selain banting harga, koran tersebut juga menulis "Moon Hoax" yang berisi kisah palsu tentang kehidupan di bulan namun malah menarik perhatian. Alhasil, The Sun pun semakin menjadi-jadi pada masanya.
Kompetisi semacam itu ternyata diamini oleh Shapiro dan Varian (2001) yang membingkainya dalam konteks strategi bisnis. Menurut mereka, perusahaan harus berinvestasi lebih banyak dalam memasarkan produknya untuk mengambil perhatian para konsumen potensial.
Sejalan dengan itu, ekonom Josef Falkinger (2008) memberikan dua model keseimbangan pasar yang mengindikasikan adanya dua level kompetisi. Pertama, perusahaan (attention-seeker) akan berkompetisi untuk merebut perhatian konsumen dengan memberikan sinyal. Baru sehabis itu, mereka yang sukses menarik perhatian akan kembali berkompetisi di kerangka pasar monopolistik.
Mengacu kepada dua level kompetisi yang ada, perusahaan mula-mula harus memberikan sinyal sekuat mungkin kepada para konsumen supaya bisa meraih pendapatan. Lebih lanjut, Falkinger menyatakan bahwa sinyal yang kuat adalah sinyal yang mampu menembus gerbang pikiran manusia. Lantas apakah 'gerbang' yang dimaksud itu?
Berbicara mengenai pikiran manusia pastinya tidak jauh-jauh dari disiplin ilmu yang lebih andal membahasnya. Psikolog Harold Phasler (1998) menyampaikan istilah 'gerbang' atau perceptual gating sebagai sebuah filter di dalam pikiran kita yang bertugas untuk menyaring informasi. Hanya informasi tersaring kemudian berhak mendapatkan perhatian kita.
Setelah itu, keberhasilan menembus 'gerbang' menjadi entri pertama perusahaan yang mengantarkannya ke kompetisi berikutnya, pasar monopolistik. Eksistensi 'gerbang' di ilmu psikologi juga semakin memperkuat alasan ilmu ekonomi menjadikan perhatian sebagai komoditas.
Kembali ke Kita
Selepas membicarakannya dari sudut pandang attention-seeker, adakah perbincangan mengenai alokasi perhatian yang kita miliki? Gabaix dan Laibson (2005) menyajikan model directed cognition yang menyinggung seputar masalah itu. Dalam modelnya, seseorang dengan kendala waktu yang terbatas hanya akan menganalisis informasi yang mungkin berguna untuknya dan mengabaikan apa yang menurutnya mubazir.
Sebagai contoh, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan sulit untuk tinggal di desa atau kota, kita pasti akan menimbang-nimbang terlebih dahulu kedua opsi yang ada. Namun, apabila kita pada dasarnya memiliki preferensi yang kuat terhadap gaya hidup perkotaan, waktu mempertimbangkan diri untuk tinggal di desa akhirnya akan sia-sia. Dengan kata lain, memikirkan pilihan yang nantinya kemungkinan besar tidak dipilih hanya membuat alokasi perhatian kita menjadi tidak optimal.
Lebih dekat lagi, kita bisa memahami seluruh konsep di atas dari hal-hal yang erat dengan keseharian kita, sebut saja YouTube. Dia menawarkan akun berbayar dengan beragam fitur unggulan, di mana salah satu yang menarik adalah bebas dari iklan. Kita sebagai penikmat layanan gratis boleh jadi merasa irit karena tidak menggelontorkan uang hanya demi beberapa detik.
Meskipun begitu, kita rupanya tetap berakhir pada pilihan untuk membayar. Hanya masalahnya, apakah kita mau membayarnya dengan uang atau justru 'perhatian' melalui iklan yang wajib ditonton?
Di akhir cerita, walaupun pemahaman akan kelangkaan perhatian sudah bisa dibentuk, perhatian nampaknya belum bisa dihitung secara akurat. Apalagi, alat untuk mengukurnya pada saat ini baru sebatas waktu, like, dan subscribe. Indikator itu jelas tidaklah sempurna untuk menilai perhatian karena angka di sosial media tidak selamanya sejalan dengan kenyataan.
Ada banyak faktor lain seperti keunikan manusia, misalnya attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), yang ikut mempengaruhi perhatian seseorang namun nyatanya masih sulit terkuantifikasi secara ekonomi.
Alhasil, tulisan ini hanya sekadar membukakan wawasan pembaca terhadap perkembangan dunia kita, suatu era di mana perhatian telah memiliki nilai ekonomi tersendiri. Satu pelajaran penting barangkali bisa dipetik: di kala semua perhatian yang kita curahkan kepada orang lain mungkin terasa sia-sia, setidaknya perhatian itu tetap berharga di mata ilmu ekonomi. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya!
Oleh Reinaldy Sutanto | Ilmu Ekonomi 2019 | Staf Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2020
Referensi tanpa Tautan
Falkinger, J. (2008). Limited Attention as a Scarce Resource in Information-Rich Economies. The Economic Journal, 118(532), 1596-1620. Retrieved August 1, 2020, from jstor.org
Gabaix, X., & Laibson, D. (2005). Bounded rationality and directed cognition. Harvard University.
Mankiw, N. G. (2016). Principles of Economics Eight Edition. Harvard University.
Pashler, Harold E. (1998). Psychology of Attention. The MIT Press.
Simon, H.A. (1971). 'Designing organizations for an information-rich world', in (M. Greenberger, ed.), Computers, Communications, and the Public Interest, pp. 38-52, Baltimore: John Hopkins Press.
Shapiro, Cal, & Varian, Hal R. (1999), Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI