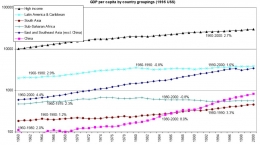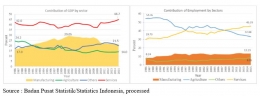Trade can make everyone better off. Atau setidaknya, itulah yang diyakini oleh para penganut ilmu ekonomi beraliran Neoklasik hingga kini. Kepercayaan ini juga yang menuntun negara-negara maju, melalui sejumlah organisasi multilateral raksasanya, untuk meresepkan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang untuk “menebus” dana pinjaman. Padahal, kebijakan tersebut tidak one-size-fits-all dan harus di-tailor sesuai konteks sosioekonomi masing-masing negara agar efektif.
Seiring kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi, mayoritas negara di dunia pun semakin interdependent dengan satu sama lain. Globalisasi yang kita kenal sekarang akhirnya berpusat pada perdagangan internasional dan investasi asing. Ekonom Harvard University Dani Rodrik sudah memperingatkan kita tentang bahaya hiperglobalisasi ini serta mengajak kita untuk mundur sejenak dan berpikir ulang tentang bentuk globalisasi yang ideal.
Sekilas, pernyataan di atas mungkin akan membuat pembaca mengernyitkan alis. Benarkah ada dampak negatif dari perdagangan bebas yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara-negara maju? Bila dirasa merugikan, mungkinkah suatu negara menarik diri dari perdagangan bebas di era globalisasi sekarang? Terakhir, kebijakan apa yang tepat bagi negara berkembang, terkhusus Indonesia? Penulis akan mencoba menjawab sikap skeptis dan rasa penasaran tersebut melalui tulisan ini.
Sekilas teori
Konsep perdagangan pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit tahun 1776, the Wealth of Nations, di mana ia menulis, “It is a maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy.” Terinspirasi oleh buku itu, ekonom Inggris David Ricardo membangun fondasi dari prinsip keunggulan komparatifnya yang terkenal.
Prinsip tersebut menyatakan bahwa pelaku perdagangan tidak perlu memiliki keunggulan absolut (i.e., kemampuan untuk memproduksi output menggunakan input yang relatif lebih sedikit). Perdagangan dapat terjadi selama orang berspesialisasi berdasarkan apa yang dapat mereka hasilkan dengan biaya peluang yang relatif lebih rendah — ini disebut keunggulan komparatif.
Bentuk perdagangan tradisional antarkeluarga perlahan berevolusi menjadi sesuatu yang terjadi antara lembaga politik terbesar saat ini, yaitu negara. Seperti diserukan oleh Smith dan Ricardo, memang betul perekonomian domestik kini dapat menyediakan lebih banyak barang dan jasa melalui perdagangan internasional. Berkat meningkatnya kompetisi di pasar, orang-orang pun dapat mengkonsumsi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah.
Peningkatan ukuran economic pie ini dapat digunakan untuk membuat semua orang menjadi lebih baik (Mankiw, 2016). Di sisi lain, ekonom juga mengakui bahwa beberapa orang menjadi worse off karena perdagangan internasional, contohnya adalah produsen dalam negeri. Namun, mereka berpendapat bahwa perdagangan selalu baik untuk kesejahteraan agregat suatu negara.
Hiperglobalisasi dan hipokrisi
Ha-Joon Chang, ekonom University of Cambridge, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang diduga tumbuh melalui perdagangan bebas, menggunakan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis pada tahap awal perkembangan mereka. Pada awal abad ke-19, tarif impor rata-rata Inggris untuk produk-produk manufaktur adalah sekitar 45-55%, sementara AS sekitar 35-45% (Chang, 2002). Jelas sekali bahwa ini jauh dari gagasan perdagangan bebas yang dicirikan memiliki hambatan tarif dan non-tarif yang rendah menurut World Trade Organization (WTO).