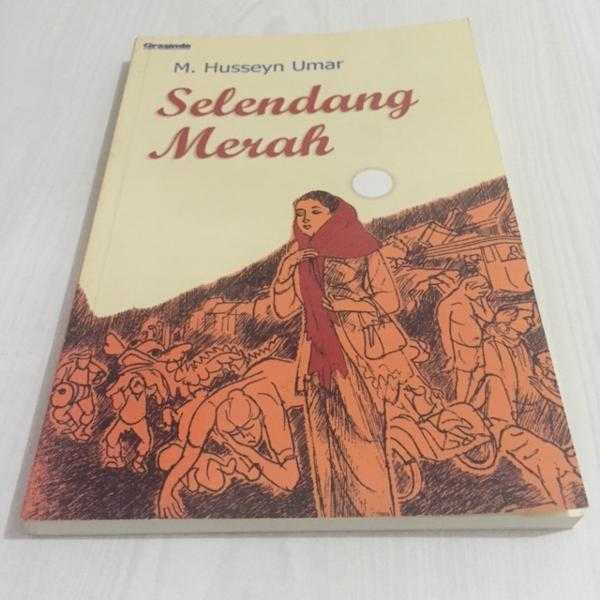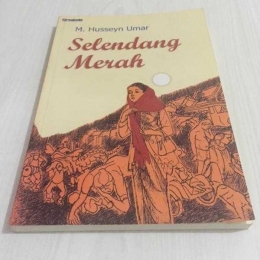Bagi saya ada beberapa hal menarik dari sejarah Indonesia 1950-an (hingga awal 1960-an) menjadi salah satu minat saya dalam kajian sejarah. Secara emosional periode ini menjadi "dekat" dengan saya karena saya dekat dengan ibu saya yang kerap bercerita tentang masa kecil dan remaja awalnya di era, terutama kehidupan Jakarta dan Bandung.
Beberapa cerita Ibu saya tentang Santa Ursula di Lapangan Banteng dan Apotek Maya di Bandung pernah saya tulis di Kompasiana. Singkatnya walaupun kehidupan ekonomi susah, masyarakat masih harmonis, santun dan hidup di Jakarta dan Bandung masih nyaman, relatif aman dan sehat.
Cerita tentang gerombolan hanya membuat warga takut melalui daerah tertentu. Saya pernah bertanya pada warga Jakarta atau Bandung atau yang hidup masa itu menyebut mereka lebih takut kalau Gunung Tangkubanparahu atau Gunung Gede meletus.
Daya tarik lain periode 1950-an sebagai negara yang baru merdeka, di satu sisi rasa nasionalisme sangat tinggi, mencintai budaya dan kesenian nasional, tetapi di satu sisi bagi remaja dan kaum muda yang mulai mudah mendapat akses pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, "pop art" terutama film Hollywood masuk.
Kalau Anda menonton film "Tiga Dara" itu adalah awal hibrida antara kultur Barat dan kultur Timur Indonesia. Dansa, berdandan gaya Elvis Presley, hingar musik rock n roll menjadi tren remaja urban, sekalipun pergaulan mereka umumnya masih memegang teguh norma timur. Tampaknya (sebagian) remaja urban waktu itu tidak ambil pusing dengan soal "gonta-ganti" kabinet , konflik elite politik.
Pada 2001 saya pertama kali membaca buku kumpulan cerpen dari satrawan M. Hussyen Umar "Selendang Merah" (terbitan Jakarta, Gramedia, 2000) memperkaya gambaran saya tentang situasi negeri ini masa Demokrasi Liberal itu. Kelahiran Medan, 21 Januari 1931 ini menulis puisi, cerpen dan ulasan sastra yang dimuat di Mimbar Indonesia, Siasat, Gelanggang dan media lain. Saya membahas berapa cerpennya untuk membahas konteks sosial kaum urban masa itu.
Masuknya Gaya Hidup Barat
Salah satu cerpennya "Kalau Anak-anakku Pulang Pakansi" (ditulis pada 1954) paling menarik perhatian saya. Tokoh utamanya seorang bapak tinggal bersama isterinya di Sumatera Barat. Enam dari sepuluh anaknya perpencar di sekolah yang berbeda tiga di Jakarta, seorang di Yogyakarta dan dua bersekolah di Bukitinggi.
Setahun sekali mereka pulang kalau menghadapi liburan besar dan inilah pakansi. Realitas masa itu sudah tertangkap sejak awal, pendidikan menengah dan perguruan tinggi masih di Jawa, mereka tingga indekost. Untuk membiayai sekolah dan hidup sehari-hari Sang Bapak gali lobang tutup lobang.
Tetapi alangkah terkejutnya Sang Ibu, isteri dari tokoh utamanya bahwa salah seorang anaknya bernama Tjal ternyata menggunakan ongkos pulang yang dikirimnya untuk tamasya ke Bali. Pada waktu itu tamasya ke Bali hal yang eksotis. Dia tidak ikut pulang dalam pakansi tahun itu.
Ada hal lainnya, seorang anaknya duduk di perguruan tinggi bernama Win dalam dialog dengan ibu dan ayahnya menggambarkan betapa kuatnya pengaruh westernisasi pada anak kuliah. Win minta dibelikan stelan jas "Black and White" seharga Rp900 (tinggi masa itu ratusan kali harga satu 1 kg beras), ditambah sepasang sepatu Barrat, kemaja Arrow, hingga gitar.
"Seorang mahasiswa tidak punya black and white dan tidak bisa dansa ketinggalan zaman, Ayah" katanya.
Mendengar ini, isteriku sungguh-sungguh memberangsang dan marah. "Bukan untuk itu engkau kami suruh bersekolah ke Jakarta," katanya (halaman 101).
Dalam berapa tulisan saya tentang Bandung 1950-an, gaya hidup Barat ini mendapatkan reaksi namun sulit untuk dibendung lagi.
Euforia Pasca Kemerdekaan
Cerpen lain "Pembesar dari Kota X" memberikan gambaran lain soal perubahan 1950-an. Tokoh utamanya seorang pegawai kantor yang hanya bergaji sepuluh perak. Sebelum penyerahan kedaulatan 1949), sep (kepala kantor) Bangsa Belanda dan terus berlangsung selama berapa tahun, sampai muncul pejabat baru yang disebut dari Kota X.
Pejabat itu minta rumah dinas. Dia menolak tinggal di Kebayoran Baru yang pada waktu itu masih dianggap hutan dan terpencil. Pejabat itu mendapat rumah di Menteng. Setelah orang Belanda menempati rumah itu didesak keluar.
Tokoh utama adalah salah seorang dari pegawai kantor ikut membersihkan rumah itu. Namun pejabat itu baru mau datang setelah dia dan keluarga naik pesawat GIA. Dengan sejumlah keheranan, awalnya tokoh utama bangga kantor itu dipimpin oleh bangsa sendiri.
Usia atasannya itu 30 tahunan jauh dari usia yang dibayangkan tokoh utamanya 40 tahunan. Pidato pertamanya meminta semua bawahannya kerja keras dan ditutup dengan kata "merdeka", tegas dan semangat. Sayangnya kepala kantor itu dengan dalih pekerjaan perlu tambah pegawai membawa orang-orangnya dari Kota X juga. Tentunya dengan gaji yang lebih besar dengan kecakapan masih dipertanyakan (halaman 68).
Cerpen itu juga ditulis pada 1954 menggambarkan euforia pasca kemerdekaan di mana penempatan orang-orang yang berjasa pada masa revolusi kerap tidak melihat kompetensi. Budaya nepotisme sudah ada sejak 1950-an.
Dalam tulisan saya tentang sejarah Bandung 1950-an, penempatan orang-orang dari kota lain menimbulkan kecemburuan sosial karena dari latar belakang budaya yang sama bukan karena keahlian. Akhirnya menimbulkan gerakan kedaerahan.
Pesan dalam cerita rasanya masih relevan dengan masa sekarang.
Korban Lain dari Masa Revolusi
Cerita lainnya berjudul "Penari Sewaan" terkait dengan perubahan masa Perang Kemerdekaan. Mantan pejuang bernama Ridwan Abdullah bertemu kali dengan isterinya yang sudah lama tidak bertemu bernama Lely di ruang dansa di Happy World Prinsenpark tempat hiburan pada pertengahan 1950-an di Jakarta.
Pada masa Revolusi, Lely adalah keluarga Indo. Ayahnya dibunuh para pemuda karena tidak bisa menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Rupanya Ridwan jatuh hati dan menikahi dia hingga keluarga yang lain terlindung. Namun Ibu Lely dendam.
Suatu ketika Ridwan tertangkap tentara Belanda, Lely dinikahi seorang Serdadu Belanda atas pengaruh ibunya yang rindu pasa keemasan zaman Hindia Belanda. Namun serdadu bule itu tewas dalam suatu pertempuran dengan TNI.
Keluarga itu terlunta dan pergi ke Singapura, Lely kemudian menjadi penari sewaan, masa itu disebut taxi-girl,selain menemani dansa orang kaya, juga bisa diajak tidur. Ibunya meninggal dan Lely harus menyambung nyawa. Namun Ridwan dan Lely tetap berpisah. Dia hanya memberikan uang enam puluh rupiah bayarannya menemani dansa.
Cerita tentang kelompok masyarakat Indo pada masa revolusi ini tidak banyak tergali. Namun mereka berada dalam posisi yang gamang antara memilih "zaman keemasan" yang sudah harus berakhir atau belajar menyesuaikan diri dengan bangsa yang baru. Lely adalah gambaran ini dan
Ridwan adalah gambaran pejuang yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil. Dia disika, kena cacar dan kena penyakit paru-paru hingga mukanya cacat. Lely tidak bisa mengenalinya segera karena Ridwan harus menutup kecacatannya dengan jengot dan jambang.
Cerpen ini ditulis pada 1955 mengingatkan saya pada cerpen Nugroho Notosutanto "Vickers Jepang" tentang mantan pejuang yang terpinggirkan dan film Usmar Ismail "Lewat Djam Malam" awal 1950-an. Cerpen Hussyein Umar lainnya "Dimulai dari Nol" (1954) juga menggambarkan mantan pejuang hidup bersahaja dengan isteri dengan tujuh anaknya.
"Ketika Ayah Hidup Kembali" (1955) menceritakan mantan kepala penjara yang pro Republik ditangkap tentara Belanda, dianggap tewas oleh keluarganya. Isteri dan anak-anaknya bekerja mulai dari pesuruh kantor di masa pendudukan dan jualan kue hingga pendidikan terbengkalai.
Suatu ketika ayahnya kembali namun sudah berubah menjadi pemberang. Belakangan diketahui karena sakit kepala akibat siksaan tentara Belanda. Ayahnya harus pensiun walau sudah mendapat surat pengangkatan kembali sebagai kepala penjara.
Revolusi bukan hanya meninggalkan korban jiwa dan harta, tetapi juga psikis.

"Selendang Merah" (1955) kisah tentang penarik doger (cokek) bernama Sinah di Tanah Abang. Sinah dinikahi seorang tukang becak dan berhenti menari hingga punya anak. Suatu ketika anaknya sakit keras membutuhkan biaya pengobatan kembali menari. Sinah mendapat uang dari hasil doger, sayang anaknya meninggal.
Cerita menarik lainnya ialah "Tukang Pijat" (ditulis pada 1950). Rupanya di Jakarta pada 1950-an dan sejak masa Belanda ada profesi tukang pijat keliling (biasanya buta) dengan memukul kaleng berteriak pijat-pijat (tidak pernah saya temui masa sekarang).
Tukang pijat dalam cerita ini bertemu tokoh utamanya seorang tua ditemani gadis muda. Disangkanya berprofesi sebagai pekerja seks (karena masih tabu masa itu), ternyata hanya mencari nafkah karena suaminya meninggal.
"Rumah" (juga pada 1950) bercerita tentang kesukaran perumahan di Jakarta masa itu. Cerita tokoh utamanya diundang sahabatnya yang dipanggil Bung Harun untuk menginap di rumahnya di Jakarta pada masa liburan. Ternyata dia sudah pindah menumpang di rumah iparnya yang juga menyewa. Bagaimana keadaan rumahnya?
Dan dalam yang Cuma punya dua kamar itu ada sembilan belas orang yang tempati. Tidur di lantai saja dengan kembang tikar. Seperti ikan dencis. Dan kalau mandi atau buang air dan lain-lain berebut. Dan celakanya, isteri atau nyonya rumah itu galak sehingga percecokan-percecokan sering terjadi...(halaman 3).
Bisa dibayangkan tinggal di rumah seperti itu yang nyaris tanpa privasi. Namun untuk mendapatkan rumah yang lebih baik sulit dan kalau pun ada mahal.
Lainnya adalah "Harapan"(1950) tentang anak jalanan bernama Mili berusia sebelas tahun hidup mengemis dan kerap mencuri dan mencopet untuk bertahan hidup. Mili merasa senang hidup di kawasan Senen yang dikenalnya dan dianggap wilayah petualangannya karena di sana restoran dan bioskop seperti Rex, Grand dan Rialto (yang masa itu kehidupan gemerlap).
Sekalipun kawasan itu rawan dalam cerita polisi ada kejadian polisi militer menembak penjahat bersenjata yang masa itu masih banyak berkeliaran, sekalipun Mili diminta orang Indonesia yang merasa malu karena orang Indonesia mengemis, Mili memilih tetap dalam petualangannya.
Membaca cerpen Husseyn Umar tentang situasi Indonesia 1950-an memberikan gambaran bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekadar merebut, tetapi juga bagaimana mengisinya. Hal yang butuh perjuangan lebih berat dan jatuh bangun. Namun pilihan yang lebih baik daripada menjadi budak bangsa asing.
Irvan Sjafari