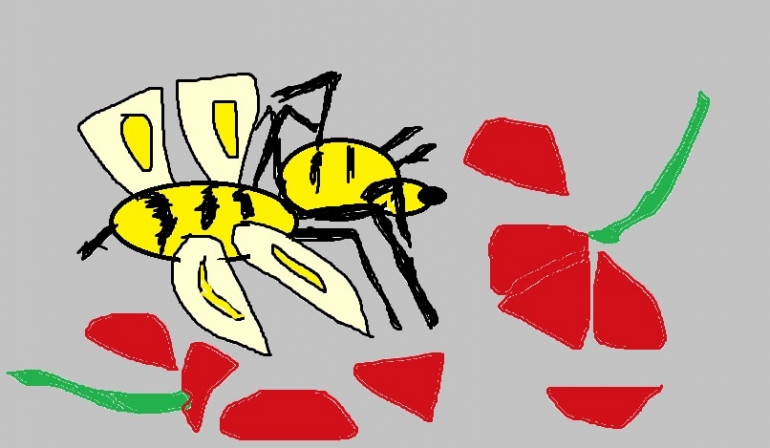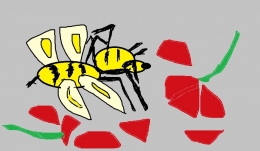SEMBILAN
Tempat Tak Diketahui. Waktu Tak Diketahui.
Lelaki tua itu tersenyum melihat wajah Alif yang memancarkan kekakuan, kecemasan, keraguan, tetapi sekaligus juga keinginan. Sementara bidadarinya jauh lebih tenang menanti Alif mengucapkan kata demi kata.
Dia menduga lelaki itu semacam wali hakim yang menikahkan pasangan di sini. Alif menyadari ratusan warga di sini sepasang-sepasang usia mereka belum mencapai 30 tahun. Hanya berapa yang lebih tua dari dia. Di antaranya yang lebih tua dari Alif penghulu dan si Wali Hakim.
Tempat duduk dia bersila di hadapan lelaki tua itu adalah ruangan bulan yang diyakininya sebagai masjid. Alif sempat juga melihat ada seorang laki-laki tua lagi di kejauhan menyaksikan mereka. Rasanya Alif mengenalnya, tapi entah di mana.
Di luar para orangtua itu. Hanya tiga pasang manusia menyaksikan mereka. Alif mengucapkan kalimat yang pernah dia dengar waktu sepupunya mengucapkan ijab Kabul. Lalu apa yang dia berikan sebagai mas kawin? Alif pucat.
Tetapi bidadarinya memberikan sebuah kotak berisi cincin emas putih. Dia tersenyum. Cincin seberat 15 gram itu pemberian ibunya yang selalu dibawanya walaupun sedang bertugas. Alif ingat terakhir ditaruh di saku celana kombinya, tepatnya dalam dompetnya sewaktu naik pesawat. Jalan Tuhan buat dirinya, pikirnya.
“Iya, cuma ini yang aku punya,” kata Alif. Darimana bidadari itu menemukannya?
Namun Alif tidak merasa penting hal itu. Sebelum ijab kabul, ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan tak pernah dijawab oleh perempuan itu.
“Namaku Alif Muharram, kamu?” Dia menoleh ke wajahnya yang tertunduk.
Bidadari itu pelan-pelan menyebut namanya dengan tulus. “Zahra Puteri Fajar, Kakanda.”
Lelaki berjanggut putih itu mengangguk. Dia membimbing Alif mengucapkan kalimat ijab kabul.
Beberapa menit berlalu.
“Kalian sah menjadi suami istri. Selamat jadi warga kami anakku.”
Alif merasa lega. Dia tak perlu menyebut lagi bidadari. Pagi ini Zahra tidak tertawa seperti biasanya. Dia meneteskan air mata, lalu mencium tangannya dengan tulus.
Malam ini seluruh negeri merayakan resepsi pernikahan mereka. Sepuluh baris meja di tepi pantai. Pas bulan purnama. Di sepanjang tempat resepsi terdapat bambu-bambu yang digantung lentera semacam fosfor yang tak pernah dilihatnya.
Berbeda sewaktu makan siang kemarin Alif hanya melihat ratusan anak remaja seusia Zahra. Pada malam ini dia melihat belasan anak-anak berlarian. Umurnya antara 5-7 tahun. Mereka suka menumpang kereta semut.
Pada malam ini makanan dibagikan oleh manusia kunang-kunang yang terbang. Ya, Tuhan, warga negeri ini memuja serangga. Perbedaan lain yang membuatnya berbunga. Zahra duduk di sebelahnya.
Malam ini seluruh negeri menyantap semacam sup sayuran dan kepiting tang rasanya sama lezatnya. Sebagai teman santap malam adalah sari kelapa yang dicampur semacam manisan yang memberikan rasa yang tak pernah dicicipinya. Alif minum dengan lahap. Rasanya minuman itu semacam tonik yang bisa membuatnya tidak tidur malamini.
“Ini yang kamu sebut lebih manis dari ramuan madu kemarin?”
Zahra tidak segera menjawab. Kemudian dia tertawa geli. Tertawanya yang pertama untuk hari ini sejak tadi tegang. “Pura-pura nggak tahu. Ya, sudah nanti kamu tahu sendiri.”
Seorang laki-laki muda duduk di sampingnya. “Aku Andro. Semua warga di sini bekerja. Setelah tiga hari bersama Zahra, kakak juga harus bekerja. Para orangtua sudah menyediakan tempat untuk kakak di Rumah Mahkota sesuai dengan keahlian kakak.”
Alif mengangguk. ”Siap!”
“Tuh, Zahra sudah mengajak pulang,” bisiknya.
Alif melihat Zahra sudah bangkit sebelum resepsi selesai. Para tamu tampaknya memaklumi. Alif mengikuti Zahra ke ruangannya di salah satu bangunan. Dia menelusuri lorong demi lorong hingga di pintu unitnya. Unit? Seperti apartemen? Ini apartemen sarang lebah.
“Zahra tidak tinggal sendiri lagi,” ujar perempuan itu. “Kakanda tidak lagi tidur di kamar tamu.”
Jantung laki-laki itu berdegub kencang. Alif mengikutinya memasuki rumah Zahra yang warnanya didominasi biru muda. Warna kesukaan Zahra. Alif duduk di sebuah kursi semacam sofa. Dia mendengar suara air di kamar mandi. Gerah rupanya. Zahra keluar dengan baju mandinya.
“Kakanda mandi, airnya masih hangat.”
Alif melihat wajah Zahra menjadi lebih jelas karena sudah tidak memakai kain penutup kepalanya seperti yang dilakukannya ketika bertemu sebelum pernikahan. Rambutnya panjang hitam legam. Kulitnya putih sedikit kekuningan. Dia menerka wajah perempuan itu ada campuran Arab, dengan mungkin Sunda atau Jawa.
Zahra merasa diperhatikan. Dia berhenti sebentar hanya satu meter di depan Alif, memberikan kesempatan untuk melihat rambutnya yang indah dengan wajah meledek. “Nah, sudah jelas kan? Cepatan mandi?”
Alif segera beranjak tanpa banyak tanya lagi.
Dia kemudian merasakan tubuhnya segar kembali setelah berendam di air rempah-rempah dan bunga itu. Dia kemudian keluar dengan baju mandi berwarna cokelat yang ada di rak hexagonal itu. Di lemari ruang makanan ada berapa tabung tertutup berisi minuman madu. Tabung ini mengingatkan Alif pada minuman kaleng di dunianya dulu.
“Zahra, aku mau minum dulu. Di lemari berapa minuman madu,”
“Ya, bawa kemari minumannya kakanda, juga untuk aku.” Suara Zahra terdengar agak manja dalam kamar.
Dengan agak canggung Alif membawa dua tabung kaca berisi minuman madu itu ke dalam kamar Zahra. Dia kemudian menyadari ada yang lebih manis dari minuman madu itu. Jantungnya kian berdetak kencang.
SEPULUH
Sebuah bangunan di kawasan Setiabudi Bandung
Ketika Alif berusia sembilan tahun
Alif turun dari angkot jurusan ledeng, Kang Parman mengikutinya dari belakang. Alif agak kesal juga ibunya tak melepasnya ke luar tanpa ditemani laki-laki berusia 20 tahunan itu. Agak susah menemukan nomor 225 di jalan itu sesuai dengan kartu namanya.
Akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang cukup besar yang lazim ditemukan di kawasan Bandung Utara.Pagarnya tertutup rapat sampai seorang perempuan setengah baya menggendong seorang anak balita membukakan pintu pagar.
Alif memasuki halaman rumah itu. “Pak Nanang…?”
“Sudah menunggu kamu di dalam…”
Alif melangkah masuk dan dia melihat beberapa anak usia empat atau lima tahun di dalam ruang tamu. Masuk lagi ke dalam ada beberapa lagi.Alif merasakan ada kesedihan mendalam.
Pak Nanang muncul dan memberikan isyarat Alif mengikutinya. “ Mau menengok kawan barumu?”
Alif mengikuti Pak Nanang ke sebuah kamar di bagian belakang. Mereka melewati taman belakang. Belasan kereta bayi dan berapa pengasuh. Alif menitikan air mata, tangisan tertawa dan celoteh bercampur menjadi satu.
“Mereka tadinya seperti bayi itu?”
“Betul anakku, betul anakku. Kami sudah menampung lebih dari tiga puluh bayi sejak yayasan ini berdiri. Ini baru di Bandung, dari Jakarta sudah merengek minta mengirim ada 20-an lagi, bayi-bayi yang dibuang, dari Tangerang, Bogor, baru Jawa Barat anakku sudah ratusan dalam lima tahun,”
“ Apa tempat ini bisa menampung, kalau jumlahnya semakin banyak?”
Pak Nanang tidak menjawab. “Entahlah.”
Alif basah matanya. Pelan-pelan ia memasuki sebuah kamar. “Kok saya jadi cengeng? Anak laki menjadi cengeng?”
“Itu tandanya kau punya hati,”
“Ada orangtua yang ingin punya anak tetapi tidak diberi. Ini dikasih kok dibuang? ”Alif bertanya dengan lugu.
Mereka terus berjalan.
“Seandainya ada satu negeri yang menerima anak-anak seperti ini dan tidak ada orang di negeri itu yang memandang seorang bayi yang dilahirkan patut disesali. Karena itu dosa orangtua mereka dan bukan dosa bayi.”
Nanang Sumarna terdiam. Dia merasa kalimat terakhir Alif terlontar dari hati. “Suatu negeri yang belum pernah ada tapi akan ada.”
Alif kemudian menemukan kawan barunya. Seorang bayi perempuan yang sedang digendong seorang pengasuh perempuan. Alif mencium keningnya.
“Kamu boleh kasih nama. Kamu berhak kasih nama.”
“Dia lebih kecil dari atom kata guru agama aku. Sangat kecil di dunia yang kejam ini. Nama depannya Zahra. Dia aku temukan di fajar yang beku. Tetapi dia putri yang cantik. Aku namakan Zahra Putri Fajar.”
Bayi itu merespon jemari Alif.
“Nama yang bagus Nak.Tampaknya dia ingin kamu bersamanya.”
“Bisa apa aku? Tetapi kalau aku bertemu dia nanti sesudah besar. Kita bisa jadi temanan nggakyaa?” Alif polos.
Terdengar suara Kang Parman dari luar. “Lif, nanti Ibu kamu marah kalau pulang malam.”
Nanang Sumarna mengangguk. Dia memberi isyarat pada Kang Parman untuk menyediakan sedikit waktu untuk Alif.
“Kakak pergi dulu yaa.” Dia mencium kening bayi itu dengan lembut. Moga kelak kita jumpa lagi. Kakak janji kalau nanti jadi orangtua tidak akan mau seperti orangtua kamu.”
“Kamu anak baik Alif.”
(BERSAMBUNG)
Irvan Sjafari
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI