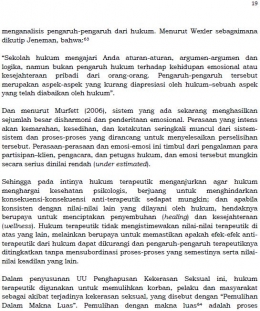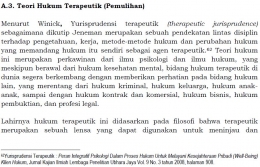Pagi ini saya membaca artikel Darurat Kekerasan Seksual pada Perempuan pada Kompas edisi cetak yang ditulis oleh Sri Wiyanti Eddyono. Penulis menyatakan,
"Kelompok masyarakat sipil dan Komnas Perempuan, misalnya, telah bolak-balik berkonsultasi di sejumlah daerah untuk menyempurnakan draf RUU ini, bahkan telah disampaikan kepada DPR sejak 2014 .... Ada beberapa anggota DPR mempertanyakan mengapa harus ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sementara telah ada RKUHP .... DPR perlu segera menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU Inisiatif DPR yang sudah nyata-nyata sangat komprehensif dalam merespons berbagai masalah yang ditemukan korban kekerasan."
Saya pun bergegas untuk mencari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai sebagai sangat komprehensif oleh Ibu Sri. Selaku dosen mata kuliah Psikologi & Intervensi Sosial, saya memang turut menaruh perhatian secara khusus terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan, sejauh ini diantaranya melalui tiga cara: (1) Mengembangkan kapasitas diri dalam melakukan konseling terhadap laki-laki pelaku kekerasan (November, 2014); (2) Memfasilitasi mahasiswa menyelenggarakan kegiatan edukatif terkait pencegahan kekerasan; serta (3) Mempublikasikan artikel terkait dalam jurnal internasional.
Yang saya temukan melalui mesin pencari Google adalah sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang bersumber dari situs web DPR RI bertanggal 10 Februari 2017. Hal yang cukup surprising, sekaligus membesarkan hati saya, adalah bahwa Naskah Akademik RUU ini menjadikan artikel saya sebagai referensi dari salah satu teori utama yang dijadikan landasan, yakni Teori Hukum Terapeutik (Pemulihan), walaupun nama saya ditulis secara tidak akurat, yakni: Jeneman (lihat Gambar 2 dan Gambar 3).
Artikel itu saya tulis sembilan tahun yang lalu, ketika saya sedang menempuh studi Magister Psikologi Sosial, berjudul "Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum", pada Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 9 No. 3 tahun 2008 (Gambar 1). Pada saat menulis artikel tersebut, saya memang berupaya mencari padanan terminologi "Therapeutic Jurisprudence" yang sedang saya dalami. Akhirnya saya memilih untuk mentranslasikan dekat dengan istilah aslinya, menjadi "Yurisprudensi Terapeutik". Alasan saya adalah bahwa di tengah-tengah langkanya diskusi tercatat mengenai hukum terapeutik, khususnya di kalangan komunitas keilmuan Psikologi pada saat itu, saya bermaksud untuk secara kuat memperkenalkan konstruk ini agar dapat diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia Indonesia. Tak dinyana, konstruk ini semakin relevan hingga pada 18 Januari 2017 yang lalu, saya menulis sebuah twit, sebagai berikut: "Bangsa kita kini, apa2 diproses hukum. Kita semakin perlu pemahaman dasar ttg Yurisprudensi Terapeutik".
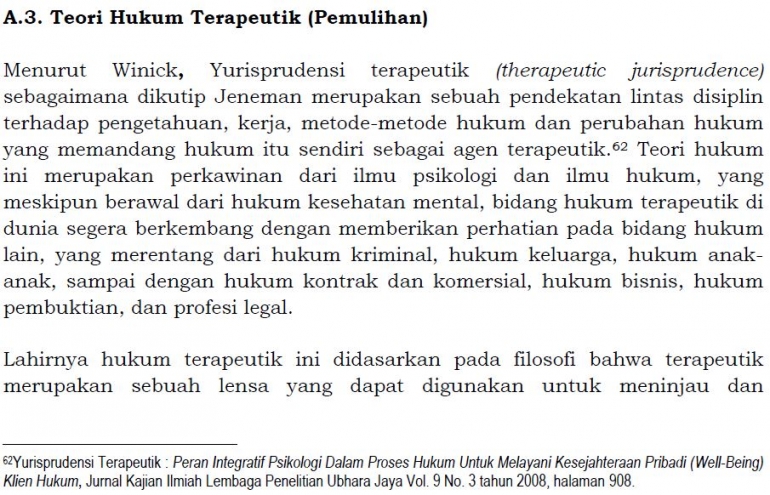
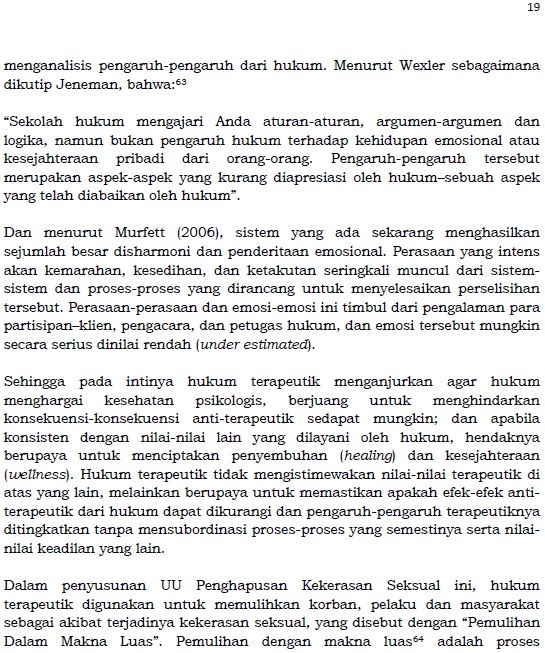
Inilah kebahagiaan seorang peneliti itu: mengetahui bahwa tulisannya dirujuk (istilah keren sekarang: disitasi; beberapa orang menyebutnya: "disitir", "disitat"), karena hal itu bermakna bahwa tulisan sang peneliti memiliki dampak, membumi, bukan "di atas", "di menara gading". Saya sungguh patut bergembira, lebih-lebih kali ini, oleh karena artikel Yurisprudensi Terapeutik dijadikan salah satu bahan bangun kebijakan publik pada tingkat perundang-undangan di negeri ini. Sebelumnya, artikel ini dijadikan referensi oleh Hakim Pengadilan Agama Painan, Sumatera Barat, dalam artikelnya yang berjudul Kompetensi Komunikasi Petugas Meja Informasi: Menimbang Komunikasi Terapeutik dan Implikasinya terhadap Penerapan Yurisprudensi Terapeutik (2012, halaman 16-19).
Ada perlunya saya mengajak kita semua untuk melihat arti penting kutipan (sitasi/citation) bagi komunitas ilmiah dan komunitas umum. Sudah sejak tahun 1984, Taylor Graham mengemukakan signifikansi dari sitasi. Ia mulai dengan menjelaskan sebuah asumsi dasar bahwa riset/penelitian adalah sebuah proses sosial, tidak berlangsung dalam ruang hampa. Oleh karena itu, masuk akal bagi dunia untuk memiliki sebuah sistem komunikasi yang merekam proses sosial ini. Secara fungsional, sistem sitasi yang merupakan bagian dari sistem komunikasi itu dapat (1) mendiseminasikan pengetahuan, (2) mengukur kontribusi individu dan kelompok ilmuwan terhadap petumbuhan pengetahuan, (3) menandai prestasi/karier akademisi serta lembaga tempatnya bekerja, (4) mendistribusikan kredit dan rekognisi dalam pengembangan gagasan dalam bidang tertentu, serta (5) memelihara secara konsisten sebuah tradisi normatif terstandar yang baik dalam memfasilitasi dinamika produksi pengetahuan baru.
Dalam hal ini, secara lentur, saya dapat membedakan antara sitasi teoretis dan sitasi praktis. Walaupun keduanya tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan, sitasi teoretis lebih menunjuk pada penggunaan kutipan untuk mengembangkan konsep, subject matter, proposisi atau tesis ilmiah baru (Metrik-nya sering disebut "Impact Factor"; SJR Rank, H-index); sedangkan sitasi praktis lebih menunjuk pada kegunaan pengutipan dalam praktik pemecahan masalah konkret, aplikasi konsep dan teori dalam terapi, pelatihan, intervensi, atau perumusan kebijakan yang nyata-nyata berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah sitasi teoretis terhadap hasil-hasil penelitian saya bersama tim, saya paparkan dalam situs web personal saya sebagai sebuah rekaman historis diri. Adapun terkait dengan sitasi praktis, terdapat sejumlah jalan untuk memperbesar peluang terjadinya jenis sitasi ini. Salah satunya adalah dengan membahasa-populerkan artikel-artikel penelitian yang terbit di jurnal dan prosiding ilmiah. Portal-portal yang membahas temuan-temuan riset yang dapat dijadikan model oleh media massa di Indonesia adalah ScienceDaily.com dan PsychologyToday.com.
Sejauh saya amati, media massa kita masih kurang tekun meliput perkembangan temuan riset sosial yang dilakukan oleh dosen/peneliti di dalam negeri sendiri dalam berbagai skalanya. Tidak heran apabila ada pihak-pihak yang menyatakan fakta bahwa kebanyakan riset sosial kita tersimpan di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam wawancara di Harian Bernas, kolom Bernas Inspirator, saya menyebutkan bahwa ada sebuah kerinduan akan "mentransformasikan tulisan-tulisan ilmiahnya ke dalam bahasa yang jauh lebih 'nge-pop' agar dapat dinikmati oleh publik yang lebih luas". Berkaitan dengan hal terakhir ini, sebenarnya mimpi bukan hanya mimpi; saya pernah mengajukan lamaran kepada Beasiswa Belajar Menulis Ilmiah Populer yang diselenggarakan oleh Tempo Institute-Knowledge Sector Initiative (KSI). Meskipun belum memperoleh kesempatan beasiswa itu, saya merekomendasikan kegiatan KSI tersebut maupun kegiatan-kegiatan sejenis untuk seluruh dosen dan peneliti yang memiliki kerinduan yang sama untuk mendarmabaktikan ilmu dan profesionalismenya kepada masyarakat seluas-luasnya (tidak terbatas di kalangan kampus).
Tidak Muluk
Hal yang disinyalir oleh Saudara Rendra Trisyanto Surya mengenai eksistensi dosen "nakal" yang membuat karya palsu untuk menjadi profesor memang sangat tidak dapat kita anggap sepi. Demikian pula, laporan David Kroll dalam Forbes yang mengungkap bahwa Profesor Universitas merupakan "a stressful job" pun banyak kebenarannya.
Kendati demikian, di tengah-tengah realitas plural mengenai dosen dan guru besar di atas, salah satu fakta yang tidak bisa kita nafikan adalah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup dosen dan peneliti tidak selalu bergantung pada hal-hal yang bersifat material dan reputasional. Ada kebahagiaan intrinsik-intensif yang diperoleh peneliti hanya dengan "terpeleset mata" bahwa karya teoretis dan empirisnya berguna barang sedikit untuk menyusun sesuatu yang berpotensi mengubah nasib masyarakat ke arah yang lebih baik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H