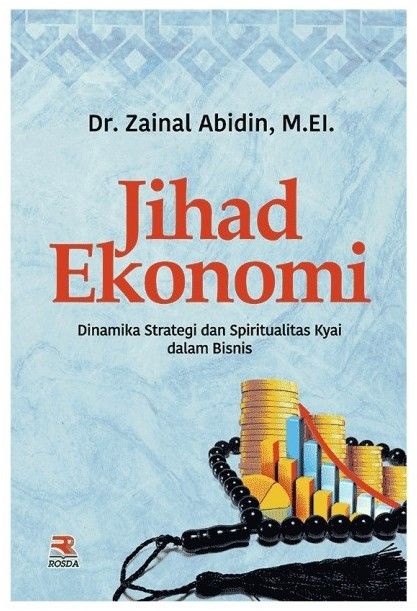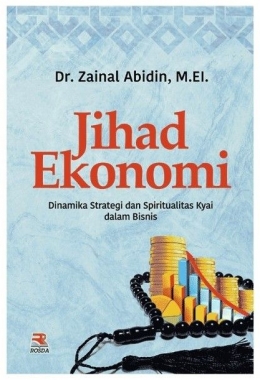Penulis buku, Zainal Abidin, berikhtiar meluaskan makna jihad yang kadung menyempit. Jihad tak melulu berasosiasi berperang fi sabilillah di medan laga. Medan jihad membentang pula pada perbaikan kesejahteraan menyangkut hajat hidup banyak orang, yakni: bidang ekonomi umat.
Dalam bab awal, pembaca seakan-akan dipecut terhadap paradoks antara agama dan ekonomi. Pemisahan keduanya yang sering disebut sekularisasi ini, nyatanya kerap menghilirkan ketimpangan sosial-ekonomi amat tajam.
Buku ini menelusuri sebab-musababnya dan, tak berposisi menjustifikasi label sekularisasi dan atau islamisasi. "Islamisasi", yang kala hari-hari ini telah banyak produk undang-undang yang menitikberatkan simbolisasi term agama pada diksi perbankan syariah, misalnya. Titik poin buku tidak membincang sarana dan prasarana "syariah" yang telah terlembagakan tersebut walau tampak kurang menjejak di masyarakat/umat.
Karena itu, Zainal Abidin menguar titik berangkat yang lebih membumi. Yakni, tengara pada sosok kiai. Sebagai pemimpin umat, atau mereka yang mengasuh pesantren, kiai adalah manifesto gerak santri dan masyarakat sekitar pesantren babakan laku keberagamaan.
Labelisasi kiai semacam ini memang benar adanya tapi menurut Zainal, mestinya tidak berhenti di satu titik tersebut. Peran kiai idealnya melebar pula pada urusan pemberdayaan ekonomi.
Ditilik mendalam, teks-teks keagamaan yang dikaji para santri, menyinggung banyak hal seputar laku perekonomian. Kitabul mal alias pembahasan seputar tata kelola harta benda, adalah sejumput kajian yang diajarkan di pesantren melalui pelajaran fikih, tarikh, tasawuf, dsb.
Hanya saja, kalangan santri dicukupkan pada lingkup pengetahuan/teori tanpa praktik lapangan. Pun, oleh tokoh sentral pesantren itu sendiri; tak banyak kiai "keluar" pesantren sejenak menjadi aktor kegiatan ekonomi.
Perspektif sosok kiai di sini bukanlah ustad atau syekh seperti citra yang lalu lalang di layar kaca/familiar. Selain tinggal di perdesaan, sejumlah kiai yang diteliti sekadar berpunya usaha bisnis cakupan kecil-menengah. Tidak sampai pada usaha besar yang berpunya ratusan karyawan dan omzet hingga miliaran rupiah.
Dalam manajerial waktu, para kiai ini tidak lantas pula terbawa dalam arus totalitas berbisnis. Justru, mereka tetap sanggup istikamah menjalankan kehidupan spiritualitas dan keilmuan di pesantren; meskipun tentunya tidak sesemaksimal andaikata tidak berpunya usaha-bisnis.
Peran kiai, ajengan, buya, dalam kultur masyarakat Indonesia, bisa dimasukkan sebagai agen perubahan sosial. Pengaruhnya amat besar dalam kemudi wilayah sosial-budaya; tapi tidak banyak yang sampai pada sekup perekonomian. Buku ini mengenalkan kiai sebagai antitesis.