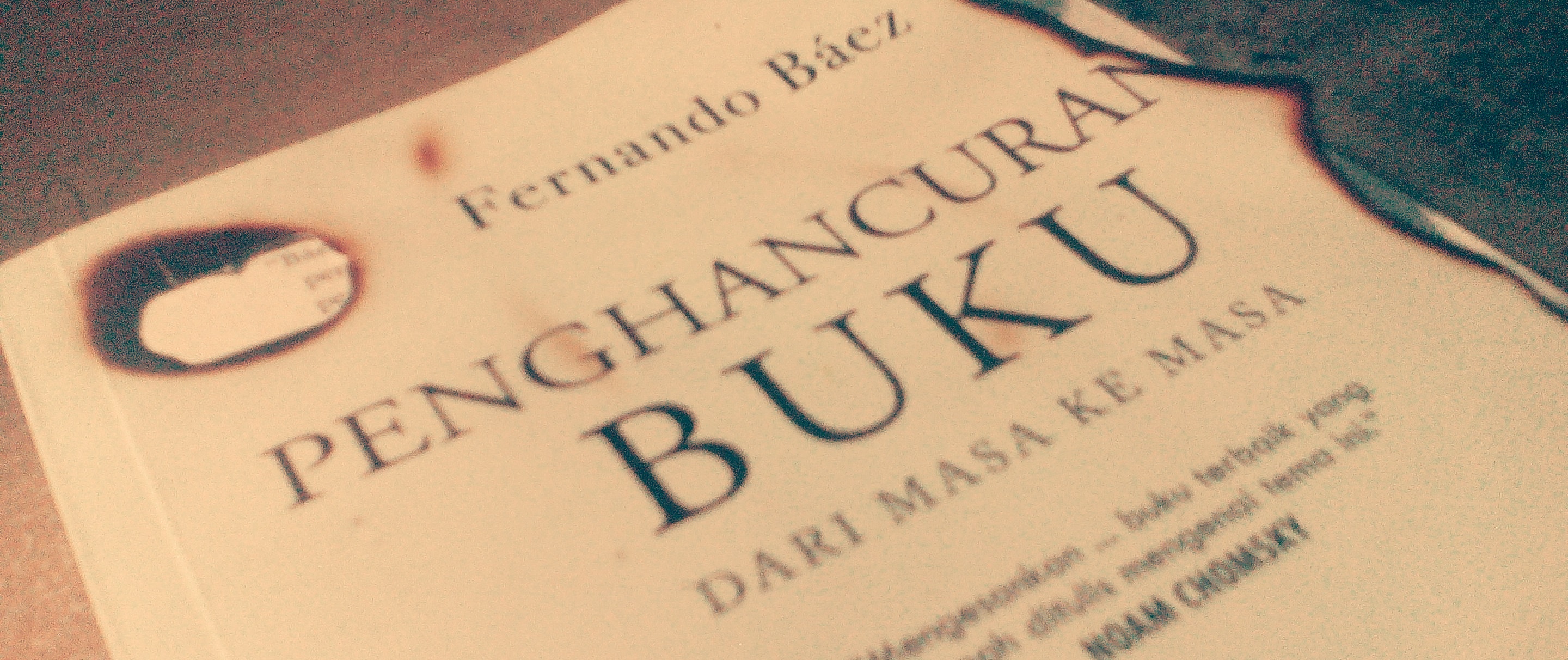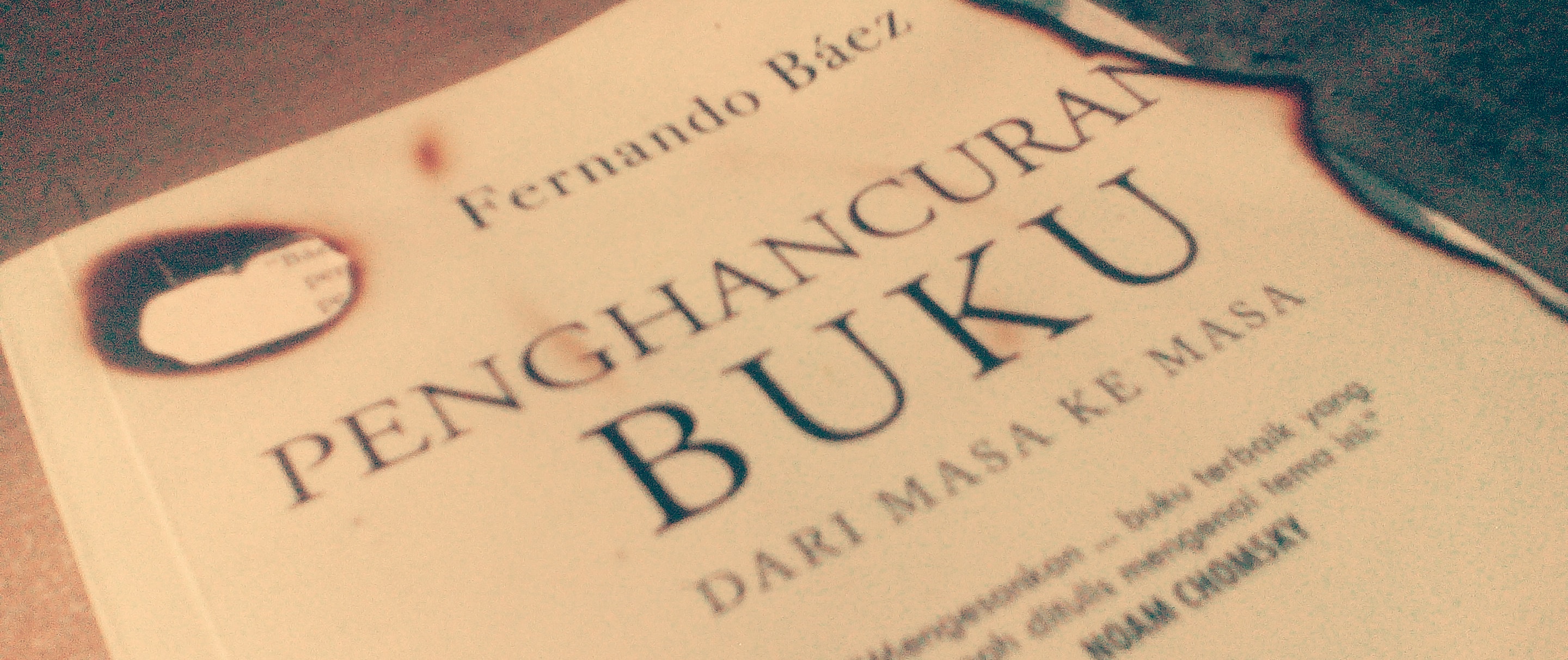Dengan pemahaman seperti diatas, terkadang saya merasa kebingungan ketika mendengar ada pelarangan bedah buku atau mungkin pemusnahan buku, seperti yang terjadi di Bali kemarin. Walaupun sebetulnya pelarangan / pembunuhan buku (librisida) sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan dahulu. Ada peristiwa pelaranganbuku Student Hidjo yang ditulis Mas Marco Kartodikromo, dan penangkapan sejumlah penulis yang mengkritik pemerintah kolonial.
Pasca kemerdekaan Indonesia pun, pelarangan buku masih saja terjadi, contohnya buku Demokrasi Kita karya Mohammad Hatta, dan Hoa Kiau di Indonesia karya Pramoedya Ananta Toer (Baez,2015:vii). Pasca reformasi pun, aksi pelarangan buku tetap berlanjut. Contohnya pelarangan buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa, dan yang terbaru adalah pelarangan bedah buku di event UWRF di Bali akhir Oktober 2015 lalu.
Hal ini tentu memprihatinkan kita semua. Karena pasca kemerdekaan, bangsa kita justru meniru praktek librisida yang dulu dilakukan oleh para penjajah dan sangat kita benci. Andaikan buku diidentikan sebagai simbol ilmu pengetahuan, maka librisida adalah bentuk penolakan atas ilmu pengetahuan serta kemajuan peradaban. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, jika kita terus mengingkari ilmu pengetahuan dan menolak perbedaan pikiran?
Sudah saatnya kita melawan ketakutan atas perbedaan yang ada dan belajar kembali menghargai perbedaan pemikiran. Ada banyak jenis buku yang kita sukai diluar sana, dan mungkin ada juga buku-buku yang kurang kita sukai. Kalau kita tidak menyukai buku tertentu, ya tidak perlu membaca buku tersebut. Atau mungkin kalau kita mau sedikit idealis, kita bisa mulai menulis buku sebagai bantahan atas buku yang kita rasa tidak bagus. Lawan tulisan dengan tulisan, lawan pemikiran dengan pemikiran, lawan buku dengan buku. Sesederhana itu analoginya. Dengan seperti itu, akan muncul budaya berpikir kritis dan mengedepankan akal sehat, bukan budaya kekerasan dan adu otot.
Pelarangan buku maupun librisida membuktikan bahwa pelaku meremehkan daya kritis pembaca, karena menganggap semua pembaca akan menelan mentah-mentah informasi dari buku tanpa filter sedikitpun. Padahal, bukankah hanya anak-anak atau orang yang belum dewasa yang menelan mentah-mentah informasi yang dibaca dari buku, karena memang belum mempunyai daya kritis yang cukup. Lalu apakah di masyarakat kita sekarang, semuanya masih berusia kanak-kanak? Atau jangan-jangan pikiran kita yang kekanak-kanakan?
Mari mulai sekarang, kita belajar merawat buku. Karena sejatinya, dengan merawat buku kita merawat nalar dan pemikiran manusia. Sebagaimana nasehat penulis lampau Jerman, Heinrich Heine: “Dimanapun mereka membakar buku, pada akhirnya mereka akan membakar manusia”.
***
Referensi: Baez, Fernando, Penghancuran Buku Dari Masa ke Masa, Marjin Kiri, Tangerang, 2015.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H