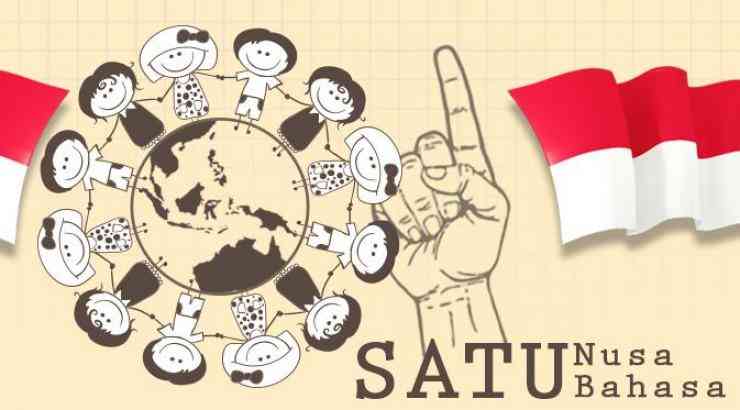Kebetulan sekarang masih dalam bulan Oktober, yang juga menjadi Bulan Bahasa 2022. Tentu, sesekali kita perlu juga secara serius melakukan perenungan terkait berbagai aspek kebahasaan.
Perenungan tersebut bisa bersifat introspeksi pada diri kita masing-masing. Sejauh ini, seperti apa kita menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, bangsa Indonesia.
Paling tidak, saat kita berbicara secara formal dalam sebuah forum pertemuan, atau saat menulis yang akan dibagikan kepada banyak orang, sedapat mungkin kita sebaiknya memperhatikan kaidah berbahasa yang baik dan benar.
Adapun dalam bahasa pergaulan sehari-hari, masih bisa ditolerir bila kita berbahasa gado-gado, campuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa Inggris.
Perenungan tersebut bisa pula dilihat dari sisi makro, maksudnya dari sisi fenomena berbahasa masyarakat kita secara umum.
Ada peribahasa Melayu yang dulu sangat terkenal, yang berbunyi "bahasa menunjukkan bangsa".
Secara tersirat, pengertian peribahasa itu sudah cukup jelas, yaitu terkait dengan identitas atau asal usul seseorang yang bisa diketahui dari bahasanya.
Namun, tahukah Anda apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "bangsa" dalam peribahasa tersebut?
Jangan keliru, bangsa yang dimaksud bukanlah apa yang kita kenal sekarang seperti dalam penyebutan "Bangsa Indonesia".
Dalam pemahaman masyarakat Melayu di zaman dulu, bangsa juga bisa dikaitkan dengan status seseorang, apakah tergolong kaum bangsawan atau masyarakat biasa.
Memang, dulunya Melayu berupa kerajaan. Bahkan, jumlah kerajaannya tidak hanya satu kalau kita melihat bekas peninggalan Kerajaan Melayu Deli, Melayu Riau, Melayu Palembang, dan sebagainya.
Jadi, kata "bangsa" mengacu pada bangsawan sebagai warga golongan atas ketika itu.
Kemudian, para ulama juga menempati strata sosial lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa yang kebanyakan jadi petani atau nelayan.
Nah, penafsiran terhadap peribahasa "bahasa menunjukkan bangsa" semakin berkembang setelah Indonesia meraih kemerdekaan.
Para pemimpin kita telah bersepakat untuk memakai sistem pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi.
Dengan demikian, dalam memilih pemimpin, kita tak lagi melihat status sosial. Pada dasarnya, siapapun boleh saja menjadi bupati, gubernur, dan bahkan presiden.
Bukankah Presiden RI sekarang ini, Joko Widodo, berasal dari kalangan masyarakat kebanyakan?
Kehidupan masa kecil Jokowi sungguh kehidupan yang sangat sederhana. Beliau tinggal di rumah bilik di pinggir kali.
Orangtua Jokowi kerap berpindah-pindah rumah kontrakan dan yang sesuai dengan kemampuan ekonominya hanya di kawasan kumuh.
Hal itu bisa dibaca dalam buku "Jokowi Menuju Cahaya", karya Alberthiene Endah yang diterbitkan pada tahun 2018.
Ayah Jokowi, Wijiatno Notomiarjo, berjualan bambu dan kayu di lapak sederhana dalam pasar tak jauh dari rumah.
Dalam berkomunikasi sehari-hari, Jokowi menggunakan gaya bahasa, intonasi, dan ekspresi yang merakyat.
Tapi, tentu dalam forum yang bersifat formal, beliau berupaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Nah, meskipun pemilihan presiden berikutnya baru akan dilaksanakan pada 2024, sekarang nama-nama tokoh yang disebut-sebut akan menjadi calon presiden, mulai diramaikan media massa.
Diharapkan para pemimpin kita, terutama pemimpin partai politik, tetap mengutamakan prinsip demokrasi dengan menyerap aspirasi rakyat banyak.
Janganlah memberikan keistimewaan pada seseorang karena semata melihat faktor keturunannya.
Jangan pula terpukau dengan bahasa yang penuh istilah "tinggi" berbau akademis dari seseorang yang berminat untuk jadi pemimpin bangsa.
Semoga kita berhasil mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup rakyat.
Kepentingan rakyat harus diletakkan lebih tinggi dari kepentingan pribadi, keluarga, partai, etnis, dan golongan lainnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI