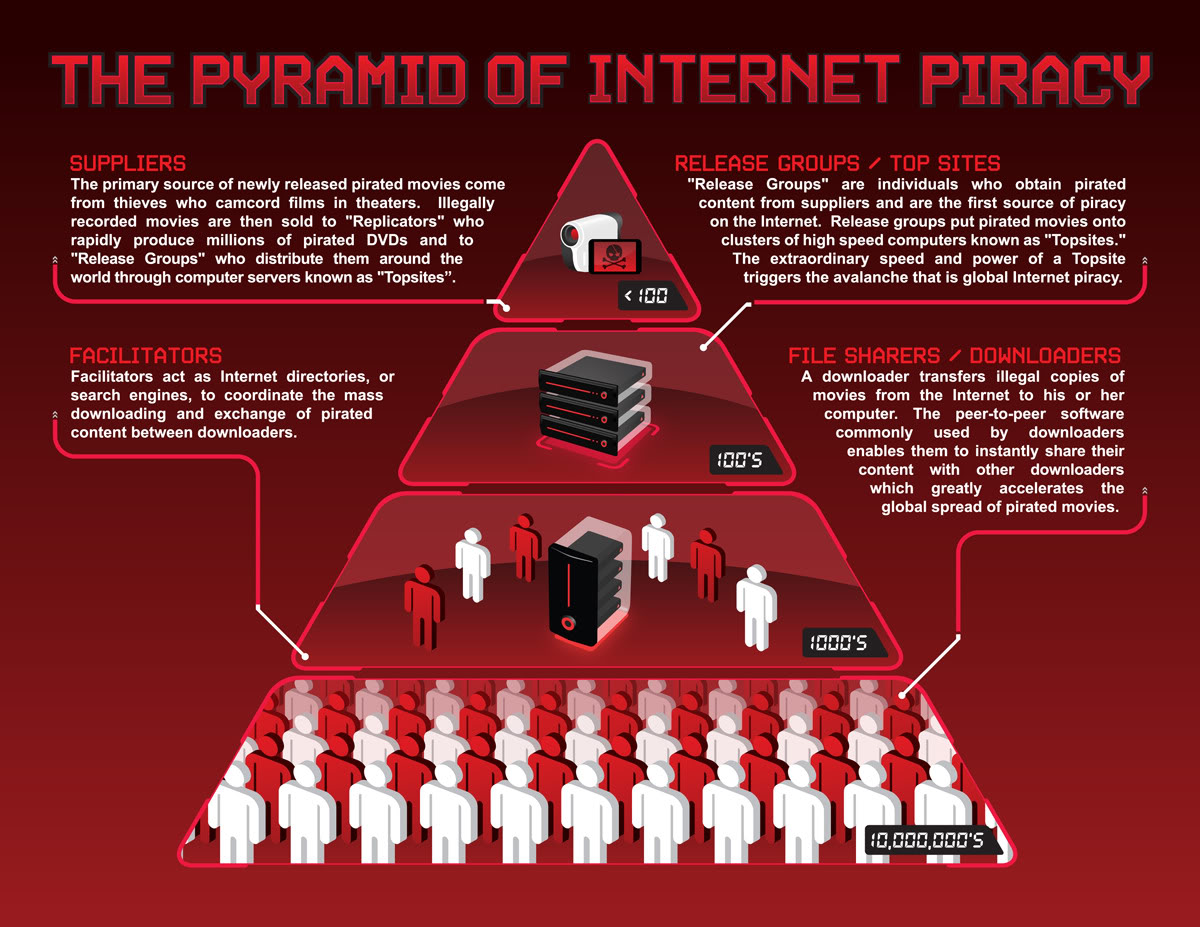Tanpa ada niat membenarkan pelaku pembajakan dan peretasan, yang mesti dilakukan oleh industri adalah mengubah model bisnis mereka. Termasuk model produk yang open-platform dimana setiap konsumen/orang bisa berpartisipasi meningkatkan nilai.
Lawrence Lessig, aktivis pengurangan pembatasan hukum atas hak cipta, merek dagang, dan spektrum frekuensi radio, menyebutkan kita tengah hidup dalam Remix Culture. Tak ada lagi produk final karena setiap orang akan melakukan pencampuran (remix) untuk meningkatkan nilai. Teknologi kolaboratif seperti internet mempermudah prosesnya.
Dalam musik, contoh nyata remix culture ini ada dalam mashup: mengkomposisikan karya musik eksisting menjadi karya baru lewat penggabungan atau modifikasi. Dalam hukum industri, mashup bisa dianggap pembajakan. Mirip dengan kisah Lego di atas, sebuah produk tidak boleh diutak-atik. Tapi mashup bertebaran di internet. Di Indonesia ada Eka Gustiwana sebagai salah satu musisi mashup tenar. Dubsmash yang ngetop akhir-akhir ini adalah platform mashup.
Yang melakukan 'pembajakan' mashup kebanyakan ini adalah para fans musisi atau lagu yang mereka mashup. Karena suka, maka mereka mashup. Hasil mashup mereka bagikan di media sosial. Artinya musisi dan label dapat promosi gratis. Mereka setia menonton musisi itu di televisi atau membayar tiket untuk konsernya. Kalau si artis jadi bintang iklan, mereka beli produknya. Mereka ikuti akun media sosial si musisi sehingga bisa jadi buzzer. Bagi musisi atau label, mashup adalah pembajakan. Tapi bagi pelakunya, mashup adalah tanda cinta, loyalitas dan kontribusi mereka kepada musisi. Lalu apakah aset berharga ini harus dimusuhi atau ditangkapi?
Melawan pembajakan musik dalam bentuk apapun hanya akan menguras waktu, energi dan uang. Tak mungkin menang. Sebaliknya, musisi atau label yang bersikeras mengambil jalur ini rentan menempatkannya pada posisi public enemy: dimusuhi, dimaki dan ramai-ramai dibikin tidak laku lagi.
Yang diperlukan oleh industri musik saat ini, kata Lessig, adalah menciptakan musik yang terbuka bagi partisipasi kreativitas. Dalam industri musik model bisnis sebenarnya juga sudah berubah. Musisi atau label tak lagi mengandalkan pemasukan dari penjualan lagu. Tapi dari honor memanggung, bintang iklan atau film, merilis produk unik, buzzer media sosial, dll.
FILM SEBAGAI HIBURAN MULTI-PLATFORM
Industri film 'masa lalu' -- dan umumnya saat ini -- hanya punya tiga cara menghasilkan uang: tiket bioskop, jual DVD dan jual film ke televisi. Faktanya, dari waktu ke waktu penjualan DVD terus menurun meski tanpa pembajakan. Awalnya adalah penyewaan DVD, kini menjadi video on demand (VOD). Motifnya sama: mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Kalau bisa keluar uang Rp10.000 lewat VOD kenapa harus beli DVD Rp100.000?
Begitu juga dengan tiket bioskop. Untuk menikmati film baru, orang tak harus lagi ke bioskop. Cukup nonton berbayar di Netflix -- yang belum hadir di Indonesia. Bayar 1, bisa ditonton ramai-ramai. Kenapa harus keluar uang Rp500.000 untuk nonton bioskop 10 orang kalau Rp10.000 dari VOD bisa menonton film yang sama beramai-ramai?
Kehadiran teknologi VOD seperti Netflix nyatanya telah mengubah industri film yang dulu diandalkan dari penjualan tiket -- yang bila laku keras disebut Box Office. Dulu dari jumlah tiket (satu orang satu tiket) popularitas film bisa diukur. Tentu saja masih akan ada orang yang akan duduk di ruang gelap selama dua jam bernama bioskop untuk menonton film. Tapi dengan VOD pengukuran Box Office tidak relevan lagi.
Sekarang industri film sudah makin sadar bahwa selama ini mereka mengabaikan elemen-elemen lain dalam bisnis hiburan. Mereka tak lagi terpaku pada bisnis tontonan layar lebar. Mereka sadar bahwa secara umum tugasnya adalah menghibur. Kata Jerry Bruckheimer, produser terkenal Hollywood, "Kami berada dalam bisnis hiburan. Kami akan menghibur anda di bioskop, tivi dan game."
Langkah itulah yang diambil industri film yang memutuskan memutar mencari arah lain ketimbang hanya memaki-maki jalan buntu pembajakan. Daripada sibuk mengubah orang (baca: memburu pembajak), lebih baik mereka mengubah dirinya sendiri. Film layar lebar saat ini juga tayang sebagai serial tivi. Avenger contohnya. Spiderman hadir di game, laku keras pula. Merchandise turut dirilis. Bahkan kartu kredit saya pun edisi Batman. Maklum, I'm the night!