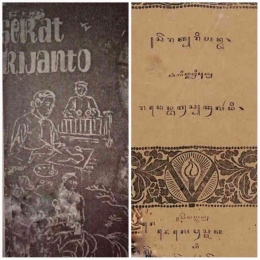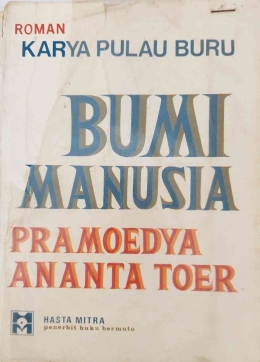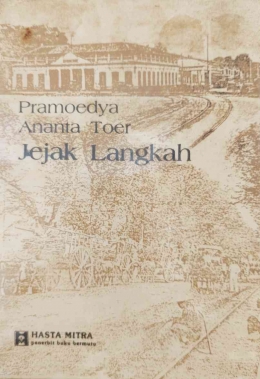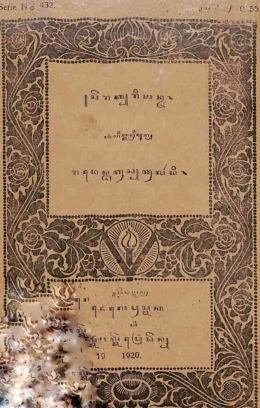Dominasi karya-karya yang bersifat hiburan dan didaktis di dalam karya sastra Jawa modern pada awal pertumbuhannya bertolak dari asumsi sebagian masyarakat Jawa bahwa keberadaan karya sastra untuk didengarkan dan bukan untuk dibaca.
Beralasan kiranya jika kemudian ada yang menyatakan bahwa sampai tahun 1960-an kesadaran keterlibatan pengarang dengan dunia pendidikan masih tampak dengan jelas.
Keadaan kurang menguntungkan ini mengondisikan karya sastra Jawa modern menjadi karya romantik didaktik atau naratif fiktif. Di dalam karya-karya naratif fiktif, karya sastra Jawa terjebak dalam konsep isi sing migunani.
Perubahan corak di dalam karya sastra tidak hanya terjadi pada sifat dan bentuk karya sastra, tetapi menyangkut pandangan pengarang mengenai berbagai hal yang melingkupinya.
Persoalan yang selalu mengundang perhatian dalam karya sastra yang tumbuh dan berkembang di Indonesia (juga negara lain) adalah persoalan ideologi, nasionalisme, dan kebudayaan.
Ketiga persoalan itu menjadi menarik karena tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan masalah sosial politik, dan ketiganya berada dalam dua sisi mata uang tak terpisahkan. Ideologi telah menjadi bagian yang tak terelakan dari sejarah kehidupan manusia.
Kasus pelarangan novel-novel panglipur wuyung pada tahun 1960-an, pengadilan atas cerita pendek "Langit Makin Mendung" karya Ki Panji Kusmin dan rangkaian novel Bumi Manusia serta Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer, tidak dapat dilepaskan dari persoalan ideologi.
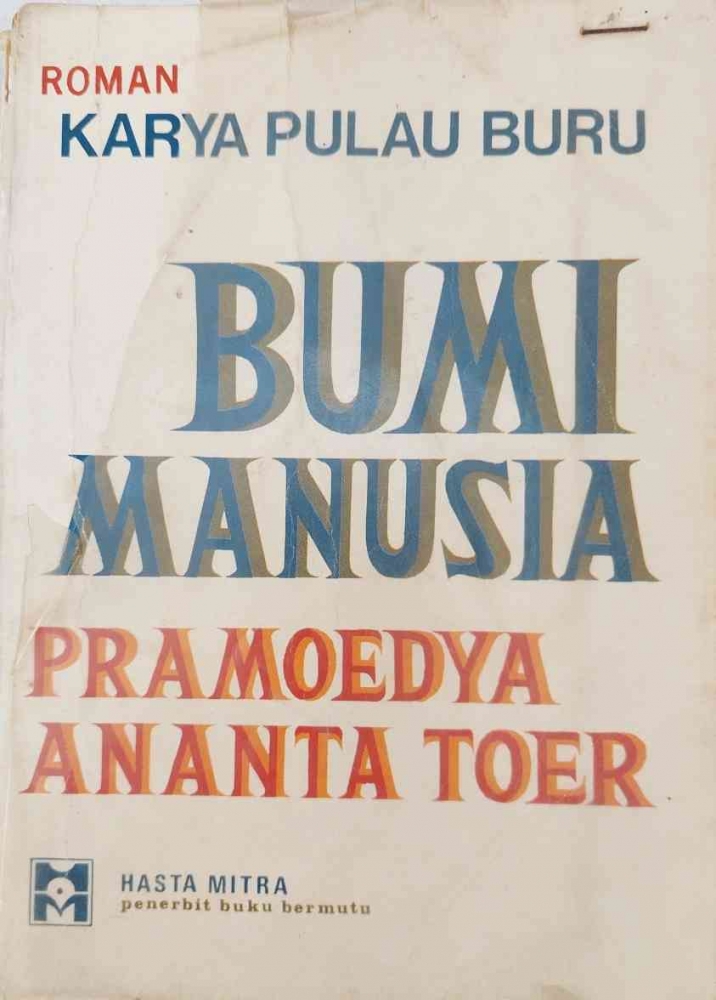
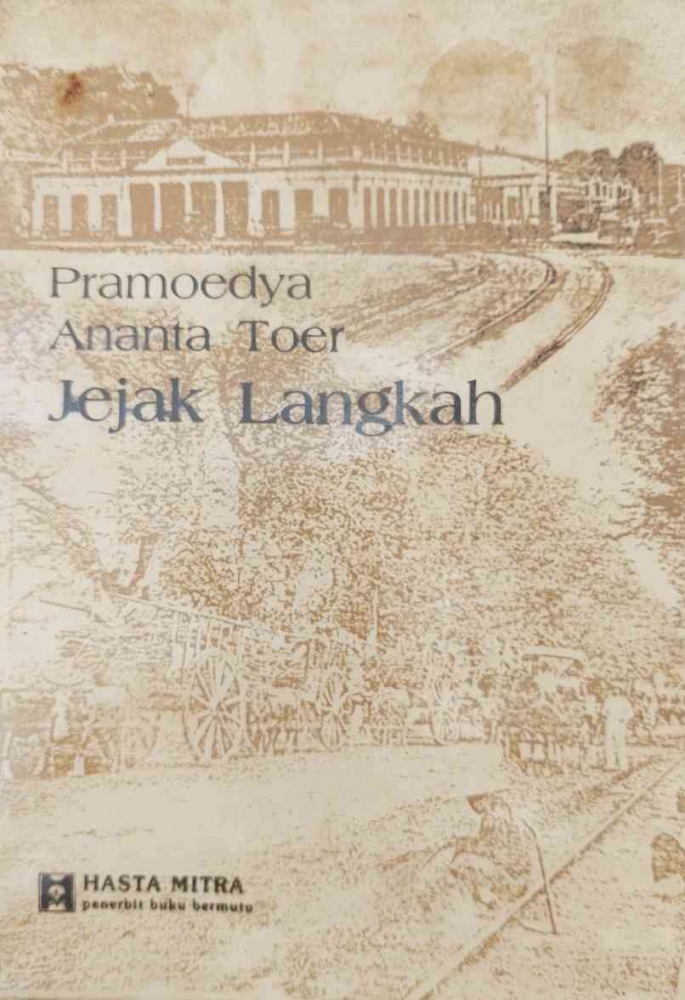
Dalam sastra Indonesia, diskurs narasi nasionalisme dan kebudayaan berpangkal dari polemik kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, dan beberapa tokoh lain yang mempersoalkan sikap bangsa Indonesia dalam memasuki kebudayaan baru: pertentangan masyarakat feodal-kolonialisme dengan kapitalisme Barat.
Sejalan dengan Sutan Takdir Alisjahbana, Tjipto Mangoenkoesoemo melihat bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk (Jawa) merupakan tugas paling penting; dan untuk itu orang Jawa harus belajar ilmu pengetahuan dan teknologi Barat---kebudayaan dan bahasa Jawa sama sekali tidak ada gunanya.
Di sisi lain, bertolak belakang dengan gagasan Tjipto Mangoenkoesoemo, Soetatmo Soerjokoesoemo (yang kemudian mendirikan Taman Siswa bersama Soewardi Soerjaningrat) berpandangan bahwa hanya nasionalisme Jawa yang memiliki landasan kuat, tempat orang Jawa dapat membangun masyarakat politiknya di masa depan.
Diskurs tersebut setidaknya tergambar lewat Kirti Njunjung Drajat (Jasawidagda, 1924) dan Gawaning Wewatekan (Koesoemadigda, 1928), keduanya mengedepankan tema perlawanan terhadap tradisi masyarakat Jawa yang mengagung-agungkan dunia priyayi dan hegemoni kekuasaan: tradisi versus modernisasi.
Setelah tahun 1960-an, tema-tema yang muncul dalam karya sastra Jawa kian beragam, hal ini terjadi karena sejak tahun 1950-an (Damono) pengarang dan pembaca di Indonesia (termasuk di dalamnya pembaca sastra Jawa) mulai berkenalan dengan berbagai jenis sastra karya sastrawan dunia lewat karya-karya terjemahan.
Di samping terjadinya perubahan sosial sejalan dengan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan, peningkatan pendidikan, dan terjadinya demokratisasi. Tidak mengherankan jika pada dasarwarsa 1950-an terbit sejumlah karya sastra Jawa yang mulai menggeser dan "menenggelamkan" karya-karya sastra piwulang.
Novel yang dianggap penting bagi sejarah sosial adalah Serat Riyanta yang memiliki kesejajaran tema dengan Galuga Salusursari (Mas Ngabehi Mangoenwidjaja, 1921), Katresnan (M. Soeratman, 1923), Larasati Modern (Sri, 1938), Kirti Njunjung Drajat (Jasawidagda, 1924), Gawaning Wewatekan (Koesoemadigda, 1928), dan Sapu Ilang Suhe (Hardjawiraga, 1921), semuanya memiliki tema modern meliputi penolakan kawin paksa, penolakan terhadap dunia priyayi, dan adanya keinginan hidup mandiri.

Tidak ada suasana konflik kelas dan kritik sosial dalam novel ini---pada waktu Riyanta menikahi Srini, maka sempurnalah cita-cita priyayi baru untuk menyatakan dirinya: "sanalika sirna rikuhipun, wasana lajeng amangun lutut"---dengan demikian, bentuk priyayi baru mendapatkan legitimasi.
Penolakan terhadap dunia priyayi (suatu jagad komunitas yang merupakan lambang "kemuliaan hidup" bagi orang Jawa) dibeberkan dalam Kirti Njunjung Drajat (Jasawidagda, 1924) dan Gawaning Wewatekan (Koesoemadigda, 1928).
Latar sosial tokoh Darba (Kirti Njunjung Drajat) serta Endra (Gawaning Wewatekan) mampu memberikan reaksi terhadap tradisi masyarakat Jawa sehingga menimbulkan tema kurang lazim dalam sastra Jawa modern, yaitu pemberontakan terhadap tradisi masyarakat Jawa yang mengagung-agungkan dunia priyayi.
Dalam Kirti Njunjung Drajat, tema tersebut dipaparkan secara eksplisit lewat pernyataan bahwa orang yang dihormati adalah orang yang mempunyai uang dan pikiran, bukan ditentukan oleh kedudukan seseorang sebagai priyayi atau wong cilik.
Pertanyaan yang patut dikedepankan adalah mengapa lahir karya karya sastra Jawa modern yang menggugat dunia kepriyayian? Mengapa Jasawidagda (sebagai seorang priyayi---ia mendapatkan gelar Raden Tumenggung dari Mangkunegaran) tiba tiba "menjungkirbalikan" dunia priyayi?
Pertanyaan kedua itu menarik untuk dicermati lebih jauh karena sebelum hadirnya Kirti Njunjung Drajat, Jasawidagda lewat beberapa karyanya selalu berpegang dan menawarkan konsep konsep dalam bidang pendidikan budi pekerti.
Secara umum dapat disebutkan bahwa sebagian besar karya karya Jasawidagda berisi etika atau bersifat didaktis (Soeprapto, 1991). Karyanya Karaton Powan (1917), Jarot I-II (1922 dan 1931), dan Pethi Wasiyat (1938), berisi ajaran moral tentang keharusan seorang anak ngabekti kepada orang tua.
Keberanian Jasawidagda "menjungkirbalikkan" dunia priyayi dalam Kirti Njunjung Drajat, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kehidupan Jasawidagda yang berpengaruh terhadap proses kreativitasnya dalam berkesenian; bagaimana konsep didaktis yang ditawarkan Jasawidagda bergerser ke arah "penjungkirbalikan" dunia priyayi.
Profesinya sebagai guru turut membingkai Jasawidagda dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang berusaha mengalihkan pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan kepada generasi muda sebagai upaya menyiapkan agar generasi muda dapat memenuhi fungsinya sebagai masyarakat Jawa, baik secara jasmaniah maupun rohaniah.
Dalam konteks budaya Jawa, pendidikan dapat berarti pemahaman terhadap unggah-ungguh, penempatan diri dalam kehidupan sehari hari dalam tegangan konsep alus, kasar, dan rasa.
Tampilnya Pethi Wasiyat dan Kirti Njungjung Drajat jelas menampakkan dinamika Jasawidagda karena dunia tradisional sudah tidak mendominasi keseluruhan cerita.
Jasawidagda menanggapi perubahan sosial budaya dengan tetap menaruh hormat kepada budaya tradisional. Sikap ini serupa dengan sikap Ki Hadjar Dewantara dalam menanggapi polemik kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane.
Kenyataan ini berbeda dengan yang tergambar dalam Kirti Njunjung Drajat; walaupun masih berpegang pada nilai nilai tradisional, tetapi novel ini terasa lebih progresif dalam menerima perubahan sosial budaya.
Perubahan yang terjadi tidak hanya tergambar lewat sikap sikap tokoh tetapi melebar ke alam pikiran tokoh, ke dunia konsep kesadaran penerimaan pembaharuan. Novel seperti ini tercipta karena Jasawidagda tampil sebagai kaum intelektual Jawa keturunan bangsawan yang memperoleh pendidikan Barat relatif memadai (sekolah di Kweekschool), aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan.
Sebagai intelektual modern, tentu saja Jasawidagda memiliki wawasan luas, mampu memprediksi perubahan-perubahan yang akan terjadi, sehingga mobilitas pergeseran priyayi bukanlah sesuatu yang dirasa istimewa---pergeseran tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan memang harus terjadi.
Lewat Kirti Njunjung Drajat, Jasawidagda berupaya menyatakan bahwa faktor uang dan materi memegang peranan bagi masyarakat yang akan datang (modern) dalam rangka pembentukan status seseorang yang secara keseluruhan akan membentuk struktur sosial dalam masyarakat.
Rujukan: Widyasastra, 2018
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H