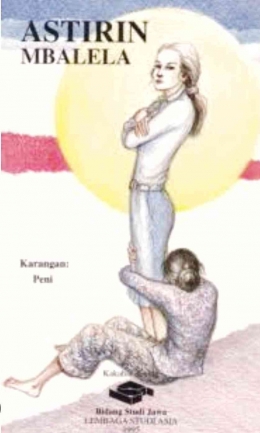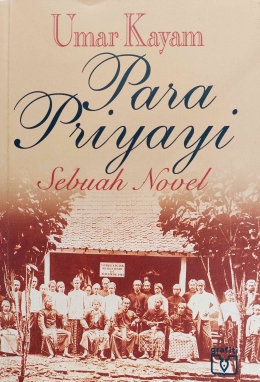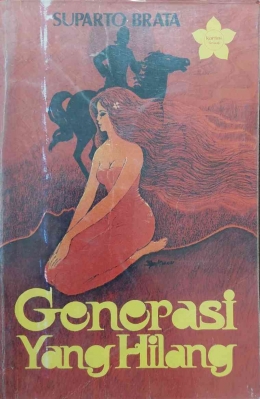Nama Suparto Brata mengacu kepada wilayah kebudayaan Jawa, apalagi jika Suparto Brata tidak enggan menuliskan gelar "Raden" di depan namanya. Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan karena ia memang merupakan keturunan trah njeron benteng. Ayahnya, Raden Suratman Bratatanaya, dan ibunya, Raden Ajeng Jembawati, keduanya berasal dari Surakarta---diduga merupakan kerabat Kraton Mangkunegaran.
Suparta Brata menikahi gadis keturunan darah biru dengan gelar kebangsawanan "Raden Rara" Ariyati. Sebagai orang Jawa tulen, dalam menuliskan tanggal lahir pun Suparto Brata tidak lupa menyertakan weton-nya, yaitu Sabtu Legi, 27 Februari 1932 atau 19 Syawal 1862 Je.
Meskipun tergolong kaum bangsawan (priyayi), Suparto Brata tidak banyak mengedepankan persoalan-persoalan kepriyayian dalam karya-karyanya, hal ini berbeda dengan Umar Kayam---seorang priyayi ("Raden Mas" dari Kraton Surakarta) yang memandang sekitarnya dari sudut priyayi sehingga tokoh-tokoh yang diciptakannya, mulai dari "Chief Sitting Bull" sampai "Drs. Citraksa dan Drs. Citraksi", dimainkan dan dilihat dari sudut priyayi.


Di lain pihak, tokoh Suryapraba ditampilkan sebagai wakil sosok masyarakat tradisional, mengagungkan derajat kebangsawanan. Relasi oposisi kedua tokoh tersebut melahirkan beragam konflik, menciptakan berbagai tragedi.
Genduk Darmirin merupakan tokoh kontroversial dengan pengingkarannya terhadap pandangan orang Jawa (pinggiran) yang menganggap dunia priyayi sebagai bentuk puncak apa yang menjadi angan-angan mereka. Seorang perempuan dikatakan beruntung atau berhasil hidupnya jika mampu bergaul dekat dengan bangsawan (priyayi) dan melahirkan bayi keturunan mereka:: derajat kebangsawanan merupakan jaminan hidup, kekayaan, dan kekuasaan.
Penolakan terhadap derajat kebangsawanan secara semiotik mengisyaratkan bahwa Genduk Darmirin merupakan sosok wanita Jawa yang kritis terhadap kepincangan-kepincangan sosial, tidak begitu saja tunduk (nrima) sebagai seorang gadis Jawa yang diikat kuat oleh tradisi.
Lewat novel ini Suparto Brata menyatakan bahwa dunia kebangsawanan hanya mendewa-dewakan tata cara feodal; sikap dan tata cara yang seharusnya sudah lama dikuburkan. Dengan ketegasan sikap itu, maka jarang sekali (bahkan mungkin tidak ada) karya Suparta Brata lainnya (terutama yang bermediakan bahasa Jawa) mengungkap masalah kepriyayian; apalagi kehendak membela dunia kepriyayian.
Suparto Brata lebih fasih bercerita mengenai nasib wong cilik: bagaimana Saiman membunuh seorang wanita demi anaknya, Giya, yang kelaparan ("Slendang Bang-Bangan"), kesengsaraan Markam melayani Pak Tawangalun ("Wong Gedhe"), tragis dramatisnya cinta Dulmawi (tukang arloji Pasar Keputran) kepada Ijah ("Trem"), dan juru ketik yang terpaksa menjadi perampok untuk membahagiakan keluarga ("Rampog").
Kepiawaian Suparto Brata menampilkan sosok wong cilik berkorelasi dengan kehidupan keluarga yang cukup menderita: ibunya pernah menjadi pembantu rumah tangga, buruh batik, dan pengasuh anak. Suparto Brata berkumpul dengan ayahnya di Surabaya hanya sekitar enam bulan karena kedua orang tuanya kemudian berpisah, Suparto Brata dibawa ibunya menetap di Solo, sekitar empat tahun, kemudian pindah ke Sragen.
Banyak kejadian di Sragen yang membekas diingatan Suparto Brata. Menjelang tidur malam, ibunya sering mendongengkan cerita-cerita rakyat "Ande-Ande Lumut", "Jaka Tarub", "Endang Rara Tompe", dan sebagainya. Setelah masuk sekolah dan dapat membaca huruf Jawa, setiap berangkat tidur, ibunya selalu membacakan cerita "Menak" (macapat yang ditembangkan). Ketika duduk di kelas tiga SD, meskipun Suparto Brata belum lancar membaca huruf latin, tetapi ia sering meminjam buku di perpustakaan sekolah, dan orang lain diminta membacakan---sementara ia mendengarkan.