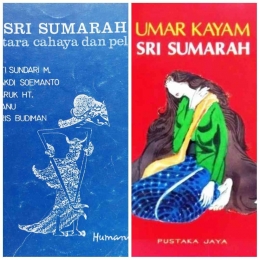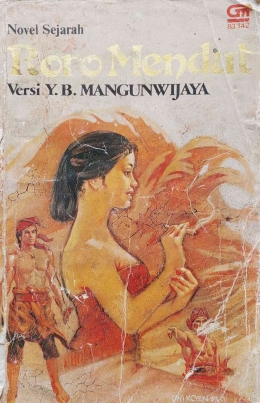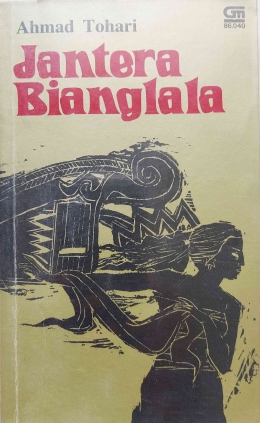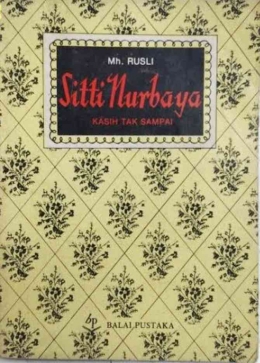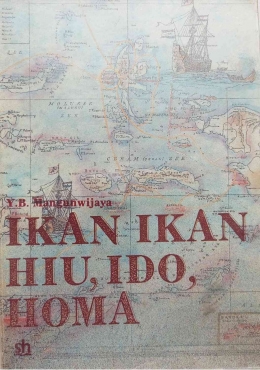/1/
Tidak dapat dipungkiri bahwa sastra dan budaya memiliki jalinan yang sangat erat. Sastra merupaka salah satu ekspresi budaya yang paling dominan karena mampu mencerminkan nilai-nilai, norma, sejarah, dan pengalaman masyarakat tertentu. Dalam perkembangan sastra Indonesia, sastra mencerminkan budaya Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan sebagainya.
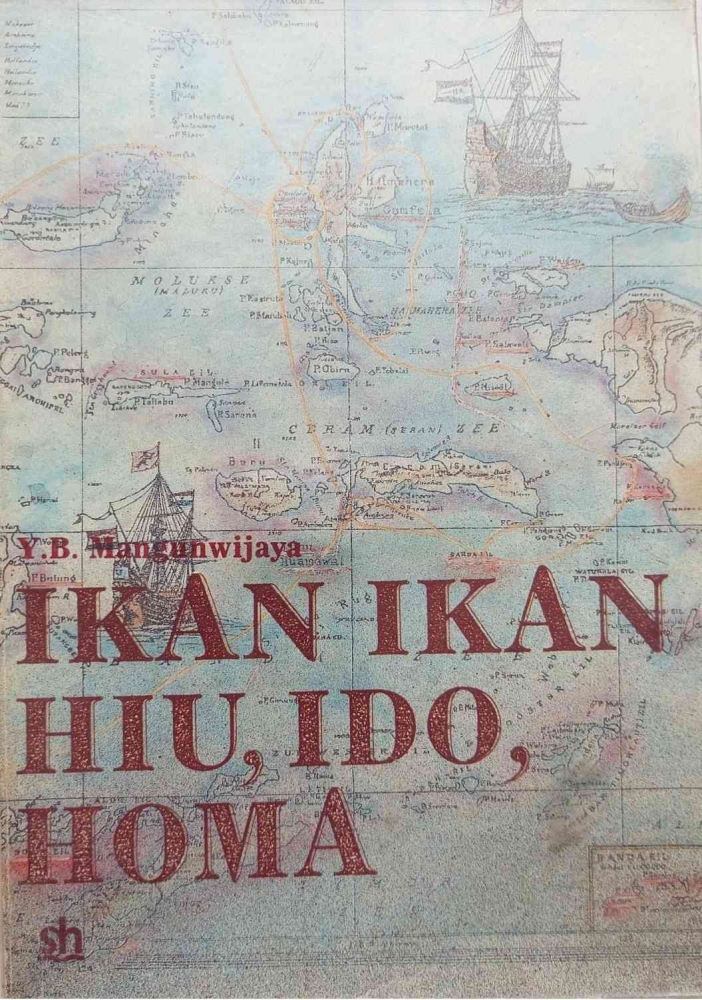
Karya sastra dapat menjadi cerminan/gambaran bagaimana masyarakat melihat dunia dan nilai-nilai yang mereka anut.
Sastra memaparkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan sosial.
Sastra dapat membantu mempertahankan dan memperkuat identitas budaya. Melalui karya sastra, sebuah kelompok budaya dapat merayakan warisan mereka, bahasa, tradisi, dan cerita-cerita khas mereka. Awal kelahiran sastra Indonesia misalnya, didominasi oleh budaya dan tradisi Minangkabau yang berkaitan dengan kawin paksa, contoh mainstream adalah novel Siti Nurbaya.
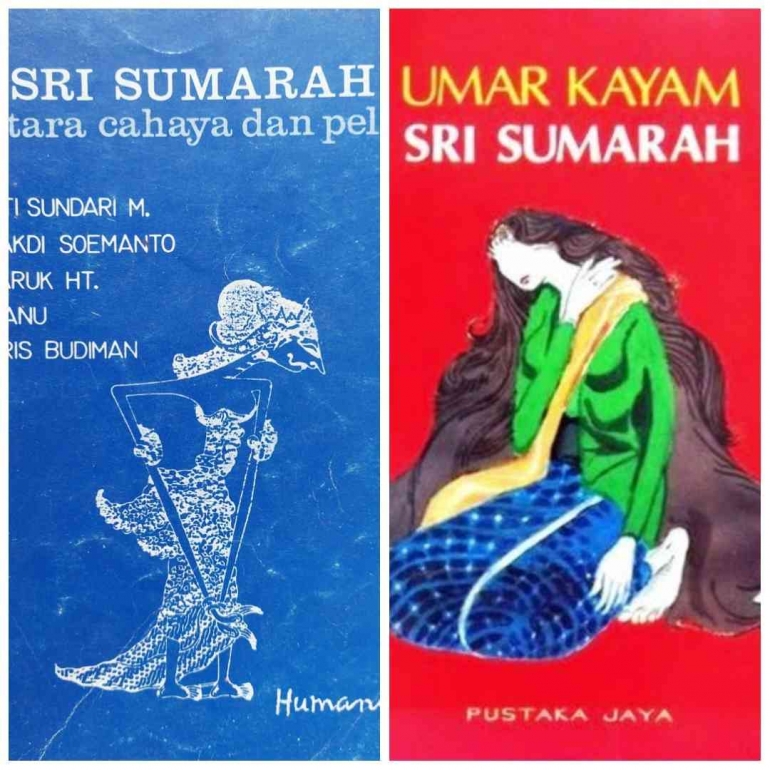
Karya-karya dengan latar lokal Jawa tersebut berkontribusi pada perkembangan bahasa Jawa. Penulis memanfaatkan kata-kata lokalitas (Jawa), gaya bahasa, atau menggunakan bahasa dengan cara yang kreatif yang mempengaruhi pemanfaatan latar sosial budaya yang dikedepankan.
Di samping itu, karya sastra klasik sering menjadi bagian integral dari warisan budaya suatu bangsa atau kelompok. Karya tersebut berfungsi membantu memelihara bahasa kuno, tradisi, dan pengetahuan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini dapat kita pahami kehadiran Serat Wulangreh, Wedhatama, atau Kalatida (Ranggawarsita). Kalatida (tanda zaman) berisi ajaran mengenai ketuhanan, takdir, ikhtiar, mawas diri, dan eling lan waspada. Hal ini juga melandasi pemikiran Mangkunegara IV dalam Serat Wedatama.
Di sisi lain, sastra adalah cara yang efektif untuk memahami budaya lain. Melalui membaca sastra dari berbagai budaya, seseorang dapat mendapatkan wawasan tentang cara pandang dan pengalaman orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dominasi sastra Sumatera (Minangkabau) dan warna lokal Jawa, misalnya, mampu membuka wawasan pembaca mengenai budaya Minang dan Jawa.
Jadi, sastra dan budaya adalah dua hal yang saling terkait dan saling memengaruhi. Sastra adalah ekspresi yang kuat dari budaya, dan melalui sastra, kita dapat memahami lebih dalam nilai-nilai, sejarah, dan pemikiran masyarakat yang berbeda.
/2/
Hal menarik dalam perkembangan karya sastra (khususnya prosa) Indonesia pada tahun 1980-an ditandai dengan terbitnya beberapa karya sastra yang berusaha mengangkat latar Jawa lewat fakta sastra sebagai elemen pembentuk cerita.
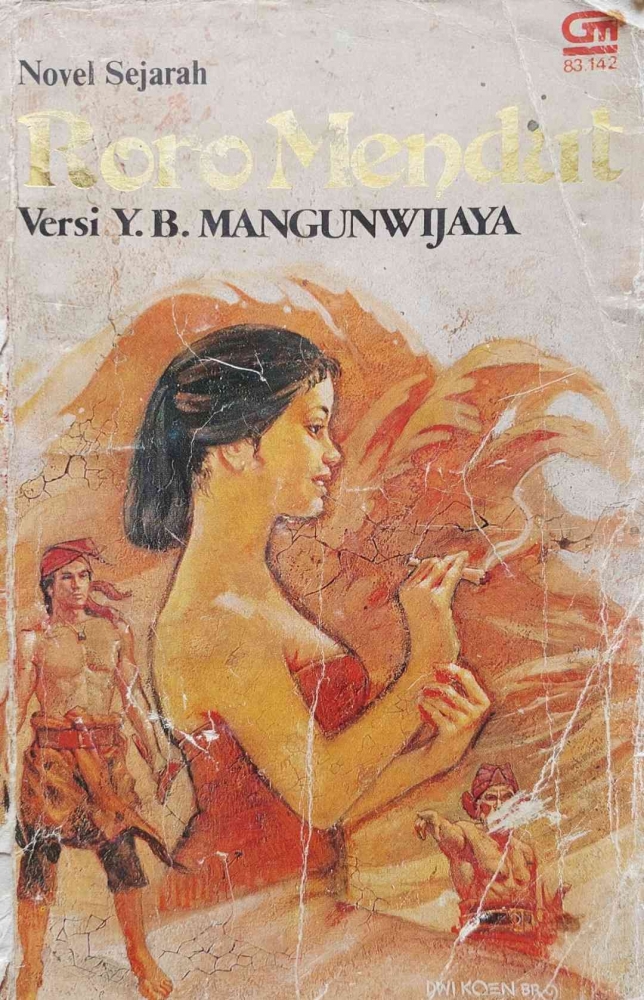
Latar Jawa dalam karya sastra Indonesia tahun 1980-an mengacu kepada cara hidup, kebiasaan- kebiasaan, cara berpikir, dan sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat Jawa. Termoshuizen (dalam Navis) membatasi latar lokal sebagai latar belakang sosiologis yang memberikan warna berbeda jika ditulis oleh pengarang dari suku bangsa lain.
Latar lokal menunjuk pada latar sosial yang khas dari daerah tertentu, latar geografis dari masyarakat tertentu yang meliputi adat istiadat, lingkungan hidup, dan sistem kehidupan subkultur tertentu.
Pengertian tersebut sejajar dengan pengertian warna lokal yang dikemukakan Abrams dalam A Glossary of Literary Terms bahwa warna lokal adalah lukisan mengenai latar, adat-istiadat, cara berpakaian, dan cara berpikir yang khas dari suatu daerah tertentu. Pengertian warna lokal mencakup penggunaan dialek dari bahasa tertentu yang dipakai dalam karya sastra.
Hakikat warna lokal merupakan realitas sosial budaya suatu daerah yang ditunjuk secara tidak langsung oleh fiksionalitas suatu karya. Secara intrinsik (dalam konteks struktur karya), warna lokal selalu dihubungkan dengan unsur latar, penokohan, gaya bahasa, dan suasana.
Kecenderungan untuk menghayati subkultur etnik seperti yang diperjuangkan oleh Umar Kayam, Linus Suryadi, Ahmad Tohari, dan sebagainya merupakan suatu usaha memperkokoh identitas keindonesiaan, usaha menghayati salah satu tradisi yang berpartisipasi dalam mewujudkan konsep (ke-)budaya(-an) Indonesia.
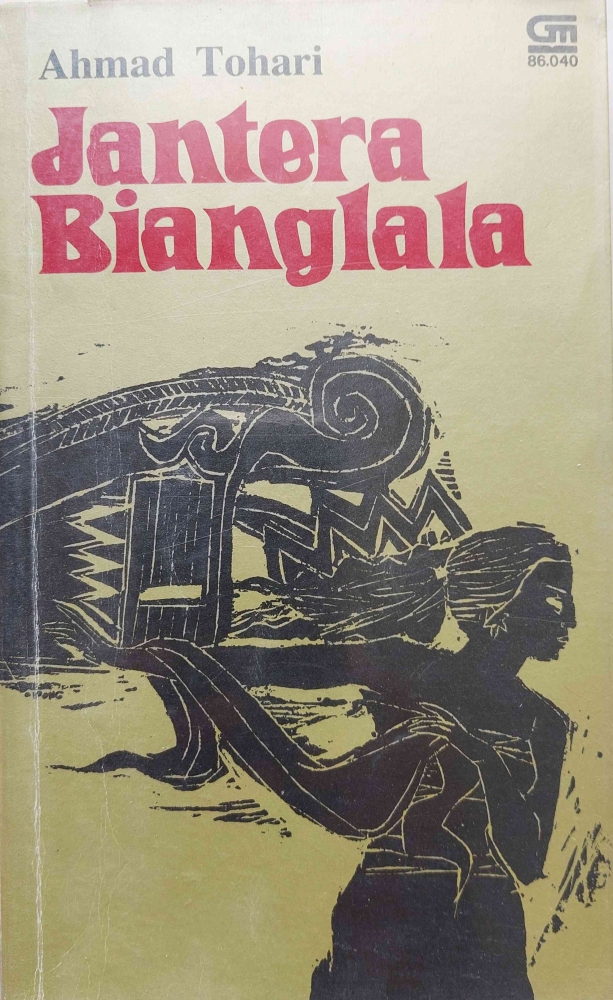
Spesifikasi pengedepanan latar Jawa tersebut terletak dalam jalinan antara latar sosial budaya yang tidak mungkin dapat dilepaskan hubungannya dengan faktor geografis. Ashadi Siregar menegaskan bahwa untuk menjadikan novel sebagai medium komunikasi budaya dapat ditempuh dengan menjadikan figur yang terindentifikasi secara rasional dengan latar belakang budaya etnis tertentu.
Di sini elemen fakta cerita yang berupa latar dan penokohan sama-sama memegang peranan penting. Dengan demikian, sebuah cerita yang mengaangkat latar masyarakat tertentu, di suatu tempat dan pada suatu masa, harus mampu memberikan suatu pengetahuan khusus tentang masyarakat yang bersangkutan lengkap dengan masalah-masalah, perwatakan, sikap hidup, dan sebagainya.

Ia merasa beruntung dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga priyayi. Apalagi ketika tuan mudanya ternyata menaruh minat kepadanya. Maka, ketika kemudian dia hamil akibat ulah tuan mudanya, dengan pasrah ia pulang ke dusun dan melahirkan. Anehnya, ia kembali lagi ke rumah tuannya. Kali ini membawa serta seorang bayi; tanpa minta dinikahi atau mengajukan usul perbaikan nasib.
Ia mengulang kembali peranan lama tanpa sedikit pun merasa ternoda. Di benak Pariyem, hidup dengan tuan muda sudah merupakan rakhmat, sekalipun dia tetap pada derajatnya yang lama dan terus dengan kerja kerasnya sebagai pembantu.
Kondisi ini setidaknya menggambarkan cita-cita masyarakat Jawa dalam menciptakan tata-tertib masyarakat yang selaras. Di dalam masyarakat Jawa, orang sebagai individu tidak menjadi penting: bersama sama mereka mewujudkan masyarakat dan keselarasan masyarakat menjamin kehidupan yang baik bagi individu- individu. Pariyem menyadari bahwa penguasa atau priyayi mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan wong cilik.
"Kalau memang sudah nasib saya
sebagai babu, apa ta repotnya?
Gusti Allah Mahaadil, kok
saya nrima ing pandum
Kalau Indonesia krisis babu
bukan hanya krisis BBM saja
O, Allah, apa nanti jadinya?
Terang, negara kocar kacir!
Karena, demikianlah hukumnya:
Ada jendral ada pengawal
ada admiral ada gedibal
Ada cantrik ada resi
ada kawula ada Gusti
Ada siswa ada guru
ada priyayi ada babu
Kedua duanya tak terpisahkan:
dua itu satu, satu itu dua
loro loroning atunggal
Tapi pangkat bukan ukuran
yang menakar martabat insan
Karena peran dan kewajiban
pangkat pun kita sandang."
(Pengakuan Pariyem, hlm. 35-36)
Kutipan di atas secara implisit mencerminkan dasar moral orang Jawa dalam menempatkan eksistensi dirinya. Dasar moral orang Jawa menurut Zoet Mulder, terletak pada kewajiban dan hubungan antara orang-orang yang tidak sama kedudukannya. WS Rendra menyatakan bahwa masing-masing individu dalam masyarakat Jawa harus tahu kedudukannya: apakah ia klerek, priyayi, kepala, rendahan, perempuan, laki-laki, semuanya punya kedudukan sendiri-sendiri dan tidak dapat disamakan begitu saja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H