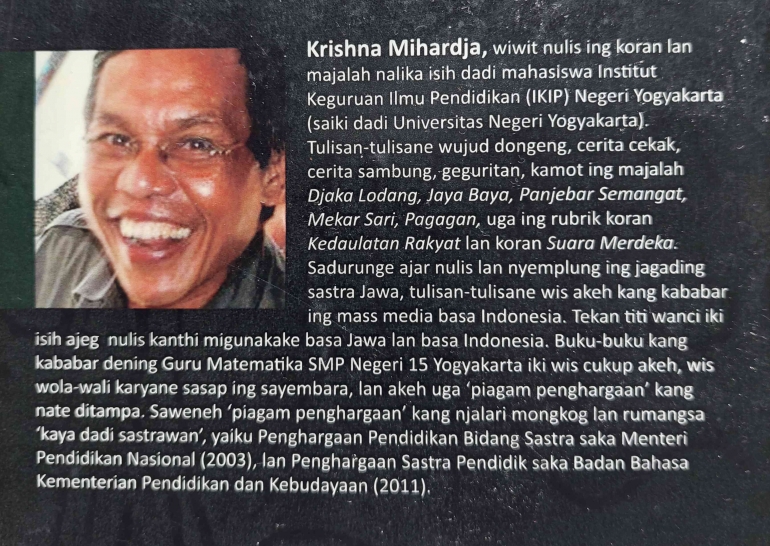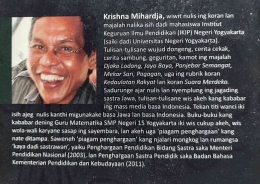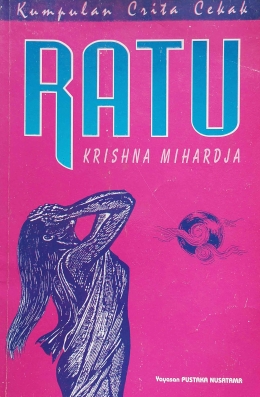Karya sastra merupakan abstraksi pemikiran dan pengalaman penulisnya. Lewat crita cekak (cerita pendek) "Horn", "Safari", dan "Ledhek" audience mampu membaca pemikiran politik Krishna mengenai Orde Baru dan hegemoni kekuasaan.
Crita cekak (cerkak) Krishna Mihardja selalu tampil dengan struktur cerita tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami pembaca. Kondisi itu setidaknya dapat dicermati dari kehadiran antologi Ratu dan antologi Pratisara. Antologi Ratu merupakan kumpulan cerpen (crita cekak---cerkak: bahasa Jawa), diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, memuat 17 cerkak. Di sisi lain, antologi Pratisara diterbitkan oleh Leutika Prio, Yogyakarta, memuat 28 cerkak---sebagian besar pernah dimuat dalam majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat, Mekar Sari, Djaka Lodang, dan Pagagan, serta sebagian kecil lainnya merupakan cerkak baru dan belum pernah dipublikasikan.
Judul-judul cerkak dalam dua antologi tersebut terkesan sederhana, misalnya "Horn", "Ratu", "Sapari", "Sandhal Jinjit" (antologi Ratu), "Kursi", "Topeng", "Kacamata", "Lara Cangkem", dan "Jenengku Asu" (antologi Pratisara). Meskipun demikian, bukan berarti cerkak-cerkak Krishna Mihardja tidak mempunyai nilai lebih.
Kesederhanaan judul dan cara bertuturnya justeru menghasilkan cerkak yang dapat dimaknai sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia mengejek diri sendiri lewat tokoh-tokoh yang ditampilkan dan di sisi lainnya menohok para penguasa serta masyarakat melalui kritik-kritik sosial dengan cara glenyengan (seenaknya sendiri) tetapi begitu mengena dan terasa tajam mengiris.
Membaca dua kumpulan cerkak Krishna Mihardja, pembaca seperti dihadapkan pada buku kajian sosial budaya dan politik dengan penggambaran berbagai friksi dalam masyarakat Indonesia.
Kejelian Krishna Mihardja memotret momen-momen kejadian dituturkan dengan cara sederhana, mudah dicerna, dibingkai dalam guyonan parikeno. Ia menyindir persoalan pergeseran nilai-nilai tradisi budaya, pemilihan lurah yang tidak lepas dari politik uang, penguasa dengan kegemaran menakut-nakuti masyarakat kecil tak berdaya, dan pemenuhan hasrat perempuan yang akhirnya membuat laki-laki kelimpungan.
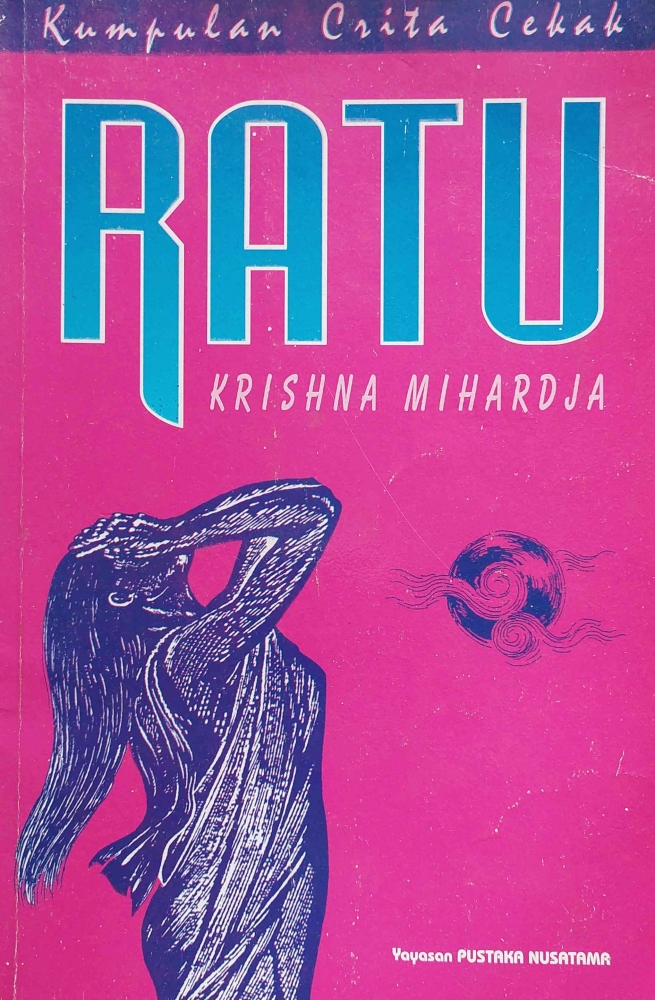
Asumsi pertama berkaitan dengan gagasan Goenawan Mohammad bahwa sastra merupakan sindiran halus (pasemon), menyarankan sesuatu yang bukan sebenarnya tetapi mendekati sifat tertentu. Dengan demikian, dalam pasemon, makna tidak secara apriori hadir. Makna hadir bukan dengan menceritakan sesuatu "sebagaimana adanya", tetapi dengan menceritakan sesuatu yang lain dari yang sebenarnya hendak dikatakan.
Asumsi kedua sejajar dengan gagasan Mudji Sutrisno bahwa ketika terjadi pergeseran tradisi (kosmologi)---dari pandangan teratur, tertata dan harmonis (dunia agraris), menuju sesuatu yang bergerak tidak pasti, nomade, dislocated (urban) ---maka terjadi dislokasi nilai.
Asumsi ketiga berangkat dari gagasan sastra pada hakikatnya merupakan suatu bentuk sistem interpretatif. Budiawan menggariskan bahwa sastra dapat dipahami dengan melihat sejauh mana ia merepresentasikan dan memisrepresentasikan ideologi dominan. Dalam konteks perubahan sosial, budaya dan politik, dapat dikaji sejauh mana karya sastra merepresentasikan dan atau memisrepresentasikan nasionalisme, pembangunan, dan stabilitas nasional.
Membaca cerkak Krishna Mihardja, pembaca seperti dihadapkan pada buku kajian sosial budaya dan politik, menggambarkan berbagai friksi dalam masyarakat Indonesia. Kejelian Krishna Mihardja memotret momen-momen kejadian dituturkan dengan cara sederhana dan mudah dicerna.
Kegelisahan Krishna Mihardja terhadap ketidakberdayaan masyarakat (khususnya masyarakat Jawa) dalam pembangunan dan pergeseran nilai-nilai tradisi, budaya, serta politik, setidaknya dapat dicermati lewat cerkak "Horn", "Sapari", dan "Ledhek".
Melalui cerkak "Horn"dan "Sapari", Krishna Mihardja menunjukkan bagaimana lewat karya sastra (dalam konteks perubahan sosial, budaya dan politik), ia merepresentasikan atau memisrepresentasikan nasionalisme, pembangunan, penguasa, dan stabilitas nasional saat karya tersebut dilahirkan (tahun 1990-an)---ketika isu mengenai pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru masih hangat diperbincangkan dan dipertentangkan. Di sisi lain, cerkak "Ledhek" memperlihatkan kegelisahan Krishna Mihardja terhadap perubahan masyarakat Jawa dari masyarakat agraris menuju masyarakat moderen.
Tragika Masyarakat di Lingkaran Penguasa dan Pembangunan
Masa pemerintahan Orde Lama selalu diidentikan dengan merajalelanya korupsi, cepatnya laju pertambahan penduduk; berakibat pada banyaknya pengangguran, merebaknya tindak kejahatan, dan tidak tercukupinya persediaan pangan. Di sisi lain, Orde Baru dikaitkan dengan program pembangunan, perbaikan, dan pengentasan kemiskinan.
Ricklefs (1995) menandaskan bahwa sejak semula pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berupaya menjalankan kebijakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi serta menyandarkan legitimasi pemerintah pada kemampuan memajukan kesejahteraan sosial .
Cerkak "Horn" mengisahkan kegigihan kepala desa Jayareja (direction) memasang horn (pengeras suara) di wilayahnya dengan tujuan mempermudah masyarakat mengatasi berbagai persoalan. Di balik tujuan "mulia" tersebut sesungguhnya tercermin keinginan Krishna Mihardja menggambarkan upaya kepala desa mendepolitisasi suara masyarakat, menenggelamkan identitas masyarakat, memperlihatkan ketidakberdayaan masyarakat melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan karena adanya domination.
Dalam realitas Orde Baru (Zaini Abar), informasi-informasi pembangunan dalam masyarakat didominasi oleh informasi-informasi bersumber dari birokrasi pemerintah melalui retorika-retorika politik meninabobokan. Pemerintah dan aparatnya (direction) melembagakan diri sebagai satu-satunya sumber informasi pembangunan (domination); sedangkan informasi-informasi faktual, objektif, dan alternatif dari masyarakat cenderung diminimalisir dengan alasan demi stabilitas pembangunan.
Hegemoni dilakukan dengan konformitas melalui penekanan dan sanksi-sanksi menakutkan; masyarakat menyesuaikan diri dengan keinginan direction karena takut akan konsekuensi-konsekuensinya. Pemerintahan Orde Baru anti terhadap kontrol, tidak mampu berhadapan dengan kritik objektif dan rakyat tidak dianggap sebagai subjek yang menjadi protagonis dari kehidupan mereka sendiri.
Dengan demikian---dalam dinamika politik Orde Baru---keberadaan rakyat benar-benar menjadi objek kekuasaan. Kecenderungan yang menyertai adalah tumbuhnya sikap fatalistik masyarakat. Pada tataran ini teralienasinya masyarakat terlihat dari ketidakberdayaan mereka melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan yang menyimpang karena adanya dominasi direction.
Perlu diingat kembali lontaran gagasan Budiawan bahwa dalam konteks Indonesia Orde Baru, negara (state) dan pembangunan (development) merupakan dua hal yang sulit dibedakan; sebab pembangunan hadir melalui kekuasaan negara dan kekuasaan negara hadir melalui pembangunan---pemerintah selalu meletakkan sesuatu di bawah kepentingan "pembangunan". Pemerintah Orde Baru mempunyai kemampuan penetrasi yang besar dan dominan sehingga dapat mengendalikan hampir segala sisi kehidupan masyrakat. Dominasi terhadap partisipasi masyarakat dapat dicermati lewat "Horn".
Secara signifikasi "Horn" mengabstraksikan bahwa direction memiliki power sangat besar, dapat memaksakan kehendak kepada klas yang dikuasai. Dalam konteks ini, hegemoni Gramsci tercermin dengan kesediaan masyarakat menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan direction dengan cara-cara tertentu.
Konformitas dalam hal ini merupakan partisipasi yang tidak terefleksikan dalam bentuk aktivitas tetap, sebab masyarakat menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dapat menolak.
Kepercayaan dan "pemuliaan" terhadap teknologi canggih (horn) pada akhirnya menciptakan situasi pelecehan-pelecehan terhadap nilai-nilai romantisme dan intuisi-intuisi tradisional yang semula diakrabi oleh klas yang dikuasai.
Krishna Mihardja memperlihatkan bagaimana masyarakat diarahkan kepada titik depresi dengan adanya upaya penyeragaman suara lewat horn. Penyeragaman tersebut berupa pengedepanan retorika-retorika pembangunan yang ekspansif guna mengakumulasikan loyalitas masyarakat. Artinya, direction melakukan dominasi secara sistematis.
Matinya Pakde Darmo Karsi (demokrasi) dalam "Horn" merupakan pasemon ironis bagi dominasi kekuasaan (direction) di desa Jayareja. Kekuatan yang begitu besar berubah menjadi sosok yang tidak jelas: kepala desa maupun masyarakat Jayareja tidak mengenal dengan baik siapa demokrasi. Di bagian akhir cerita, Krishna Mihardja mengisyaratkan bahwa "Horn" merupakan wacana/hipotesis mengenai dua fenomena pembangunan Orde Baru, yaitu peniscayaan pembangunan dan dominasi negara atas masyarakat.
Krishna Mihardja, dalam beberapa tulisannya mencoba menggambarkan potret kehidupan sosial yang lucu dan menyebalkan agar pembaca memperoleh pencerahan atas gelapnya Orde Baru.
"Bagi saya, Orba adalah lelucon-lelucon yang inspiratif untuk dijadikan tulisan. Saya pernah diuber-uber (wong mbuh sapa---tidak jelas siapa oknumnya) hingga ke sekolah tempat saya mengajar. Itu terjadi hanya karena menulis cerpen di koran Berita Nasional. Bagaimana, sungguh keterlaluankan Orba itu? Tapi tetep menyenangkan karena banyak ide-ide yang saya dapat dari sana," jelas Krishna Mihardja ketika diwawancarai.
Cerkak "Sapari" mempunyai keinginan kuat memperlihatkan biaya sosial-ekonomi yang tinggi untuk mencapai kedudukan sebagai direction dalam masyarakat. Meskipun semula seorang guru bernama Pak Marto (tokoh utama dalam "Sapari") menolak memakai baju safari, toh akhirnya dengan dominasi direction, terpaksa memakai baju safari.
Kekalahan Pak Marto merupakan kekalahan klas yang dikuasai terhadap hegemoni--memproduksi simbol-simbol kewibawaan politik lewat baju safari. Baju safari hadir sebagai direction patronsip, harus ditaati, dihormati, tidak boleh ditentang. Dengan kata lain, hegemoni kekuasaan berlangsung karena Pak Marto takut akan konsekuensi-konsekuensi jika tidak menyesuaikan dengan keinginan direction. Dalam bahasa Gramsci, hegemoni terjadi lewat konformitas, ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi menakutkan.
Seni Tradisi dalam Arus Modernisasi
Banyak orang beranggapan bahwa makna kata tradisional dan modern merupakan dua hal saling berlawanan, membentuk oposisi biner. Kondisi tersebut memicu adanya anggapan bahwa sesuatu yang tradisional adalah hal-hal yang berbau "masa lalu" dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan modern mengacu kepada sifat-sifat terbarukan (up to date) dan selalu mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian, bagi kebanyakan orang, sesuatu yang tradisional diasumsikan akan tergilas oleh sesuatu yang modern. Pada kasus perkembangan seni, banyak orang menganggap bahwa kesenian tradisional akan kalah dengan kesenian modern karena kesenian modern dianggap lebih mampu mengikuti zaman.

Dalam cerkak "Ledhek," kegelisahan Krishna Mihardja diwakili oleh kebimbangan tokoh Kuning (Ning) memenuhi permintaan kedua orang tuanya agar melestarikan dan meneruskan kesenian ledhek yang pernah digeluti orang tuanya. Tarik ulur antara keinginan membiarkan kesenian ledhek tergerus zaman dan hasrat menghidupkan kembali agar ledhek tetap eksis di tengah masyarakat (moderen), menimbulkan konflik berkepanjangan.
Kegelisahan Krishna Mihardja tidak berujud pada penyesalan terhadap eksistensi kesenian tradisional, tetapi berujung pada kesadaran bahwa perubahan masyarakat akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi kesenian tradisional.
Bagi Krishna Mihardja, kesenian tradisional jika ingin tetap eksis, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hanya kesenian yang bisa beradaptasi dengan keadaan akan mampu bertahan. Pemikiran ini sejajar dengan gagasan Mudji Sutrisno bahwa ketika terjadi pergeseran tradisi, maka akan ada dislokasi nilai.
Sejak semula, Krisna Mihardja (lewat tokoh Kuning) ingin menekankan bahwa masa kejayaan ledhek akan tenggelam ditelan zaman.
Pilihan yang dilakukan Krishna Mihardja agar ledhek tidak terasing dari masyarakat moderen adalah dengan mencarikan tempat ke dalam dislokasi nilai masyarakat moderen sehingga menemukan outlet, menemukan pencarian-pencarian atau oasis-oasis dari keterasingannya. Perlu diingat kembali gagasan Mudji Sutrisno bahwa ketika terjadi pergeseran tradisi (kosmologi)---dari pandangan yang teratur, tertata dan harmonis (dunia agraris), menuju sesuatu yang bergerak tidak pasti, nomade (urban) ---maka terjadi dislokasi nilai.
Seni ledhek akhirnya menemukan outlet, oasis dari keterasingannya dengan mentransformasikan kebaya menjadi rok mini, gerakan ledhek menjadi goyang ndangdut, rambut yang tergelung rapi menjadi terurai lepas, kendangan yang semula teratur menjadi rancak. Tragedi "hilangnya" Kuning saat pentas di alun-alun kabupaten---yang tersisa di atas panggung pertunjukkan hanya hati Kuning---dan bagian lainnya sudah digilas zaman, merupakan pasemon bahwa pada akhirnya kesenian tradisional tetap akan terpinggirkan dalam kehidupan dunia moderen, meskipun sudah mengalami transformasi.
Umar Kayam menyatakan, baik masyarakat maupun negara, pada suatu masa akan berubah, bahkan menghendaki perubahan dan transformasi; kenyataan tersebut menujukkan bahwa cepat atau lambat serat-serat suatu budaya, pada suatu saat membusuk dan tidak berfungsi lagi sebagai pengikat kesatuan kebudayaan.
Krishna Mihardja dalam wawancara menjelaskan bahwa karena ia orang jawa ndesa, maka benar-benar ingin mempertahankan apa pun tentang seni Jawa, semuanya saja. Semua seni dicoba ditempelkan pada dirinya.
Krishna Mihardja suka dan bisa karawitan, nembang (meski suaranya cempreng), memahami wayang, kethoprak, suka tari, mengerti sedikit tentang pakaian tradisional Jawa---ia merupakan salah satu anggota tim dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Budaya yang diberlakukan di DIY beberapa tahun silam.
Meskipun begitu, melihat fakta yang ada, ketika lebih banyak orang mulai memalingkan muka dari seni tradisi, karena modernisasi dianggap lebih menjanjikan dalam segalanya, maka Krishna Mihardja memilih bersikap realistis, tak mampu berbuat apa pun terhadap perkembangan kesenian tradisional kecuali "mem-push" diri sendiri.
Terhadap keluarga pun, ia tak mampu berbuat banyak mencari jalan keluar dalam mempertahankan kesenian tradisional. Contoh konkret diambilkan dari kedua orang anaknya, yang satu bisa menari Jawa dan nabuh (memainkan) gamelan, sedangkan anak satunya lagi tak tertarik sama sekali terhadap seni tradisi Jawa. "Jadi, sikap saya terhadap seni tradisi adalah: saya hanya bisa mem-push diri sendiri, sedikit meneladani masyarakat sekitar, dan selebihnya bersikap realistis dengan menunggu apa yang akan terjadi",
Seperti ucapan Bung Karno, siapa yang mampu membendung air bah? Air bah itu diandaikan Krishna Mihardja sebagai modernisasi yang dimotori teknologi informasi dan komunikasi yang rasa-rasanya saat ini sudah menjadi "dewa" baru bagi sebagian besar manusia.
*Herry Mardianto
Rujukan: Proseding BBY, 2016
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI