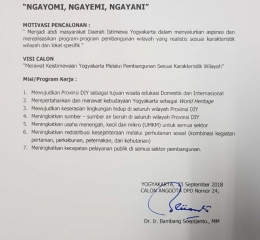Fenomena "klitih" barangkali bukan sesuatu yang baru di Yogyakarta. Justru, fenomena ini sudah lama berlangsung dan seolah tidak ada habisnya. Lebih ironis lagi, kejadian ini dilakukan umumnya oleh pelajar SMA yang sungguh masih muda di tempat yang kerap dijuluki "Kota Pelajar".
Fenomena ini marak-maraknya terjadi sekitar antara tahun 2005 hingga 2011. Saat itu, siswa SMA yang baru pulang sekolah kerap berkendara motor bersama secara iring-iringan. Mereka berkonvoi dengan sekitar 10 motor, lebih banyak tentu lebih baik.
Ketika mereka bertemu dengan siswa sekolah lain, mereka akan melihat dari sekolah mana pelajar yang mereka temui. Jika berasal dari sekolah yang cenderung dekat dengan mereka, maka tegur-sapa ramah bisa terjadi. Namun, jika berpapasan dengan pelajar dari sekolah yang bermusuhan, perkelahian pun sangat mungkin terjadi.
Hari-hari aktif sekolah pun menjadi situasi "perang" yang selalu mencekam. Beberapa pelajar yang berhati-hati pun mencoba memakai jaket saat pulang sekolah agar tidak ketahuan mereka berasal dari sekolah mana.
Dengan memakai jaket, maka logo sekolah di bagian lengan seragam jadi tak nampak. Puncaknya pun terjadi di hari Sabtu, karena di hari tersebut, umumnya sekolah memberlakukan seragam khusus dengan khas atribut sekolah.
Artinya, kini identitas asal sekolah dapat terlihat di bagian warna celana, sangat sulit untuk menyembunyikannya. Perkelahian pun jadi lebih marak di hari tersebut.
Guru-guru dan pihak sekolah bukannya tidak mengetahui. Berbagai himbauan dan usaha mempersuasi pelajar pun sudah sering dilakukan. Tapi apa daya, perkelahian terjadi di luar jam sekolah, membuat pihak sekolah pun tidak bisa berbuat banyak.
Menurut pengakuan mantan pelaku ataupun korban klitih, sebenarnya istilah "klitih" berawal dari sesuatu yang jauh dari negatif. Klitih berasal dari kata "klitikan" yang maksudnya adalah "Pasar Klitikan", sebuah pasar barang bekas di daerah Pakuncen, jalan HOS Cokroaminoto.
Pelajar kerap mendatangi pasar ini sehabis pulang sekolah bersama-sama sambil santai untuk membeli barang bekas. Dalam perjalanan inilah, kemungkinan beberapa insiden perkelahian antar pelajar sekolah kerap terjadi. Sesuatu yang sudah tentu tidak bisa dibanggakan.
Klitih akhirnya menjadi hal yang "dibudayakan" dalam kultur sosial kehidupan pelajar. Para pelajar senior mewariskan narasi kebencian mereka atas sekolah lain kepada adik kelas mereka. Kemudian saat sudah menjadi senior, adik kelas tersebut pun mewariskan kebencian yang sama pada adik kelasnya lagi.
Dalam narasi tersebut, diwacanakan bahwa berkelahi dengan pelajar dari sekolah musuh adalah sesuatu yang keren. Dengan berkelahi, mereka membalaskan dendam kakak kelasnya dulu sekaligus meneguhkan kekuasaan sebagai sekolah paling ditakuti di Yogyakarta.
Anak muda SMA yang rata-rata tentu masih mengalami krisis identitas dan merasa haus pengakuan, lantas menganut baik-baik budaya premanisme ini. Lagi-lagi, ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan.
Hingga pada suatu masa tertentu, dinas terkait di Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk menyeragamkan semua seragam SMA di kota ini. Artinya, tidak ada lagi logo sekolah yang terlalu mencolok di lengan kanan, semuanya sama berbunyi "Pelajar Kota Yogyakarta". Konon, kebijakan ini cukup ampuh. Insiden klitih mulai berkurang dan bahkan hampir punah di akhir tahun 2011.
Namun lambat-laun, klitih kembali terjadi dengan pola yang sungguh berbeda. Klitih tidak lagi terjadi siang atau sore hari di jam pulang sekolah, namun terjadi di malam atau pagi buta. Pelakunya tidak lagi mengenakan seragam sekolah, namun baju biasa dan membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka pun melakukan klitih dengan motif yang berbeda: menjambret, merampok, hingga membunuh. Sayangnya, identitas si pelaku kadang juga masih sama, anak muda pelajar masih bau kencur.
Kejadian demi kejadian pun terjadi, namun ada tiga kejadian besar yang cukup besar dan menyita perhatian:
Pertama, kejadian di daerah sekitar Jalan Monjali pada pukul lima pagi. Korban adalah seorang perempuan (mengendarai motor) dijambret tasnya oleh dua orang pemuda (yang juga mengendarai motor). Beruntung, perempuan itu berani mengejar, menabrak motor pelaku, dan akhirnya pelaku tertangkap.
Kedua, pembacokan yang dilakukan sekelompok orang di Jalan Kapten Pierre Tendean. Korban selamat namun mendapatkan puluhan jahitan. Ketiga, pembacokan terjadi di dekat Mirota Kampus UGM. Korban tewas yang diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM atas nama Dwi Ramadhani Herlangga. Kejadian tersebut terjadi sekitar saat jam sahur.
Kejadian terakhir menjadi pembicaraan paling santer. Sebab sebelum kejadian, korban baru saja membagikan sahur gratis kepada orang-orang sekitar. Sayang, di saat dia bikin aksi mulia, pada saat itulah dia harus meregang nyawa pula.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa klitih sudah bukan lagi kenakalan remaja dengan krisis identitasnya lagi. Namun, sudah bertransformasi menjadi kejahatan kriminal yang serius. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggapi ini, tentu harus jadi perhatian tersendiri.
Yogyakarta dengan semangat pendidikannya yang tinggi, seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Ribuan pelajar dari berbagai penjuru daerah di Indonesia sudah sering datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Bukan saja menjadi destinasi edukasi, Yogyakarta bahkan bisa menjadi tujuan wisata pendidikan.


Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H