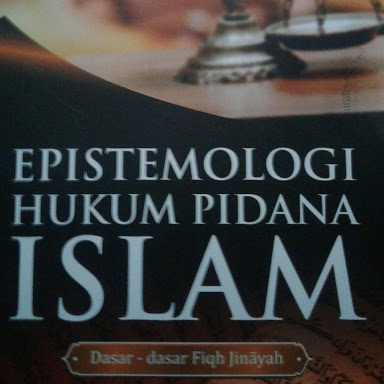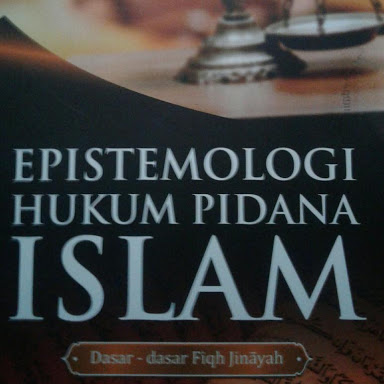Dari definisi di atas, metode ini coraknya adalah deduktif, dimana untuk menemukan hukum baru (premis minor) harus berpatok kepada premis umum, yaitu berupa hukum asal. Di sini terjadi perbedaan antara Al-Gajali dan As-Syatibi. Bagi Al-Ghajali premis minor (hukum cabang) itu sifatnya pasif, karena dialah yang dicari status hukumnya. Ini bisa dimaklumi, kerena qiyas-nya Ghajali dipengaruhi oleh silogismenya Aristoteles. Sementara bagi Syatibi premis minor itu harus aktif, dia harus berdealetika dengan premis mayor.
3. Metode Istislahi (Teleologis)
Metode istislāhī adalah metode penggalian hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur’an dan Hadis. Atau metode ini secara sederhana disebut sebagai metode yang dalam penggalian hukum menjadikan tujuan hukum (maqāsid as-syarī’ah) sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, kemaslahatan umum merupakan tujuan dari hukum Islam. Para ulama usul fikih mendefiniskan maslahat sebagai bentuk apresiasi dari ketertiban hukum dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat dan menghindar dari kerusakan (min tahqīq al-maslahah au jalbi madharrah).
Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa tidak semua kemaslahatan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Kemaslahatan yang sah dijadikan sebagai tujuan dari penggalian hukum adalah kemaslahatan yang didukunng oleh nash, dan selaras dengan semangat syarak secara umum. Berangkat dari sini, para ahli membagi maslahat itu kepada tiga ketegori: maslahat yang diakui legalitasnya dalam syariat, baik langsung maupun tidak langsung (maslahah mu’tabarah); maslahat yang legalitasnya ditolak oleh syariat (maslahah mulghah); dan maslahat yang tidak ada legalitasnya, apakah dia ditolak atau diterima oleh syariat (maslahah mursalah).
C. Validitas Pengetahuan
Problem epistemologi yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Sebenarnya ada banyak teori uji kebenaran dalam epistemologi. Penyusun hanya mengambi tiga dari teori-teori uji kebenaran tersebut yang dianggap paling sering digunakan dalam hukum Islam, yaitu teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan otoritarianisme.
Pertama, teori kebenaran korespondensi adalah persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan atau realita. Suatu proposisi dikatakan benar apabila proposisi itu saling bersesuaian dengan dengan dunia kenyataan yang diungkapakan dalam pernyataan itu, atau fakta yang menjadi objek pengetahuan.
Dalam konteks hukum, suatu hukum dikatakan benar atau mempunyai validitas, ketika dia mempunyai korespondensi dengan kenyataan atau realitas yang hidup yang dihadapi oleh masyarakat. Hukum yang tidak punya relevansi dengan kondisi riil masyarakat pada hakikatnya bukanlah hukum. Salah satu tokoh yang menggunakan ini adalah Imam As-Syatibi.
Kedua, teori kebenaran koherensi adalah sesuatu dinggap benar ketika dia mempunyai kesesuaian (koheren) atau keharmonisan dengan sesuatu yang memiliki hirarki yang lebih tinggi. Hirarki yang lebih tinggi disini adalah berupa teks-teks, baik itu al-Qur’an maupun Hadis. Ahli hukum yang menggunakan ini adalah Imam Al-Ghazali. Ketiga, teori kebenaran otoritarianisme adalah teori yang membuktikan telah ada dan terjadinya prilaku otoritarian dan despotik oleh seseorang atas orang lain, baik karena didasarkan atas otoritas koersif maupun persuasif. Kebenaran dalam teori ini didasarkan pada pemegang otoritas. Dalam konteks hukum Islam, Syi’ah dan Ahmadiyah Qadian dalam satu sisi bisa dimasukkan ke golongan ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H