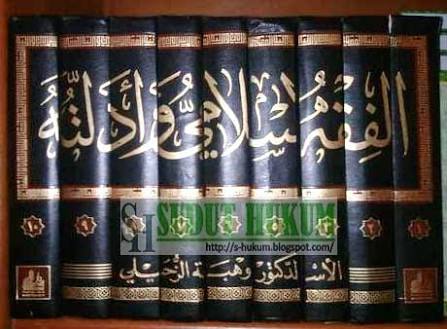Dalam suatu acara seminar mengenai pengoptimalan zakat di Indonesia, yang diadakan oleh jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, sang narasumber membuat pertanyaan sekaligus pernyataan yang bagi saya sangat mengganjal. Apakah fikih itu termasuk ilmu pengetahuan? Apakah zakat yang dalam kitab-kitab fikih disebutkan dapat mensejahterakan masyarakat bisa diverifikasi? Pertanyaan itu kemudian dijawab sendiri oleh narasumber bahwa fikih bukanlah bagian dari ilmu pengetahun.
Sang narasumber yang ketika itu menjabat sebagai dekan di salah satu universitas Islam ternama di Jakarta, menjadikan positivismenya Auguste Comte sebagai argumennya. Menurutnya, fikih (hukum Islam) masuk pada level metafisika, belum sampai pada level positif dalam ketegorisasi Comte.
Di sinilah letak permasalahannya, karena sang narasumber tidak menjelasakan apa definisi hukum menurut Auguste Comte. Dalam ilmu mantiq (logika), defenisi (ta’rif) adalah “ruhnya argumen”.
Boleh jadi kita mengambil kesimpulan yang berbeda terhadap sesuatu disebabkan oleh definisi yang kita pegangi juga berbeda. MUI dan JIL berbeda dalam menyikapi pluralisme, karena definisi yang mereka buat juga berbeda. Abu Hanifah dan Imam Syafii berbeda pendapat mengenai istihsan, disebabkan definisi keduanya juga berbeda.
Menurut Comte, hukum adalah sekumpulan norma-norma yang abstrak yang terkadang irrasional. Berangkat dari definisi ini kemudian Comte menyatakan bahwa hukum tidak termasuk dalam ketegori ilmu pengetahuan, kerena sifatnya yang abstrak. Sesuatu yang abstrak menurut Comte tidak bisa diverifikasi, yang otomatis dia masuk pada wilayah metafisika.
Bagaimana dengan hukum Islam? Apakah dia masuk pada level metafisika seperti yang disebutkan Comte? Di sinilah posisi tulisan ini.
Hukum Islam ketika didefinisikan dengan definisi yang dibuat para ushuliyyin sebagai titah ilahi (khitabullah) yang tertuju kepada perbuatan manusia yang berisi tuntutan, penetapan atau pemberian alternatif. Maka penulis sepakat dengan Comte, hukum Islam masuk pada level metafisika. Khitabullah (titah ilahi) adalah sesuatu yang transendental yang tidak bisa diverifikasi. Bagi Comte, sesuatu itu bisa diverifikasi ketika dia bersifat empirik.
Akan tetapi mendefinisikan hukum Islam seperti di atas adalah sesuatu tindakan simplikasi. Hukum Islam bukanlah sekadar kumpulan teks al-Quran dan Hadis, yang dari sana semua persolan kehidupan bisa terjawab dan teratasi. Al-Quran lahir di ruang tidak hampa untuk merespons segala persoalan kemanusian yang terus bergerak dinamis.
Dalam merespons persoalan inilah al-Qu’ran punya interrelasi dengan ajaran lain semisal teks hadist, nalar, maslahah dan realiatas yang hidup. Adanya interrelasi ketiga kompenen ini: teks, nalar, dan realitas yang hidup, sudah cukup untuk meruntuhkan argumen sang narasumber tadi bahwa hukum Islam bukan hanya sekadar berada pada wilayah metafisika-transendental, melain masuk pada level positif-empiris. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan di bawah ini.
Pertama, interrelasi teks al-Qur’an dengan teks hadist. Dalam hukum Islam teks hadist mempunyai posisi kedua dalam hierarki setelah a-Qur’an. Ini disebabkan fungsinya sebagai penjelas, penafsir, penguat, bahkan pembuat hukum baru. Disebabkan posisinya yang sangat penting ini, al-Auza’i (w.157) pernah menandaskan bahwa ketergantungan al-Qur’an terhadap Hadist lebih besar ketimbang ketergantungan Hadist kepada al-Qur’an.
Kedua, interrelasi teks dengan nalar. Sejatinya teks wahyu –baik itu al-Qur’an ataupun Hadist– bersikap diam. Yang menggerakkan teks wahyu adalah nalar manusia. Nalar manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi tolak ukur (mi’yar) dalam menggali apa yang ada di balik teks wahyu tersebut. Pada masa awal Islam, nalar Nabi lah yang berfungsi untuk memediasi antara teks wahyu dengan realitas yang hidup sesuai dengan kebutuhan manusia ketika itu. Pasca meninggalnya Nabi, tugas ini diberikan kepada para nalar juris Islam.