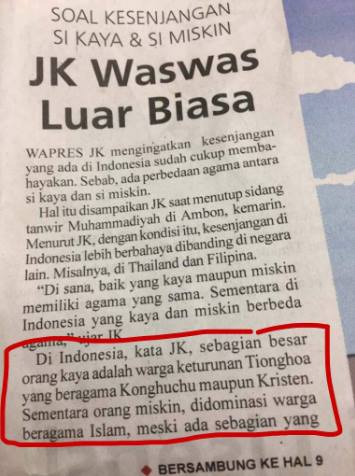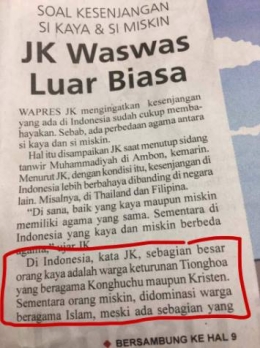Kawanku kecilku, namanya Tong Sen, membantu ibunya berjualan kue. Kue-kue dititipkan di warung-warung pada pagi hari ketika dia berangkat sekolah naik sepeda. Sore, sekitar pukul 17.00 dia akan mengambil lagi di warung-warung. Kalau ada sisa, aku dan kawan-kawan kampung diberi kue itu.
Dan, tidak jauh dari kampung kami, dulu ada orang gila satu-satunya, Tionghoa pula, Pak. Namanya Akiun. Gaya berjalan seperti aparat dengan kayu sebagai tongkat atau senjata. Konon (gosip orang kampung), Akiun gila karena mengencingi sebuah kuburan tua yang sudah tidak jelas. Orang kampung kami tidak seorang pun gila, Pak. Kami diajarkan tetua kampung, kalau mau pipis di alam terbuka (kebun atau hutan), harus bilang, “Numpang kencing, Tuk (Tuk/Atuk=kakek).”
Di sekolahku dulu, Pak, ada kawan sekolah (Etnis Tionghoa) yang berseragam sekolah lusuh, bahkan berhenti sekolah (Kelas 1 SMP) karena berasal dari keluarga miskin. Namanya Tet Khiong. Kecil-kurus. Kelihatan sekali kurang gizi. Ayahnya pernah jadi nelayan tapi kemudian lumpuh karena terkena sengatan ikan kecos (ikan pari kecil yang bertanduk dekat ekor). Dia berlima atau enam saudara, dan dia sulung.
Penjaga bahkan pesuruh SMP kami bernama Apuk adalah orang Tionghoa. Apuk tidak pernah membantah ketika disuruh apa pun oleh kepala sekolah dan guru. Disuruh beli sayur-mayur untuk seorang guru Melayu pun, Apuk berangkat ke pasar berjarak 1,5 km naik sepeda genjot. Tidak jarang Apuk ‘kerjain’ kawan-kawanku, baik kawan Tionghoa, Melayu, Batak, Flores, dan Jawa. Tidak pernah ada prasangka sosial, Pak. Juga sekolah tempat bapakku mengajar di STM Sungailiat adalah orang Tionghoa.
Ya, Bapak JK bisa bayangkan, bagaimana seandainya sekolah Bapak dulu ada penjaga bahkan pesuruh sekolah beretnis Tionghoa, bahkan seandainya dulu keluarga Bapak memiliki asisten rumah tangga beretnis Tionghoa?
Bapak pun pasti bisa membayangkan, bagaimana masa kecilku dibentuk dalam lingkungan sosial yang menyenangkan tanpa terkontaminasi prasangka sosial dari stereotipe terhadap orang Tionghoa-Kong Hucu.
Ketahuilah, Pak, tidak sedikit buruh kasar, dari pencetak batubata yang berpanas-panas hingga pramuniaga di kawasan pertokoan Tionghoa adalah orang Tionghoa sendiri. Sebagian rumah mereka masih semi permanen pula, Pak.
Dulu, ketika aku dan kawan-kawan kampung sedang musim main pangkak (adu buah karet), aku sering mencari buah karet di dekat tempat tukang kayu yang beretnis Tionghoa. Makan siang mereka, dengan mataku sendiri kulihat, berupa nasi berlauk ikan asin kecil, Pak. Bukan satu-dua kali kulihat, Pak. Ada juga kawan Tionghoa-ku, cuma beda kampung, nyaris saban hari makan bulgur, Pak. Apa itu bulgur, Bapak pasti tahu.
Ketahuilah, Pak, generasi awal etnis Tionghoa di Bangka bukanlah berkelas pedagang apalagi pengusaha-pebisnis kelas kakap-hiu-paus. Bukan pula kelas terpelajar dengan kemampuan intelektual serba luar biasa, Pak. Rasa senasib orang Melayu-Tionghoa Bangka sebelum 1900-an terbentuk karena mayoritas orang Tionghoa di Bangka adalah buruh/kuli/pekerja kasar, baik di perkebunan maupun pembuatan bangunan.
Buruh Tionghoa beberapa kali memberontak terhadap Kolonial Belanda. Rasa senasib itulah yang kemudian menyatukan Melayu-Bangka dan Tionghoa dalam persaudaraan nasional melawan Kolonial Belanda. Rumah Mayor Chung A Thiam (orang Tionghoa-Kong Hucu) di Muntok, Bangka Barat, menjadi salah satu saksi sejarah, dimana Belanda menjadikan Chung A Thiam sebagai seorang mayor tentara Belanda untuk meredam pemberontakan orang Tionghoa.
Sejarah itu tertulis dalam buku sejarah Babel, Pak. Aku pernah membacanya di Perpustakaan Daerah Sungailiat. Mungkin ada di Perpustakaan Nasional R.I.