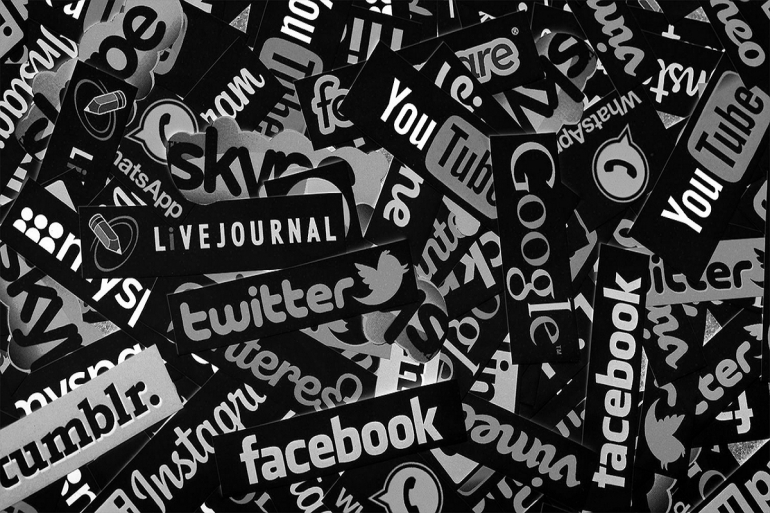Bagaimana sih rasanya diburu orang banyak karena sebuah kesalahan atau kejahatan? Diburu bukan secara fisik. Tapi di dunia digital. Mengerikan. Traumatis. Mungkin orang yang diburu akhirnya mengucilkan diri. Digital bounty atau sayembara mencari pelaku secara digital kini cukup sering kita temui di media sosial.
Seperti tindakan main hakim sendiri atas maling ayam, kini digital bounty atau vigilantism pun semakin marak. Jika di dunia nyata kita berlari mengejar si maling. Memburu pelaku secara digital dilakukan dengan doxing. Bahkan bukan tidak mungkin melacak kediaman pelaku dan mendatanginya. Ini hanya merupakan dampak aktivitas di permukaan.
Namun ada dampak yang abadi dan signifikan yang terjadi. Mulai dari dampak psikis karena nama atau kasus menjadi viral. Juga secara sosial-ekonomi, jejak digital seperti nama, foto, alamat, sampai nomor telepon membuat pelaku dipenjara atas kasusnya seumur hidup.
Pelaku distigma selamanya atas perilakunya di mata publik. Pelaku pun mungkin urung melamar kerja jika bagian HRD mengecek jejak digital dirinya.
Perburuan secara siber yang cukup terkenal pernah terjadi pada 2006 di Tiongkok. Perburuan ini dimula dengan beredarnya video online yang menunjukkan seorang wanita membunuh anak kucing dengan sepatu hak tingginya. Netizen yang marah memposting foto pelaku wanita secara online.
Banyak orang kemudian berusaha melacaknya di dunia nyata. Kolaborasi virtual ini, pada akhirnya mendapatkan nama dan tempat kerja pelaku. Dampaknya, ia ditangguhkan dari tempat kerjanya dan diminta melakukan permintaan maaf ke publik.
Di bulan Juni, Rachel Vennya membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa memberikan identitas lengkap seorang hater bernama Fathin. Bagi siapa yang bisa menemukan pelaku IP address akan diberikan hadiah uang sebesar Rp 15 juta. Walau kemudian sayembara ini dibatalkan dan disesalkan Rachel.
Di kasus lain, nama Imam Kurniawan mendadak menjadi target perburuan manusia. Imam diduga menuliskan komentar yang asusila kepada keluarga korban tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402.
Sayembara pada Imam dimulai oleh akun Facebook Fajar ArbayuBae. Dia juga memulai skema donasi terbuka mulai dari Rp 2 juta sebagai hadiah. Netizen pun ramai-ramai menyumbangkan uang mereka mulai Rp 10.000 hingga Rp 5 juta. Sebanyak Rp 21 juta telah terkumpul.
Aktivitas main hakim sendiri (vigilantism) telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Konsep vigilantism sendiri telah berkembang menjadi sebuah kontrol sosial yang bertujuan sebagai konsep pengendalian kejahatan. Di media dunia digital, konsep main hakim sendiri bersalin rupa menjadi lebih menakutkan.
Karena kemudahan pengguna platform digital untuk mencari, meminta, dan menyebarkan informasi pribadi, memprovokasi kemarahan secara kultur dan politik pun mudah dilakukan. Wacana dan tanggapan sosial netizen seperti kecaman dan mendiskreditkan konten sangat bervariasi.
Aktivitas kolaborasi ini bisa menjadi bagian ketidakpercayaan publik atas sistem hukum yang berlaku. Secara implisit, main hakim sendiri pun menjadi bentuk ketidakpercayaan atas ketegasan pihak berwajib, seperti pada kasus korupsi. Di dunia nyata, memassa maling ayam juga menjadi praktik ketidakpercayaan publik pada hukum.
Jika di dunia nyata, main hakim sendiri minim hukuman secara pidana. Lalu bagaimana jika di platform digital?
Saat netizen bisa menjadi siapa saja dan apa saja. Netizen pun tidak dibatasi lokasi, waktu, dan akses. Seperti kasus seorang hater Ayu Ting Ting yang ternyata pelaku perundungan sedang bekerja di luar negeri.
Platform digital selain telah mengamplifikasi konsep main hakim sendiri (vigilantism). Ia juga telah memberikan inovasi vigilantism dengan konsep sayembara (bounty). Di waktu ke depan, digital bounty belum akan surut atau malah akan semakin sering dijumpai.
Bukan saja publik figur yang melakukannya, mungkin juga orang biasa. Atau yang lebih mengkhawatirkan, akan ada kelompok yang sengaja menjadi 'pemburu pelaku' di platform digital. Sebaiknya kita perlu tahu dan memahami dampaknya.
Salam,
Wonogiri, 17 September 2021
11:48 am
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H