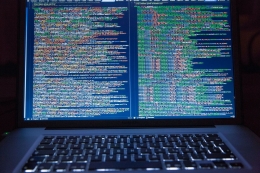Buzzword atau frasa nge-trend saat ini adalah Propaganda Rusia (PR). Walau frasa ini sudah diteliti dan dipublikasi sejak 2017. Namun di ajang Pilpres 2019 di Indonesia. Frasa PR dipolitisasi dan dibuat sensasi berita semata. Sampai-sampai ada kelompok melaporkan kubu petahana soal statement PR ini.
Walau mungkin secara kontekstual maksud yang diucapkan adalah propaganda ala Russia. Karena tanpa kata 'ala', tersurat makna bahwa negara Rusia turut campur dalam Pilpres 2019 Indonesia.
Terlepas dari pemaknaan kontekstual tersebut. Ada tiga proposisi yang perlu kita pahami dari PR. Berikut yang bisa saya rangkum.
- Pertama, memang ada keterlibatan pihak Rusia dalam Pilpres US di tahun 2016
- Kedua, terlalu prematur jika mengaitkan Pilpres kita dengan propaganda 'ala' Rusia
- Ketiga, publik kita sudah melek hoaks pada Pilpres 2019
Pertama, memang ada pihak di Rusia yang terlibat dalam Pilpres 2016 di US.
Tetapi belum terbukti apakah pemerintahannya juga turut serta. Walau banyak tuduhan dan bukti yang didapat. Rekam jejak digital masih bisa disangkal dan dianggap tidak mengancam keamanan nasional.
Dirangkum dari Wired usai Pilres US 2016, Jonathan Albright menemukan fingerprints atau jejak digital troll yang dikelola di Rusia. Trolls atau kelompok ini menggunakan bot untuk membuat gaduh dengan hoaks dan menggiring opini via Facebook, YouTube, dan Google.
Albright adalah seorang periset dari Columbia University. Jejak digital troll dari Rusia terendus Albright di Oktober 2017. Dan sempat diberitakan Washington Post pada 5 Oktober 2017.
Albright menemukan 470 situs yang dibeli pihak Rusia menyebarkan lebih dari 500 laman konten. Dengan bantuan bot laman konten ini di-share atau disebar ke Facebook. Diperkirakan jumlah share mencapai miliaran kali.
Setelah ditelusur secara digital forensic. Pelakunya adalah sebuah troll farm Rusia bernama Internet Research Agency (IRA). Ada 6 situs yang dipublikasi Albright menjadi troll IRA yaitu Blacktivists, United Muslims of America, Being Patriotic, Heart of Texas, Secured Borders dan LGBT United.
Sejak 2015, IRA membeli 3.000 iklan di Facebook. Iklan-iklan ini gencar mempromosikan iklan berideologi politik yang ekstrim. Iklan ini dikabarkan sudah mencapai lebih dari 10 juta users Facebook saat kampanye US 2016.
Ditambah, ditemukan pula lebih dari 80.000 video yang diunggah ke YouTube secara sporadis ribuan kali. Video-video ini dijadikan referensi pada ratusan situs yang dikelola IRA. Dengan kata lain menjadi pemvalidasi opini via Facebook. Dan juga menjadi 'recommended video' di platform YouTube sendiri.
Dengan kata lain, di US sendiri munculnya terma PR terbukti setelah ada riset digital forensic yang komprehensif dan longitudinal. Disertai data berupa digital fingerprints mendetail. Maka 'menuduh' ada pihak dari Rusia yang membuat propaganda pada Pilpres US 2016 sudah cukup valid.
Walau sayangnya, kini pihak FCC maupun FBI tidak menganggap intervensi pihak dari Rusia ini adalah kejahatan. Walau bukti jejak digital dan upaya penggiringan opini via sosial media sudah cukup jelas.

Dengan kata lain, pernyataan soal adanya intervensi ala Rusia pada Pilpres 2019 di Indonesia cukup gegabah. Saat bukti secara digital forensic belum cukup memadai. Sistematika pengolahan dan penyajian data pun masih tersebar dan mungkin belum cukup valid.
Pemaknaan terma PR sendiri berarti ada pihak asing atau pihak ke tiga dalam kontestasi Pilpres di US. Seperti yang telah ditelaah Albright dalam setiap laporan riset digitalnya. Ada IRA di Rusia yang mengelola ratusan troll digital untuk menggiring opini publik US saat Pilpres 2016.
Dalam memaknai PR sebagai propaganda 'ala' Rusia sendiri. Harus setidaknya tersirat pola penggiringan opini pihak lain yang campur tangan dalam peta perpolitikan saat Pilpres.
Apakah di Pilpres 2019 di Indonesia terlihat ada pihak asing? Atau adakah pola PR dari pihak ketiga yang terlibat?
Perang tagar yang dihimpun tim Drone Emprit (DE) pimpinan Ismail Fahmi pun belum bisa melihat adanya kaitan asing. Dalam 'perang tagar' antar simpatisan, DE menemukan jika ada kubu yang menggunakan bot dalam perang tagar yang sering terjadi.
Ada yang menarik dari perang tagar #VisiMisiJokowiMenang versus #HaramMemilihPemimpinIngkarJanji. DE menemukan kubu pembuat tagar yang kedua lebih organik dan interaksinya tinggi. Dengan kata lain, akun yang mendongkrak tagar ini bisa disebut akun asli.
Sedang untuk tagar yang pertama, akun yang digunakan diindikasi adalah bot. Akun bot biasanya dibuat masif, sedikit followers, dan sporadis dalam mendukung sebuah tagar. Interaksi untuk mendukung tagar pun dianggap lemah.
Akun pendukung tagar #HaramMemilihPemimpinIngkar diindikasi DE adalah sebagai pendukung HTI. Hal ini diamati dari akun-akun ini juga sempat mengusung tagar #UdahKhilafahAja atau #TerbuktiDustaJadiPetaka. Dan laporan lengkap dari kedua contoh tagar DE bisa dilihat disini.
Kembali kepada proposisi kedua. Apakah ada intervensi digital pihak asing ala PR di Pilpres 2019? Dari pengamatan DE dan saya pribadi, belum cukup signifikan bukti metode PR telah dijalankan pada Pilpres kita saat ini.
Pembuat sentimen dengan tagar untuk trending masih diindikasi dari pendukung kedua pasang Capres. Belum ditemukan jejak digital pihak asing yang yang secara masif dan sistematik bahkan random menyusupi perang tagar Pilpres.
Dan yang saya pribadi lihat, peran tim siber masing-masing timses masih cukup dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi langsung pihak asing diluar negara kita belum begitu nampak.
Namun, sepertinya ada pola 'hybrid' yang coba diterapkan untuk menggiring opini. Gabungan diseminasi hoaks dan ajakan golput bisa jadi dilakukan pihak tertentu untuk mendelegitimasi hasil Pilpres nanti.
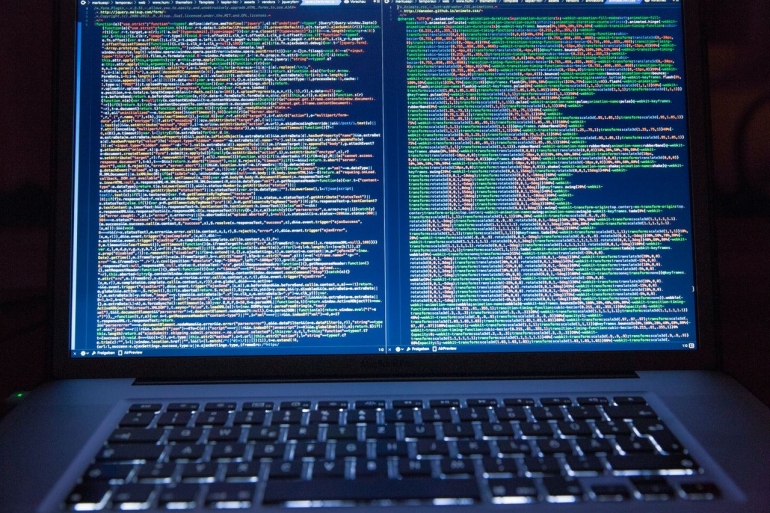
Perlawanan pemerintah dan banyak komunitas menangkal hoaks saat Pilpres bukan main-main. Karena publik sudah cukup terinformasi dan paham bahaya hoaks. Hoaks politik yang beredar saat Pilpres 2019 kini diawasi, dibongkar, dan disebarkan banyak pihak yang peduli.
Kemenkominfo pun sering mempublis verifikasi fakta hoaks. Melalui beragam akun sosmed milik Menkominfo, hoaks yang ada bisa dengan cepat dan real-time dihadapi. Bahkan beberapa kali Menkominfo merilis laporan hoaks secara berkala.
Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) pun sejak 2016 aktif melawan hoaks via fact-check, forum FB, dan aplikasi HBT. Tim cek fakta Mafindo sudah terverifikasi oleh IFCN (International Fact-Checking Network) dari Poynter Institute. IFCN juga memverifikasi Kompas, Tirto.id, Tempo.co dan Liputan6.
Cekfakta.com pun telah mengkolaborasikan Mafindo, AJI, bersama 22 media kredibel lain. Diharapkan, cekfakta.com ini menjadi crowdsource dan referensi bersama agar publik melihat fakta dari hoaks yang sudah ada.
Jawa Barat pun belum lama membuat Tim Jabar Saber Hoaks. Tim ini selain men-debunking hoaks secara umum. Mereka juga merilis fakta hoaks yang bersifat kelokalan atau terjadi di Jawa Barat saja. Dan banyak tim cek fakta lain yang membongkar hoaks tanpa lelah.
Bisa kita simpulkan bahwa publik kita telah siap menghadapi hoaks secara teknis. Komunitas, media, bahkan aplikasi cek fakta sudah ada. Publik pun via sosmed sudah bisa bersinggungan dengan tim cek fakta manapun.
Berbeda kenyataannya ketika Pilpres US di tahun 2016. Publik disana belum banyak menyadari penggiringan opini ala PR yang sedang terjadi. Skandal Cambridge Analytica (CA) sendiri baru terbongkar setahun kemudian. Setelah diungkap mantan periset CA bahwa 80 juta akun diduga telah dieksploitasi.
Publik kita lebih siap dan aware akan hoaks dan propaganda. Indikasinya terlihat dari sentimen trending topic saling serang yang berubah-ubah. Informasi hoaks atau misinformasi yang ada pun banyak yang didaur ulang dari tahun sebelumnya.
Kesimpulan
Ketiga proposisi diatas yang tidak banyak dinarasikan media. Karena media yang ada mungkin mencari sensasi. Dan mereka urung memberitakan kompleksitas dunia digital dan metode 'propaganda Rusia' itu sendiri.
Secara empiris, belum ada digital fingerprints yang menunjuk keterlibatan Rusia atau pihak asing diluar negara kita. Kegaduhan linimasa pun masih didominasi sentiman oleh akun asli dan bot yang bersifat lokal.
Dan yang paling utama, publik kita sudah cukup mengerti apa yang terjadi di Pilpres US. Walau literasi digital dan media belum menjadi bagian kurikulum pendidikan. Namun gaung dan kesadaran menangkal hoaks sudah cukup mengena dan bermanfaat untuk publik.
Salam,
Solo, 07 Februari 2019
11:27 pm
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI