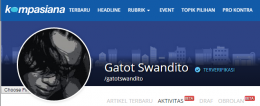“Saya Gatot ... Gatot Swandito,” kata saya saat mengenalkan diri kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi yang menjamu makan siang belasan Kompasianer di Istana pada 19 Mei 2015. “Saya lebih dikenal oleh kader PKS ....”
“Grrr ...” Presiden dan teman-teman Kompasianer spontan tertawa.
Saya berhenti. Aneh juga, kok Presiden tertawa begitu mendengar kata “PKS” yang saya ucapkan. Kalau yang tertawa itu Kang Pepih Nugraha, Bang Gunawan, Mas Ninoy N Karundeng, Mbak Niken Setyawati, atau Om Stevanus Tony, masih bisa diterima akal sehat karena teman-teman Kompasianer itu pasti mengenal luar-dalam “genre” tulisan saya. Lha, Jokowi juga tertawa spontan. Jangan-jangan ....
Ah, sorry to say kalau waktu itu saya kegeeran. Apalagi Jokowi pun sempat mengaku kalau sering mengakses Kompasiana di waktu luangnya. Tidak heran kalau Jokowi menganal karakter tulisan-tulisan yang diposting di Kompasiana.
“Judulnya serem-serem. Tapi, isinya beda dengan judulnya,” kata Jokowi disusul tawa kecilnya.
Jadi, tidak salah juga kalau saya geer. Toh, bagi saya geer itu #YangPentingHatinya.
Sebenarnya, saya agak-agak heran, kok bisa ikut diundang ke Istana. Bukan apa-apa, mungkin di antara reribuan pendukung Jokowi, saya termasuk pendukung yang tidak membigotkan diri.
Contohnya, sewaktu pendukung Jokowi masih hanyut dalam suasana pesta meriah pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2014, sehari kemudian saya menulis “Berbahasa Inggris di Istana, Jokowi Melanggar Sumpah”. Jadi, bisa dibilang dari ratusan juta warga negara Indonesia, sayalah orang pertama yang menilai Jokowi sudah bisa dimakzulkan. Waktu itu ada yang bilang kalau saya mulai ngawur dan mengacau. Katanya , inilah-itulah. Saya diamkan saja, ogah menanggapinya.
Eh, pas tanggal 10 November 2014 buka Tempo.co, mata saya tertuju dan terfokus pada judul berita “Pidato Berbahasa Inggris, Jokowi Bisa Langgar Sumpah” Ups, ciyus? Saya baca beritanya dengan skala ketelitian per inchi. Dalam beritanya itu, Tempo mengutip pernyataan Profesor Hikmahanto Juwana. Menurut ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia itu, Jokowi sudah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RI jika berpidato menggunakan bahasa Inggris di salah satu sesi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation di Beijing.
Nah, kalau cas cis cus pakai bahasa Inggris di luar negeri saja dianggap melanggar sumpah jabatan, apalagi di dalam negeri. Logikanya sangat jelas, jadi tidak ada sedikit pun kengawuran dalam alam pikiran saya yang tertuang pada artikel tersebut. Malah saya jadi geer karena lebih dulu ketimbang Hikmahanto yang bergelar profesor itu.
Jangankan setelah Jokowi dilantik, pas lagi panas-panasnya kampanye saja saya posting artikel “Quick Count Ngawur: Di Arab Jokowi Raih 75 %, Prabowo Caplok 20 %” yang ditayangkan pada 5 Juli 2014 atau 4 hari jelang hari pencoblosan Pilpres 2014. Sebelum menayangkan artikel itu, saya sempat ribut-ribut di status Facebook milik teman Kompasianer pendukung Jokowi. “Mana ada hasil quick count, wong kotak suaranya saja belum dibuka. Quick count itu berdasarkan pada penghitungan suara. Mungkin yang dimaksud exit poll,” begitu komentar saya yang langsung disoraki Kompasianer pendukung Prabowo-Hatta.
Ketimbang ribut-ribut di Facebook, saya tuliskan saja dalam satu artikel lantas ditayangkan pada jam itu juga. Karuan saja, saya kena risik teman-teman pendukung Jokowi. Ada yang bilang saya sok pintar, penghianat, culun, dan masih banyak lagi. Wajar saja kalau banyak teman yang kesal, bagaimana pun juga tulisan itu di-copas oleh pendukung Prabowo-Hatta. Malah, PKSpiyungan.org pun ikut menuliskannya.
Bukannya malah bagus kalau ke-hoax-an itu dibeberkan oleh pendukung Jokowi sendiri. Apalagi, setelah tulisan saya itu tersebar, banyak media, termasuk media arus utama, yang merubah judul dan isi beritanya ada juga yang menghapus. Terus, sorry to say di mana kesalahan yang saya buat?
Soal di risik atau di-bully, sorry to say, buat saya bukan masalah lagi. Memang kadang suka jengkel juga. Tapi, justru dari situ saya jadi merasa seperti selebritis. Kan, banyak seleb yang malah bangga kalau dirisik. Katanya, hater-hater yang membuli itu malah bikin para selebritis kian tersohor. Malah ada seleb yang bilang kalau ulah hater itu sebenarnya wujud dari rasa sayang.
Sejak aktif di Kompasiana pada 2013 (terdaftar sejak 23 Oktober 2009) saya punya banyak hater dari beragam kelompok, mulai kader PKS, kader HTI, pendukung Prabowo-Hatta, malah sekarang bertambah dengan masuknya pendukung Ahok. Jadi, kalau Kompasiana menggelar lomba banyak-banyakan hater, saya yakin bakal menang. Hater Kompasianer lainkan paling banyak lima biji. Malah ada yang tidak punya sama sekali. Jadi, sorry to say kalau di Kompasiana ini cuma saya yang pantas ngaku-ngaku selebritis.
Ada yang tanya, “Kok masih kalem balas komen-komen yang nge-bully?”
Saya jawab singkat-singkat saja, “Yang penting hatinya.”
Bully, kalau kata Barbara Coloroso, “Bullying is not about anger, it is about contempt. It is an excuse to put someonedown so the bully can feel up”. Jadi, bully tidak cuma sebuah agresi. Bully atau risik harus memenuhi unsur-unsur pengulangan, ketidakseimbangan kekuatan (imbalance power), dan timbulnya rasa takut, khawatir, ataupun cemas bagi korbannya,
Poin pertama terpenuhi, karena dilakukan berulang-ulang.. Poin kedua juga terpenuhi karena saya sendirian dan yang merisik jumlahnya lebih banyak. Tapi, poin ketiga tidak terpenuhi karena saya tidak merasa takut, khawatir, dan cemas. Kalau begitu saya belum jadi korban bully. Kan, #YangPentingHatinya.
Itulah alasan pasti kenapa sampai saat ini saya masih tetap eksis di Kompasiana. Kalau dipikir-pikir, saya ini memang bermental selebritis. Mungkin, selevel dengan selebritis papan atas seperti Syarini, Julia Perez alias Jupe, Dewi Persik atau Depe, Nikita Mirzani aka NM, dan tentu saja Ahmad Dani yang sekarang sedang berkampanye untuk pencalonannya sebagai Bupati Bekasi. Mereka itu, biarpun dirisik, tetap saja eksis. Malah sering nongol di acara-acara gosip dari pagi sampai pagi lagi. Dani malah rajin bercicicuit di dahan Twitter.
Kalau membaca tulisan-tulisan teman yang ikut “festifal”8 tahun Kompasiana, rerata isinya tentang tulisan yang berkesan bagi penulisnya. Ada juga yang menuliskan kesannya tentang pertemanan di antara Kompasianer. Sorry to say ... sorry to say ... sorry to say, saya mah beda atuh. Kalau saya mah,momen terbaik ngompasianaitu ya pas dibuli. Karena dari situ saya tahu kalau tulisan saya bukan hanya sekadar dibaca, tapi juga dipahami, dan juga berhasil mengobok-obok emosi pembacanya.
Perkara kena risik itu urusan belakangan. Buat saya, menulis ya menulis saja. Saya tidak mau terkrangkeng dalam situasi dukung-mendukung atau mihak-memihak. Sewaktu Hidayat Nur Wahid dibuli gegara bilang kalau dirinya capres terkuat 2014 versi Pemira (Pemilu Raya), saya bela dengan menulis “Sekalipun Benar, HNW Tetap Dicibir”
Persoalan benar-atau salah dengan opini yang saya tulis, itu soal lain. Buat saya yang terpenting olah pikir yang tertuang dalam tulisan tidak menyimpang dari data atau informasi yang ada. Opini boleh salah, itu kata Kang Pepih dalam satu artikelnya. Dan, saya sangat setuju dengan artikel tersebut. Jangankan netizen, analisa badan intelijen yang diolah dari data atau informasi yang keakuratannya berskala 99 % saja masih sering meleset. Salah dalam menganalisa suatu peristiwa itu wajar, sebab yang diolah adalah persoalan sosial yang bersifat dinamis, bukan meja, kursi, mobil, air, planet, atau benda mati lainnya.
Setiap memposting artikel, saya juga tidak mengharapkan semua pembaca setuju. Sebelas-dua belas dengan selebritis yang tahu kalau tidak semua audien dapat menikmati pertunjukannya. Rambut sama hitam, pendapat bisa berbeda. Begitu kata pepatah. Mau ditepuktangani penonton, mau dicuekbebeki, atau mau ditimpuki dengan gelas plastik, toh Syarini, Jupe, Dewi, Depe, NM, dan Dani tetap selebritis yang terkenal. Begitu juga dengan saya. Mau tulisan saya disetujui pembaca, mau dibantah, mau dibuli, toh itu semua tidak mengurangi kadar keselebritisan saya.
Tapi, benar kata para selebritis. Jadi terkenal itu ada enaknya ada juga tidak enaknya. Begitu juga dengan pengalaman yang pernah saya alami dan pernah saya ceritakan ke Mpok Mike dan Kak Elde. Ceritanya begini, apada suatu ketika, saya mengurus ATM di sebuah bank di kota Cirebon. Tibalah giliran saya dilayani oleh CS bank yang cantik berjilbab. Seperti biasa, saya menyodorkan buku rekening dan KTP. Tidak perlu berlama-lama urusan ATM pun kelar.
“Maaf, Pak, ini dengan Pak Gatot Swandito yang menulis di Kompasiana bukan?” tanya mbak CS yang cantik itu sambil tersenyum.
Mendengar pertanyaan itu, naluri keselebritisan saya langsung tergerak. “Benar. Saya memang Gatot Swandito yang di Kompasiana,” jawab saya bangga. Tangan kiri saya pun langsung merogoh saku celana kiri untuk mengambil HP. Maksudnya untuk menunjukkan kalau saya memang benar selebritis Kompasiana yang dikenalnya itu.
Sementara saya mengutak-atik layar HP, saya mendengar Mbak CS bercerita. Katanya, ia sering membaca tulisan di kanal Fiksiana dan beberapa kali menayangkan karya fiksinya di sana. Mendengar cerita Mbak CS saya tersenyum manis penuh pesona nan memikat. Senang rasanya ketemu sesama Kompasianer. Apalagi Kompasianer itu mengenali saya. Naluri keselebritisan saya pun makin bergolak. Begitu saya mau menunjukkan dashboard Kompasiana akun Gatot Swandito, Mbak CS bertanya, “Oh ya Mas, kalau Mas Elde dengan Mas Anu itu kenapa sih ...?”
Welah dalah, Mbak CS-nya ini, bagaimana toh? Ketemuannya sama siapa, kenalnya sama siapa. Dan, sorry to say, yang selebritis di Kompasiana itu siapa? Lha, kok yang ditanya malah Kompasianer yang lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H