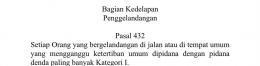Salah satu pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disepakati Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/9/2019) lalu adalah tentang gelandangan.
Ancaman pidana terhadap gelandangan diatur dalam Pasal 432 RKUHP yang menyebut, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Rp 1 juta).
Dalam hal ini, ada satu hal menarik terkait alasan penerapan pidana denda bagi gelandangan sebagaimana disampaikan Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil.
Anggota DPR dari Fraksi PKS itu mengatakan, pasal tentang gelandangan ini bertujuan mendorong agar pemerintah berupaya mengurangi jumlah gelandangan. Bahkan menurutnya, pasal ini justru menjadi instrumen dalam memaksa pemerintah agar memperhatikan warga negaranya.
"Makanya justru itu negara harus bertanggung jawab agar warganya tidak jadi gelandangan. Kalau kita ngomong seperti ini seolah tidak nyambung, tetapi sebenarnya ini hukum tidak bisa berdiri sendiri," kata Nasir seperti dilansir Kompas, Kamis (19/9).
Sampai di sini (menurut saya), dasar pemikiran atau cara pandang wakil rakyat terhadap orang-orang miskin yang disebut gelandangan itu, sudah benar. Bahkan, cukup manusiawi.
KUHP sering disebut sebagai hukum warisan kolonial sehingga perlu direvisi dengan mengacu kepada hukum Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.
Meski sudah diamandemen berkali-kali, pasal 34 ayat (1) UUD 1945 masih berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mereka, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan -- yang disebut gelandangan itu adalah rakyat miskin yang harus dipelihara negara.
Maka menjadi tepat apa yang dikatakan anggota DPR Nasir Djamil bahwa pasal mengenai gelandangan dalam RKUHP itu akan menjadi instrumen dalam memaksa pemerintah agar memperhatikan warga negaranya (agar tidak menjadi gelandangan).
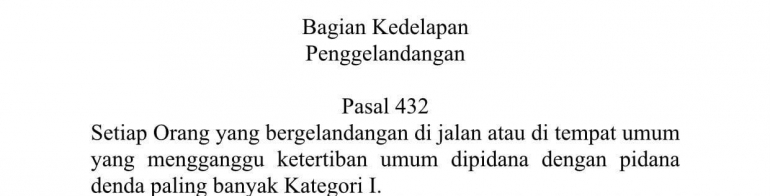
Gelandangan yang mestinya diperhatikan pemerintah, gelandangan yang mestinya dipelihara negara, justru diancam pidana sesuai pasal dalam RKUHP tersebut.
Logikanya, apabila tujuan adanya pasal mengenai gelandangan dalam KUHP untuk memaksa pemerintah agar memperhatikan warganya, maka pejabat pemerintah-lah yang seharusnya diancam pidana jika di wilayahnya terdapat warga yang menjadi gelandangan.
Di tingkat daerah, bupati atau walikota-lah yang mestinya didakwa melanggar hukum karena lalai memperhatikan warganya sehingga ada yang sampai tidur di jalanan, mengemis dan meminta-minta agar bisa makan.
Memang, pasal mengenai gelandangan dalam RKUHP ini bukan hal baru. Dalam KUHP yang berlaku selama ini (sebelum revisi) pun juga mengatur tentang gelandangan, tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda. RKHUP hanya mengubah pidana kurungan yang disebut di KUHP (Pasal 505 Ayat 1 dan ayat 2), menjadi pidana denda.
Akan tetapi substansinya tetap sama. Gelandangan tetap saja menjadi kelompok masyarakat yang tidak disukai, bahkan dibenci negara. Gelandangan adalah orang-orang yang didakwa melanggar hukum karena dianggap mengganggu ketertiban umum.
Bukankah mereka itu termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mestinya dipelihara oleh negara? Bukankah jika di tengah masyarakat masih terdapat gelandangan justru merupakan bukti bahwa negara gagal menjalankan fungsinya?
Tidak adakah cara yang lebih bijak selain mendakwa dan mengancam mereka pidana karena dianggap sebagai sampah masyarakat? Sungguh, betapa menyedihkannya hidup seorang gelandangan di sebuah negara merdeka yang kononnya kaya raya.
Saat ini, masih ada harapan untuk mengubah atau meninjau ulang pasal-pasal kontroversial RKUHP yang menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk tentang gelandangan, karena Presiden Joko Widodo telah meminta DPR menunda pengesahan.
Apabila semangat merevisi KUHP agar kita tidak lagi menggunakan kitab undang-undang produk kolonial, sebaiknya pasal mengenai gelandangan ditiadakan.
Jika memang harus ada, pasal mengenai gelandangan sepertinya akan lebih bagus kalau bunyinya, bupati atau walikota dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I apabila di wilayahnya ada satu warga yang menjadi gelandangan.
Bunyi pasal yang seperti itu akan sangat pas menjadi instrumen dalam memaksa pemerintah agar memperhatikan warga negaranya (agar tidak menjadi gelandangan) sebagaimana yang dikatakan Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil.
Atau, jika para gelandangan memang ditakdirkan sebagai orang yang dibenci dan dimusuhi negara karena dianggap menggganggu ketertiban umum sehingga perlu dibuatkan Undang-Undang untuk memidanakan, amandemen Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menjadi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipidana oleh negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H