Masalah kemiskinan merupakan keprihatinan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR tanggal 16 Agustus lalu. Sebenarnya ada solusi sederhana untuk pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam doukumen Nawacita pada bagian kemandirian ekonomi, yaitu menggunakan “energi kerakyatan” biofuel dengan rakyat sebagai aktor utama penyedia energi nasional.
Menilik dokumen Nawacita bagian kedaulatan dan kemandirian energi, Jokowi-JK mengisyaratkan menggalakan penggunaan biofuel yang berbasis domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Jika saja Pemerintah serius mewujudkannya, penulis mencatat sedikitnya ada lima sasaran Nawacita akan terwujud sekaligus yaitu; membangun Indonesia dari pinggiran, pengurangan angka kemiskinan, kemandirian energi nasional, pengurangan emisi karbon serta Land Reform atau redistribusi kepemilikan tanah.
Untuk mewujudkan rakyat miskin sebagai aktor di industri biofuel, caranya dengan melibatkan penduduk miskin dalam rantai suplai energi nasional. Membagi “kue” raksasa sektor energi yang bernilai ratusan triliun setiap tahunnya dan mendistribusikan kepada penduduk miskin, adalah pilihan paling rasional dalam mengurangi persentase penduduk miskin secara signifikan dalam waktu singkat.
Pintu masuk penduduk miskin kedalam rantai suplai energi nasional adalah dengan cara sederhana yaitu menanam ubi kayu atau populer disebut singkong sebagai bahan baku pembuatan bioethanol. Bioethanol murni dapat menjadi pengganti BBM jenis Premium yang setiap tahunnya di konsumsi sekitar 30 juta kiloliter secara nasional.
Mengapa tanaman singkong yang dipilih untuk dikembangkan secara masal? Menurut Prihandana dalam bukunya “Bioetanol Ubi Kayu: Bahan Bakar Masa Depan” memberi pertimbangan digunakannya singkong sebagai bahan baku etanol: a) Singkong sudah sejak lama dikenal dan dibudidayakan secara turun-menurun oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, b) singkong telah tersebar di 55 kabupaten seluruh provinsi, c) singkong merupakan tanaman yang mempunyai tingkat toleransi tinggi terhadap tanah dengan tingkat kesuburan rendah, dan mampu berproduksi baik pada lahan sub optimal. Bahkan tanah seperti di daerah Gunung Kidul pun singkong bisa berkembang dibantu dengan pemupukan dan masa tanam 2-3 bulan lebih panjang dibandingkan ditanam di daerah subur seperti daerah Malang misalnya.
Untuk urusan varietas unggul singkong, Kementerian Pertanian dan Balai Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (BALITKABI) sudah menghasilkan beberapa varietas yang terbukti unggul dalam hal potensi hasil dan rendemen yang tinggi jika diolah menjadi bioetanol nantinya.
Dari sisi kesiapan teknologi, pengolahan singkong menjadi bioetanol tidak memerlukan teknologi yang tinggi dan berbiaya triliyunan layaknya pengilangan minyak mentah. Bahkan kalau dimungkinkan oleh pemerintah, UMKM skala rumahanpun dapat diberdayakan dalam mengolah singkong menjadi bioetanol. Kesimpulanya dari sisi tanaman dan teknologi pengolahan Indonesia siap untuk itu.
Dari uji coba penggunaan Premium yang dicampur bioetanol sebesar 10% terhadap daya dan torsi pada mesin statis dan dinamis yang dilakukan di laboratorium TMP BPPT Serpong, menunjukan performa mesin relatif lebih baik dari Pertamax. Dari jumlah emisi berbahaya, tercatat Premium dicampur dengan bioethanol lebih ramah lingkungan karena menghasilkan lebih sedikit emisi berbahaya seperti karbon dioksida. Ini sejalan dengan Nawacita yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26-41% dari periode 2010 - 2020.
Kedua hal positif diatas dapat terjadi sebab bioethanol mengandung 35% oksigen lebih banyak dari Premium sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran. Tercatat semakin besar persentase penyampuran bioetanol pada Premium, semakin baik kedua aspek diatas.
Satu hal lagi keuntungan membudidayakan singkong adalah tidak tergantung dengan bibit yang dipasok dari luar. Bibit berupa stek diambil dari tanaman singkong sehabis panen. Diantara tanaman singkong juga dapat tanaman lain seperti kacang-kacangan. Untuk pupuk hanya dibutuhkan total 400 kg per satu musim tanam (8-11 bulan) terdiri dari pupuk Urea, SP36 dan KCL.
Singkatnya singkong atau tanaman ubi kayu ditinjau dari aspek bahan baku , aspek teknologi, aspek lingkungan serta aspek komersial lebih menjanjikan sebagai bahan baku pembuatan bioethanol dibandingkan tetes tebu misalnya.
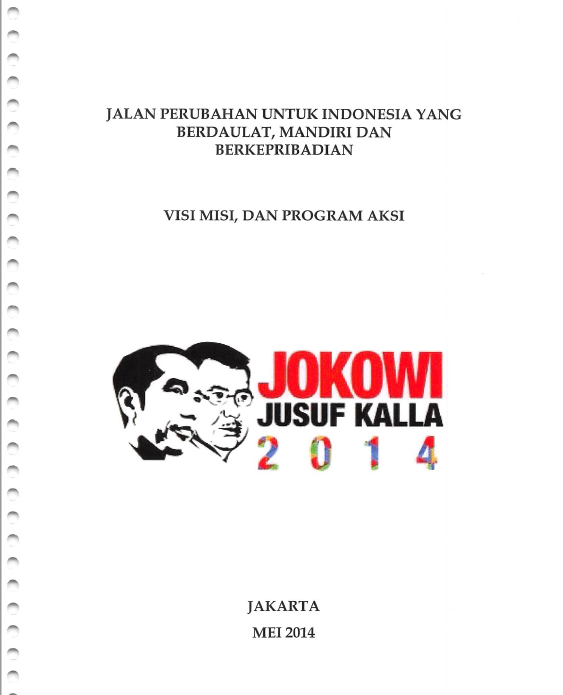
Bayangkan jika setiap 1 KK penduduk miskin mendapat hak menggarap tanah sebesar 2 hektar, dan setiap hektarnya dapat menghasilkan 30 ton singkong, maka pendapatan kotor setiap KK adalah Rp 60 juta pertahun atau Rp 5 juta perbulan dari berbudidaya singkong saja. Belum lagi jika mereka mendapatkan hasil dari menanam tanaman tumpang sari atau mendirikan usaha patungan untuk mengolah singkong menjadi bioethanol.
Berapa lahan yang dibutuhkan? Pemerintah cukup menyediakan lahan seluas 1,2 – 1,5 juta hektar. Ini juga sejalan dengan Nawacita yang bahkan akan membagikan 9 juta hektar lahan bagi petani dan buruh tani. Dengan memberikan lahan 2 hektar per KK, kalau 1 KK terdiri dari 4 jiwa maka aka nada 2,4 - 3 juta jiwa yang secara langsung terangkat dari garis kemiskinan. Belum lagi efek berantai menggeliatnya perekonomian sekitar perkebunan singkong, akan ada sekian juta orang akan terangkat dari jurang kemiskinan. Ini sejalan dengan Nawacita yang mendorong pembanguanan dari desa/pinggiran.
Sekarang tinggal apakah kemauan Pemerintah mau menangkap peluang ini, sebab ada lima sasaran Nawacita terwujud sekaligus dengan pengentaskan kemiskinan sebagai sasaran utama. Berikut dengan “bonus” yang berlimpah seperti; mengurangi laju devisa keluar negeri akibat impor minyak mentah atau premium, sampai menahan laju urbanisasi ke kota. Intinya singkong akan menggairahkan perekonomian nasional secara berkesinambungan sebab bioethanol adalah termasuk energi baru yang terbarukan (EBT).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H








