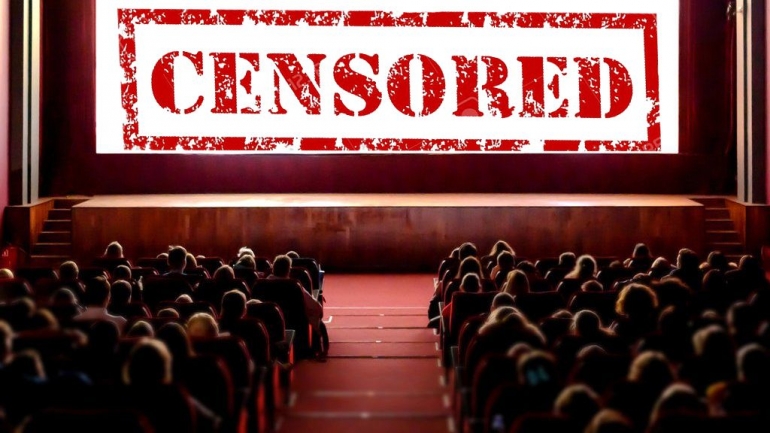Pernahkah kalian menonton sebuah film di bioskop, yang mana film tersebut mengalami pemenggalan adegan ditengah-tengah alur yang sedang berjalan, sehingga mempengaruhi koherensi cerita dalam film tersebut? Ya, itu merupakan 'ulah' dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Sejak Lembaga ini masih bernama Panitia Pengawas Film pada dekade 40-an akhir, tugas dan fungsinya adalah untuk menyensor bagian-bagian dari film yang dianggap tidak sesuai dengan cerminan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang tentang perfilman.
Seiring perkembangan zaman dan perubahan pemerintahan, aturan penyensorannya ikut mengalami perubahan. Seperti pada zaman Nippon masih menjajah Indonesia, film-film Hollywood yang boleh ditayangkan hanyalah film dengan muatan soal kejahatan barat, dan persahabatan dengan benua Asia.
Nippon juga mengontrol penuh konten propaganda yang wajib dikandung dalam film berupa muatan soal kehebatan tentara Jepang, budaya Jepang, hingga penggambaran Jepang yang merangkul pribumi.
Memasuki era pasca kemerdekaan, tepatnya pada awal lahirnya perfilman nasional pada 1950-1951, aturan penyensoran jadi berfokus pada pelarangan film-film yang memuat anjuran perang, pelanggaran codex perwira, hingga penggambaran upaya untuk merobohkan pemerintahan sendiri.
Hingga pada 1965, diterbitkan ketentuan utama atas pelarangan film yang mengandung unsur ideologi lain, selain ideologi Pancasila, hal tersebut bisa dianggap sebagai buntut dari peristiwa Gerakan 30 September PKI.
Walau begitu, Badan Sensor Film (BSF) tidak begitu konservatif soal konten yang berbau seksual, sehingga maraknya film-film dengan muatan BuPaTi & SekWilDa (Buka Paha Tinggi, Sekitar Wilayah Dada) sampai dekade 80-an.
Memasuki dekade 90-an, perkembangan media televisi nasional yang semakin marak dan dibuatnya undang-undang penyiaran sehingga mempengaruhi peraturan sensor yang menganut pencacahan rating usia.
Dari situ mulailah timbul aturan yang cukup ketat dalam penyensoran film dan konten di televisi. Aturan tersebut hingga saat ini masih dianut oleh KPI dan LSF dalam menjalankan tugasnya.
Menyikapi hal tersebut, tidak sedikit para pembuat dan penonton film malah mengeluhkan kalau LSF dituduh sebagai 'tukang mutilasi' dan 'tukang kebiri' kreativitas. Lebih parahnya, LSF dipandang sebagai Lembaga sensor yang asal penggal tanpa memperdulikan koherensi dan esensi cerita dari film tersebut.
Pada dasarnya, penyensoran akan dilakukan berdasarkan kesepakatan rating usia yang diinginkan pihak rumah produksi dan keputusan akhir dari LSF.
Adegan-adegan seperti pornografi, kekerasan, sadisme hingga penggunaan narkotika bisa saja lolos untuk kategori usia 21 tahun keatas, namun adegan-adegan tersebut tentunya akan dipenggal habis-haisan jika disesuaikan untuk kategori rating usia 13 tahun ke atas. Adegan-adegan yang memancing penyensoran tetap saja dilarang untuk disajikan secara ekplisit.
Menurut aturan kategori rating usia LSF, untuk kategori 17 tahun keatas, muatan film yang sensitif dituntut untuk disajikan secara proporsional dan edukatif, sedangkan untuk kategori 21 tahun keatas, muatan film yang sensitif disajikan secara tidak berlebihan.
Maka pada akhirnya, para pembuat film lokal dengan visi yang liar dan gemar bermain dengan unsur sensitif tetap tidak memiliki porsi yang utuh dalam berekspresi dan berkreasi lewat media film.
Di era media baru seperti sekarang, masyarakat semakin mudah dalam mengakses berbagai konten digital yang tersedia. Salah satunya adalah film yang kini bisa diakses dimana saja dan kapan saja lewat platform OTT (Over-the-top).
Film-film yang tersedia di layanan OTT tersebut tidak melewati proses penyensoran oleh KPI maupun LSF, sehingga semua jenis film dengan muatan konten apapun bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat yang berlangganan OTT.
Menyikapi hal tersebut, LSF membuat kampanye Sensor Mandiri yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk pintar dalam memilah dan memilih film yang sesuai dengan kategori usia.
Kampanye tersebut tentunya sebagai upaya realisasi dari tupoksi LSF dalam menjaga tontonan yang akan dikonsumsi masyarakat secara bebas. Terlebih lagi, film selain sebagai karya seni juga merupakan suatu produk budaya yang dapat mempenetrasikan muatannya kepada penonton.
Tentu penonton harus bijak dan open-minded dalam memilih tontonan yang akan mereka konsumsi, sehingga semua muatan budaya asing ataupun muatan sensitif tidak akan mempengaruhi pemikiran serta memicu perbuatan buruk.
Gerakan sensor mandiri ini tentunya bisa dibilang positif dan memberi kebebasan kepada penonton, tanpa harus adanya pemenggalan adegan di sana-sini, pembatasan konten yang 'layak' atau 'tidak layak' hingga pembatasan kebebasan para sineas dalam menyampaikan gagasannya lewat film. Nah, itu berlaku untuk film-film yang beredar di OTT,
sedangkan di bioskop? apakah film-film bioskop juga bisa menerapkan hal serupa? Film beredar tanpa pemenggalan, menerapkan sensor mandiri dan memberi kebebasan kepada penonton untuk memilih tontonan mereka? Sayangnya tidak.
Aturan sensor mandiri yang memberi kebebasan pembuat dan penonton film untuk membuat dan menonton film secara utuh tanpa pemotongan, tentu memerlukan perubahan undang-undang dan kode etik penyensoran untuk dapat mengimplementasikan sensor mandiri yang benar-benar bebas secara utuh pada film-film yang tayang di bioskop.
Pada acara webinar Brawijaya Movie Day (10/10) Ketua LSF, Rommy Fibri Hardianto mengatakan bahwa LSF yang sekarang tidak seperti dulu yang asal potong, asal gunting, namun lebih 'demokratis' dalam melakukan penyensoran.
Selain memberikan kebebasan penonton untuk memilih tontonannya, lewat gerakan Sensor Mandiri, LSF juga memberi kebebasan kepada para pembuat film untuk menyensor filmnya sendiri.
Rumah produksi memberikan permintaan kategori rating usia untuk film mereka sebelum LSF melakukan screening, lalu pihak LSF akan memberikan beberapa catatan adegan tertentu yang harus dipotong, dan menyerahkannya kepada pihak rumah produksi untuk diedit ulang.
Sebelum itu, LSF akan melakukan diskusi dengan pihak rumah produksi setelah selesai menonton dan membuat catatan tentang adegan-adegan yang harus dipotong. Dari pihak rumah produksi pun boleh memberikan argumen jika adegan yang tercatat oleh LSF merupakan adegan yang vital dan punya konteks yang penting untuk keseluruhan cerita.
Hal tersebut dilakukan setelah banyaknya kritik yang menganggap LSF memotong secara asal tanpa pertimbangan konsep, konten, dan konteks dari film yang disensor.
Proses penyensoran yang sekarang memang lebih 'demokratis' ketimbang proses penyensoran yang dulu asal potong, asal penggal, asal mutilasi habis secara sepihak oleh lembaga penyensoran.
Namun pada akhirnya, semua mekanisme penyensoran tetap berada di bawah undang-undang dan kode etik penyensoran, sineas tanah air dituntut wajib untuk 'tunduk' kepada aturan mainnya. Ya kesimpulannya, sineas lokal tetap harus main aman, ya?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H