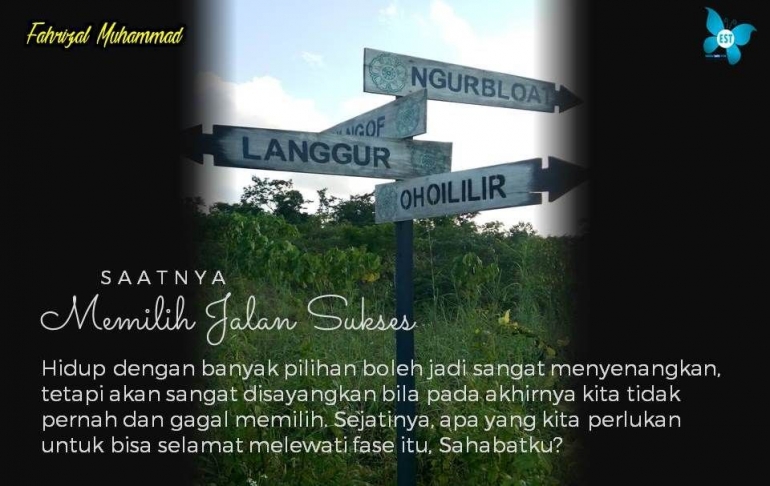Ada cerita cukup menarik dari sebuah kelas pelatihan di Hotel Selecta, Batu, Malang, Jawa Timur, Oktober 2005. Ketika itu hadir sebagai peserta seorang mahasiswi jurusan Teknik Elektro ITB. Ketika memasuki sesi perencanaan hidup, ia berbagi di hadapan seluruh peserta: selama ini hidupnya mengalir saja seperti arus air dan tanpa perencanaan apa-apa. Untung saja, katanya, dia sudah tersesat di jalan yang benar. Coba bayangkan bila dia tersesat di jalan yang salah, bisa jadi ia tidak akan ada di ruangan tersebut.
Tersesat di jalan yang benar! Jangan-jangan ini pulalah yang telah terjadi pada sebagian besar kehidupan kita. Tanpa kita sadari, sejumlah hal baik selama ini kita peroleh dalam derajat kemudahan tertentu dan tanpa rencana.
Oleh karena itu, kita tidak benar-benar menyadari bahwa pencapaian kita hakikatnya merupakan satu upaya sadar dalam kerangka besar sebuah perencanaan hidup yang komprehensif dan holistik. Jangan-jangan selama ini semua diperjuangkan sesaat, on the spot, dan dalam semangat "gimana besok aja!"
Metamorfosis Rencana
Hidup dengan rencana memang belum menjadi trend apalagi habit. Dia masih menjadi wacana di ruang kelas pelatihan dan akademis. Mengapa?
Karena, pertama, rencana itu wilayah ide. Dia tak nyata, setidaknya untuk saat ini. Membayangkan sesuatu yang belum nyata membutuhkan energi lebih karena belum adanya pengalaman. Kalau pun ada pengalaman orang lain tentang itu, tidak serta merta dapat diterjemahkan melalui langkah yang persis sama karena pasti sudah berjarak pada banyak hal: tempat, waktu, dan aktornya.
Kedua, yang kita visualisasikan bukanlah sesuatu yang pernah kita alami dan bukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Ala bisa karena biasa, begitu kata pepatah.
Sedangkan ini berbeda dengan pengalaman kita sebelumnya. Barangkali yang setidaknya dapat membantu adalah pengalaman dalam bidang yang sama pada dimensi yang berbeda. Pembiasaan berpkir tentang sesuatu yang transendental pada titik ini sangat diperlukan. Terlalu lama menenggelamkan diri dalam suasana dan kebiasaan berpikir sekadar untuk kekinian dan kebendaan sangat tidak membantu.
Ketiga, kekuatan visual mensyaratkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang kita bayangkan. Kenal dan tahu harus naik statusnya menjadi paham dan mengerti. Sejumlah informasi penting dan perbendaharaan pengetahuan tentang itu mestilah kita miliki. Atau paling tidak, dunia itu bukanlah sesuatu yang asing tetapi telah menjadi sesuatu yang kita "dekati" meskipun baru dalam tataran ide.
Itu artinya, kecenderungan pada dunia itu sangat menentukan tingkat pemahaman kita. Sebelum kita mendetailkan rencana tentang sesuatu sejumlah informasi penting mestinya telah menjadi bagian dari pengetahuan kita. Dengan demikian, kita punya modal yang cukup memadai untuk mengimplementasikan apa yang disarankan oleh Covey tentang perlunya "mendahulukan yang utama (first thing first)".
Keempat, Keterampilan visualisasi pun pada akhirnya menuntut kesabaran untuk menekuri tiap inci hal baru dalam satu rangkaian perencanaan yang boleh jadi masih asing. Namun demikian, sesuatu yang belum kita kenal tapi ingin sekali kita ketahui dengan baik justru seringkali memunculkan rasa ingin tahu yang kuat.
Rasa penasaran akan memberikan energi lebih untuk itu. Rasa itulah yang pada gilirannya menjadi pembeda. Meskipun begitu, penasaran tidak boleh membunuh kesabaran. Biarlah proses itu menjadi salah satu kenikmatan kita menjalaninya. Jangan terburu-buru dan jangan asal-asalan.
Kelima, visualisasi pada akhirnya mensyaratkan realisasi. Rencana tetap ada di benak dan di atas kertas dan itu belum nyata. Orang yang berencana menjadi dokter tidak akan jadi dokter tanpa aksi, tanpa melakukan segala rencana yang telah ditulisnya. Yang berhenti pada tataran ingin, ia meremehkan dirinya sendiri.
Yang puas hanya pada tataran rencana, justru ia telah menipu nuraninya dan berkhianat pada kemampuannya berbuat. Nah, realisasi inilah yang mesti ada di wilayah real berupa kerja dan aksi. Setidaknya, di tataran inilah kemalasan kita ditantang.
Seluruh penumpang Lion Air telah duduk di kursinya masing-masing. Pesawat pun didorong towing car menuju run away. Persiapan take off dimulai. Seorang pramugari menyapa para penumpang, "Bapak, Ibu, pelanggan kami yang terhormat. Selamat datang di Boeing 737 seri 900-ER, Lion Air. Kita akan terbang ke Polonia, Medan. Waktu tempuh Jakarta-Medan selama 2 jam. Tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Medan. Kita akan terbang 37.000 kaki di atas permukaan laut. Selamat menikmati penerbangan Anda!"
Alhamdulillah...ada waktu dua jam. Kita bisa melanjutkan mimpi yang terputus karena mesti berangkat setelah tahajud untuk kemudian menembus lalu lintas Jakarta di pagi-pagi buta; kita bisa sarapan nasi ulam yang kita beli di depan gerbang masuk kompleks perumahan; kita bisa melanjutkan baca Bayang-Bayang Pohon Delima-nya Tariq Ali yang tertunda-tunda seminggu ini karena kesibukan; kita bisa baca Lion Mag edisi bulan ini yang terselip di belakang kursi di depan kita;
Kita pun bisa menikmati pemandangan Jakarta yang bergegas dalam deru asap kendaraan dan kesibukan hari kerja dari ketinggian sambil mensyukuri atas nikmat Allah terbebas sejenak dari rutinitas seperti itu. Pendek kata, waktu dua jam yang diwartakan pramugari tadi dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas sesuai kebutuhan kita masing-masing.
Pesawat pun take-off. Kita pun duduk manis, tenang, dan nyaman. Bismillah...
Namun, suasana itu akan sangat kontras bila pada kesempatan yang sama, pramugari mengatakan demikian,"Bapak, Ibu, pelanggan kami yang terhormat. Selamat datang di Boeing 737 seri 900-ER, Lion Air. Kita akan terbang ke Polonia Medan. Waktu tempuh Jakarta-Medan selama 2 jam. Tidak ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Medan. Kita akan terbang 37.000 kaki di atas permukaan laut. Mudah-mudahan bahan bakarnya cukup!"
Ups! Saya yakin, meskipun tiket yang kita beli itu lebih mahal dua kali lipat daripada harga normal, kita akan berebutan menuju pintu keluar. Saya juga yakin, ada yang akan nekad membuka pintu darurat dan melompat ke luar. Ini masalah hidup, coy! Masa' iya ingin kita korbankan hidup yang cuma sekali dan sangat berharga ini hanya untuk sebuah penerbangan nekad tanpa persiapan dan rencana. Gak la yaw!
Sahabat, tanpa kita sadari, jangan-jangan selama ini kita hidup seperti halnya ujaran pramugari yang kedua di atas. Yang penting jalan. Yang penting hidup. Padahal, hidup begitu sangat berharga untuk disia-siakan. Kita harus punya rencana dan visualisasi masa depan. Ketika hidup asal hidup, maka buah dari kehidupan seperti itu pasti asal-asalan. Malu, dong, kalau khalifah Allah hidup dengan cara dan hasil yang asal-asalan.
Mengapa fenomena tersebut nampaknya meluas di masyarakat kita? Setidaknya ada sejumlah hipotesis tentang itu. Pertama, merasa aman dan nyaman dalam alam yang meninabobokan. Kita hidup di sepanjang garis khatulistiwa. Di wilayah ini matahari bersinar sepanjang tahun, sehingga sumber daya alam sebagai sarana hidup menjadi sangat bersahabat.
Namun, sejumlah fakta menunjukkan bahwa umumnya manusia yang hidup di negara-negara dengan empat musim memiliki etos kerja yang tinggi, sedangkan yang hidup di negara-negara tropis cenderung sedang dan rendah. Harold M. Proshansky, William H. Ittelson, dan Leanne G. Rivlin mencoba mencari ada tidaknya pengaruh perubahan iklim di negara-negara sub-tropis terhadap etos kerja masyarakatnya.
Dalam Environmental Psychology: Man and His Physical Setting (1970) mereka memaparkan, masyarakat di negara-negara sub-tropis memiliki etos kerja yang tinggi. Hal itu karena keadaan alam yang sangat keras. Dalam dunia pertanian misalnya, mereka yang tinggal di daerah berempat musim harus berusaha mengumpulkan makanan sebanyak mungkin untuk menghadapi musim dingin. Tradisi inilah yang dipercaya sebagai akar dari etos kerja yang tinggi dalam masyarakat sub-tropis tersebut. Masyarakat Jepang, misalnya, memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Indonesia yang berada di daerah tropis.
Bolehlah hipotesis dan kesimpulan di atas memberikan gambaran kepada kita tentang etos kerja masyarakat di negara sub-tropis yang lebih baik daripada etos kerja masyarakat tropis. Tetapi fakta lain memberikan informasi berbeda: sejumlah negara non sub-tropis pun pada titiknya dapat menjadi negara dengan etos kerja yang baik.
Singapura, misalnya. Artinya, ada titik ketika faktor iklim tidak lagi menjadi penentu tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat. Ada faktor lain yang dapat bermain di sini, setidaknya faktor mind set tentang fitrah penciptaan dan hubungannya dengan kerja itu sendiri.
Kedua, belum (baca: tidak) mau berpikir jangka panjang. Fenomena "ingin cepat", main trabas, dan serba instant menjadi sejumlah indikasi kondisi ini. Sejumlah pelanggaran hukum, norma, dan tata nilai terjadi ketika penyakit "ingin cepat" ini terjadi. Sejumlah aktivitas konyol dan tidak masuk akal dipaksa normal dalam benak dan pandangan kita.
Pola pikir itulah yang pada akhirnya akan melahirkan sikap dan perilaku berpola. Ketika ini dianggap wajar, maka orang tidak lagi membedakan mana benar mana salah. Absurd. Pada gilirannya, dengan cara ini pulalah begitu banyak orang menjadikan cara "ingin cepat", main trabas, dan serba instant sebagai solusi dalam permasalahan hidup mereka.
Di zaman ini, orang tidak lagi tertarik dengan kata-kata bijak, seperti "mari kita tunda kesenangan untuk kebahagiaan yang hakiki". Orang tidak lagi percaya dengan "berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian". Orang akhirnya lebih senang berprinsip, kalau bisa cepat mengapa harus lama, kalau ada yang mudah mengapa cari yang susah, atau kalau bisa dapat banyak mengapa mesti bangga hanya dengan dapat sedikit.
Apalagi, sanksi di tengah masyarakat permisif sekarang ini tidak memberikan efek jera sedikit pun. Predikat tersangka, terdakwa, atau bahkan vonis penjara sekali pun tidak sempat membuat gentar dan malu orang. Rasa malu telah menjadi omong kosong. Bahkan semua itu nyaris dianggap sebagai konsekuensi logis dari upaya meraih "sukses". Bahayanya adalah ketika pada titiknya orang menganggap semua itu biasa, maka kaburlah batas antara salah dan benar, suci dan kotor, jujur dan dusta, halal dan haram. Naudzubillah min dzalik.
Pada mulanya muncul dan berkembang pada orang perorang. Tetapi ketika sudah memenuhi kepala dan menjadi a set of value semakin banyak orang, maka tata nilai itu menjadi pola bertingkah laku. Kita "belajar" menyesuaikan tingkah laku kita dengan tata nilai yang "dianggap benar" itu. Celakanya, bila "yang dianggap benar" itu adalah hasil modifikasi dari sejumlah aspek yang kurang baik, maka tanpa kita sadari, kita sedang mendukung sebuah konstruksi tata nilai yang salah.
Nah, bila organisasi dan negara dipenuhi orang-orang yang demikian dan tidak ada gerakan serius untuk melawan gelombang dahsyat itu bahkan diam-diam mengamini dan merasa menjadi bagian dari fenomena tersebut, maka sangat mungkin kondisi tersebut dipraktikkan secara masif sebagai way of life bangsa atau organisasi tersebut.
Padahal, sejumlah pribadi boleh menjadi role model tentang ini. Matshusita, misalnya. Ia telah memberikan contoh tentang pentingnya berfikir jangka panjang. Tidak tanggung-tanggung, ia mencontohkan dengan visi 250 tahun yang diterapkannya di Panasonic, Jepang. Bila di Jepang muncul pribadi seperti Matshusita, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial tempat Matshushita tumbuh telah memungkinkan munculnya pola pikir yang demikian.
Pada gilirannya, ketika ia hidup di masanya, ia punya kans untuk merekonstruksi tata nilai di sekelilingnya. Bukankah itu masuk akal? Nah, apa lagi yang kita tunggu? Let's go!
Ketiga, merasa powerfull dan kreatif bila kepepet. Benarkah terdesak atau kepepet itu sangat positif sehingga menjadi salah satu kondisi yang tidak perlu dihindari apalagi ditakuti? Memang ada benarnya, kondisi itu tidak perlu ditakuti. Bahkan sejumlah pengalaman kita menunjukkan fenomena menarik: semakin kepepet dan terdesak, kita (merasa) semakin pintar dan kreatif. Benarkah demikian?
Sejatinya, kepepet adalah satu kondisi ketika kita tidak lagi punya waktu cukup untuk sejumlah pekerjaan yang mesti terselesaikan. Bahasa Indonesianya terpepet, terimpit, terjepit, terdesak, atau berada dalam keadaan kacau atau sukar. Kondisi itu lazim kita alami ketika misalnya, malam sudah sangat larut tapi kita harus menyelesaikan take home test karena besok pagi ditunggu dosen;
Ketika menghadapi test, kita masih harus menyelesaikan sejumlah soal pilihan ganda padahal waktu hanya tinggal beberapa menit lagi (hitung kancing, deh). Oleh karena itu, tidak aneh bila SKS yang semestinya Sistem Kredit Semester diplesetkan menjadi Sistem Kebut Semalam. Nah, pengalaman tidak baik itu pada titiknya dipercaya sebagai salah satu pengalaman menarik yang layak tiru. Padahal, kita sedang berada dalam "bahaya".
Pernahkah Anda merasa kepepet? Betulkah ketika kepepet kita menjadi sangat cerdas? Ketika kepepet, kita sering mengira kalau hasil kerja kita pada satu hal itulah yang terbaik, tetapi belum tentu. Kita menganggapnya seperti itu karena memang tidak ada waktu lagi untuk berfikir. Tidak sedikit yang berkilah,"Lho, Mas, itu kan namanya the power of kepepet!"
The Power of Kepepet (2008) adalah sebuah buku yang ditulis Jaya Setiabudi. Isi buku itu tidak mengajarkan kita untuk mencintai situasi kepepet seperti yang kita bicarakan ini. Buku itu mengabarkan kepada kita sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang entrepreneur, di antaranya adalah menciptakan kondisi kepepet. Kepepet dalam konteks ini menurut hemat saya adalah bahasa lain dari kondisi kritis dalam formulasi krilangkun-nya Yohanes Surya.
Menempatkan diri pada kondisi kepepet atau kritis adalah dengan menentukan sasaran yang jelas. Sasaran itu haruslah dibuat setinggi-tingginya dan waktu capai yang cukup. Misalnya, seorang pemuda yang ingin memiliki lembaga bimbingan belajar terkemuka di provinsinya dalam 5 tahun mendatang. Pemuda tersebut telah berani menempatkan dirinya pada kondisi kepepet. Kondisi itulah yang akan menyebabkan semesta bereaksi. Semesta akan mengatur diri untuk membantu agar kondisi kritis tersebut dapat terlewati dengan baik.
Jadi, hidup "gimana besok aja", bukanlah gaya hidup sehat dan modern. Itu gaya hidup yang semestinya sudah jadi bagian dari zaman jahiliyah yang harus ditinggalkan demi kehidupan yang lebih baik. Bukankah hidup yang tidak bergaransi dan tak mungkin kembali ini harus berarti, Sahabatku? Wa Allah A'lam bish-shawab.
Depok, 26 Maret 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H