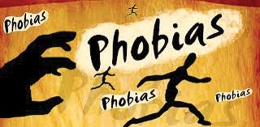Fenomena Ahok ternyata telah memunculkan banyak ketakutan. Ketakutan itu tidak hanya dialami oleh para kaum elit politik (politisi), elit budaya (budayawan), maupun elit agama (agamawan). Bahkan lebih jauh fenomena Ahok juga menciptakan rasa ketakutan pada kalangan pejabat pemerintahan dan masyarakat urban yang terpinggirkan.
Istilah Ahokbia saya adaptasi dan adopsi dari istilah atau konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh seorang tokoh. Seorang tokoh itu biasanya mempunyai pengaruh dan otoritas politik dan atau ilmu pengetahuan dalam menentukan arah suatu pembangunan. Karena itu, seorang tokoh politik atau ilmuwan yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu bangsa, maka pada namanya dilekatkan tambahan istilah nomic. Maka kita kenal ada istilah Hattanomic (1), Habibienomic, Hattanomic (2), SBY-nomic, dan mungkin masih ada lainnya.
Fenomena Ahok
Tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi sebuah fenomena tersendiri. Fenomena pertama, pada diri Ahok melekat dua atau lebih identitas minoritas. Identitas mana yang membuat public menggambarkannya sebagai sesuatu yang stigmatis, yang dalam perkembangan sesuai dengan dinamika social dan politik, sering dijadikan sebagai sasaran tembak. Minoritas etnis, agama, dan atau gaya kepemimpinan (leadership styles).
Fenomena kedua, Ahok memposisikan diri sebagai seseorang yang hendak berdiri di luar arus utama (mainstream). Bahkan kadang, karena sikap itu sehingga orang harus menggambarkannya sebagai menentang arus. Kelaziman yang ‘menyenangkan’ selama ini dinikmati oleh sebagian besar elemen masyarakat, elit politik, elit budaya, dan elit agama serta elit pemerintahan, dengan sengaja diterebas. Kesenangan-kesenangan yang sudah menjadi sesuatu yang mentradisi, meski itu harus mengorbankan kepentingan umum, sengaja dihentikan.
Fenomena ketiga, gaya kepemimpinan Ahok yang tanpa kompromi dan tidak tedeng aling-aling membuat sebagian elemen bangsa ini kegerahan. Apalagi harus ditambah dengan model komunikasi politik yang kurang memperhatikan tatakrama, sopan santun ala orang Timur. Model komunikasi politik yang ‘tidak lazim’, yang mana oleh sebagian orang menyebutkannya sebagai bahasa comberan.
Fenomena keempat, Ahok hendak memberikan sebuah kesan yang bersifat monumental ‘ingin dikenang’, sebagai hero. Ahok tidak terlalu mempedulikan efek balik dari sebuah kemungkinan kebijakan yang akan menggerus kepercayaan terhadap dirinya. Baginya, tidak penting untuk terpilih kembali menjabat sebagai seorang Kepala Daerah, jika harus bermanis muka dan berkata ‘lugu’. Ahok ingin menegaskan bahwa untuk membangun sebuah peradaban baru yang lebih memberi harapan untuk semua, maka harus siap menerima resiko. Karena pada setiap pilihan (politik) pasti memiliki resiko sebagai konsekuensi logis atas pilihan itu.
Fenomena kelima, Ahok hendak ingin membangun nilai baru. Nilai kejujuran, spotivitas, kemajemukan dalam kebhinekaan, konsistensi, fairness, komitmen, tanggung jawab, dan keberanian menantang arus. Bahwa bukan merupakan sebuah hal yang muspra dan mustahil, bila kemauan baik yang diikuti dengan kemauan politik serta itikad untuk berbuat baik demi kepentingn bersama, pasti akan menghadirkan sebuah panorama yang indah bagi kebersamaan dalam membangun harmoni bagi semua. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial sekretarian, yang hanya menciptakan inharmonisasi interaksi sosial.
Fenomena keenam, Ahok telah menjadi public enemy (musuh public), khususnya bagi kelompok dan elemen masyarakat yang merasa ‘dirugikan’ karena kehadirannya. Maka berbagai stigma minor dihadirpentaskan ke ranah public untuk mengkapitalisasi kebencian yang membuncah terhadap Ahok. Tidak berhenti hanya di batas itu, Ahok seolah-olah dianggap sebagai ‘penduduk haram’ di negeri Indonesia yang menganut bhineka tunggal ika ini. Karena ‘penduduk haram’, maka haram baginya menjadi pejabat publik, termasuk menjadi Kepala Daerah pada satu daerah territorial di negeri khatulistiwa ini.
Karena tidak ingin langsung membatasi hak Ahok karena ‘keharamannya’, maka doktrin agama pun dipompatuntaskan untuk menyerang Ahok. Umat ‘diintimidasi’ sebagai melakukan tindakan haram bila bukan memilih pemimpin yang seiman dengannya, tapi memilih pemimpin kafir. Meski pemimpin kafir memiliki dan memenuhi semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang jujur dan adil. Terjadi gejala ekploitasi nilai religiusitas untuk memanipulasi sentimen dan tingkat keimanan serta kesalehan umat.
Fenomena ketujuh, Ahok dinilai dapat menularkan virus dan pengaruh buruk terhadap sebuah model dan atau style kepemimpinan. Model dan style kepemimpinan yang cenderung menantang arus, meski hal itu demi alasan menghadirkan sebuah contoh peradaban pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pola komunikasi politik Ahok dinilai sebagai akan memberi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Pola komunikasi dengan pilihan kata yang masih dianggap tabu dalam tata karma dan kesantunan orang timur. Meski dalam konteksnya, hal kadang dinilai sebagai sebuah terapi kejut.
Fenomena kedelapan, Ahok ternyata juga memiliki sisi kemanusiaan yang sangat manusiawi, bereaksi ketika merasa tersudut. Kepribadian yang dianggap belum matang, karena sangat reaktif. Maka, tanpa memperhatikan ‘tabu politik’, Ahok tanpa merasa berdosa harus menyentil doktrin keyakinan agama lain sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Heboh al-Maidah 51 adalah contoh kasus di mana Ahok kurang wise dalam memahami psikologi umat mayoritas, sehingga dengan enteng menyentil isu yang sangat sensitive yang akan mengancam keberagaman Indonesia.
Gejala Ahokbia
‘Ahokbia’ merupakan kata yang terbentuk dari kata Ahok dan phobia. Kata Ahok, merujuk pada nama tenar dari Gubernur DKI Jakarta saat ini. Sedangkan kata bia, merupakan potongan akhir sukukata dari kata phobia. Phobia merupkan istilah dalam ilmu psikologi yang menjelaskan tentang rasa ketakutan pada sebuah obyek atau situasi tertentu. Boleh dikata, gabuangan kedua kata Ahok dan phobia, yang menjadi Ahokbia, ini sangat dipaksakan. hehehe
Phobia berasal dari kata phobi, yang berarti takut atau cemas yang tidak rasional dirasakan atau dialami seseorang. Dengan demikian, phobia adalah rasa takut yang berlebihan terhadap suatu benda atau situasi atau seseorang tertentu, tetapi tidak dengan alasan dan sebab yang jelas, tidak sesuai dengan kenyataan. Seseorang yang mengalami phobia akan merasakan ketakutan, kecemasan yang tidak tetap dan tidak rasional terhadap suatu obyek atau situasi tertentu (sumber).
Berdasarkan definisi tersebut dapat digambarkan suasana kekinian di mana terhadap kemunculan fenomena Ahok telah melahirkan pula rasa kecemasan, ketakutan, dan kondisi-kondisi lain di ranah publik dan sosial kemasyarakatan. Fenomena Ahok seperti telah diuraikan di atas sedikit banyak memberi kontribusi terhadap munculnya rasa kecemasan dan ketakutan sosial itu.
Jika kita mau merunut sedikit ke belakang maka akan terkuak betapa resistensi terhadap Ahok, telah mulai muncul ketika dia hadir mendampingi Jokowi dalam perhelatan Pilkada DKI 2012. Ketika itu, sudah mulai muncul kampanye yang membawa isu-isu primordial, seperti suku, etnis, dan kepercayaan (agama). Hanya saja, karena posisi Ahok pada saat itu hanya sebagai DKI-2, sehingga isu-isu primordial itu hanya berhenti pada sasaran antara, yakni Jokowi.
Maka kemudian merebak isu orangtua Jokowi yang nonmuslim yang dikampanyekan raja dangdut Rhoma Irama. Isu tersebut kemudian mentah, sehingga pasangan Jokowi-Ahok melaju ‘menggusur’ petahana, Fauzi Bowo.
Resistensi sebagai bentuk ‘ketakutan’ pun kemudian berkembang dan meluas. Eskalasi ‘ketakutan’ itu semakin menjadi-jadi setelah usai Pilpres, yang memaksa Jokowi harus meninggalkan Balaikota untuk berpindah ke istana. Otomatis tampuk kekuasaan di Balaikota bergeser dan beralih tangan dalam genggaman Ahok. Sontak saja, rasa takut itu kemudian membesar, sehingga mendorong salah satu ormas harus melantik seseorang yang dari tampangnya saja menggelikan menjadi Gubernur tandingan.
Mulai saat itu, kampanye dengan menggunakan isu agama mulai deras mengalir. Sampai puncaknya, Ahok harus dengan terpaksa ‘meladeni’ kampanye yang dilakukan oleh orang-orang dan kelompok-kelompok dari elemen masyarakat yang menggunakan doktrin agama untuk menyerangnya diri. Maka hebohlah jagat perpolitikan dan sosial Indonesia, karena Ahok bersikap ‘nyeleneh‘ menyinggung surah al-Maidah 51, doktrin yang sangat sensitif dari kepercayaan dan keyakinan umat Islam.
Sayang sekali reaksi umat Islam pun tidak cukup elegan, meski ada sebagian elemen umat Islam telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ‘penistaan’ yang dituduhkan ke Ahok melalui jalur hukum. Padahal awal berkembang tuduhan penistaan agama itu, hanya menuntut Ahok meminta maaf. Akan tetapi, setelah hal itu dipenuhi, rupanya kemudian bertambah lagi tuntutan, harus diproses hukum.
Sementara pihak penegak hukum telah memberikan komitmen untuk memproses kasus tersebut, dan bahkan Ahok pun telah dengan gentelman menyatakan mempersilahkan pihak berwajib untuk memproses pengaduan masayarakat itu. Lagi-lagi dalam ‘masa tunggu’, kita menunjukkan lagi sikap yang kurang elegan, tidak bersabar. Ketidaksabaran ini kemudian menimbulkan kesan sebagai bentuk lain dari target sesungguhnya yang hendak dicapai, yakni motif politik. Menggagalkan Ahok sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 yang akan datang.
Istilah Ahokbia
Ada sebuah ‘insiden’ kecil yang terjadi Kamis (20/10/2016), ketika saya bertemu dengan seorang pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Makassar. Karena ‘insiden’ kecil itu, saya kemudian terinspirasi untuk mencoba menggabungkan dua kata menjadi sebuah istilah, yakni ‘Ahokbia’.
‘Insiden’ itu berawal ketika saya bersama istri mengurus Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) berupa paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Ketika mendapat giliran diperiksa berkas permohonan untuk mendapatkan paspor, saya sedikit mendapat hambatan. Sementara istri saya berjalan mulus.
Hambatan itu berupa ‘penolakan’ terhadap berkas saya. Di mana, setelah diperiksa dan diverifikasi, berkas permohonan saya dinyatakan belum memenuhi syarat. ‘Cacat’ syarat itu disebabkan karena tanggal lahir pada identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Akte Kelahiran.
Pokoknya ada perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum pada KTP dan KK, dengan tanggal lahir yang tertera di Akte Kelahiran. Karena perbedaan tanggal lahir tersebut maka pihak Imigrasi menolak untuk memproses lanjut permohonan saya.
Permohonan saya akan kembali diproses apabila saya melakukan perbaikan terhadap perbedaan tanggal lahir pada dokumen-dokumen pendukung tersebut. Sebagai jalan keluarnya, pihak Imigrasi kemudian menyarankan agar saya mendatangi Kantor Dinas Dukcapil untuk meminta perubahan tanggal dengan menyesuaikan tanggal lahir pada Akte Kelahiran mengikuti tanggal yang tertera di KTP maupun KK.
Maka dengan semangat 45, saya pun bergegas menuju Kantor Dinas Dukcapil Makassar. Setiba di Dinas Dukcapil, saya mengikuti prosedur operasional yang berlaku, dan kemudian bertemu petugas yang melayani counter perubahan akte. Kepada petugas tersebut saya menjelaskan tujuan saya. Akan tetapi, karena petugas counter tersebut kurang memahami penjelasan maksud kedatangan saya, maka dia meminta saya untuk menghadap langsung ke pimpinannya.
Di sinilah ‘insiden’ yang mengilhami saya untuk membuat tulisan dengan judul ‘Ahokbia’ ini. Ketika saya menjelaskan maksud kedatangan saya ingin mengurus perbaikan Akte Kelahiran, di luar dugaan saya, pejabat itu tiba-tiba mengatakan bahwa “ini bukan aturan Ahok”.
Saya pun tertegun, antara terkejut dan ingin ketawa. Terkejut karena tanpa babibu, kok, dalam hal yang sedang saya urus, si pejabat malah membawa-bawa nama Ahok? Sementara apa yang sedang saya jelaskan tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan gonjang-ganjing di ibukota negeri, di mana Ahok sebagai kepala Pemerintahannya.
Di samping ‘insiden’ itu, ada ‘insiden’ lain, sehingga membuat saya semakin mempermantap menulis artikel dengan judul ‘Ahokbia’ ini. Kejadian itu, setelah saya mendengar isi khutbah ketika saya sholat Jumat (21/10/2016) di Masjid Balaikota Makassar. Apa pasal?
Pasalnya karena khatib Jumat di Masjid Balaikota Makassar itu, rupanya dalam ‘orasinya’ merasa perlu menyinggung Ahok dan konsep kepemimpinan dalam Islam. Katanya, bahwa dia ingin menyitir ayat al-Qur’an, yang sangat jarang dijadikan materi khutbah atau ceramah, karena takut dicap sebagai oarng yang tidak demokratis. Karena dianggap ayat tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi.
Mendengar itu, sebelum dia menyebut nama Gubernur DKI Jakarta sekarang, feelling saya sudah mengatakan bahwa pasti ini akan merembet ke masalah Ahok. Dan benar saja, Ahok memang telah menjadi fenomena yang menggetarkan sebagian elemen bangsa ini. Maka kata-kata kafir, pemimpin kafir, dan istilah lainnya yang sangat stigmatis meluncur deras dari mulutnya.
Dalam salah satu khutbahnya, si Khatib menegaskan bahwa bagaimana mungkin mengharapkan penduduk negeri menjadi beriman, jika pemimpinnya saja kafir. Pada bagian lain si Khatib menyebutkan bahwa sejujur-jujurnya, seadil-adilnya pemimpin kafir, tetaplah dia seorang kafir. Jadi apa pun predikat ‘mulia nan baik’ yang dilekatkan pada kepemimpinan si kafir itu, tidak akan memberi kredit point atas ‘kebaikan’ yang telah dihadirkan. Kemudian meluncur deras isi khutbah yang sungguh sangat mendiskreditkan seseorang hanya atas alasan berbeda keyakinan.
Saya hanya menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam dalam hati mendengar khutbah Jumat itu. Mungkinkah sebagai rangkaian dari ritual ibadah (dua rukun khutbah Jumat merupakan pengganti dua rakaat sholat dhuhur), diisi dengan ceramah yang bersifat mencaci maki, mengumpat, dan menghujat?
Setelah dua kejadian itu, pertanyaan pun berkelebat dalam pikiran dan juga hati saya. Ini ada (gejala) apa? Ada masalah apa antara si pejabat itu dengan Ahok sehingga harus membawa-bawa nama Ahok dalam urusan saya? Mungkinkah, sedang muncul gejala massif, yakni ketakutan terhadap fenomena Ahok? Adakah getaran ‘perubahan’ yang ditawarkan Ahok di ibukota, akan merambah jauh sehingga membuat pejabat-pejabat dan juga khatib jumat yang ada di daerah merasa kegerahan? Mungkinkah muncul gejala phobia, jangan-jangan fenomena Ahok ini akan melanda daerah sehingga membuat mereka juga menjadi tidak nyaman?
Konsep Pembangunan Ekonomi
‘Ahokbia’ merupakan istilah yang sengaja saya gabung dari kata Ahok dan phobia dengan mengadaptasi istilah-istilah yang sebelumnya dikenal publik. Misalnya sebuah konsep pembangunan ekonomi dengan orang (tokoh) yang mengembangkan konsep itu. Sebut saja, Habibienomic, merujuk pada konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh mantan Presiden RI ke-3, B. J. Habibie. Atau sebelumnya, dikenal pula Hattanomic (1), yang merujuk pada konsep pembangunan ekonomi berdasarkan pemikiran mantan Wakil Presiden RI ke-1, Mohammad Hatta.
Begitu pula ketika Presiden ke-6, Soesila Bambang Yhudoyono (SBY) menjalankan pemerintahan, yang dinilai cenderung memberikan proteksi yang berlebihan, sehingga muncul istilah Hattanomic (2). Hattanomic (2) merujuk pada konsep pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh rezim SBY, di bawah komando Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa pada saat itu.
Hatta-nomics (2), itulah istilah yang disematkan oleh Kevin O Rourke, pengamat ekonomi lulusan Harvard University, terhadap orientasi kebijakan ekonomi saat ini yang dinilai protektif, restriktif dalam perdagangan dan membatasi modal asing (sumber).
Sedangkan Hattanomic (1) versi Wakil Presiden RI ke-1, Mohammad Hatta, pada intinya adalah "memastikan tidak ada paria di Indonesia." Pandangan konsep pembangunan ekonomi Mohammad Hatta ini merupakan pengaruh pandangan Charles Fourier yang sering dikutipnya: nous voulons batir un monde ou tout le monde soit heureux (kami mau membangun dunia yang di dalamnya setiap orang bahagia). Karena itu, basisnya pemerataan ekonomi, keadilan sosial dan kemerdekaan abadi (sumber).
Habibienomics adalah istilah yang diberikan oleh Kwik Kian Gie terhadap konsep pembangunan ekonomi yang diajukan oleh Habibie awal tahun 90-an. Suatu konsep yang sebenarnya berasal dari ekonom-ekonom MIT dimana teknologi menjadi salah penggerak utama dari kemajuan (ekonomi) sebuah bangsa (sumber). Istilah "Habibienomics" pertama kali ditawarkan oleh pengamat ekonomi terkemuka Kwik Kian Gie dalam harian Kompas 3 Maret 1993 dengan tulisannya berJudul "Konsef Pembangunan Ekonomi Prof. Habibie" (sumber).
Implikasi Habibienomics dinilai cukup fleksibel dan mampu mewadahi grand fusionantara pertumbuhan, pemerataan, partisipasi, dan kepentingan nasional (sumber). Namun dalam perkembangannya konsep Habibienomic mengalami kegagalan.
Bagaimana Ahoknomic?
Nah merujuk pada contoh konsep pembangunan ekonomi di atas, mungkinkah cara pembangunan kota yang dikembangkan dan sedang digalakkan Ahok saat ini juga akan melahirkan sebuah konsep pembangunan ekonomi a la Ahok? Katakanlah Ahoknomic? Atau malah hanya berhenti pada rasa takut (Ahok-bia) semata karena model atau pendekatan yang dipilih Ahok dalam menata kota bersifat menggusur tanpa kompromi?
Wallahu a’lam bish-shawabi
Makassar, 22102016
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H