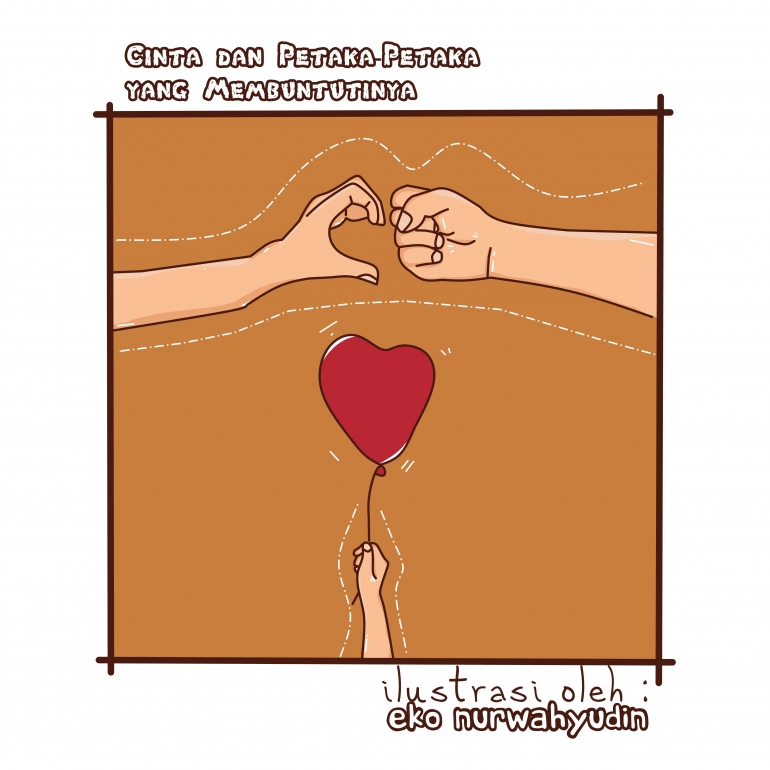Judul : Beauty and Sadness
Penulis : Yasunari Kawabata
Penerjemah : Zulkarnaen Ishak
Penerbit : Immortal Publisher
Cetakan : I, 2017
Tebal : 245 halaman
ISBN : 976-602-1142-89-9
Peresensi : Eko Nurwahyudin
Aliran waktu dan air sungai tidak akan pernah kembali.
Yasuani Kawabata seorang peraih Nobel Sastra 1968, melalui novel Beauty and Sadness mengangkat cinta sebagai anugerah yang pasti tumbuh dan mengakar pada hidup manusia sekaligus petaka yang berguguran dengan cara dan waktu yang tak terduga. Yasunari membagi cerita ke dalam sembilan bab, dimana ia membukanya dengan sebuah renjana yang dialami si tokoh : Oki Toshiro, seorang satrawan yang berusia lima puluh empat tahun terhadap Otoko, selingkuhannya seorang Pelukis Tradisional Jepang berusia tiga puluh sembilan.
Kisah cinta yang terjalin diantara keduanya terjadi dua puluh empat tahun silam saat umur Otoko lima belas tahun. Persoalan mulai rumit saat Otoko hamil tetapi Oki tidak bisa meninggalkan Istrinya Fumiko karena keberadaan anak laki-lakinya. Di usianya yang sangat muda, Otoko melahirkan bayi prematur yang telah ia kandung selama tujuh bulan di sebuah klinik kecil dan kotor di pinggiran kota Tokyo. Namun sang bayi meninggal, dan Otoko belum pernah melihat mayat bayinya sama sekali sehingga membuat Otoko depresi sampai harus direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.
Permasalahan tersebut diulas dengan apik lantaran Penulis memadukan antara sebuah perjalanan tokoh menemui tokoh selingkuhannya, perasaan renjana, dan pengalaman traumatis. Pepaduan kontras yang ditampilkan secara bergantian bahkan diulas dengan penggambaran setting pemandangan yang tenang namun berubah menjadi haru : Oki duduk di atas, kotatsu. Kedua sikutnya ditopang pada meja rendah berlapis kapas yang menghadap ke sebuah anglo bara yang panas. Dia mendengar seekor burung bersiul. Bunyi balok-balok yang dimuat ke atas truk bergaung di seluruh lembah. Dari salah satu tempat jauh di bukit-bukit sebelah barat menyembur bunyi peluit yang menyayat dan melenting-lenting dari kereta api yang masuk atau keluar dari terowongan. Serta merta dia teringat pada tangis seorang bayi yang baru lahir (hlm.15-16).
Tak hanya kritik sosial tentang kehamilan usia muda yang berpotensi kelahiran prematur dan upaya pembunuhan anak hasil hubungan gelap, Yasunari mengangkat irisan dan arsiran sebuah cinta yakni kebencian, upaya balas dendam, ketulusan, serta sikap kasih sayang.
Keiko, seorang Pelukis beraliran abstrak berusia duapuluh empat tahun yang menjadi murid dan pengikut Otoko berniat membalaskan pengalaman pahit yang dialami gurunya kepada Oki lebih lebih kepada keluarganya termasuk kepada Fumiko dan Tichiro (anak Oki). Cara pembalasan dendam yang digambarkan Penulis pun tergolong unik yakni dengan memikat hati Oki dan Taichiro dan membuat cemburu Fumiko.
Lantas bagaimana mungkin pembalasan dendam tersebut berangkat dari sebatas hubungan murid yang tidak terima tentang masa lalu yang kelam sang guru? Tidak. Penulis dengan kepiawaiannya mengangkat tema yang tak lazim yakni hubungan yang lebih besar dan mendalam -- percintaan yang terjadi diantara guru dan pengikutnya -- lesbian.
Pembahasan perihal hubungan sesama jenis antara Otoko dan Keiko mulai penulis bahas ketika Oki mencari alasan guna meredam Fumiko yang cemburu dan curiga terhadap gelagat Keiko. Adapun alasan yang pada mulanya tidak masuk akal tersebut mulai ditampilkan sebagai sifat unik dari cinta yakni terbebas dari penghalang apapun seperti jenis kelamin. Tetapi, bagaimanapun sifat cinta yang demikian niscaya adanya, penulis berpandangan bahwa hubungan demikian timbul atas permasalahan yang kompleks. Seperti pada pernyataan Otoko, "Barangkali benar, tetapi bagaimanapun Otoko itu perempuan. Bukanlah tindakan yang murni sama sekali kalau seorang perempuan mengabdikan seluruh hidupnya bagi perempuan lain" (hlm. 94). Lebih lanjut, pada bab Bunga Teratai Dalam Nyala Api Otoko memilih melakukan hubungan lesbi dikarenakan trauma atas pengalaman cinta bersama seorang laki-laki yang membuatnya melajang dan pada kemudian hari ia memilih menjalin hubungan sesama jenis dengan Keiko. Hubungan itupun tidak didasarkan atas perasaan suka sama suka -- sebatas pelarian. Otoko tetap tidak mampu membenci. Kadar cinta Otoko seperti yang terungkap, "Waktu yang berlalu menyebabkan kenangan Otoko atas pelukan itu berangsur-angsur menjadi murni. Kenangan itu berubah dari sesuatu yang bersifat lahiriah menjadi sesuatu yang bersifat batiniah....Apabila Otoko mengingat apa yang sudah diajarkan Oki, lalu menirunya saat dia mencumbui Keiko, dia khawatir pengelihatan yang suci itu akan menjadi kotor, bahkan musnah" (hlm. 145). Hanya saja, untuk alasan Keiko memilih menjadi seorang lesbi tidak dijelaskan oleh Penulis.
Adapun, kelemahan lain dalam novel ini yakni adanya penceritaan yang terkesan patah (hlm. 33) yang pada mulanya membahas Oki yang tengah menyantap masakan buatan Otoko kemudian pembahasan meloncat tanpa perantara ilustrasi ke pembahasan kenangan traumatis Otoko. Kelemahan yang lain seperti, beberapa kata yang dicetak miring tetapi disayangkan tidak diberikan penjelasan melalui catatan kaki maupun di halaman tersendiri dan tidak dicantumkannya penjelasan profil Penerjemah buku meskipun singkat. Sebab membaca karya terjemahan tidak bisa mengesampingkan perihal penerjemah dan kualitas terjemahannya. Akhirnya, buku ini menjadi bacaan yang direkomendasikan bagi siapapun untuk mengeksplorasi cinta tiga generasi ke permasalahan serta petaka yang kerap tidak terduga dan meledak sewaktu-waktu.
Catatan: Resensi ini penulis ini pernah dimuat oleh Omah Oksoro. Namun dikarenakan beberapa jejak digital penulis hilang akibat permasalahan pada situs website Omah Aksoro, maka penulis terbitkan ulang di situs kompasiana penulis sendiri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H