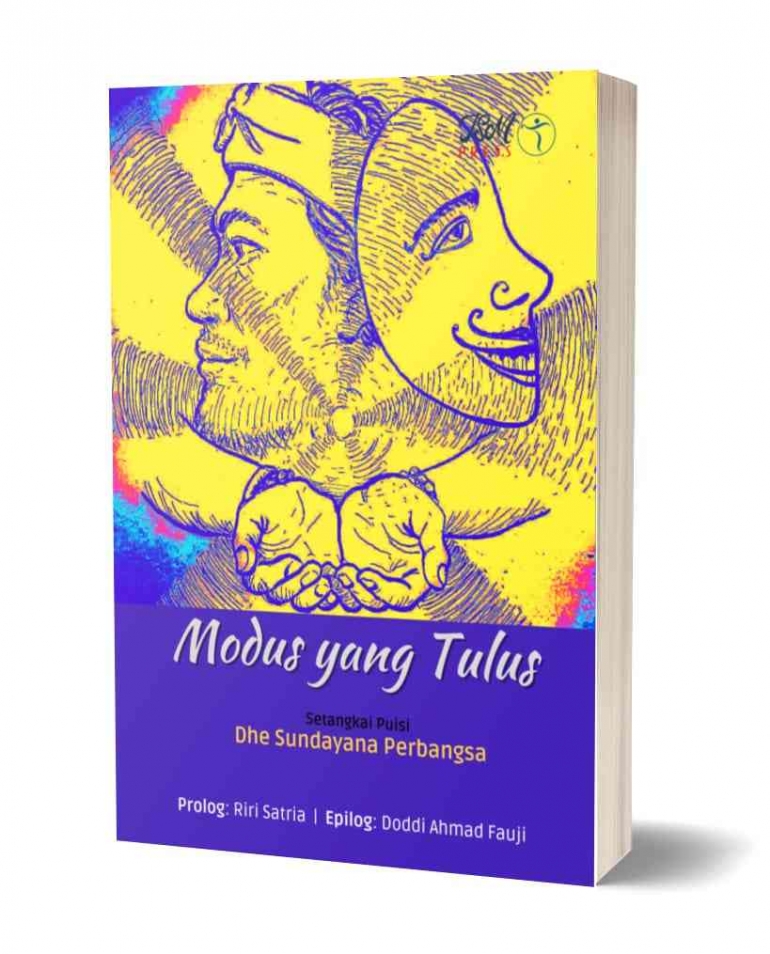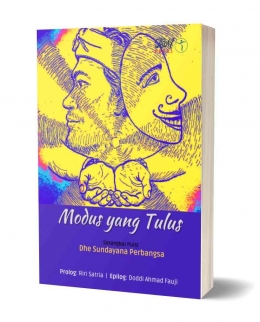Sebagai seorang urban
Aku kehilangan peta
Mengeja makna kepulangan
Dari puing-puing halaman yang tersisa
De Sundayana menulis larik-larik di atas, pada barik terakhir dalam puisinya yang berjuluk Kehilangan Peta. Barik di atas adalah traktat politik individual, yang menguar dari rasa murung seseorang saat berinteraksi dalam sosial-kultur bangsa Indonesia terkini, terutama yang berlasung dan terselenggara di kawasan-kawasan borderline (perbatasan).
Ada banyak manusia merasa teralienasi dan tercerabut dari sesuatu yang dianggapnya sebagai akar, untuk menjalar ke depan, menjadi cabang dan ranting, bertumbuh menjadi pohon yang rindang, gemah ripah loh jinawi. Namun jalan di depan kini, tampak terjal, luak-liuk dan berkelok, seperti memasuki kota mesteri yang dihuni banyak hantu, dan kertika berdialog dengan diri sendiri, terasa ini jiwa dan raga, seperti pohon yang makin sebatang kara. Kondisi seperti itu, paling mudah dibahasakan dengan larik-larik lirisistik.
Sejatinya puisi liris di Indonesia, memang didominasi oleh diksi kemurungan, muram, kadang menggerutu sambil memunggungi yang digerutui. Ada sejumlah puisi liris yang menghujat, dengan gayabahasa ironis, satiristik, dan sarkastik, seperti yang ditulis Wiji Thukul. Namun entah kenapa, puisi seperti itu termasuk langka muncul ke permukaan dan menjadi pembicaraan.
Dalam konvensi penulisan puisi, ada istilah puisi liris, puisi naratif, dan puisi dramatik. Konvensi tersebut telah lama diakui dan digunakan oleh para pengamat atau peneliti sastra, termasuk saya ikut meyakininya (Fauji, Menghidupkan Ruh Puisi, 2018).
Apapun bentuk atau jenisnya, saya meyakini, karya literasi akan menjadi larik-larik dokumentasi peristiwa pada suatu kurun. Para sejarawan, sosilog, dan antopolog yang mencoba memasuki kehidupan di jaman buhun misalnya, salah satunya melakukan konfirmasi dan tafsiran terhadap karya sastra yang pernah ditulis pada jaman itu. Pada tahun 3.000, para antropolog yang merumuskan kehidupan di tahun 2.000-an, saya yakin, akan melakukan konfirmasi hasil penelitiannya, pada traktat yang ditulis para penyiar.
Sebuah pertanyaan pernah dilayangkan seorang profesor dari Rusia kepada saya, dalam seminar membaca budaya Indonesia terkini, di Moscow Government University sekira April 2004, adalah tentang puisi-puisi Indonesia yang disesaki diksi-diksi murung dan muram, bahkan ketika menyatakan cinta, kenapa seperti itu?
Saya jawab waktu itu, puisi memang saksi jaman, dan bangsa kami yang lama dijajah, kini pun masih dijajah oleh para borjuase dan oligarkhi, yang mencekik dengan sistem perekonomian kapitalisme-liberalistik. Mayoritas penyair bukan dari kalangan menengah menuju 'the have,' malah cukup banyak penyair yang menjalani kehidupan bohemian, dan sebagai manusia, ia ikut merasakan dan menyaksikan sendiri ketimpangan antara segelintis 'the have' yang menjajah kalangan bawah lewat struktur dan regulasi. Pengalaman dan kesaksiannya itu, didokumentasikan melalui diksi-diksi murung dan muram. Penggalan barik gubahan Dhe Sundayana di atas, adalah pembuktiannya.
Puisi pertama dalam antologinya, diberi judul 'PEKERJA HARIAN', berisi seperti di bawah.
Pukul enam
langit putih tapioka
ada awan di sepasang mata
ada gigih di satu jiwa
dan wajahmu musim penghujan
sepagi ini, aku mesti sadar
sesegera merambah belukar
tidak ada yang aku tunggu selain pajar
karena rumah adalah akar
awal tumbuhnya pertanggungjawaban
dan tempat segala lelah direbahkan.
Bekasi, 2020
***
JUGA bila merujuk pada puisi-puisi yang digubah penyair generasi kelahiran 1940-1960-an, diksi kemurungan itu dapat ditemukan pada banyak puisi, bahkan ketika hendak menyatakan cinta. Mari kita tengok beberapa contoh di bawah.
Puisi 'Aku Ingin' besutan Sapardi Djoko Damono: ...dengan kata yang tak sempat diucapkan, 'kayu' kepada 'api' yang menjadikannya 'abu'. Ada kayu dan api, dan sebenarnya terjadi proses pembakaran, hingga terciptalah abu.
Puisi 'Pernyataan Cinta' gubahan Acep Zamzam Noor: Aku mencintaimu dengan lambung yang perih, pikiran yang dikacaukan harga sembako, pemogokan, serta kerusuhan yang meletus di mana-mana.
Juga dalam puisi 'Menggoda Tujuh Kupu-kupu' gubahan Afrizal Malna: Aku tidak berjalan dengan mata melek. Kau pergi dengan mata/ tidur. Orang di sini membawa beban berat. Bukan soal melihat./ Dalam beban itu isinya sampah. Bukan pergi dan tidak tidur. Kita/ sibuk mencari tempat membuang sampah itu untuk mengisinya/ kembali dengan sampah.
Akan terus berlahiran lirisme seperti itu, terutama dari penyair Indonesia, yang menghadapi kondisi kamuflatif di banyak bidang, dan di banyak strata sosial. Akar masalah terdapat pada para penafsir dan pelaksana Falsafah Pancasila yang sebatas mengagung-agungkan Pancasila sebagai jargon, namun ternyata memanfaatkannya untuk menindas. Juga pada tafsir ajaran agama yang tampak agung namun berbau mitos yang mengawang, alias tidak membumi, terus didendangkan syariatnya, namun dipunggungi hakikatnya. Nyaris tipis pembuktian dalam perbuatan dari frase 'rahmatan lilalamin' (berkah bagi semesta), atau diktum sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang nyata, keadilan bagi segelintir orang yang mau dan bisa merapat ke dalam lingkaran excellent, yang menyemburkan waham hiprokrit di berbagai lini, melahirkan ketimpangan. Penyair menyuarakan kemurungan itu, dalam lirik-lirik yang menggerutu atau menghujat, terkadang melalui diksi cinta yang kusut dan berbelit-belit.
Maka bagi saya, membaca suasana kekinian Indonesia, adalah tantangan untuk memasuki puisi yang berangkat dari 'pengalaman tubuh' (meminjam istilah Afrizal). Penyair harus menjadi aktivis dalam kehidupan. Ia tidak cukup hanya menjadi pengamat kehidupan lalu membahasakannya dalam puisi atau prosa absurd, atau dalam esay yang semerbak. Penyair terutama, kepada prosais saya agak fesimistik, pembahasaan kondisi harus lahir dari aktivitasnya, bukan dari sekedar pengamatan ala peneliti akademis.
Indonesia membutuhkan para begawan (budayawan) yang bukan hanya klaim dari dirinya, tapi perangai dan sikapnya mencerminkan kebegawanan. Indonesia membutuhkan Wiji Thukul, Radhar Pancadahana, Rendra, Afrizal Malna, yang memuisikan perbuatannya, tentu dengan warna dan diksi yang menjadi miliknya. Di Indonesia, saat ini dan ke depan, selama Pancasila masih menjadi kitab basa-basi, membutuhkan penyair yang meneror pikiran semua kalangan. Harapan ini memang seperti utopia, tapi lebih baik daripada bersikap apatistik.
Pada sekira 25% puisi dalam antologi ini, Dhe Sundayana mengarah pada gambaran penulisan puisi-puisi yang saya bayangkan, yang dinukil dari pengalaman perjalanannya, atau penyair sering mendramatisir dengan menyebutnya sebagai hasil ziarah. Tulisan ini menjadi epilog, tapi bisa menjadi prolog ke depan, sebelum puisi dituliskan.
Doddi Ahmad Fauji
Esayis dan editor
Esai lain dari Doddi Ahmad Fauji, bisa dilihat DI SINI
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H