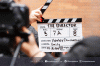Pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke 74 saya mendapat ajakan dari Kakak saya untuk menonton sebuh film yang berjudul Bumi Manusia. Dari judulnya saya sempat menerka-nerka, apakah ini Bumi Manusia yang diangkat dari novel karya Pramoedia Ananta Toer dengan judul yang sama, atau memang hanya ada kesamaan judul saja? Kakak saya pun menjawab "Iya ini dari Novel karya Pram".
Sebelum mulai bercerita tentang film tersebut saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa saya bukanlah seorang penggemar sastra namun tidak juga asing dengan karya-karya sastra, karena kebetulan saya suka baca beberapa buku dan juga mengenal beberapa judul buku dan pengarang terkenal.
Saya bukanlah penggemar sastra garis keras yang mampu melahap berbagai macam karya sastra yang membahas permasalahan dan problematika kompleks terkait gesekan ideologi yang berusaha disampaikan para sastrawan. Saya hanyalah pemuda yang pernah mencari ilmu di fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas Indonesia, atau yang dulunya disebut dengan Fakultas Sastra dari jurusan Arkeologi, sebuah ilmu yang menurut saya paling banyak mengandalkan hard science dibanding jurusan-jurusan lain di fakultas itu.
Selama saya kuliah, sering kali teman-teman saya dari berbagai jurusan seperti sastra Indonesia, filsafat dan jurusan-jurusan lain penggemar bacaan-bacaan "berat" menenteng buku karya Pram yang berjudul "Bumi Manusia", mungkin bagi mereka itu bukanlah bacaan berat, hanya sekedar hiburan di waktu luang untuk mengisi ruang-ruang di kepala mereka yang secara konstan harus terus mereka isi. Namun yang jelas sejak saat itu saya terpapar dengan keindahan dunia sastra yang tidak pernah saya singgahi sebelumnya. Sebuah dunia abstrak dari ranah ide yang berusaha dihadirkan dalam dunia fisik melalui tulisan.
Cukup dengan sedikit perkenalan saya, kembali mengenai film Bumi Manusia, film ini ternyata disutradarai oleh Hanung Bramantyo, salah satu sutradara Indonesia yang saya tahu pernah membuat film yang berjudul "tanda tanya" sebuah film yang menggambarkan kompleksitas hubungan dari keberagaman di Indonesia khususnya hubungan antar umat beragama yang berbeda keyakinan.
Walau banyak kritik yang menyerang terhadap film "Tanda Tanya" tersebut, menurut saya karya Hanung ini patut diapresiasi sebagai sebuah langkah maju dalam perkembangan karya perfilman di masanya. Film "tanda tanya" membuat saya mulai melabeli Hanung sebagai salah satu sutradara Indonesia yang menghasilkan karya yang bagus. Karena itu saya tidak terlalu ragu untuk menerima tawaran kakak saya menonton film hasil adaptasi dari novel karya Pram dengan judul yang sama "Bumi Manusia".
Tidak ada ekspektasi yang berlebihan terhadap film ini, mengetahui pemeran tokoh utama "Minke" diperankan oleh Iqbaal Ramadhan seorang aktor muda yang mendapat kepopulerannya dari film "Dilan". Ekspektasi saya juga tidak saya patok terlalu tinggi ketika saya menyadari bahwa biaya produksi film di Indonesia tentu tidak bisa dibandingkan dengan biaya produksi film-film Hollywood yang mampu memberi modal yang besar dalam menghadirkan latar cerita yang apik.
Satu-satunya tujuan saya menonton film ini adalah menyegarkan ingatan saya tentang cerita dari novel Bumi Manusia dan interaksi antar tokohnya, karena sejujurnya saya belum pernah menyelesaikan membaca novel itu sampai selesai, hanya beberapa bab di awal yang tiba-tiba lompat ke beberapa bab di tengah-tengah lalu dengan tidak sabaran membaca sipnosis dan resensi buku yang tersedia dan mengklaimn diri saya dengan predikat seorang yang "pernah" membaca karya sastra dari Pram.
Durasi film yang mencapai 3 jam ini pun membuat saya memperhatikan layar bioskop dengan lekat-lekat sambil mengeryitkan dahi dan selebihnya asyik menggeliat di kursi karena sibuk membenarkan posisi kaki, apakah kaki saya seharusnya berselonjor ke depan, duduk dengan rapi, ataukah harus menyilangkan satu kaki diatas kaki lainnya. Alur cerita yang disuguhkan seakan tidak raya, mengingat durasi film yang begitu panjang seharusnya dipertimbangkan untuk mononjolkan kedetilan cerita di dalam novel yang biasanya tereduksi ketika cerita dalam novel dialihwahanakan menjadi sebuah film. Saya kecewa dengan film tersebut.
Film tersebut tidak berhasil mengguggah sisi emosional saya sebagai penonton untuk terlarut dalam cerita maupun memukau mata saya dengan detil dan ketelitian dari setting cerita yang disuguhkan. Aspek-aspek cerita yang ingin disampaikan Pram melalui novelnya seakan hilang dan dilebur menjadi suatu tontonan ber-genre romantisme picisan.
Tak heran ketika Iqbaal Ramadhan yang sebelumnya menjadi "DILAN", seorang tokoh yang jago dalam urusan kata-kata gombal, dijadikan tokoh utama Minke yang kini terlihat sebagai ahli dalam hal percintaan. Kebiasaan saya yang menyukai hal-hal detil terutama terkait dengan sisi historis dari sebuah film pun tergelitik untuk terus mengkritisi properti dan setting film yang dipakai, apakah properti dan setting sudah disesuaikan dengan riset konteks jamannya atau dibuat sekadarnya.
Keakuratan Konteks Sejarah dalam Latar Film Bumi Manusia
Perhatian saya yang pertama tertuju pada rumah kediaman Herman Mellema. Sebuah rumah yang digambarkan merupakan kediaman yang berada di pinggiran kota yang di kelilingi oleh perkebunan pribadi miliknya. Dalam penggambaran di film tersebut, rumah Herman Mellema merupakan rumah kayu berarsitektur seperti layaknya rumah kebaya, rumah tradisional khas betawi, dan memiliki tingkat.
Saya tentu tidak tahu secara pasti apakah memang lazim sebuah warga Belanda di tanah East indies memiliki rumah yang berbentuk seperti itu karena tentunya kita harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk membuktikannya, namun saya lebih sering melihat sebuah rumah bergaya arsitektur indies maupun campuran antara Indies dengan rumah tradisional joglo tanpa tingkat yang dibangun dengan material utama batu kali yang diplester pada kajian-kajian arkeologis rumah perkebunan di jaman kolonial.
Bangsa eropa merupakan bangsa yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka dalam bidang teknik pembangunan, masonry dan arsitektur. Pada era kolonial mereka akhirnya membawa serta pengetahuan itu ke negara-negara koloninya untuk mereka terapkan pada setiap proyek pembangunan di negara koloni, tak terkecuali pemukiman atau rumah tinggal.
Pada awalnya, orang-orang Belanda menerapkan rancangan arsitektur yang serupa dengan bentuk rumah tradisional di negara asalnya. Mereka membangun rumah dengan penampang memanjang, tertutup, atap tinggi dan penampang jendela dan pintu yang terbatas, hal ini mungkin terkait dengan keberadaan musim-musim yang ada di negara asalnya, yang membuat mereka harus bertahan dalam keadaan yang ekstrim.
Arsitektur rumah tradisional belanda dengan atap yang tinggi memungkinkan orang belanda untuk bertahan hidup di musim salju karena atap yang tinggi akan mengurangi tekanan diatas bangunan dari salju yang menumpuk di atap, namun hal tersebut ternyata tidak dibutuhkan di wilayah tropis seperti Hindia timur.
Hindia timur yang berada dalam wilayah tropis, memungkinkan para perancang bangunan belanda menggabungkan dua jenis gaya arsitektur dalam satu bangunan, yaitu arsitektur eropa (art-deco, rationalism, collonial) dengan arsitektur vernakuler tradisional di Indonesia, dari sinilah lahir arsitektur bergaya Indies.
Arsitektur Indies pada bangunan pemukiman umumnya memiliki penampang yang melebar dengan atap yang landai dan memanjang yang bersambung membentuk penutup serambi atau beranda di samping bangunan, bangunan indies memiliki atap yang menyerupai rumah joglo namun lebih rendah. Jadi sungguh sangat membingungkan bagi saya ketika rumah kediaman Herman Mellema tidak seperti gambaran rumah di masanya pada saat itu.
Selain kediaman keluarga Mellema itu sendiri kita juga bisa memperhatikan apa yang dikerjakan Nyai Ontosoroh untuk menghidupi keluarganya, yaitu usaha perkebunan milik Herman Mellema yang ia jalankan sendiri. Sepintas tidak ada yang salah dengan kegiatan perkebunan yang terjadi dalam film tersebut, namun jika kita mempertanyakan tentang seberapa akurat kegiatan tersebut dengan konteks jamannya pada saat itu, saya pun kembali ragu.
Dalam beberapa scene di film tersebut Annelies Mellema yang diperankan Mawar Eva de Jongh berusaha untuk membantu para pekerja perkebunan untuk mengumpulkan hasil panen, ia memetik sejenis tanaman yang saya rasa mirip dengan pare dan juga menghitung hasil panen cabai. Saya memang belum membaca lengkap dan terperinci novel karya Pramoedya Ananta Toer ini dan secara pasti tahu apakah memang Pram menggambarkan Nyai Ontosoroh menanam sayuran seperti pare dan cabai dan berusaha memperdagangkannya, karena jika jawabannya adalah iya, rasanya sungguh aneh dan bertentangan dengan logika ekonomi pada masa tersebut.
Kehadiran Belanda di Nusantara, seperti yang kita ketahui, dilandasi oleh keinginan untuk memonopoli pasar perdagangan rempah. Dorongan ini ini dipicu oleh kejadian yang terjadi dimasa sebelumnya ketika beberapa bangsa yang ada di timur tengah memutus jalur perdagangan antara Asia jauh dengan eropa.
Mendapat efek dari kejadian di masa sebelumnya, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba mengembangkan teknologi navigasi laut dan perkapalan mereka untuk mereka gunakan dalam penjelajahan samudra di dunia, masa ini dikenal dengan sebutan The age of Discovery. Singkatnya bangsa eropa pun menemukan sumber dari penghasil rempah-rempah yang mereka hargai dengan nilai tinggi yaitu wilayah-wilayah di Asia dan wilayah-wilayah di benua baru Amerika.
Melalui VOC dan kemudian kerajaan Belanda itu sendiri, orang-orang Belanda berusaha menguasai wilayah nusantara untuk mereka manfaatkan hasil alamnya. Mereka mencari tanaman rempah ke wilayah Maluku, sumatra, dan jawa; menggali hasil tambang di Papua dan Kalimantan; dan juga membuat perkebunan yang menghasilkan komoditas dagang bagi mereka, seperti perkebunan tebu, teh, tembakau, karet. Sayangnya saya jarang mendengar bahwa orang-orang eropa ini memerlukan sayur-sayuran sebagai komoditas dagang mereka, walaupun tentu masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wonokromo sebuah wilayah yang digambarkan sebagai tempat keluarga Mellema bermukim selama di East-Indies, merupakan wilayah dataran rendah yang dekat dengan wilayah pantai dan laut. Fakta ini akan menyadarkan kita bahwa mungkin iklim Wonokromo bukanlah iklim yang ideal untuk menanam sayur-sayuran, sedangkan di sisi lain tanaman tebu yang kebetulan merupakan komoditas dagang pada saat itu mungkin saja lebih cocok untuk ditanam di sana.
Keberadaan perkebunan tebu di wilayah Jawa Timur pada masa kolonial pun juga dapat ditelusuri jejak arkologisnya. Jejak ini mengungkap kepada kita bahwa mungkin perkebunan Tebu di wilayah Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dari pihak Belanda pada masa itu karena terdapat beberapa gudang dan rel untuk lori-lori pengangkut hasil perkebunan tebu yang ada di wilayah Jawa Timur.
Jadi dengan konteks sejarah seperti itu akan sangat sulit bagi saya membayangkan seorang Herman Mellema yang merupakan hartawan Belanda, bangsa yang membutuhkan dan menilai tinggi komoditas perkebunan, menggunakan lahan perkebunannya di Wonokromo untuk menanam sayuran untuk diperdagangkan.
Baiklah saya tidak akan melanjutkan celotehan saya mengenai latar dari film Bumi Manusia terhadap konteks sejarah yang sebenarnya, karena besar kemungkinan saya yang justru salah menjabarkan fakta-fakta yang terkait.
Namun inilah harapan saya ketika sebuah karya novel disajikan kembali dalam bentuk film, film yang kuat dalam elemen visual seharusnya dapat menggali dan merekonstruksi ulang peristiwa yang diceritakan di dalam novel dan memberikan patokan dan arah yang lebih akurat dibandingkan dengan imajinasi-imajinasi individual di masa mendatang yang sudah terlepas dari konteks sejarah saat cerita itu dituturkan.
Film dengan tema kesejarahan seharusnya membawa keunggulannya dalam bidang penggambaran yang nyata.
Gagalnya interpretasi karya sastra Bumi Manusia
Keesokan harinya setelah saya menonton film Bumi Manusia, saya menemukan video yang diunggah oleh kanal 'Asumsi' dari platform berbagi video, Youtube. Video tersebut menayangkan berbagai wawancara ke beberapa tokoh masyarakat mengenai novel Bumi Manusia karya Pram dan juga komentar tentang berbagai versi adaptasinya dalam bentuk teater maupun yang baru kita saksikan sekarang ini adalah: film.
Masing-masing tokoh seperti Budiman Sudjatmiko, Faiza Mardzoeki, Felix Nesi, dan Goenawan Mohamad menceritakan pengalaman mereka mengenai cerita dalam Novel Bumi Manusia itu, bagaimana mereka berkenalan dengan karya-karya dari Pram, bagaimana mereka menginterpretasikan karya tersebut,dan bagaimana karya tersebut menginspirasi mereka atau bagaimana penilaian mereka terhadap karya pram tersebut.
Wawancara dalam video itu sangat menarik terutama ketika saya menemukan satu bagian dalam video itu di mana Felix Nesi menyatakan dengan tegas bahwa adalah suatu kejahatan untuk mengangkat karya sastra ke dalam sebuah film, lalu diikuti dengan pernyataan bernada pesimis dari Goenawan Mohamad yang mengatakan bahwa adaptasi karya sastra menjadi film atau bentuk lain biasanya jelek.
Ya reaksi dari beberapa orang yang saya kenal sangat menggemari sastra pun serupa, mereka sangat benci ketika mengetahui bahwa Bumi Manusia akan diadaptasi menjadi film, apalagi ditambah dengan pemeran utama 'Minke' yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, seorang aktor yang memiliki persona yang kurang cocok dengan tokoh yang dimainkan. Tapi memang setelah saya menonton film tersebut ujaran-ujaran sinis mereka memang terbukti, adaptasi film-nya sungguh kepayahan dalam menggambarkan situasi yang diceritakan di dalam novel.
Persoalan utama yang ingin disampaikan dalam novel tentang kesewenangan kolonial beserta hambatan dari sistem feodal jawa sangat jauh dari kata baik, kalau tidak ingin dikatakan sangat buruk. Interaksi karakter dan juga interaksi kelompok golongan yang seharusnya bisa memberikan gambaran nyata tentang situasi sosial,politik dan hukum pada masa itu seakan luput menjadi fokus utama dalam film, tergantikan dengan adegan-adegan romantisme yang menurut saya kurang jelas peruntukannya.
Film Bumi Manusia tidak berhasil menangkap dan menggambarkan bagaimana dinamika masyarakat di Hindia Timur yang terdiri dari berbagai golongan dengan akar budaya, pandangan ideologi, dan hukum yang berbeda saling bergesek, bertubruk, bersinergi dan berhubungan.
Ambil saja kalangan Indo dalam cerita itu, menurut saya pribadi, kalangan Indo merupakan kalangan yang cukup dilematis kehadirannya dalam masyarakat di masa itu. Kalangan indo tidak pernah dianggap seutuhnya sebagai orang Belanda karena mereka memiliki darah pribumi dan mereka pun banyak dibenci oleh kalangan pribumi karena memiliki darah penjajah dalam dirinya.
Dengan glorifikasi terhadap bangsa eropa yang menempati strata sosial teratas dalam masyarakat, kalangan indo mendambakan dirinya juga berada pada strata yang sama dengan orang-orang eropa asli, namun sayangnya sekeras apapun mereka menjadikan diri mereka "Belanda" tak kunjung mereka mendapat tempat dalam strata sosial bangsa-bangsa eropa, mereka pun mendapatkan diskriminasi.
Diskriminasi terhadap mereka pun tak hanya dari kalangan orang-orang eropa saja, mereka juga mendapatkan diskriminasi dari kalangan pribumi, mereka dicurigai sebagai kaki tangan para penjajah.
Itulah mengapa tokoh-tokoh seperti Robert Mellema, Robert Suurhoff, dan Jan Dapperste seharusnya menjadi kunci dalam film tersebut untuk menjungkirbalikkan persepsi diantara dua pihak dominan yang saling bersebrangan yaitu para pengkoloni eropa dengan kalangan feodal jawa. Namun kekuatan ini nampaknya tidak dimanfaatkan pembuat film untuk memaksimalkan pesan yang hendak digambarkan pram melalui novelnya.
Kehadiran Babah Ah Tjong dan Meiko yang mewakili kalangan yang dikelompokkan sebagai timur asing pun dihadirkan tanpa nilai berarti di dalam film. Diskusi-diskusi Minke dengan dua bersaudara de la Croix tidak dimanfaatkan pembuat film untuk mendorong para penontonya tersadar dari amnesia sejarah akan isu-isu sosial-politik yang pernah terjadi di Hindia Belanda kala itu, isu-isu yang nantinya akan membawa pemikiran pemuda-pemudi untuk mencetuskan kemerdekaan bagi bangsanya sendiri.
Dari semua kekurangan yang telah saya sampaikan membawa kita pada pertanyaan apakah hal ini serta merta membuat kehadiran film merupakan penghinaan terhadap karya sastra?
Menilai arti kehadiran Film Bumi Manusia
Felix Nesi, seperti dalam wawancara yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin bisa mengatakan pengadaptasian novel Bumi Manusia menjadi film adalah sebuah kejahatan, sedangkan ujaran pesimistis dari Goenawan Mohamad yang mengatakan film hasil adaptasi novel biasanya jelek, mungkin juga terbukti, namun hal tersebut tidak bisa membuat kita terburu-buru menarik kesimpulan bahwa kehadiran film tersebut memang buruk adanya.
Kehadiran film Bumi Manusia menurut saya memberikan harapan baik dalam dunia perfilman maupun dalam perkembangan sastra di jaman sekarang. Dalam film itu saya pun dibuat kagum dengan pembawaan karakter Nyai Ontosoroh oleh Sha Ine Febriyanti, karakter ibu Minke oleh Ayu Laksmi, dan bahkan Minke sendiri yang dibawakan oleh Iqbaal Ramadhan, meskipun mungkin sebagai Minke yang berbeda dari penggambaran dalam novel.
Saya juga kagum dengan dialog-dialog dalam film yang mempertimbangkan keragaman bahasa dari spektrum yang berbeda seperti Bahasa Belanda, Prancis, Inggris, Jawa, dan Melayu yang secara sengaja dihadirkan dalam film untuk menunjang konteks sejarahnya.
Belum lagi mengenai motivasi yang tinggi sang sutradara, Hanung Bramantyo untuk mengupayakan segala elemen dalam film mewakili konteks jamannya dengan membuat rel kereta, rumah, dan latar perkotaan sendiri dengan anggaran produksi yang saya rasa cukup minim dibandingkan dengan Holywood.
Kehadiran film ini nyatanya memberikan efek samping yang akan menjadi solusi dari kekhawatiran kalangan pemerhati sastra. Kekhawatiran akan matinya kritik sastra dan juga keberlanjutan dari dunia sastra itu sendiri di kalangan anak muda. Seperti yang disampaikan Goenawan Mohamad yang juga mengutarakan pernyataan bernada serupa dimana perkembangan sastra di Indonesia tidak lagi ada.
Sastra tidak lagi didiskusikan oleh para pelajar secara luas, hanya sebagian kecil kelompok saja yang masih melakukannya selain itu hampir tidak ada orang di jaman sekarang yang menggubah karya sastra yang baru. Mungkin dunia sastra sudah mendekati hari kiamatnya, namun nyatanya tidak.
Contoh yang nyata adalah apa yang terjadi pada diri saya, segera ketika mendengar film Bumi Manusia di rilis saya pun mulai menaruh minat lagi dalam membaca berbagai karya sastra. Dan sepertinya saya pun tidak sendiri karena buku-buku pram, khususnya yang berjudul Bumi Manusia yaitu buku yang sama yang selalu bertengger di rak-rak toko buku jarang tersentuh ketika saya kuliah, kini telah habis dibeli oleh orang, bahkan hingga pihak penerbit memutuskan untuk mencetak ulang.
Pada akhirnya kehadiran film Bumi Manusia yang mengangkat sebuah karya sastra dari Pramoedya Ananta Toer mendorong banyak orang untuk kembali menikmati sastra, dan bukan hanya itu saja mereka tertarik mencari sumber utamanya untuk mendapatkan cerita yang lebih utuh, bukankah ini awal yang baik untuk memulai kembali tradisi kritik sastra?
Perkembangan jaman yang semakin modern membawa kita pada tantangan yang berbeda. Jika pada jaman dahulu pemikiran-pemikiran revolusioner termanifestasi melalui tulisan, di jaman sekarang kita memiliki medium yang lebih beragam untuk merekam ide dan menyampaikan pandangan, film adalah salah satunya.
Film Bumi Manusia mungkin sangat jauh dari predikat mahakarya, namun dengan film ini Indonesia telah memulai langkahnya dalam evolusi dunia perfilman yang lebih maju. Jadi mengapa kita tidak memanfaatkannya se-kreatif mungkin? alih-alih mengutuk perubahan yang merupakan keniscayaan?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI