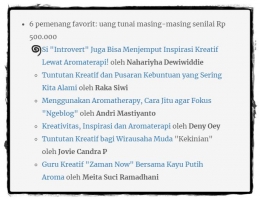Ngapain sih, bertahan nulis di Kompasiana?
Dijamu Presiden nggak diundang, membuat buku keroyokan tidak diajak, apa sih yang kamu dapatkan di sini?
Menjadi satu dari ratusan ribu murid-murid di sekolah Kompasiana alias Kompasianer sungguh merupakan kebanggaan. Bagaimana tidak, "sekolah virtual" ini masih yang terfavorit di negeri ini, (pernah) dapat penghargaan pula. Dan, walaupun kepala sekolahnya ganti lagi (sekarang Nurulloh), ada saja kedatangan murid-murid baru yang ingin belajar menulis di sini.
Tapi, apakah saya tetap bertahan jadi murid di Kompasiana dengan segala dinamikanya? Tidak, malah pernah bolos sekolah selama 8 bulan pas musim pemilu (jangan ditiru ya!). Akibatnya, pas kembali lagi ke sini, murid-murid yang lebih junior meraih kemajuan bahkan sampai dinominasikan sebagai calon murid teladan. Sedangkan saya? Terasa tinggal kelas deh.
Walaupun demikian, di tengah prestasiku yang biasa saja, tetap saja saya dapat apresiasi. Bukti bahwa saya bukan murid idiot yang tak bisa apa-apa. Setidaknya, potensiku bisa berkembang dan melaju berkat diriku bersekolah di Kompasiana ini.
Yang kemudian, datanglah surel yang tak terduga.
Terkejut?
Ya pastilah. Saya sebenarnya nggak muluk-muluk nunggu pesan yang masuk ke kotak masuk e-mailku. Tapi menyematkan alamat surelku di profil, siapa tahu ada kejutan yang mau berkomunikasi denganku lebih lanjut.
Dan itu terbukti. Awal 2018 lalu diriku mendapatkan e-mail tak terduga dari salah seorang Kompasianer yang kini namanya berjejer di antara calon-calon fiksianer teladan. Dia mengapresiasi tulisanku yang tentang anak blasteran itu sembari menjelaskan, bahwa sewaktu membaca artikelku, dia merasakan apa yang kutuliskan di artikel tersebut.
Wah-wah, emang gak salah. Diriku menuliskannya murni dari sanubari. Sampai-sampai, saya buatkan artikel balasan untuk dia, ya murni berbagi pengalamanku bahwa jadi anak berdarah campuran memang membuat kami benar-benar mengerti akan perbedaan dan keberagaman.