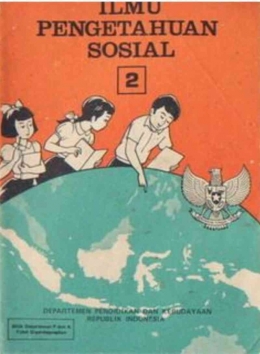Namun, imajinasi dan impian kami tidak bisa dibatasi oleh tradisi tersebut, karena kami memang lebih menggemari film kartun, lagu-lagu pop, dan film cerita akhir pekan.
Berusaha Menjadi Modern Tanpa Perlu Sepenuhnya Modern
Masa kecil saya, orang tua, kawan- kawan, dan warga lainnya di era 80- an dengan beragam peristiwa sosio- kultural yang terjadi merupakan penanda perjumpaan lokalitas dan modernitas sebagai akibat kuatnya pengaruh ekonomi-politik pembangunanisme Orba.
Ekonomi-politik saya pahami dalam konsep Marxian (Marx, 1991, 1992; Lebowitz, 2002; Wood, 2003), yakni relasi antara struktur dasar (base structure) dan struktur supra (superstructure). Tesis utama yang diusung adalah bahwa basis ekonomi (struktur dasar) akan menentukan struktur supra yang di dalamnya termasuk persoalan ideologi, agama, relasi sosial, politik, maupun budaya.
Kelas pemodal yang ditopang rezim negara dengan kemampuan modal dan alat produksinya mampu menggerakkan mekanisme dan moda produksi yang melibatkan kreator dan buruh dalam organisasi dan praktik kerja untuk menciptakan benda industrial yang mempunyai nila guna dan tukar serta bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya melalui proses sirkulasi, distribusi, dan konsumsi.
Proses tersebut mendorong terjadinya perubahan orientasi ideologi masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur dan praktik sosio-kultural.
Menjadi modern sebagai dampak dari kolonialisme dan pembangunanisme merupakan orientasi yang mengakibatkan pergeseran dan perubahan kehidupan masyarakat desa. Meskipun demikian, menjadi modern pada masa itu tetap tidak meninggalkan sepenuhnya tradisi. Kami tetap patuh kepada orang tua, meskipun kami sudah terbiasa menonton keliaran para tokoh kartun.
Kami masih mencintai kesenian tradisional tanpa disuruh, meskipun tidak paham sepenuhnya apa-apa yang dinarasikan. Para bapak masih sering cangkrukkan atau jagongan di warung atau gardu dusun membicarakan masalah-masalah aktual, seperti pertanian dan keamanan, meskipun dari pertengahan sampai akhir 80-an intensitasnya mulai berkurang karena televisi menghadirkan pesona lain.
Weber (dikutip dalam Heath, 2004:672) menggunakan istilah "hilangnya daya magis" atau "pesona dunia" (Entzauberung/ disenchantment/ demagicalization) untuk menggambarkan sebuah kondisi sosio-kultural tempat masyarakat yang mengalami modernisasi lebih menggunakan rasionalitas dan pengetahuan sebagai pijakan dalam memandang dunia.
Akibatnya, pesona-pesona dunia (seperti keyakinan terhadap magis, kekuatan alam, dan lain-lain) perlahan-lahan akan hilang dari nilai, institusi sosial, dan praksis kultural masyarakat.
Weber, tentu, melihat realitas tersebut dalam masyarakat industrial. Sementara, bagi masyarakat desa, pesona-pesona dunia desa tidak hilang sepenuhnya, karena modernitas juga tidak menguasai kami secara penuh meskipun punya potensi hegemonik dalam menggerakkan orientasi dan praksis kultural desa.