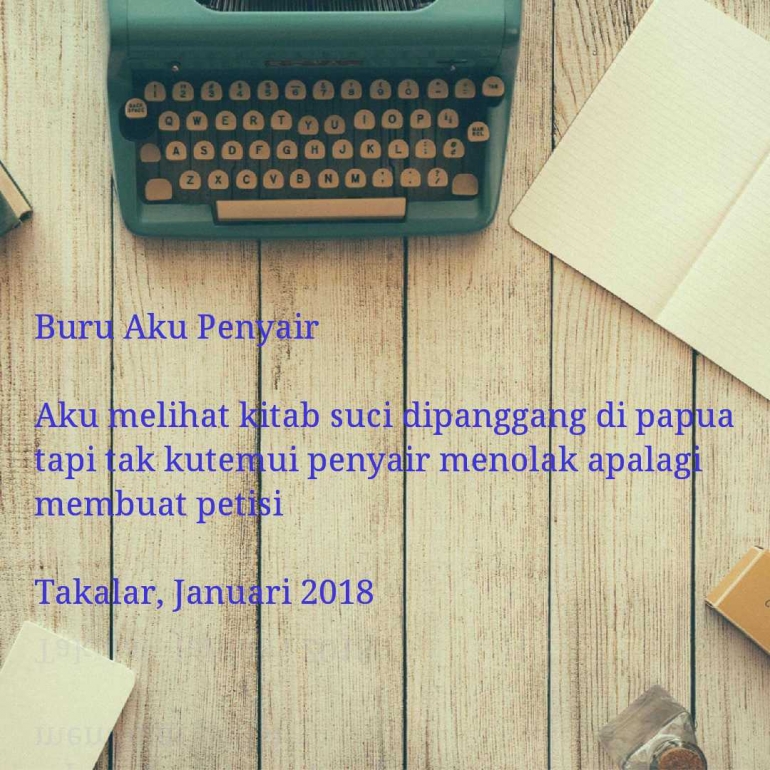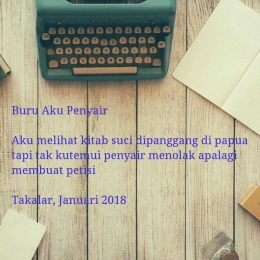"Aku melihat kitab suci dipanggang di papua tapi tak kutemui penyair menolak apalagi membuat petisi"Pemandangan sastra indonesia kini ramai dibicarakan, bahkan tahun politik 2018 tersisih. Pihak satu menyatakan bahwa sastra indonesia kini menemukan titik baru dari kejenuhan dengan bentuk dan gaya yang harus bertransformasi. Pihak lain menyatakan bahwa sastra indonesia sedang pesakitan, sebab gejolak ketidak sepakatan terhadap seorang penulis yang mengakui dirinya punya peran mendobrak sejarah sastra indonesia.
Hal ini menuai dinamika menarik untuk kembali memerhatikan sastra indonesia juga beberapa peristiwa yang mengikutinya. Apakah ini membuktikan bahwa sastra indonesia menuju pendewasaan? Atau kini sastra indonesia divonis sakit dan tidak baik-baik?
Jika benar adanya, sebuah gelora sejarah pernah terjadi di Bandung tahun 1974 yang perlu dikenang kembali, yakni "Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir" yakni sebuah acara pertemuan masyarakat sastra yang dipelopori oleh Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Acara yang dianggap pembeda dari acara seminar, simposium, acara lucu tapi serius. Dalam acara ini Slamet Kirnanto bertindak sebagai "Jaksa" dengan tuntutan "Mendakwah Kehidupan Puisi Indonesia Akhir-Akhir Ini Tidak Sehat, Tidak Jelas dan Brengsek".Acara pengadilan ini menghakimi Kritikus Indonesia, Penulis, dan Redaktur Media.
Pada polemik sastra dewasa ini, perlukah acara pertemuan sastra yang didesain untuk mendudukkan saksi, tersangka dan jaksa penuntut? Sekiranya acara ini mampu mendengar kebenaran dibanding saling serang satu sama lain namun tak mendidik.
Tak henti-hentinya proyek buku didengungkan dan ditolak, juga kini merambah mengenai pengklaiman bahwa sebelum Denny JA memproklamirkan dirinya sebagai penggagas puisi esai, sebelum itu katanya telah ada sebuah puisi esai dengan menambahkan catatan kaki di tiap karyanya, dan bukan Denny JA sebagai pelopor. Lalu apakah kita akan berada pada lingkaran perdebatan ini saja tanpa memikirkan untuk menulis terus, membaharu, dan memperbaiki kualitas tulisan sendiri? Biarkan waktu yang menilai.
***
Kita membayangkan betapa indahnya jika kita berbicara mengenai sastra indonesia khususnya puisi mampu bergerak melawan, mampu merepresantasikan nilai-nilai kenabian, humanisasi dan perjuangan transenden.
Apa kabar bentuk puisi Wiji Tukul, WS Rendra dan Gus Mus? Pertanyaan itu menjadi intrik membayangkan para penulis-penulis hanya memikirkan makna kandung tiap puisi, tanpa banyak pikir mengenai aliran, pakem dan bentuk-bentuk yang harus diimani. Sastra kini hanya sikap gaya, diksi, tapi kadang terlepas dari derita lingkungan. Sastra bukan lagi media perjuangan, bukan lagi pembawa pesan kenabian, tapi seakan kitab yang harus dibela mati-matian. Meskipun pembelaan kita kadang kala hanya ikut berpartisipasi mencari panggung nama.
Jika benar adanya bahwa sastra telah menyampingkan perjuangan, maka sastra tidak lebih seperti kacang yang lupa kulit. Perjuangan menulis Wiji Tukul walaupun diredam penguasa kini lupa dibicarakan, dan lebih menyibukkan diri membela sastra indonesia. Pembelaan siapakah paling benar dicatatan sejarah sastra indonesia di masa akan datang?
"Aku melihat kitab suci dipanggang di papua tapi tak kutemui penyair menolak apalagi membuat petisi"
"Derita kemiskinan, politik keterlaluan, kebijakan penguasa yang memiskinkan, agama yang dihina, mahalnya pendidikan, ujaran kebencian, pengangguran bertambah adalah musuh sastra yang dilupakan oleh beberapa penyair"