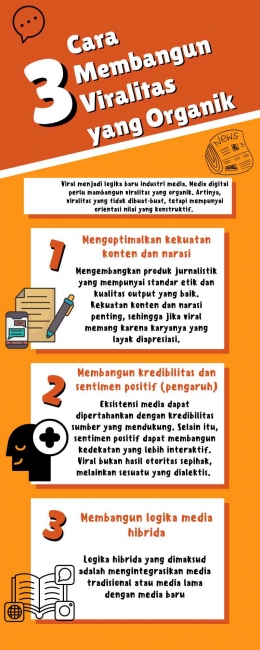Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan konsep digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Salah satunya adalah bentuk penetrasi digital dalam industri media.
Media sosial maupun media massa terus berkembang dengan beradaptasi dan menyesuaikan konten-konten yang diminati oleh publik di era media baru.
Viral dan Media Baru
Dalam era media baru, audiens yang sebelumnya hanya berperan sebagai konsumen sekarang memiliki kesempatan menjadi produsen informasi dan konten media.
Mereka pun berlomba-lomba menghasilkan produk-produk media yang berkiblat pada logika viralitas dan ketenaran.
Verdy Firmantoro menyebutkan bahwa fenomena ini dikenal sebagai desentralisasi informasi, di mana setiap individu memiliki peran dalam menentukan agenda media.
Media konvensional seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya yang memegang posisi penting sebagai media arus utama perlahan-lahan digeser oleh media sosial dan internet.

Di tengah arus disrupsi, media dan pers dituntut untuk menjaga amanah reformasi, sebagai akselerator perubahan yang bekerja hanya dengan fakta-fakta dan data-data yang ada.
Permasalahannya, media dan pers berada di tengah konflik berat, di satu sisi mereka perlu menghadapi hibridisasi global, di sisi lain mereka juga berhadapan dengan kelindan kekuasaan.
Viral dan Kebenaran Semu
Logika viral identik dengan media digital, termasuk media sosial.
Seiring dengan pergerakan arus zaman dan tuntutan permintaan pasar, pertimbangan untuk mengikuti logika viral juga mulai dipraktekkan oleh media-media konvensional.
Media konvensional mulai bergerak memasuki platform online guna terus bertahan dari gempuran digitalisasi media.
Persoalannya adalah media-media ini kerap kali terjebak dalam perlombaan mengejar rating dan viralitas parsial.

Media berbondong-bondong melakukan eksploitasi konten-konten yang membangkitkan wacana publik melalui informasi yang dibalut sentimen emosi untuk memancing perhatian audiens daripada menyebar informasi yang telah melalui pertimbangan-pertimbangan rasional.
Padahal media dan pers diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai intermediary institutions (lembaga perantara atau penghubung) narasi kebenaran.
Pendekatan viral yang bertumpu pada nalar jaringan dan penyebaran yang begitu cepat layaknya virus berpotensi mengancam logika media yang mengutamakan kerja-kerja etis dan profesional.
Konten-konten viral yang diproduksi oleh media online kerap kali mengabaikan kode etik pers dan bahkan memiliki kecenderungan mengarah ke konten hoaks yang tentunya merupakan ancaman besar bagi demokratisasi informasi.
Meskipun berada di tengah era kebebasan berpendapat dan semua orang berhak berekspresi, tidak semerta-merta membenarkan penggunaan logika viral yang justru mengaburkan realitas yang sesungguhnya, jargon "yang viral, yang benar" merupakan bentuk pseudo-kebenaran atau kebenaran semu.

Industri media dipenuhi dengan bisnis praktik buzzer yang aktif melakukan propaganda digital. Hal ini menunjukkan bahwa rezim informasi dikuasai oleh para penguasa like, share, dan comment.
Pengguna media digital yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai validasi sebagai sumber informasi tetapi memiliki kemampuan untuk menentukan opini publik hanya berdasarkan pada jumlah pengikut merupakan suatu bencana.
Media dan pers yang diisi oleh wartawan profesional seharusnya mengedepankan independensi, integritas, profesionalisme, non-diskriminasi serta berkomitmen untuk berpegang teguh pada nurani dan nilai-nilai luhur yang pantas dijunjung.
Berangkat dari nilai-nilai tersebut, pers dapat membingkai informasi menjadi berita yang berisikan data-data terverifikasi, telah melalui proses investigasi yang sesuai sehingga lahirlah karya-karya jurnalistik yang mencerahkan dan mencerdaskan audiensnya.
Media dan pers idealnya dapat mendorong semangat literasi dan membantu menciptakan ruang publik yang mampu memfasilitasi pertukaran ide, gagasan, pengetahuan, serta wacana-wacana produktif.
Seperti ungkapan Thomas Jefferson, bahwa "Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia, sebagai makhluk rasional, moral dan sosial".

Viral dan Kasusnya
Melansir dari detik.com pada bulan Februari 2020, terdapat pemberitaan mengenai Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, tentang "Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila" sempat menjadi berita viral yang ramai dibahas di kalangan masyarakat.
Alhasil, muncul banyak reaksi keras dari para tokoh-tokoh, publik. maupun netizen yang kontra bahkan sampai melakukan perudungan kepada kepala BPIP yang sekaligus juga merupakan mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Meskipun begitu, terdapat dilema dan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala BPIP tersebut. Apakah berita tersebut hanya hasil framing dari media? Apakah alasan berita tersebut menjadi sangat viral?

Bono Setyo, selaku Direktur Center of Communication Studies and Training (COMTC) dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan bahwa kasus pemberitaan viral ini bermula dari wawancara detik.com pada Prof. Yudian, yang selanjutnya ditulis menjadi berita di media online dengan headline "Kepala BPIP Sebut Agama sebagai Musuh Terbesar Pancasila".
Bono menyebutkan bahwa masalah bermula dikarenakan adanya communication gap antara wawancara yang dilakukan detik.com dengan pemberitaan yang ditulis di situs beritanya.
Sebagaimana berita merupakan produk atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh seorang wartawan yang juga seorang manusia, maka terkadang secara manusiawi pula wartawan tersebut mengalami distorsi akibat penafsiran atau interpretasi secara subyektif.
Wartawan yang tentunya memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk menghasilkan berita yang menjual sehingga menerapkan konsep "bad news is a good new" dan terkadang wartawan secara sengaja menggunakan teknik menulis headline yang clickbait yang menarik, bombastis, dan bahkan terkadang kontroversial sehingga mendapatkan perhatian dari masyarakat dan netizen.

Hasilnya, headline pemberitaan detik.com tentang wawancara dengan kepala BPIP tersebut dapat dikatakan berhasil atau sukses. Hal ini dibuktikan dengan respon yang sangat signifikan dari berbagai kalangan masyarakat dan netizen.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Center of Communication Studies and Training (COMTC) yang bekerja sama juga dengan Median-analytic, diketahui sejak berita tersebut diunggah sampai tanggal 13 Februari 2020 terdapat sebanyak 15.000 tweet yang masuk, dan tagar yang paling banyak muncul atas isu tersebut adalah #bubarkanbpip.
Fenomena tersebut menunjukkan betapa "kejam"nya media dan pers ketika oknum jurnalis yang hanya mengejar sensasi atau kepentingan sesaat melalui logika viralitas.
Banyak masyarakat dan netizen yang seharusnya dapat menggunakan logika manusia untuk berpikir jernih dan rasional justru terseret ke dalam logika medial viral yang notabene irasional dan terkadang hanya berbentuk framing.
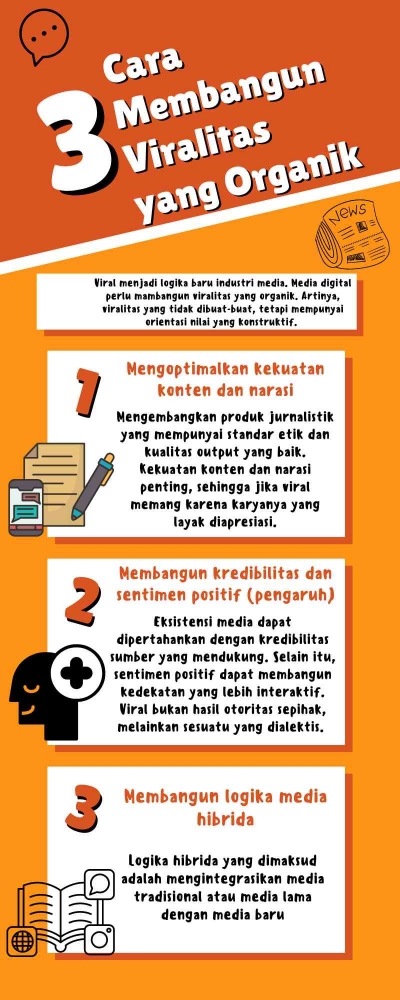
Bono juga menyerukan pentingnya literasi media, baik untuk masyarakat dan netizen serta para pelaku jurnalistik yakni, pemberitaan atau informasi dari media penting namun jangan ditelan mentah-mentah apalagi hanya berdasarkan interpretasi headline atau lead berita.
Kemudian, bagi masyarakat dan netizen agar membangun kebiasaan untuk selalu membaca berita secara utuh serta melakukan check and recheck dengan sumber berita langsung atau melalui pemberitaan lain agar kita tidak terseret pada logika viral media.
Yang terakhir, bagi media khususnya para jurnalis agar lebih memperbanyak berita positif, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat dan netizen.
Dengan demikian, masyarakat akan tetap memiliki sikap kritis tetapi tidak sampai pada tahap konflik sosial hanya karena misinterpretasi atas suatu berita.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI