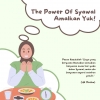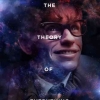"Memang harus mahal harga sebuah keyakinan itu. Ndak boleh murah. Makin mahal, makin berharga...Saya tidak pernah menyesal menolak Orde Baru. Itu semua dilakukan dengan sadar, jadi nggak ada tempat untuk penyesalan..." (kutipan ucapan Om Jaya - Film "Surat Dari Praha")
Mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah memiliki satuan resmi bentukan Pemerintah, yang mengandung kata "Mafia". Mungkin. Satuan tersebut bernama Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, disingkat Satgas PMH, yang dibentuk era pemerintahan SBY. Dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, kata "Mafia" disebut sebagai "perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal)".
Jelas kata "Mafia" tidak mengandung makna yang positif. Dalam dunia ekonomi politik Indonesia, pernah dikenal istilah "Berkeley Mafia". Istilah "Berkeley Mafia" dicetuskan oleh seorang aktivis-penulis 'kiri' AS, David Ransom, dalam majalah Ramparts, edisi bulan Oktober tahun 1970. "Berkeley Mafia" yang dimaksud merujuk pada ekonom-ekonom Indonesia lulusan universitas di Amerika Serikat (terutama University of California, Berkeley).
Para ekonom tersebut merupakan arsitek utama perekonomian Indonesia pada awal kemunculan Orde Baru pimpinan Soeharto. Selain Widjojo Nitisastro, ekonom yang dianggap menjadi 'anggota' Mafia Berkeley, antara lain adalah Emil Salim dan Saleh Afif. Mereka adalah para dosen FE UI yang mendapat tugas studi ke AS di antara tahun 1959 -- 1964, yang kemudian menduduki posisi penting di era Orde Baru
Ransom memiliki teori konspirasi bahwa Amerika Serikat (AS) telah merencanakan sejak dini munculnya pemerintahan militer yang antikomunis ditopang oleh sekelompok ahli ekonomi didikan AS (yaitu Widjojo dan kawan-kawan). Ransom menghubungkan "Mafia Berkeley" dengan desain CIA untuk menggulingkan Soekarno, melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia, kemudian mendudukkan Soeharto di kekuasaan untuk menjalankan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada Barat.
Teori konspirasi memang seru untuk jadi obrolan sambil minum kopi dan makan gorengan. Tapi sampai sejauh mana kebenarannya, hanya Tuhan, dan (mungkin) kaum intelijen yang tahu. Faktanya, memang ekonom yang dikaitkan sebagai "Mafia Berkeley" menduduki posisi penting dalam pemerintahan era Orde Baru. Apakah semua dosen FE UI yang studi di Amerika Serikat pada era itu, memang akhirnya mengalami nasib yang sama?
Ternyata, ada seorang dosen FE UI yang berangkat ke Amerika Serikat tahun 1959 untuk belajar di Stanford University, mengalami nasib yang berbeda. Jauh berbeda. Bagaikan bumi dan langit.
Sang dosen ini bahkan dianggap "telah menunjukkan itikad tidak baik" oleh pemerintah Indonesia, passportnya dicabut, sempat kerja serabutan (di antaranya termasuk menjadi kuli pabrik cat di Mainz, Jerman), tidak bisa kembali ke tanah air selama puluhan tahun, dan dianggap komunis. Namanya Batara Simatupang.
Anomali
Apa yang membuat Batara menjadi anomali dengan memiliki jalan hidup bertolak belakang dari koleganya sesama dosen FE UI yang dituding sebagai "Mafia Berkeley"?
Dalam buku otobiografi dan kumpulan tulisannya, yang diterbitkan terbatas oleh Yayasan Del di tahun 2012, Batara menceritakan, semua bermula dari perubahan politik di Indonesia sejak peristiwa G30S tahun 1965.
Setelah selesai studinya di Stanford, Amerika Serikat, pimpinan FE UI (Prof. Sadli) menugaskan Batara belajar ekonomi sosialis di Yugoslavia, dan akhirnya di Polandia. Alasan penugasan tersebut adalah dirasakan perlunya dosen FE UI yang memahami ekonomi sosialis. Saat itu FE UI sering diserang oleh kaum 'kiri' karena dianggap tidak mengajarkan ekonomi sosialis dalam kurikulumnya.
Batara menceritakan beberapa hari setelah menerima surat penugasan tersebut, dirinya ditelepon Prof. G. Pauker, yang waktu itu diperbantukan di Rand Corporation (sebuah think-tank di Amerika Serikat), bahwa tersedia beasiswa di Stanford University untuk merampungkan studi doktoral bagi Batara.
Namun tanpa pikir panjang, Batara menolak tawaran beasiswa tersebut, dan setia pada penugasan yang diberikan FE UI. Batara kemudian berangkat ke Yugoslavia dan akhirnya ke Polandia.
Saat Batara di Polandia, terjadilah peristiwa G30S tahun 1965. Warga Indonesia yang belajar di negeri-negeri sosialis terkena dampaknya. Bulan September 1966, KBRI di Warsawa, memerintahkan para mahasiswa Indonesia untuk hadir dan menjalani screening. Batara dan 10 orang mahasiswa Indonesia lain, menolak hadir. Singkatnya, mereka menolak Orde Baru. Dalam usia muda dan penuh idealisme, Batara dan kawan-kawannya barangkali tidak pernah membayangkan bahwa keputusan tersebut berpengaruh secara fundamental terhadap kehidupan mereka.
Tak menunggu lama, tanggal 4 Oktober 1966 KBRI menerbitkan surat keputusan yang mencabut passport Batara dan 10 mahasiswa lainnya. Batara dan teman-temannya menjadi manusia tanpa tanah air.
Batara berkisah, "Bagi saya keputusan pencabutan passport oleh KBRI di Warsawa ini sangat mengejutkan dan tidak adil. Nasib yang sama juga menimpa ratusan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri sosialis di Eropa Timur, Uni Soviet, dan Asia."
Buat penulis yang lahir dan besar di era Orde Baru, sukar membayangkan penderitaan yang dialami oleh para mahasiswa yang menjadi "stateless" tersebut.
Dalam hal ini, film "Surat Dari Praha" (2016), patut diapresiasi, karena membuat kita memiliki sedikit gambaran mengenai kehidupan para mahasiswa "stateless" tersebut. Film ini berkisah tentang mahasiswa Indonesia yang mengalami nasib seperti Batara, dengan lokasi di Praha (menggunakan nama : Jaya - diperankan Tyo Pakusadewo. Di awal film disebutkan "inspired by true events", sayangnya tidak disebutkan sosok yang menjadi inspirasi film ini). Keterasingan, kesepian, dan barangkali perasaan dikhianati oleh negara yang mereka cintai, merupakan keseharian mereka. Tidak terkecuali Batara.
Berdamai dengan diri sendiri
Saat membaca otobiografinya, penulis merasa ada sedikit penyesalan mengenai penolakannya terhadap tawaran beasiswa PhD di Stanford. Batara menyebutkan, ia mungkin terlalu antusias untuk mempelajari sosialisme di Yugoslavia, sehingga tidak mempertimbangkan lebih lanjut tawaran beasiswa PhD di Stanford. Namun, sepertinya Batara sudah berdamai dengan dirinya.
Dalam pertemuan dengan Emil Salim tahun 1984 (kedatangan ini dibantu oleh Sabam Siagian, wartawan senior. Dalam kunjungan ini, Batara wajib secara rutin melapor ke bagian intel kepolisian), Emil Salim menuliskan, "Saya tahu Batara menderita batin. Namun ia bercerita dengan menekankan fakta-fakta, tak ada emosi atau kebencian yang meluap... Tak ada kata mengeluh dari mulut Batara."
Batara meninggalkan Indonesia tahun 1959 dengan mimpi dan harapan yang besar untuk bisa membangun bangsanya menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, ia datang kembali ke Indonesia 25 tahun kemudian, sebagai seorang anak bangsa dengan cap "tidak bersih" oleh rezim Orde Baru yang berkuasa.

Dalam buku tipis "Catatan Spiritual di balik sosok Sobron Aidit" (BPK Gunung Mulia, 2005), diceritakan bahwa setiap kali Sobron mengucapkan bagian doa Bapa Kami mengenai pengampunan, seakan ada sesuatu yang menghambat kerongkongannya.
"Sepertinya saya berbohong saat mengucapkannya! Bagaimana saya mampu mengampuni orang yang sudah membunuh keluarga, teman dan sahabat saya...bahkan ratusan ribu sampai jutaan jiwa!"
Luka batin yang dalam membutuhkan pengampunan yang mendalam. Urusan ampuni -- mengampuni , maaf -- memaafkan sehubungan peristiwa G30S 1965 ini memang rumit dan kompleks.
Setelah Orde baru berakhir, hanya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berani meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Gus Dur meminta maaf kepada korban 65, orang-orang yang dituduh PKI dan keluarga yang dibunuh. Anehnya (atau justru tidak aneh?), banyak pihak yang mencela permintaan maaf Gus Dur.

Bulan Juni 2018 lalu Batara telah meninggal di Belanda, dalam usia 86 (Batara lahir tanggal 25 Mei 1932). Batara memang memperoleh kewarganegaraan Belanda sejak Maret 1984.

Dalam kunjungan Batara tahun 2007 di Jakarta, diadakan pertemuan yang diprakarsai Sabam Sirait (politikus PDI-P), dan menghadirkan beberapa ekonom senior (antara lain Ali Wardana, Daoed Joesoef, Hari Tjan Silalahi, Adrianus Mooy, Thee Kian Wie, dll).
Pertemuan itu dirangkum oleh Sabam Siagian dan ditampilkan dalam kolom "Catatan Jakarta" di harian Suara Pembaruan tanggal 9 Juni 2007, dengan judul "Pertemuan dengan Batara Simatupang". Sabam Siagian menuliskan bahwa salah seorang peserta diskusi menjuluki Batara sebagai "The wandering member of the Berkeley Mafia".
Batara hanyalah salah satu dari sekian banyak korban peristiwa 1965. Andaikata Batara pulang ke Indonesia sebagai salah satu "Berkeley Mafia", jalan hidupnya mungkin berbeda. Tapi sejarah dan masa lalu tidak pernah kenal "andaikata". Yang sudah terjadi tidak bisa diubah.
Namun agar lebih utuh, cerita mengenai "Mafia Berkeley" barangkali perlu juga memasukkan kisah adanya dosen FE UI yang sempat belajar ekonomi sosialis dan sempat terbuang, serta mengembara di Eropa sebagai manusia tanpa tanah air, akibat kondisi politik 1965. Juga untuk mengingatkan kita kembali bahwa para korban 1965 juga manusia Indonesia yang perlu mendapatkan keadilan.
Artikel lain mengenai Batara Simatupang: historia.id
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI