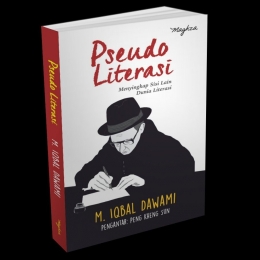Resensi Buku Nyeleneh | Pseudo Literasi: Menyingkap Sisi Lain Dunia Literasi | M. Iqbal Dawami | Maghza Pustaka, April 2017 | 156 h.
Tahun 2006, rasanya (ya rasanya) saya sempat membuat geger jagat perbukuan Indonesia dengan menerbitkan buku The True Power of Water di bawah bendera MQS yang kala itu saya pimpin. Buku karya Masaru Emoto itu termasuk yang fenomenal mengungkap keajaiban air karena bentuk molekulnya dapat berubah merespons informasi baik atau buruk yang dipaparkan kepadanya (air itu). Perubahan itu mengandung energi penyembuhan yang disebut HADO--dengan cerdik kami ubah kepanjangannya menjadi Hikmah Air Dalam Olahjiwa. Bisa aja ....
Kalangan ilmuwan pun bereaksi menyatakan apa yang disampaikan Masaru Emoto itu adalah pseudo science alias sains yang semu dan cenderung menipu. Walau begitu, buku versi terjemahan itu laku keras sampai menyentuh angka 80.000 eksemplar sebelum MQS saya tinggalkan. Buku itu pun dibalas dengan buku berjudul The Untrue Power of Water. Patut dihargai karena memang lebih baik melawan buku dengan buku.
Tapi, tulisan ini bukan hendak membahas buku itu karena bakal panjang lebar pembahasannya, termasuk soal pro dan kontra. Biarlah hanya saya dan Allah saja yang tahu.
Saya teringat buku itu ketika membaca buku Pseudo Literasi yang ditulis, M. Iqbal Dawami, terbitan Maghza Pustaka 2017. Judulnya menarik hati saya karena ada anak judul Menyingkap Sisi Lain Dunia Literasi, untungnya bukan sisi gelap.
Buku ini sebentuk kumpulan esai yang dalam istilah saya menggunakan pola outline butiran. Ada 20 esai yang disajikan Iqbal terkait dunia literasi meskipun lebih banyak Iqbal menulis tentang pernak-pernik dunia buku--atau tepatnya karut-marut dunia literasi menurut pemberi kata pengantar Peng Khek Shun.
Saya coba mencerna judul dan isi buku ini. Apa yang dimaksud Iqbal soal kesemuan atau secara sarkastis disebut "tipuan literasi" ini? Rupanya Iqbal dalam bukunya menandai fenomena orang-orang yang bergelut dalam bidang literasi, tetapi perilaku sebenarnya tidak literat.
Contoh fenomena paling gampang saya pernah mengkritik bahwa banyak pemilik atau direktur penerbit buku yang sebenarnya tidak membaca atau tidak terlalu tertarik dengan buku. Perkara ini juga pernah mengemuka sewaktu Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) dipimpin oleh Ajip Rosidi tahun 1970-an hingga 1980-an. Di tubuh Ikapi muncul Ikapi garis idealis dan garis bisnis.
Mereka yang tumbuh dari garis bisnis karena melihat peluang proyek Inpres (pengadaan buku bacaan SD dan SMP-SMA) yang menggiurkan. Jadi, omong kosong jargon mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar mereka laksanakan--begitu tulis Hawe Setiawan dalam buku 50 Tahun Ikapi Membangun Masyarakat Cerdas (2000).
Di dalam bukunya Iqbal juga menyentil para pegiat atau aktivis literasi yang mendirikan TBM dan sibuk menggembar-gemborkan pentingnya membaca, tetapi mereka sendiri tidak menunjukkan perilaku atau kebiasaan membaca. Senangnya memang gagah-gagahan sebagai pejuang literasi di jalan sunyi.
Hal yang nyata juga terjadi di ruang-ruang akademis kita. Banyak guru dan dosen yang tidak membaca, apalagi menulis. Namun, sebutan mereka adalah pendidik yang seharusnya menjadikan buku sebagai basis pengetahuan mereka. Ya itulah namanya juga pseudo--apakah guru dan dosen itu jadi-jadian, saya juga tidak mengerti.
Lebih menarik lagi kalau membahas soal penulis dan kehidupannya. Iqbal juga mempertanyakan mengapa ada orang yang memotivasi bahwa menulis itu bisa kaya, tetapi contohnya itu-itu saja. Contohnya, pasti J.K. Rowling, Andrea Hirata, atau Habiburrahman El-Shirazy. Semua datanya sama terkait penjualan novel yang meledak, tetapi angka pasti sebenarnya tidak pernah ada yang tahu.
Saya ingin menambahkan bahwa lebih naif lagi jika ada penulis yang menulis tentang kaya dari menulis, tetapi dia sendiri belum kaya karena masih berada di bawah garis kekayaan. Lebih naif lagi seorang penulis yang baru menulis 1-2 buku, lalu berani membuat pelatihan menulis dengan topik bagaimana menjadi penulis best seller. Penulisnya yang laku terjual, bukan bukunya (ya, mestinya menjadi penulis buku best seller). Itulah uniknya Indonesia.
Ada lagi yang lebih semu, menulis antologi, tetapi posisinya hanya sebagai kontributor satu tulisan, lalu ia mengaku sebagai penulis buku. Buku itu adalah buku antologi, buku solonya menyusul. Baru pada tahun 2010-an-lah saya mendengar istilah buku solo--waktu itu memang saya sedang bekerja di sebuah penerbit di Solo, hehehe.
Jadi, kesemuan yang diungkap Iqbal menurut saya kurang banyak. Mungkin kalau banyak, bukunya jadi tebal dan berharga mahal dan negara kita malah dijuluki negara pseudo-literasi.
Ini yang menarik, bahkan, Iqbal juga bilang writerpreneur itu bukan solusi, tetapi pelarian. Nah, di sini saya rada-rada tersungging, bukan senyuman, melainkan kacamata saya. Masa iya sih?
Kenapa harus ada writerpreneur? Pertanyaan ini adalah pertanyaan serius yang hendak saya tanyakan kepada para penulis yang menganjurkan untuk menjadi pengusaha tulis-menulis .... (h. 48)
Berarti telunjuk Iqbal mengarah kepada saya yang lagi membaca dengan serius dan saya akan jawab dengan serius juga, tapi santai. Iqbal mengatakan menjadi writerpreneur itu bukan solusi, melainkan pelarian. Hal itu menunjukkan bekerja sebagai penulis (buku) itu memang tidak layak di Indonesia.
Lalu, Iqbal beralih kepada memperbaiki sistem yang menurut Peng Kheng Sun sudah karut-marut ini--terus terang saya penasaran sama Pak Peng Kheng Sun, siapa beliau? Lantas, saya googling ternyata beliau seorang akademisi dan penulis produktif juga, berarti saya kurang gaul. Seketika saya jadi ingat The Liang Gie, seorang guru dan pakar menulis (juga pakar administrasi) dari Jogja tahun 1980-an, tetapi beliau kalah populer dibandingkan Gorys Keraf waktu itu.
Kembali soal writerpreneur mungkin Iqbal perlu membaca buku Chicken Soup for the Writer's Soul yang versi Indonesianya berjudul Harga Sebuah Impian terbitan Gramedia. Salah satu kontributornya adalah Dan Poynter yang disebut-sebut sebagai God Father ribuan buku di Amerika. Poynter adalah orang yang mengompori banyak penulis untuk menerbitkan bukunya sendiri karena menghadapi belasan, bahkan puluhan kali penolakan dari penerbit. Self-publishing telah menjadi tradisi di Amerika meskipun negara itu dikenal sebagai raksasa dunia buku.
Self-publisher itu adalah writerpreneur, sama halnya yang dilakukan Iqbal dengan Penerbit Maghza Pustaka-nya yang menerbitkan buku Pseudo Literasi--namun jika penerbit ini menerbitkan buku lain bukan karya Iqbal, jadinya publisher. Itu sebuah pilihan sebagai bentuk "perlawanan" terhadap hegemoni penerbit konvensional--para penulis sering menyebutnya major publisher, padahal masih ada yang di atas major pangkatnya, hehehe.
Memang Iqbal tidak tuntas membahas pseudo writerpreneur ini. Saya pribadi untuk menjaga idealisme dan pemikiran saya dari kontaminasi bisnis jasa, saya tetap menulis buku sendiri dan tetap ada yang saya kirimkan ke penerbit. Belakangan, saya mulai lagi menulis untuk dikirimkan ke media massa. Dua tulisan saya sukses ditolak Kompas. Mungkin saya sudah terlalu tua untuk menulis opini.
Saya tidak terlalu memikirkan soal royalti atau imbalan karena ini sebuah perjuangan. Jika ingin mendapatkan royalti yang nendang, buku saya harus laris. Itu saja, titik tanpa koma.
Mengapa saya harus gusar merasa diperlakukan "tidak adil" dengan buku-buku yang laku keras itu, seperti novel Tere Liye, Pidi Baiq, Dee, dan Raditya? Dunia ini terasa tidak adil karena sebenarnya kapasitas menulis saya tidak sebaik Tere, Pidi, Dee, atau Raditya dalam fiksi. Ya, berarti itu salahnya saya, mengapa tidak menjadi penyanyi dulu seperti Dee (hehehe). Kalau saya mau seperti mereka, saya harus melakukan riset terhadap fenomena keunggulan karya mereka karena mereka pada dasarnya juga dulu memulai dari bawah.
Boleh jadi kita sedikit "nyinyir" kok buku begitu bisa laku. Itulah kelebihan penulis buku best seller yang mampu meraba hati para pembacanya. Mereka membuat buku yang "baik dan bagus" untuk pembacanya, bukan untuk kita yang tidak ingin membacanya.
Soal ini saya sudah sedikit insaf. Ya, sedikit, yaitu tidak lagi ingin "nyinyir" dengan penulis sebelah. Kita punya jalan masing-masing, termasuk jalan writerpreneurship. Memang ada indikasi pseudo bahwa tidak semua writerpreneur itu benar-benar penulis. Lho, kok bisa?
Ya bisa saja, orang yang merasa mampu menulis, padahal tidak mampu, menawarkan jasanya untuk menulis. Orang yang tidak mampu mengedit, tiba-tiba berani jadi editor. Satu lagi pseudo itu, orang yang baru lulus kuliah, mengaku menjadi penulis freelance. Kalau pengertian freelance di luar negeri adalah mereka yang sudah pernah bekerja secara profesional di perusahaan, lalu keluar karena ingin bebas. Lha, di kita karena tidak diterima kerja di mana-mana, lalu mendeklarasikan dirinya jadi freelancer.
Tingkah ini saya lihat juga pada beberapa penulis. Awalnya ia melamar menjadi editor di penerbit, tetapi tidak diterima. Terus mulai dia gembar-gembor jadi writerpreneur itu lebih bermakna dan mengasyikkan daripada kerja kantoran. Nah, ini yang baru dapat disinyalir sebagai pelarian.
Kembali yang saya tangkap bentuk kegelisahan Iqbal soal sistem yang tidak menghargai penulis di negeri ini. Ya, itu saya akui sampai-sampai saya harus berbusa-busa ikut merumuskan RUU Sistem Perbukuan yang sudah disahkan DPR. Semuanya ingin saya bela dan belah, penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, dan penerbit. Harus ada produk hukum tertinggi yang menjadi dasar untuk "menggugat" negara memperhatikan nasib pelaku perbukuan.
Mungkin ada juga yang tidak suka kalau saya mengidekan perlunya sertifikasi penulis. Ngapain coba jadi dibuat susah dengan sertifikasi segala? Kalau sudah bicara sistem, memang harus ada standar, indikator, dan lain-lain, termasuk pengorbanan. Hal yang tidak dapat distandardisasi dan diukur adalah kreativitas. Karena itu, sulit mengukur harga buku hanya dari fisiknya, bukan dari kontennya.
Ada yang bilang harga buku A mahal jika dibandingkan buku B. Ternyata yang dibandingkan fisiknya, bukan kontennya. Ini juga pseudo-literasi!
Bahasan ini tampaknya sudah berkepanjangan. Hehehe. Maaf Mas Iqbal, yang pasti Anda sudah menulis buku yang menyengat, terutama menyengat orang yang memuji-muji buku Anda, tetapi tidak membelinya. Mereka itu ibarat semur literasi--tampak menggiurkan, tetapi tidak ada dagingnya.
Mas Iqbal ini juga sebenarnya sedang melakukan "pelarian". Lha di dalam biografi singkatnya ia mengajak orang bekerja sama dalam penulisan, editing, penerbitan buku, seminar literasi, dan pelatihan menulis .... Artinya, Mas Iqbal lagi nawarin jasa. Apakah ini pseudo-literasi juga?
Jelas bukan, itu nyata. Apa yang nyata juga sebenarnya saya ingin sekali menulis buku seperti Pseudo Literasi ini. Ini buku penting untuk para penulis dan pegiat literasi yang lagi pening. Gimana nggak pening ketika Pak Jokowi bertanya, "Apa itu literasi?" Apalagi, kalau Pak Jokowi nanya, "Siapa yang tahu apa itu pseudo-literasi?" Pasti tidak ada yang pulang dapat sepeda.
Karena itu, beli bukunya siapa tahu Anda diundang Presiden. Jangan cuma baca resensi karena itu sama dengan pseudo-literasi--orang yang mengaku sudah membaca buku, padahal cuma baca resensi.[]